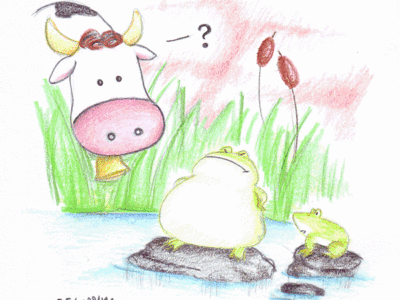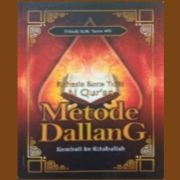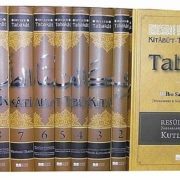Malam Jumat, bakda Isya di kantor pondok. 12 orang kumpul-kumpul santai. Kang Akbar, kepala keamanan tampak di sana. Ia selonjoran di bangku sambil ngelus-ngelus rotan, senjata ampuh untuk ngoprak-ngoprak santri jika bel waktu ngaji berbunyi dan bangunin seisi pondok saat Subuh hari. Saat itu, saya juga sedang ada di sana, melaporkan absen mingguan kegiatan asrama. Jelak-jelek begini, dulu saya seksi pendidikan di Asrama G, singkatan Al-Ghazali.
“Kang, wis do mangan durung?” Dul Manan tiba-tiba muncul, berdiri di pintun. Biasa, tanpa babibu. Mamat yang duduk menghadap komputer nyautin tanpa melihat ke pintu, tempat Dul Manan berdiri: “Gimana Kang Dul? Mau ikut jamaah makan malam? Tunggu 30 menit lagi!”
Pertanyaan Mamat tampak underestimate. Dan bukan hanya dia yang punya sikap seperti itu pada Dul Manan. Bahkan boleh dibilang minoritas saja yang memandang Dul Manan dengan respek. Kadang bisa dimaklumi. Tapi kadang juga kasihan. Saya sebagai teman sekamarnya juga punya sikap ambigu, kadang masa bodoh, kadang kasihan. Kalau saya sedang waras, sering mbatin: Masa seisi pondok ini tak ada yang welas asih seperti Kiai Abdul Fattah Tambakberas yang begitu welas asih kepada semua santri, pun pada santri yang nakalnya tidak terpikirkan? Masa tidak ada yang meniru Kiai As’ad yang suka keliling kampung bagi-bagi rokok dan beras pada preman yang bukan saja gak sembayang, tapi kerap dijumpai tersungkur di pos ronda lantaran mabuk?
Tapi, kalau ingat Dul Manan sedang mbeling, pikiran warasku tadi hilang secara otomatis, apalagi kalau ingat sweterku yang belum sebulan, dipakai dia tanpa bilang-bilang, dan bolong di bagian lengan karena rokok. “Karepmu Dul kowe arep ngopo…” Saya hanya bisa mbatin.
Kembali ke suasana kantor pondok. Mendengar jawaban Mamat, Dul Manan tidak tersinggung sama sekali. Dia cuek, seperti pemain bola yang sudah terlatih menghadapi penonton yang mencemoohnya. Dia bahkan dengan percaya diri mengatakan akan kembali ke kantor 30an menit lagi sambil bawa lauk yang belum pernah dia bawa.
“Kebeneran kalau 30 menit lagi. Tunggu saya, Kang. Saya ikut makan. Tenang, saya patung lauk..”
Setelah mengatakan itu dia nyepeda agak ngebut. Sepada milik pondok, dia pakai tanpa babibu. Kang Akbar tetep ngelus-ngelus rotan, tanpa respon sedikit pun kehadiran Dul Manan. Namun, setelah Dul Manan pergi, Kang Akbar membuka pembicaraan:
“Enaknya diapain bocah itu? Kemarin sore nyaris saja kucingnya Ning Ais kena lemparan bakiaknya. Bocah itu masa gak tahu itu kucingnya ndalem? Piye Kang Amin? Si Dul kan konco sekamarmu?”
Kang Akbar kalau bicara memang gitu, kalimat tanya jauh lebih banyak daripada jenis kalimat lain. Maklum, salah satu tugasnya memang melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan pada santri yang melanggar. “Sampean saja tanya, Kang, apalagi saya,” jawabku menambah persoalan.
“Kang, nganu, saya menduga Dul Manan akan kembali dengan membawa sate ayam Cak Imun. Dia hampir tiap bulan nraktir anak kamar sate ayam. Bulan ini belum, mungkin jatah kamar dialihkan ke sini,” saya kasih info, dengan tujuan membelokkan tema ngobrol Kang Akbar.
Mamat yang dari tadi ngadep komputer angkat bicara, kali ini menatap saya dan Akbar: “Kok royal amat, banyak duit cah ndableg iku?”
“Tidak royal sebetulnya, cuma dia memang suka mikir sesuatu yang temannya sering lalai,” jawabku.
“Contohnya?” Tanya Mamat penasaran.
“Contohnya makan sate ayam. Kami semua kan suka lalai dengan makanan enak,” jawabku sambil tertawa. (Bersambung) [HW]