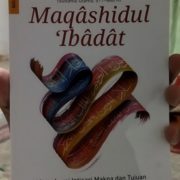Sinar mentari mulai tampak melewati celah-celah pepohonan. Para burung telah berangkat untuk menjemput rezeki yang telah ditakdirkan Tuhan. Wahid yang baru selesai menyapu pelataran rumah, kini tengah mengistirahatkan diri sebentar. Ia duduk meluruskan kaki, menghirup udara segar pagi hari. Sejenak Wahid menutup mata, pikirannya kembali teringat akan berita duka seminggu lepas. Kiai Ali, sosok yang telah banyak membimbing Wahid dalam agama, sekarang telah tiada.
Ingatan tersebut membuat hati Wahid sesak, seolah ia belum siap kehilangan guru yang sangat ditaatinya tersebut. Air mata Wahid pun tak terbendung. Ia menunduk menyembunyikan wajah sedihnya dari dunia. “Maafkan saya, Kiai!”, Wahid bergumam dalam hati. Ucapannya tersebut seakan menyiratkan penyesalan yang begitu dalam. Meski demikian, Wahid berusaha untuk menguatkan diri. Bagaimana pun ia harus tetap melanjutkan hidup meski sosok yang selama ini membimbingnya telah dipanggil oleh Allah swt.
*****
Dua bulan terlewati sudah. Wahid sekarang menjadi ustaz yang mengisi kajian keagamaan di surau dekat rumahnya. Setiap bakda maghrib, masyarakat sekitar datang ke surau untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Wahid. Kitab yang dikaji oleh Wahid adalah kitab Nashaih al-‘Ibad karya Imam al-Nawawi. Durasi pengajiannya tidak lama, setiap terdengar azan isya’ dari surau lain maka pengajian akan diakhiri. Hal ini membuat masyarakat kerasan untuk selalu mengikuti pengajian Wahid tersebut.
Inisiator dari pengajian bakda maghrib tersebut adalah Wahid sendiri. Saat itu ia teringat bahwa Kiai Ali berpesan kepada seluruh anak muridnya supaya mereka menjadi tangan panjang para ulama dalam menyebarkan syiar Islam. Berangkat dari hal itu, Wahid pun mengajak masyarakat sekitar surau untuk berembuk terkait pengajian bakda maghrib. Masyarakat sendiri banyak yang setuju dengan hal itu. Pasalnya, kegiatan di surau telah terasa mati selama satu tahun terakhir. Oleh sebab itu, mereka ingin kembali menghidupkannya.
Pengajian bakda maghrib itu tidak terkesan kaku, tapi masyarakat yang ada di surau menyimak dengan khusyuk. Sesekali Wahid memberi kesempatan masyarakat untuk bertanya, barangkali ada beberapa hal yang belum dipahami. Mulanya masyarakat sebatas mendengarkan apa yang disampaikan Wahid. Namun, lama-lama mereka pun akhirnya mau membuka diri untuk bertanya pada Wahid.
Belum genap satu bulan menjadi ustaz, Wahid kini justru menjadi sosok yang selalu menjawab segala pertanyaan. Pernah di satu kesempatan Wahid menjawab pertanyaan soal fikih, padahal sebenarnya ia belum paham betul dengan masalah yang ditanyakan tersebut. Lama-lama Wahid berubah jadi sosok yang terlampau banyak berbicara dan menjawab. Bahkan, tak jarang Wahid memberikan jawaban yang terlalu lebar, yang keluar dari konteks pertanyaan.
Perubahan kepribadian Wahid tersebut disadari oleh masyarakat. Mereka kini justru merasa agak risih dengan sikap Wahid yang seperti itu. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat kerap membicarakannya.
“Ustaz Wahid sekarang beda, ya!? Dia seperti sudah bukan dirinya yang dahulu”, celetuk Kang Fahim sambil mengupas kacang rebus.
“Iya. Padahal dulu dia orang yang proporsional dalam menyampaikan ajaran agama. Tapi sekarang, dia terkesan telah melampaui batas”, sahut Kang Amir menyetujui.
“Terus gimana, Kang? Masih mau ikut ngaji bakda maghrib di surau?”, tanya Kang Abdul.
‘Ya…..sebenarnya aku sendiri udah nggak terlalu nyaman. Tapi kalau kita semua nggak ikut ngaji lagi, nanti takutnya masyarakat lain juga pada nggak ikut ngaji”, Kang Amir mempertimbangkan.
“Ya sudah! Kalau memang begitu, mau-nggak mau kita tetap ikut ngaji bakda maghrib. Yah…..hitung-hitung sebagai usaha kita meramaikan surau kembali”, Kang Fahim memberi kesimpulan.
*****
Di sisi lain, Wahid merasa bahwa dirinya telah menjalankan pesan dari kiainya. Dia menilai dirinya telah berhasil menjadi tangan panjang para ulama. Wahid menganggap bahwa dialah yang kini mengambil peran sebagai pembimbing masyarakat. Namun, di satu kesempatan Wahid berkonflik dengan beberapa orang perkara toa surau.
“Bapak-bapak sekalian! Saya berniat untuk menambah dua buah toa lagi. Selain itu, saya juga memiliki keinginan untuk meninggikan posisi toa. Oleh sebab itu, saya memohon kepada bapak-bapak sekalian untuk memberikan sedekah dengan nominal Rp200.000,00 guna mewujudkan hal tersebut. Semua ini tidak lain bertujuan supaya syiar Islam yang berasal di surau ini dapat menyebar lebih luas lagi”, ucap Wahid tanpa meminta sedikit pun pendapat pada peserta musyawarah lain.
Orang-orang yang hadir di sana terdiam. Raut wajah mereka tampak menyiratkan ketidaksetujuan. Keheningan tersebut lantas terpecah oleh salah seorang peserta musyawarah yang mengangkat tangan.
”Mohon maaf, Ustaz! Bukannya saya tidak mau bersedekah. Hanya saja, bila melihat kondisi yang ada, tampaknya keinginan Ustaz tadi belum waktunya untuk diwujudkan saat ini. Dua buah toa yang telah terpasang di surau ini rasanya masih sangat cukup untuk menjangkau masyarakat sekitar. Selain itu, tak jauh dari sini juga sudah ada beberapa surau lagi”, Kang Amir mencoba berpendapat dengan santun.
Peserta musyawarah lainnya mengangguk-angguk. Mereka lantas bersahut-sahutan mengiyakan pendapat Kang Amir tadi, berusaha meyakinkan Wahid.
“Tidak! Tidak ada alasan untuk menolak niat saya ini. Bagaimana pun syiar Islam harus lantang disebarkan”, Wahid menolak mentah-mentah pendapat Kang Amir yang disetujui oleh mayoritas peserta musyawarah itu.
“Tapi Ustaz…”
“Maaf! Keputusan sudah bulat. Tidak ada lagi pertimbangan lain”, Wahid menepis.
Musyawarah malam itu lantas diakhiri. Namun, ia justru menyisakan keterpaksaan di hati mayoritas peserta musyawarah. Meski demikian, Wahid sama sekali tak merasa bersalah. Ia justru merasa bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar, tegas dalam menegakkan kebenaran yang diyakininya.
Saat telah sampai di rumah, entah mengapa Wahid merasa sangat mengantuk. Ia pun bergegas menuju tempat tidur untuk melelapkan diri. Tak butuh waktu lama bagi Wahid untuk menidurkan kesadaran dirinya. Dalam tidurnya tersebut, Wahid mendapat mimpi yang tak pernah dialaminya selama ini. Kiai Ali mendatangi dirinya melalui alam mimpi.
“Kiai! Bagaimana keadaan Kiai sekarang?. Sebelumnya mohon maaf, Kiai! Saya hendak memberitahukan bahwa saya telah menjalankan pesan Kiai supaya kami, para santri, menjadi penerus para ulama”, tutur Wahid yang sangat bahagia karena dapat bertemu dengan Kiainya.
Kiai Ali terdiam, tak menjawab apa pun. Wahid pun tak lagi mengucap apa-apa, ia menunggu respons dari Kiai Ali. Sejenak kemudian Kiai Ali menarik napas dalam, bersiap untuk menuturkan kalimat.
“Tidak, Wahid! Ada satu pesanku yang telah kaulupakan. Cobalah mengingatnya!”
Belum sempat Wahid merespons, sosok Kiai Ali lantas menghilang dari hadapannya. Meninggalkan satu pertanyaan besar pada diri Wahid.
Mimpi barusan lantas membuat Wahid terbangun. Ia masih ingat detail mimpi tersebut. Guna mengikis kegelisahannya, Wahid pun mengambil air wudlu untuk kemudian mendirikan sholat malam. Selesai sholat, Wahid kembali memikirkan mimpinya. Ia terus berusaha mencari pesan Kiai Ali yang dilupakannya. Hasilnya masih nihil, ia merasa telah melaksanakan seluruh pesan kiainya tersebut.
Di malam berikutnya, Wahid kembali mendapat mimpi yang sama. Kiai Ali tetap mengatakan bahwa ada satu pesan darinya yang dilupakan oleh Wahid. Wahid pun sama, ia masih tak menemukan pesan apa yang telah dilupakannya. Hingga di hari ketujuh Kiai Ali pun berkata, “Wahid! Ini terakhir kali aku mendatangimu. Oleh sebab itu, aku sangat berharap kau dapat menemukan pesanku yang telah kaulupakan.”
Meski telah satu minggu diingatkan kiainya, Wahid tetap tak mengingat pesan mana yang telah dilupakannya. Akhirnya, kedatangan terakhir Kiai Ali dalam mimpi Wahid hanya menyisakan pertanyaan yang tak pernah ada jawabannya bagi Wahid. Dan, Wahid pun tetap menjadi orang yang sama. []