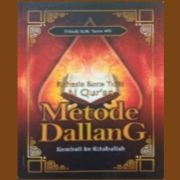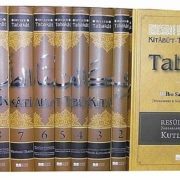Sebagai kaum beragama, manusia ditugaskan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ajaran agamanya. Berangkat dari sini, manusia kemudian memiliki tuntutan untuk mempelajari pendidikan agama, agar mampu menjadi insan yang senantiasa berjalan sesuai dengan aturan agamanya.
Namun dalam perkembangannya, setiap jenis ilmu yang dipelajari mengalami pengkotak-kotakan sesuai dengan spesifikasinya. Ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dinamakan Matematika, ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup disebut dengan Biologi, ilmu yang membahas tentang Ketuhanan biasa disebut dengan Ilmu Kalam/Tauhid/Teologi, ilmu yang mendalami hukum Islam dinamakan Fikih, ilmu yang menelisik tentang metode pengambilan hukum Islam dinamakan dengan Ilmu Ushul Fikih, dan beberapa cabang keilmuan lain dengan tema kajiannya masing-masing.
Dari pembagian ini kemudian muncul kategorisasi yang lain lagi, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Pengelompokan ini masih sering dijumpai di beberapa lembaga pendidikan (tidak semuanya). Fakta ini kemudian didukung dengan menerapkan jargon “ilmu agama lebih penting daripada ilmu umum”, atau “ilmu agama harus lebih dulu dipelajari ketimbang yang lainnya”, dan atau memberikan porsi besar untuk ilmu agama dan porsi kecil untuk ilmu umum.
Konsep ini sebenarnya masih ambigu. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan ilmu agama? Apa pula yang disebut dengan ilmu umum? Bagaimana membedakan keduanya? Apa indikator yang bisa dijadikan tolok ukur untuk keduanya?
Selama ini, ilmu agama ‘seolah’ diidentikkan dengan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan kepercayaan, ibadah ritual, dan ibadah sosial (muamalah). Contohnya seperti Tauhid, Fikih, Ushul Fikih, Qawaid Fiqhiyyah, Tasawwuf. Sekalipun ada pula tema-tema lain yang masuk dalam kategori ilmu agama, misalnya dalam tataran kaidah bahasa Arab adalah Nahwu, Sharaf, Balaghah, Manthiq, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum mempelajari ilmu Manthiq. Ilmu tentang bahasa Arab ini dimasukkan ke dalam ranah ilmu agama karena memang sumber otoritatif Islam tertulis dalam bahasa Arab. Akan tetapi, ilmu-ilmu lain seperti misalnya Biologi, Fisika, Kimia, Sosiologi, Antropologi, Bahasa Indonesia, Matematika, Ekonomi, dan keilmuan-keilmuan lain yang tidak dikaji dari kitab berbahasa Arab seolah dimarginalkan dari tipologi ilmu agama.
Paradigma seperti ini sangat ironi sekali. Sebab yang justru nampak adalah pengertian agama yang sangat sempit dan jauh dari spirit yang progresif. Bagaimana bisa kita mengatakan Biologi adalah ilmu umum, sementara Al-Quran berbicara tentang proses penciptaan biologis manusia secara jelas dan bahkan diulang-ulang di beberapa ayat? Salah satunya yang menceritakan peristiwa terjadinya embrio manusia dan perkembangannya adalah QS. Al-Hajj:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
Bagaimana pula kita bisa mengatakan matematika bukan ilmu agama, sementara dalam ilmu faraidh atau hukum warisan juga membutuhkan ilmu matematika? Bagaimana pula kita mengatakan sosiologi, antropologi sebagai ilmu umum yang seolah-olah tidak memiliki korelasi dengan agama? Sementara banyak sekali perintah untuk manusia agar saling mengenal satu sama lain, lintas agama, suku, budaya, dan tradisi?
Dikotomi ini sudah seharusnya dihilangkan dari lembaga pendidikan. Karena justru akan memperburuk citra Islam yang seolah hanya menganggap ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang dipelajari dengan merujuk kitab berbahasa Arab.
Kiranya kita perlu menengok dan belajar sejarah kembali. Kita memiliki ulama/ilmuwan yang menjadi pionir lahirnya ilmu-ilmu yang saat ini dikategorikan sebagai ilmu umum. Misalnya Ibnu Sina dengan kitab monumentalnya yang berjudul Al-Qanun fi At-Thib (Kitab Kedokteran). Jika berbicara mengenai ilmu kedokteran, tentu saja banyak sekali bagian-bagian di dalamnya; kesehatan manusia, proses reproduksi, jenis-jenis penyakit, bagaimana tata cara penyembuhannya, yang sesungguhnya mencakup beberapa prinsip dalam Maqashid Syariah, yaitu hifz an-nafs (menjaga diri/jiwa raga), hifz al-aql (menjaga akal). Lantas, masihkah kita mau menamakan ilmu biologi termasuk ilmu umum?
Begitu juga dengan keilmuan lain yang justru para sarjana Muslim abad pertengahan banyak memberikan kontribusi untuk peradaban Islam. Seperti Al-Khawarizmi dengan rumus Al-Jabar, Umar Khayyam sebagai perintis Geometri Analitik, Al-Farghani, Al-Battani, At-Thusi sebagai ahli astronomi. Ibn Al-Haitsam, Al-Biruni, Al-Khazini yang menaruh perhatian besar terhadap Fisika. Jabir bin Hayyan, seorang sufi yang ahli Kimia, dan masih banyak ulama-ulama lain yang menjadi kontributor terbesar dalam kekayaan khazanah intelektual Islam.
Melihat realitas sejarah yang demikian, seharusnya kita tidak perlu lagi mendikotomikan disiplin keilmuan dengan ilmu agama dan ilmu umum, apalagi sampai mengatakan ilmu dunia dan ilmu akhirat yang justru akan mempersempit agama itu sendiri. Karena semua ilmu adalah ilmu. Jika pun diksi agama dipaksakan, maka semua ilmu adalah ilmu agama. Hanya saja yang membedakan adalah tingkatannya; primer, sekunder, tersier.
Primer misalnya ilmu yang berkaitan dengan akidah atau ushul ad-din (ajaran pokok agama). Hal ini sekaligus penegasan bahwa yang utama perlu ditanamkan dalam setiap jiwa manusia adalah kepercayaan terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang transenden (ghaib). Setelah itu kemudian dilanjutkan kepada tahap sekunder, misalnya ilmu yang berkaitan furu’ ad-din (cabang ajaran agama) atau yang biasa disebut dengan syariah. Syariah di sini sebenarnya bukan hanya sekedar praktik ibadah individual atau ritual keagamaan saja, tapi juga ibadah sosial. Termasuk di dalamnya tata cara bermasyarakat, memahami kondisi sosio-kultural masyarakat, hingga pada tahap penerapan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, namun juga kontekstual. Sebenarnya konteks fikih yang kita pelajari pun demikian. Sebab kitab-kitab fikih sebagian besar memuat tentang muamalah (tata cara bersosialisasi).
Tersier misalnya ilmu-ilmu pelengkap yang berfungsi sebagai penyempurna atas keduanya. Banyak sekali tentunya ilmu-ilmu yang masuk kategori ini. Misalnya di era milenial sekarang adalah ilmu teknologi informasi, yang di dalamnya memuat tata cara membuat konten sosial-media yang menarik dan dijadikan sebagai sarana dakwah, meliputi tema, setting, alur, design, dan hal-hal lainnya. Sebab tidak bisa dipungkiri, kesemua itu sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman.
Menurut hemat penulis, ketiga tipologi di atas sebenarnya tidak bersifat paten dan bisa saja berubah. Kategori tersier mungkin saja bisa menjadi sekunder, apabila situasi dan kondisi menuntut demikian. Begitu pula halnya dalam kategori Maqashid Syariah yang bersifat fleksibel tergantung kondisi yang mengitarinya, yang meliputi dlaruriyyat (sangat perlu/urgen), hajiyyat (kebutuhan), dan tahsiniyyat (penyempurnaan/pembaharuan/perbaikan). Tapi tentu saja tingkatan atau kategori keilmuan yang penulis tawarkan di atas tidak sama dengan tingkatan yang ada dalam Maqashid Syariah ini, karena konteks pembahasan dan cakupannya berbeda.
Ala kulli hal, tingkat urgensitas ilmu yang paling primer adalah yang berkaitan dengan ushul ad-din (ajaran pokok agama). Dan tidak perlu lagi memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, sebab esensi ajaran Islam adalah menuntut ilmu. Al-Quran menjelaskan dalam QS. Al-Mujadilah 11:
یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا قِیلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُوا۟ فِی ٱلۡمَجَـٰلِسِ فَٱفۡسَحُوا۟ یَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِیلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ یَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمۡ وَٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَـٰتࣲۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیر
Bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Ilmu di sini sifatnya universal. Semua cakupan ilmu masuk di dalamnya.
Begitu pula di dalam hadis yang sudah sangat famous di kalangan para pelajar:
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد
اطلبوا العلم ولو بالصين
Tidak ada lafadz al-ilm ad-din atau al-ilm asy-syar’i dalam redaksi hadis tersebut. Dengan demikian jelas bahwa esensi perintahnya adalah menuntut ilmu, apapun jenis keilmuannya.
Definisi ilmu tidak perlu dipersempit lagi dengan hanya menonjolkan diksi agama, karena akan berimbas pada pemahaman keilmuan yang sempit, dan bahkan justru akan tampak mempersempit agama itu sendiri. Agama yang seharusnya mencakup semua lini kehidupan manusia, jangan dibatasi hanya dengan menambahkan kata agama setelah kata ilmu. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber otoritatif Islam bersifat universal, yang sesungguhnya sudah mencakup semua ilmu-ilmu yang senantiasa dinamis. [HW]