Lupakan dulu tukang masker naik haji, ceramah ngawur tentang haramnya musik, mualaf pseudo ustaz dan ulama picisan pengasong intoleransi, kali ini kita ngopi ke Benua Biru.
Pada abad pertengahan di Eropa—yang lazim disebut dark age (zaman kegelapan)—teologi selalu tampil sebagai “sang domina”, pengangkang filsafat sekaligus pendera sains. Tentu Anda masih ingat bukan, bagaimana Galileo dihukum mati karena pandangannya bertentangan dengan fatwa gereja? Praktis, para filsuf dianggap anti agama, anti doa, musuh agama dan memang filsafat itu bukan mantra sekaligus doa.
Sebagaimana tidak semua orang butuh filsafat, tidak setiap orang pula butuh agama. Mengapa? Hidup tak selalu berkorelasi dengan keduanya. Apa sebab? Tiap manusia tidak sama, tiap tempurung pasti berbeda. Sains tidak butuh agama, dan agama tidak memerlukan sains untuk diimani serta dijalani pemeluknya. Sementara itu, filsafat (sebagaimana agama) ada kalanya malfungsi, tidak bekerja, ada kalanya sangat berguna.
Namun demikian, manusia membutuhkan keduanya. Fritjof Capra menambahkan dalam magnum opusnya “The Tao of Physic”, bahkan manusia membutuhkan mistik untuk menjalani hidupnya. Terbukti, mitos cukup berperan membentuk peradaban manusia, terutama mitos kecantikan.
Benarkah filsafat musuh agama? Bukankah telah banyak tuduhan murahan dan sinisme kampungan bahwa filsafat merusak seluruh korpus agama, salah satunya yang digaungkan oleh kiblat kaum puritan alias Wahabi, Ibnu Taymiyah? Bagaimana meluruskan pandangan ini?
Telah sejak lama Immanuel Kant, dengan agnotismenya, menjaga batas-batas nalar dan agama justru secara rasional dan dari perspektif nalar murni. Akan tetapi, GWF Hegel malah menghancurkan dan menghapus demarkasi itu, dan tak lama kemudian, Soren Kierkegaard tetap mempertahankan batas-batas iman dan rasio itu justru dari sisi iman Kristiani. Ada apa gerangan atau gerangan yang mengada-ada?
Memang, hubungan filsafat dengan teologi, atau setidaknya rasio dengan wahyu, tak lain adalah topik klasik tentang kawin-cerai di satu sisi dan perselingkuhan di sisi lain. Peran filsafat sebagai ancilla theologiae bagi gereja abad pertengahan adalah catatan hitam sejarah bagi filsafat, jika bukan lubang hitam bagi agama, sampai kelak zaman pencerahan datang dengan pongahnya sains dan jumawanya teknologi.
Acapkali, filsafat dituduh sebagai sumber ketidakpercayaan terhadap apapun selain dirinya, biang keladi relativisme nilai-nilai dan bahkan nihilisme akut terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Relatif karena kebenaran memiliki lanskapnya sendiri dalam filsafat, nihil karena agama tak cukup menjadi solusi dalam hidup yang kompleks. Meskipun tentu saja tuduhan gerombolan Wahabi dan kaum puritan tidak secerdas itu. Yang paling penting bagi para Wahaboy, ormas pentungan, parpol penjual agama, kaum monaslimin dan sebangsanya, tudingan haram dan kafir dulu, bid’ah dan syirik dilayangkan dulu, urusan lain belakangan. Toh nanti ada juragan-juragan yang mau kasih nasi bungkus.
Sementara gereja terus mewaspadai krisis iman akibat filsafat, mazhab-mazhab utama dalam filsafat Barat malah mencurigai penyusupan teologi ke dalam argumentasi-argumentasinya.
Meski terlalu lantang, aliran-aliran filsafat itu ingin meninggalkan metafisika dan pada gilirannya teologi juga. Ini semacam dendam sejarah dari rasio selama kekang abad pertengahan membelenggu di bawah kendali oknum otoritas gereja. Adakah ini sedang de javu di Indonesia pasca formalisme agama merebak di setiap denyut kehidupan?
Di sisi lain, karena para oknum pemangku agama semakin antipati filsafat, agama kian mengalami radikalisasi, kian luntur keluas-muliaannya, semakin banal cinta-kasihnya. Walhasil, krisis rasionalitas kaum beragama di abad pertengahan itu menyebabkan puritanisasi dan kekerasan atas nama agama hingga era revolusi industri 4.0 ini. Nggak percaya?
Tengok saja menjamurnya uspal (ustaz palsu), ulama karbitan dan mualaf-mualaf mendadak dai satu-dua dekade terakhir: mencaci-maki agama lama, cari makan di agama yang baru, begitu ceramah teriak-teriak layaknya makelar terminal zaman Orde Baru. Kualitas mereka, karena memang karbitan, lahir dari kontes dai televisi dan ajang-ajang pencarian bakat bau kentut lainnya, maka para usdak (ustaz dadakan) itu harus jual agama, jualan kafir-syirik-bid’ah-takhayul-khurafat, karena memang ilmu tidak mereka punya.
Ini pula yang menjadi salah satu penyebab utama yang membumihanguskan sebagian negara Timur Tengah dan belakangan menyeruak mengemuka di Negeri kita. Semua berasal dari krisis akal sehat. Dampaknya, beragama tanpa akal ala ormas radikal dan paguyuban nasi bungkus alumni Monas. Jakarta telah manuai hasil dari jualan isu SARA dengan memilki gubernur maniak ngeles, ahli tata kata, bukan tata kota! Itu pun masih dibela mati-matian oleh pendukungnya meski tak becus kerja.
Bahkan, gerombolan cuti nalar permanen yang istikamah dengan kebebalan dan bangga dengan defisit otaknya serta-merta secara serampangan menawarkan konsep negara khilafah sebagai solusi bagi segala persoalan hidup. Bukankah sebaiknya cacat logika dan krisis akal sehat stadium 4 itu diobati terlebih dahulu sebelum berbicara tentang negara? Miskin solusinya kerja, dungu solusinya belajar, jomblo solusinya menikah, bukan khilafah!. [HW]
Bersambung…




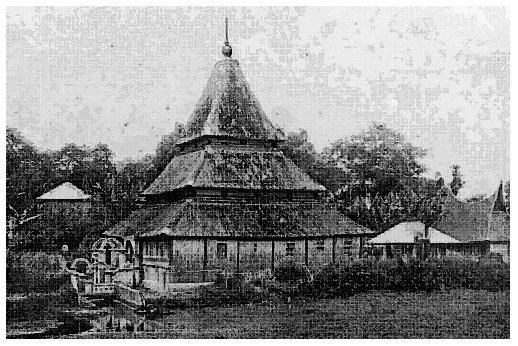



















[…] kita semua akan mengikuti kelompok takfiri yang ditimpa musibah pemikiran ataukah kita mengikuti Nabi […]
[…] dan kesadaran mereka tentang karakteristik ajaran Islam yang memang tidak memisahkan antara agama dan negara. Bahkan sejak dasawarsa 1980-an, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial […]
[…] kepentingan dari mengangkat pemimpin dalam Islam adalah menegakkan Agama Islam serta mengarahkan perpolitikan sebuah negara agar tidak melewati batas syariat, kepentingan […]