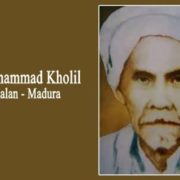Apa yang membuat seorang sukses dalam suatu bidang tertentu, apakah bakat yang ia miliki? Atau apakah garis-darah yang ia punya yang berasal dari darah biru lalu lantas membuatnya lekas cepat dalam menguasai hal tertentu? Atau, apakah bakat alamiahnya lah yang justru membentuknya?
Namun bila hal-hal di atas kita amini sama sekali bersama dengan itu tanpa kita pikirkan lebih jauh. Lalu bagaimana nasib mereka yang terlahir—tanpa maksud diskriminasi—tanpa bakat, mampukah mereka mahir dan profesional dalam bidang tertentu pula? Layaknya mereka yang di atas tadi.
Kadang, kita terlalu sepakat dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya teruji secara klinis dan kuat. Dan yang lebih parah, kesepakatan tersebut turut disebarluaskan tanpa tanggung jawab moral sedikit pun. Miris memang!
Dalam cerita klasik: satu ketika, seorang pemuda diberi tantangan oleh ayahnya untuk memecahkan sebuah batu yang ukurannya setengah badannya. Ia yang masih dalam usia produktif pun menerimanya yakin, bahwa dirinya dapat dengan mudah memecahkannya atau minimal meskipun tak begitu mudah—mungkin—cuma butuh barang sepuluh atau lima belas pukulan agar batu dapat terbelah.
Sang ayah memberinya gada dan mempersilakan; si pemuda pun menerima dengan semangat, antusias dan dengan senyum yang terurai di bibirnya cerah.
Ia lantas menunaikan pukulan pertamanya yang diawali tarikan nafas sambil-lalu ditahan di perut agar dapat menghempas kuat. Pukulan pertama ditunaikan, namun si batu masih bergeming seolah ia hanya tersapu angin sayup-tipis. Pukulan kedua kembali digedorkan dengan kekuatan yang sama, namun itu berbanding lurus dengan hasilnya. Pukulan ketiga pun langsung ditunaikan tanpa pikir panjang, tapi kondisi masih tak berubah. Ia lantas memukulkan gadanya lebih kuat berulang kali sampai terhitung lima belas kali—sesuai bayangannya di awal—akan tetapi si batu cuma terkikis sedikit, seolah ia hanya dihantam menggunakan martil.
Pemuda itu lantas menegakkan gadanya dengan besi berada di tanah untuk menyangga dirinya sambil mengusap peluh yang mulai keluar. Napasnya tersengal, irama jantungnya mulai menaikkan frekuensi, dan tubuhnya pun mulai panas.
Sang ayah hanya menyaksikan sambil memberi semangat yang dibungkus senyum kecil berjarak lima belas meter dari dirinya.
Ia kembali memukul, lebih kuat dan terus menerus, konstan, dan sampai lima puluh kali—dalam hitungan ayahnya. Namun batu itu hanya pecah sebesar buah salak, ia pun mendengus serta mulai gusar. Dan memikirkan cara atau teknik memukul seperti apa yang efektif dan efisien agar dapat membuat kekohan batu itu musnah sehingga ia bisa pecah bahkan kalau bisa menjadi berkeping-keping.
Ia mengganti posisi, memukul dengan cara sedikit memiringkan badan dari yang semula lurus tegak dan ancang-ancang gada di atas kepalanya pun diubahnya dengan gada dari samping dan posisi membungkuk. Pukulan dihempaskan dengan kuat, sambil mengerang, melambangkan kegeraman yang lahir karena si batu tak kunjung pecah juga. Namun nihilisme masih menjadi hasil yang ia saksikan. Hingga pukulannya yang ke seratus dua kali—dalam hitungan ayahnya—ia tak kunjung mampu memecahkan batu tersebut selain cuma merompalkan sebesar dua buah salak saja. Mengecawakan sekali, pikirnya.
Ia lantas terduduk, dan lalu membaringkan tubuh sejajar dengan tanah. Membuka mulut lebar, memejamkan mata karena kefrustasian rupa-rupanya menyergap dirinya mendapati begitu rupa susah-payahnya untuk memecahkan batu tersebut. Padahal prasangkanya awal, ia—mungkin—hanya butuh lima belas kali untuk memecahkannya, tapi faktanya jauh di luar prasangkanya.
Melihat si anak menyerah, sang ayah pun menghampiri lalu menanyakan apakah ia masih memiliki minat buat melanjutkan tantangan tersebut? Yang lalu dijawab spontan menggunakan gelengan kepala-menyerah sudah. Sang ayah mengulurkan tangan, membantunya duduk lalu memberinya minum supaya kesegaran merambat di dirinya.
Sang ayah pun mengapresiasi upaya keras anaknya: sampai bermandikan keringat. Betapa kuat usaha si anak demi dapat menunaikan tantangannya, meskipun hasilnya di luar dugaan—si anak.
Sang ayah lalu meminta izin meminjam gadanya sambil-lalu meminta izin pula untuk memukul batu tersebut. Dengan rasa kecewa, si anak pun menyerahkan gada, menganggukkan kepala—menyesali kegagalannya—sembari menduga apakah sang ayah mampu memecahkan batu tersebut, padahal usianya sudah berambut putih sekujur kepala dan apabila berjalan pun seolah nyaris ambruk disapu angin.
Tanpa bercakap panjang, sang ayah mengambil ancang-ancang, menarik nafas dalam-dalam, menyimpannya di perut, lalu menghempaskan gada sekuat tenaga yang ia punya—di sisa-sisa usia tuanya. Pukulan pertama ditunaikan, si batu masih tetap. Lalu disusul pukulan kedua, dan tak lama disusul pukulan ketiga. Krak…bunyi terdengar jelas oleh keduanya, dan memecah suasana batin si anak yang lantas membuatnya kaget menyaksikan bahwa si batu pecah menjadi dua, tepat seperti yang ia lihat.
Sang ayah pun tersenyum lembut, si anak ternganga mendapati kejadian yang sulit—baginya—untuk dipercaya. Sangat mengejutkan memang, hal itu terjadi. Sang ayah lantas menghampirinya, mengambil sikap jongkok di depannya sambil mengatakan bahwa sebenarnya bukan karena dirinya—sang ayah—yang hebat dapat memecahkan batu tersebut, namun itu lebih karena sudah didahuluinya—si pemuda—memukul sampai seratus dua kali. Tak hanya di situ, ia lantas mengimbuhi bahwa sejatinya hanya butuh pukulan seratus lima kali untuk dapat membuat batu tersebut pecah.
Si pemuda mengangguk paham dengan penejelasan ayahnya. Ia hanya kurang sabar dan gigih dalam melakukan perbuatannya sehingga ia malah menyerah sebelum hasilnya menjadi kenyataan. Andai ia sedikit saja lebih sabar, mungkin hasilnya lain.
Pembaca yang budiman, mungkin kita kerap terjebak pada pernyataan bakat yang—lagi-lagi—rasa-rasanya menjadi musuh terbesar manusia untuk bertindak. Dan hal itu pada akhirnya bukan cuma menjebak, namun juga membunuh karakter manusia dalam kehidupannya. Ia lantas enggan melakukan suatu aktivitas apa pun secara konsisten karena minder dengan satu kata bernama ‘Bakat’ itu tadi yang mengendap pekat di pikirannya.
Hal demikian perlu kita buang jauh-jauh bahkan bila perlu kita bunuh—sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Sebab meskipun kita mengakui kosa kata tersebut ada, namun di saat yang sama betapa pun kita tidak dianugerahi bakat spesifik, mestinya dapat disadari bersama bahwa kita masih memiliki senjata ampuh bernama ‘Minat’, kegigihan, keuletan yang dapat mengantarkan kita mahir dalam bidang tertentu. Sehingga kita tak cuma bisa memecahkan batu yang keras seperti kisah di atas, namun juga dapat meremukkan batu kebodohan dalam diri dan kita pun menjadi pribadi yang arif serta santun.
Lebih jauh, kita sangat jamak mendengar sebuah peristiwa—juga tutur klasik selain di atas—di mana tetesan air pun dapat menggerus batu hingga membentuk ceruk lebar, dalam kondisi tetesan yang terus menerus. Sebagai manusia yang berakal dan berbudi, mustahil rasanya bila kerja keras tak mebuahkan buah sama sekali. Tak mungkin juga bila satu aktivitas tertentu—semisal: menulis, memasak, melukis, menggambar, memahat—yang dilakukan berulang kali tak melahirkan hasil yang nyata sama sekali. Karena pada dasarnya: hasil tak akan menghianati proses. Maka pada akhirnya, perangkat itu bernama kegigihan yang dapat menjadi senjata ampuh bagi siapa pun.
Tabik, salam. [HW]