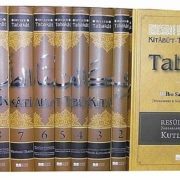Merdeka belajar datang dengan sejumlah janji. Meredefinisikan ulang arti menjadi pendidik, peserta didik, sekolah, dan seperti biasa menggunakan hak politiknya untuk mengganti kurikulum lagi. Apa yang disebut guru, bukanlah jenis pekerjaan yang terlindungi oleh paradigma ekonomi global. Misal tren bahwa semua hal harus terdigitalisasi. Firmannya adalah Guru harus bisa menyesuaikan diri dengan beragam ketidakpastian dari industri digital yang terus bergerak tanpa henti. Untuk tidak mengatakan sedang terombang ambing oleh jenis industri yang belum tentu bisa melindungi pelaku ekonomi sekalipun.
Guru bukan entitas yang utuh. Ia adalah kreator konten pendidikan, komoditas, target pasar, dan konsumen dari layanan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, guru dituntut untuk memproduksi banyak Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyusun tahapan pengetahuan serta strategi dan langkah-langkahnya. Ia bukan lagi template pengetahuan utuh yang sudah jadi sebagaimana web 1.0, dimana pengetahuan terpajang dan bersifat pasif. Dengan masifnya penggunaan media sosial dan datangnya era Web 2.0, pengetahuan tidak lagi bersifat materil tertutup seperti menggenggam buku, pengetahuan diasumsikan sebagai relasi informasi.
Pengetahuan dianggap ruang berisi informasi yang baru menjadi pengetahuan jika sudah berada dalam sirkulasi jaringan sosial. Dalam dunia internet, pengetahuan berada dalam interaksi. Seperti komentar dalam media sosial. Bayangkan perbedaan flashdisk dengan hardisk. Flashdisk diasumsikan sebagai wadah yang bisa menyimpan data. Sedangkan Hardisk adalah piringan kecil yang berputar melewati read-write head. Informasi dalam hardisk hanya bisa hadir, jika piringan berputar dipanggil oleh read-write head. 010001 001000010 0000111. Jadi, pengetahuan tercipta ‘diantara’ relasi, bukan tersimpan, sebagaimana buku dan perpustakaan. Ruang semacam ini sebenarnya sangat ringkih karena berbasiskan digital, yang pada dasarnya masih mengandalkan energi listrik yang dihasilkan tenaga fosil.
Cobalah matikan listrik, semua janji industri digital hancur berkeping-keping dalam kegelapan. Ironinya, para pemangku kebijakan pendidikan nasional pernah berpidato dihadapan UNESCO bahwa arah pendidikan nasional mengutamakan kesadaran lingkungan dan pentingnya pemanasan global. Sementara tenaga utama industri digital di negeri katulistiwa, yang menebang pohon seluas lapangan bola setiap jamnya, hanya demi tambang penghasil listrik yang dalam proses transportasinya saja mengotori terumbu karang sepanjang Kalimantan dan Pulau Jawa. Agaknya, sindiran Presiden bahwa kesadaran lingkungan jangan hanya ‘bicara saja’ berlaku bagi kebijakan pendidikan dinegerinya sendiri.
Cara kerja mikro ini adalah masa depan cara kerja guru jika dihadap-hadapkan secara langsung dengan industri digital. Ia harus terus berputar tanpa henti, mereproduksi pengetahuan secara terus menerus untuk terus membuatnya ‘hadir’ dalam sirkulasi jejaring informasi internet.
Untuk tidak tenggelam, ia harus mereproduksi konten setiap hari. Ini adalah jenis persaingan yang berlaku diantara pelaku ekonomi digital. Jika guru didorong ke arah tersebut, bukan hanya murid, tujuan pendidikan nasional akan tenggelam karena tidak sanggup mengejar jejak jejaring informasi yang bergerak tidak tentu dan acak.
Ini adalah situasi yang disengaja, bukan tidak terelakan. Pemangku kebijakan pendidikan, yang tidak mampu menghadirkan alternatif, mengamini ketidakmampuan mereka secara taqlid buta. Mereka mengasumsikan bahwa ini adalah masa depan yang benar. Seperti kaum konservatif yang ceramah tentang kebebasan.
Oleh sebab itu, para guru penggerak yang baru saja mengikuti beberapa sesi webinar diwajibkan memposting refleksi yang tidak reflektif. Diakui atau tidak, mereka didorong untuk memposting refleksi pembelajaran, seperti inklusi dan diagnosis namun dengan kata-kata yang sudah disiapkan untuk dibagikan secara masal. Artinya pemangku kebijakan lebih mengkhawatirkan engagement media sosial, sehingga refleksi pembelajaran justru didorong untuk populer dengan cara-cara masal.
Perintah untuk menyebarkan refleksi dalam media sosial pribadi guru ketika mengkuti program semacam ini adalah tanda kurangnya kepercayaan diri pemangku kebijakan ‘guru penggerak’ bahwa apa yang mereka sebut refleksi harusnya adalah bentuk kesadaran. Mereka lebih butuh pembuktian dalam jejak digital. Hal ini menegaskan bahwa laporan keberhasilan refleksi pendidikan lebih bernilai daripada kesadaran reflektif itu sendiri. Para guru bukan tidak menyadari ini. Kepatuhan para guru untuk melaksanakan perintah semacam ini, karena kepatuhan yang vulgar ini tidak bisa membuat mereka sedikit menutupinya untuk mengganti kata-kata reflektif yang telah disiapkan dengan kalimat reflektif itu sendiri.
Selain itu program guru berbagi, yang mirip dengan iklan restoran yang memenuhi spam email juga hanya mengisi ruang-ruang kosong dalam memori awan yang sempit. Setiap guru berbagi , tidak ada editorial atau penjaga kualitas dari program semacam ini. Seolah-olah adalah keriuhan yang dipenuhi akun robotik.
Pada titik ini, apa yang disebut pendidikan sirna, digantikan sekedar konten pembelajaran. Jika penentunya adalah reproduksi, maka guru yang masih setia terhadap arah pendidikan nasional esensial, akan tergerus oleh mereka yang merasa sudah benar dengan tagline ‘merdeka belajar’ dan ‘guru penggerak.’
Pada dasarnya kedua gerakan ini tidak ideologis dan tidak mengijinkan para guru untuk memanggil kembali ruang kritis tempat dimana mereka memikirkan ulang secara serius apa yang disebut filsafat pendidikan. Teknologi pendidikan, sebagaimana fungsinya bergeser menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Beragam tagline lainnya akan muncul menutupi kenyataan bahwa para guru bergerak menjauhi cita-cita pendidikan nasional. Kecuali bahwa para pemangku kebijakan pendidikan kembali menutupinya dengan tagline-tagline baru seperti ‘berpihak pada murid.’ Sungguh merupakan harga yang sangat mahal jika triliunan rupiah anggaraan pendidikan pada akhirnya dibakar hanya untuk melahirkan tagline-tagline pendidikan.
*
Dorongan agar guru melek digital, berkaitan dengan kekhawatiran bahwa profesi ini terlambat untuk ikut dalam sirkulasi media sosial dan memiliki posisi dalam konten pendidikan. Dorongan ini tidak memperdulikan betapa besar kesenjangan antara pemain kakap konten pembelajaran dengan seperangkat teknologi digital tingkat wahid dengan para guru yang masih dijejali berbagai webinar kiat-kiat membuat video pembelajaran. Kesenjangan ini hanya mendorong kuantitas konten pendidikan namun alfa dalam meningkatkan kualitas konten pembelajaran. Alhasil guru hanya menjadi buzzer bagi tema pendidikan yang tersesat, justru, melalui peta jalan pendidikan yang tidak memberikan jalan pendidikan yang sesuai cita-cita pendidikan nasional.
Murid, sudah sejak lama menjadi pusat pembelajaran. Ia adalah subjek aktif. Dalam pengertian Platonian, didalam diri setiap murid terdapat dunia itu sendiri. Mereka diasumsikan memiliki pengetahuan itu sendiri, yang diperlukan dalam pembelajaran adalah menggali potensi yang memang telah ada dalam anak itu sendiri. Demi mempertahankan novelti, kebaruan dalam janji periodik, maka munculah tagline berpihak pada murid. Keberpihakan itu memang penting. Namun keberpihakan pada murid dalam konteks pendidikan nasional dengan keberpihakan pada murid sebagai penerima jasa pelayanan adalah dua hal yang berbeda. Jika dibalik, maka hasilnya akan terbalik-balik. Misal merdeka belajar yang tidak memerdekakan dan guru penggerak yang tidak kemana-mana.
*
Perubahan kurikulum disambut meriah bukan karena kebaruan dan kehebatannya. Namun para guru sudah berpengalaman bahwa jika mereka tidak mengikuti kurikulum yang baru, sebagai bentuk resiko politik, mereka tidak akan menikmati beragam privilige yang hanya disiapkan bagi mereka yang mengklaim menerima konsep baru dari pakar yang anti pakar.
Bukan sekali pemangku kebijakan pendidikan kita mengklaim bahwa para guru sebaiknya saling belajar diantara sesama mereka, dan jangan terlalu mengikuti nasihat para pakar. Nasehat semacam ini benar jika dikatakan oleh guru, namun sebagai sesama pakar, maka sifatnya berubah menjadi persaingan telemarketing.
Padahal, pakar lahir dari pengalaman mereka dalam membaca, mengalami dan meriset. Ironinya, ‘Merdeka Belajar’ dasarnya lahir dari sekumpulan pakar yang merasa lebih tahu arah pendidikan nasional daripada guru itu sendiri. Sebenarnya persaingan antar pakar sah secara pengetahuan dan berfungsi dialektik. Namun mengenyahkan keberadaan pakar pendidikan lain hanya karena tidak sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional adalah cara kasar menyinggirkan pesaing dengan cara membubarkan kompetisi.
Mental semacam ini sudah otoriter sejak dalam pikiran. Bisa disimpulkan, kalimat naif bahwa kurikulum ini boleh dicoba adalah bentuk pemaksaan bahwa kurikulum ini harus diikuti, sedikit atau banyak, jika para guru menolak, mereka akan ditinggalkan.
Jika para guru telah sampai pada kesadaran ini, maka hanya perlawanan yang mampu menghadirkan kemerdekaan dalam tiap mereka. Kehendak untuk melawan adalah nenek moyang dari cita-cita pendidikan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan kekuatan alternatif dalam peta pendidikan nasional untuk terus melawan, bukan sekedar berbeda, namun untuk menunjukan bahwa merdeka belajar hanya bisa dicapai dengan cara merebut kemerdekaannya terlebih dahulu.
Dalam kacamata Hegelian, kondisi semacam ini akan terbentur dengan sendirinya sehingga sejarah akan memperbaiki dirinya sendiri. Namun, para pengikut Hegel lupa, mereka yang akan tergerus sejarah juga berupaya untuk menunda benturan-benturan semacam itu dengan cara memediasi konflik vertikal menjadi konflik sesama (horizontal). Guru akan dipisah-pisahkan sesuai kelas mereka. Baik yang honorer dengan mereka yang sudah sejahtera. Diantara mereka yang kurang sejahtera akan dibagi-bagi kembali sehingga mereka akan bersaing sesama mereka dan melupakan bahwa peta pendidikan dan kebijakan pendidikan, terutama berkaitan nasib guru, akan ditunda secara terus menerus dan periodik.
Tanda-tanda semacam ini sebenarnya sudah terkemuka. Misal janji manis pada hari guru dan kabar buruk di akhir tahun. Atau menutupi kegagalan dengan keberhasilan simbolik. Misal mengklaim keberhasilan dalam mensejahterakan guru dalam bentuk poster, statemen, dan kampanye media sosial bahwa menteri pendidikan yang mereka anggap tanpa cela padahal bukan nabi, berhasil melakukan rekruitmen guru melalui ilusi statistik. Hanya kebodohan masal yang membuat siapapun menganggap 170.000 ribu yang berhasil direkrut pemerintah, bahkan tanpa jaminan pensiun sekalipun dianggap berhasil meskipun yang dijanjikan adalah rekruitmen 1.000.000 guru.
Patut diketahui, bagi mereka yang berharap pendidikan adalah proses kepatuhan masal, perlu menyadari bahwa pembangkangan juga dilahirkan oleh lembaga pendidikan baik sekolah dan Pesantren. Ki Hajar pendiri sekolah swasta Taman Siswa, Syekh Hasyim Asyari pendiri NU pemilik Pesantren non-pemerintah dan KH Achmad Dahlan pendiri sekolah swasta Muhammadiyah, adalah pembangkang daripada sistem pendidikan nasional Pemerintah Kolonial Belanda. Perlawanan dan pembangkangan memiliki sanad yang jelas, begitupun janji manis pendidikan bukan hal baru dalam sejarah. []
Iman Zanatul Haeri,