Dunia anak-anak adalah jagad nirmala adiwarna. Dunia asmaraloka yang kita senantiasa ingin kembali bernostos dan algos alias bernostalgia tiap temaram membekap, saat lindap melilit maupun rona senja menyergap kelelahan kerja dan penatnya hidup. Kerap kali kita bersenandika untuk kembali menjadi bayi lagi, mengatupkan kenakalan pada kasih ibu.
Namun demikian, sedari orok, kita sudah dibentuk untuk mencari kambing hitam. Sebuah permisalan, apabila ada balita jatuh dari sepeda mainan, orang tua mereka lantas memukul sepeda, menyalahkan sepeda, memukul lantai, bukan malah mengedukasi sang anak agar lebih mawas diri dan menyadari bahwa jatuh-bangun itu biasa dalam hidup.
Tengiknya, sekolah melanjutkan serentetan taksa itu dan semakin ugal-ugalan menabalkan kultur kambing hitam ini. Murid dan mahasiswa menjadi sasaran kambing hitam guru, dosen dan orang tua, juga perundungan bahkan pelecehan kakak kelas. Guru diintimidasi kepala sekolah, lantas para kepala itu diteror kepala dinas terkait untuk membuat manipulasi data oleh karena kucing-kucingan mencari celah korupsi dan penyelewengan anggaran.
Ada ujar-ujar lama yang terus berkelindan di sudut-sudut kampus: mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada kaprodi, kaprodi juga takut pada dekan, lantas dekan takut pada rektor, kemudian rektor takut kepada dirjen dan menteri, pada gilirannya menteri takut terhadap presiden, konon presiden takut didemo mahasiswa dan ujung-ujungnya mahasiswa takut kepada ibu kos. Nah, lingkaran takut inilah yang melahirkan kultur bawahan selalu salah dan atasan otomatis benar. Menjilat saat menjadi bawahan dan menindas tatkala menjadi atasan. Tak habis-habislah kambing hitam disalah-salahkan.
Selain kambing hitam, masih ada sederet istilah binatang yang “dipinjam” dan lalu dimiliki secara permanen oleh bangsa manusia, misalnya: kumpul kebo, sapi perah, tikus kantor, kelinci percobaan, lintah darat, buaya darat, ayam kampus, kupu-kupu malam, ulat bulu, bajingan tengik, bajing loncat, gurita bisnis, gurita cikeas, kambing congek, singa betina, singa ompong, jago kandang, gajah bengkak, ular berbisa, serigala cendana, srigala berbulu kambing, bandot tua, kampret, cebong serta belakangan kadal gurun alis kadrun, dan masih banyak lagi. Tak peduli apakah bangsa binatang protes perihal sinisme dan atau sarkasme (dalam konteks bahwa tak jarang binatang lebih baik dari manusia) tersebut. Namun demikian, pada kesempatan ini kita hanya akan membincang soal kambing hitam.
Dahulu, pasca suksesi berdarah dari Demak, Pajang, Jipang dan berlanjut ke Mataram Islam, Panembahan Senopati—untuk menlindungi dan melanggengkan aristokrasinya—sengaja memanggil para pendekar, begawan, resi dan elit kampung untuk ngenger (mengabdi) ke istana dengan iming-iming gelar Ki Gede dan Ki Ageng, mereka diangkat menjadi ASN dan digaji dari APBN untuk meredam gejolak pemberontakan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan politik istana serta demi mendapatkan legitimasi politis manakala Mataram hendak melakukan ekspansi dan aneksasi ke negara-negara tetangga. Ini terus berlanjut sekurang-kurangnya hingga Panembahan Hanyokrowari dan Panembahan Hanyokrokusumo alias Sultan Agung, pahlawan nasional. Tentu, Anda juga bisa menebak bahwa mitos gunung Merapi, wahyu keprabon dan Nyi Roro Kidul tak lain adalah bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan.
Beberapa dekade silam, dalam pembuangannya di Bandaneira, Sutan Sjahrir selalu merenungi peradaban kita di tengah Revolusi Kemerdekaan—ia menulis buku berjudul Renungan Indonesia. Karuan saja, ia sangat prihatin dengan peradaban Timur yang bermental menyembah-nyembah, ngaourancang menunduk sambil pegang ‘burung’, bersikap budak dan memang sebagaimana dituduhkan Belanda, orientalis dan banyak tempurung jahat lainnya, kita ini inlander, candala yang inferior dalam segala hal.
Secara serampangan, kita lantas mengkambing-hitamkan penjajah, terutama saat ini penjajahan modern, penjajahan ekonomi, mental gaya hidup hingga ideologi. Ini semua ulah dari sistem kultur serta manifestasi dari sikap rendah diri alias inferior tadi. Eksesnya, sulit merdeka, sulit beradab, sulit berkembang, dan tentu saja terus menikmati penjajahan dengan berharap siapa tahu kelak masuk surga. Inilah pandangan masokhistik kebanyakan kita. Tentu, tema ini mengundang sekian sawala tak berujung, debat kusir, sebab di sisi lain, muasal bangsa-bangsa Nusantara adalah bangsa besar, penjajah dan penakluk.
Namun demikian, mengejutkan, Sjahrir ternyata memproyeksi bahwa Barat dan Timur akan padam dan lalu kemudian tenggelam sementara peradaban baru akan muncul di tengah belantara penjajahan, dari jenggala ketertindasan, seiring dengan semakin dihargainya setiap manusia berdasarkan kemanusiaannya, oleh karena harkatnya setelah rentetan pengalaman pelik dengan sederet derita dan nestapa pasca perang kemerdekaan lalu diendapkan dalam laboratorium nilai-nilai perjuangan, nuraga dan berbagi rasa senasib sepenanggungan untuk merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Tetapi, mungkinkah ramalan humanis Sjahrir ini adan menjadi nyata tanpa kita membangun revolusi rohani, kejernihan batin, keheningan kalbu, kebeningan budi, keagungan pekerti dan kearifan wiyata? Bukankah mengendapkan gejolak di luar diri dan gelegak di dalam diri sendiri dalam lanskap keindonesiaan dan bingkai kebinekaan tidak pernah selesai hanya dengan kurikulum di sekolah semata—yang jamak kita mafhumi sebagai industri, menjadi dagangan dan sebagian dagelan? Nah, kecerdasan macam apakah yang harus kita cangkokkan kepada anak-anak kita? Tidakkah kita mencium bau busuk sampai ke tulang sumsum bahwa model pendidikan warisan penjajah ini sangat membuka ruang untuk memperjual-belikan guru, murid, kompetensi, bahan ajar dan bahkan gelar? Benarkah produksi masal kambing hitam dimulai dari bangku sekolah, khususnya pasca kolonial?
Ego primordial selalu meniscayakan kambing hitam, entah agama, suku, bahasa dan bahkan (mirisnya) tingkat pendidikan dan strata sosial. Faktanya, justru segala bentuk kesenjangan dimulai dan di sulut para elit: agamawan, politisi, pebisnis, pesuruh partai, ilmuwan menara gading, sosialita, buzzer dan penentu kebijakan lainnya. Cara pandang teknokratis yang mengabaikan jagad nilai semacam ini adalah buah dari pendidikan yang salah, pembonsaian logika sajak di sekolah. Sekurang-kurangnya kita bisa dapati dalam satu dekade ini bahwa guru dan dosen sibuk diperbudak sertifikasi dan polas-poles pemberkasan. Sementara itu guru honorer selalu kena prank dan ghosting. (bersambung) (HNZ)




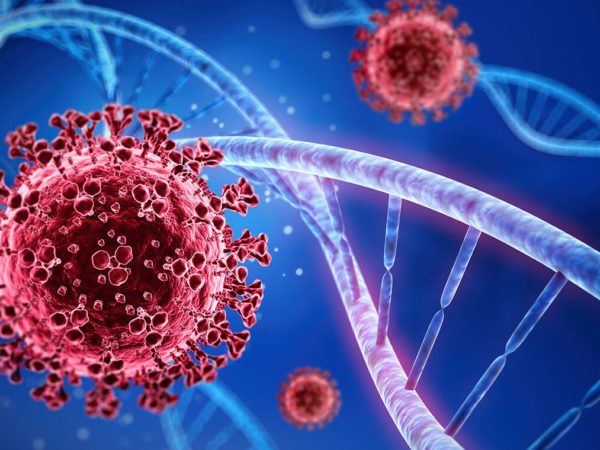









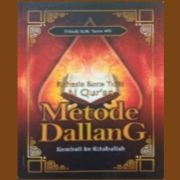

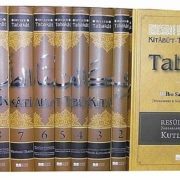







[…] Baca Juga: Muasal Kambing Hitam […]