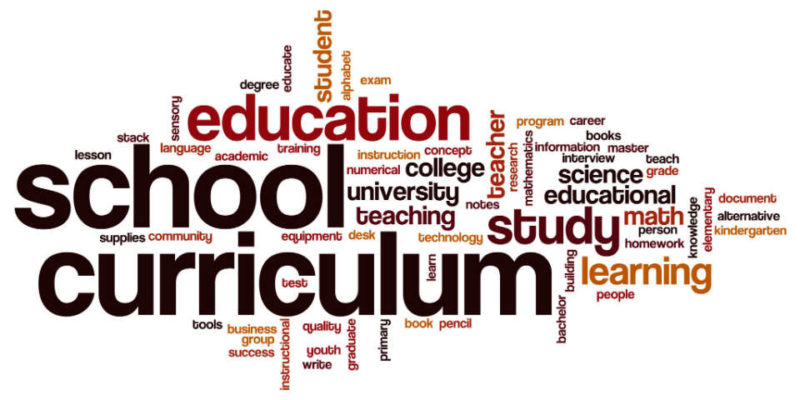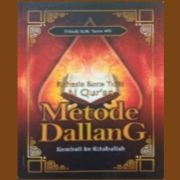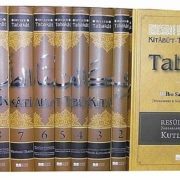Tahun 2020, saya sengaja memviralkan bahwa mata pelajaran sejarah akan dihapuskan dengan memberikan indikasi bahwa jaringan lembaga intelektual tertentu sebagai aktor di belakangnya. Saat itu, tersebar di lingkungan pendidik, peneliti dan masyarakat sejarah, dokumen power point penyederhanaan kurikulum. Isinya, pelajaran sejarah peminatan hilang. Tujuh belas jam pelajaran sejarah yang sama persis dengan tanggal proklamasi–semoga ini hanya kebetulan–menyusut menjadi 6 jam saja.
Menyebut pelajaran sejarah dihapuskan, adalah upaya politik media agar situasi ini mendapatkan perhatian publik. Ini hanya berhasil pada satu tahap, namun respon kalangan sejarah yang terlalu kompromis, membuat isu ini tenggelam seperti buih sabun. Rilis Kominfo yang menyatakan informasi ini keliru sangat memprihatinkan karena pada dasarnya memang mapel sejarah ada yang hilang.
Penyederhanaan ini bukan tanpa dasar. Persepsi yang dibangun adalah beban belajar anak yang begitu berat. Sehingga diperlukan pengurangan, penyederhanaan bahkan mengembalikan materi pelajaran dalam Kompetensi Dasar (KD) yang begitu detail menjadi esensial. Pukulan besar hadirnya Covid-19 di penghujung tahun 2019, makin menonjolkan keberadaan kompetensi dasar yang berat sebagai biang dari lemahnya kemampuan literasi, matematik dan sains anak. Nilai PISA, diracap berulang-ulang oleh Kemdikbud yang sekarang ‘ristek’ sebagai mantra bahwa kurikulum yang usianya baru tujuh tahun merupakan kambing hitam, dan perubahan kurikulum adalah konsep pasukan berkuda pangeran tampan yang menjanjikan pembebasan dengan tagline ‘merdeka belajar.’
Semua masalah pendidikan, akibat konvensi nilai dan karakter dalam Kurikulum 2013 diarahkan pada perubahan kurikulum sebagai jawaban. Padahal dari Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration dan Communication (4C) yang terlalu gemuk untuk diterapkan secara menyeluruh justru ditambahkan Computational Thinking dan Compassion (2C) oleh Nadiem Makarim. Begitupun 18 karakter dalam kurtilas yang mestinya membuat peserta didik bagaikan malaikat jika berhasil menerapkannya, disederhanakan menjadi profil pelajar Pancasila yang berisi enam karakter yang lebih asing, aneh, dan membingungkan.
Sebagai orang sejarah, agak sulit memahami berkebinekaan global, diksi yang dipakai dalam salah satu profil pelajar Pancasila. Mengapa berkebinekaan harus disandingkan dengan global? Jika anda, mau sedikit saja membaca sejarah, kata Bhineka ini lahir pada masa Majapahit, konsep yang dicatat dalam kitab kuno bernama Sutasoma, yang ditulis kaum intelektual-religius saat itu bernama mpu Tantular. Tantular sendiri menulis ‘Bhineka’ untuk menunjukan suatu perpaduan, silang budaya antara Hindu-Budha di kepulauan Nusantara.
Jika ditelisik, baik Hindu dan Budha merupakan kepercayaan dan kebudayaan asing, yang dikirim ke negeri ini melalui lintas jalur perdagangan internasional. Perdagangan yang membentang dari selatan Jazirah Arab, teluk Persia dan India menuju Tiongkok yang melalui perlintasan kepulauan Nusantara menunjukan bahwa pengaruh Hindu-budha adalah globalisasi itu sendiri.
Menyandingkan antara kata Kebhinekaan dengan kata global adalah bukti bahwa pembuat konsep ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan minimum yang sangat mungkin sudah diajarkan pada jenjang Sekolah menengah Atas dalam negeri. Wajar kemudian jika seorang sejarawan yang prihatin masalah ini mengatakan ‘saya mendengar bahwa pembuat kebijakan ini bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bagaimana dia bisa memahami kondisi pendidikan tanah air?’ Edward Said pasti setuju dengan pertanyaan seperti itu sebagaimana ia mempertanyakan mengapa banyak ahli timur tengah dari Barat bahkan tidak bisa bahasa Arab? Apa jaminan mereka tidak bias?
Dari contoh kecil ini semua, menjadi masuk akal, bahwa dari sekian persoalan pendidikan di negeri ini, dari kesenjangan fasilitas hingga kesenjangan digital serta lemahnya literasi dan daya kritis, ada upaya jalan memutar untuk menyalahkan mapel sejarah sebagai biang keladi. Alasan utamanya, bahwa para pemangku kebijakan pendidikan yang melahirkan konsep kurikulum tanpa dasar sejarah memang menganggap bahwa mata pelajaran sejarah tidak lebih penting daripada pelajaran olahraga. Hal ini tertuang PP nomor 4 tahun 2022 yang sama sekali tidak menyebut pelajaran sejarah sebagai muatan wajib.
Kewajiban belajar sejarah sebenarnya bukan berita baik. Kewajiban ini secara praktis tidak akan menyelamatkan pelajar dari ancaman pengangguran, atau jaminan terampil menjadi kaum pekerja. Sejarah peminatan memang berisi pengetahuan sejarah yang tidak berkorelasi langsung dengan kehidupan praktis.
Apa hubungan reformasi gereja yang diajarkan sejarah peminatan bagi pelajar muslim? Konten dakwah? Untuk apa siswa belajar peradaban kuno Machu Picchu? Apa keuntungan mempelajari faham-faham besar dari liberalisme hingga sosialisme di era digital? Mengapa pelajar harus mempelajari pecahnya Yugoslavia, perang Teluk, berbagai kudeta di Amerika Latin selama perang dingin padahal sekarang situasi dunia sudah berubah?
Pertanyaan itu pernah ditanyakan penulis kepada siswa dan sebagai besar tidak bisa menjawabnya.
Mudah mengatakan bahwa hal ini membuktikan bahwa materi sejarah tidak akan berguna secara praktis bahkan ketika pelajar tersebut baru saja keluar dari kelas sejarah. Dalam jangka pendek, pengetahuan semacam itu tidak membantu siswa untuk menaikan taraf hidupnya atau membantunya dalam memperoleh ketenangan hidup.
Karena membaca sejarah membangkitkan keresahan. Bukan kegiatan kursus dengan rumus belajar cepat. Pada masa Hindu-budha, mereka yang bisa membaca sejarah hanyalah kaum Brahmana. Sampai masa keemasan Islam, membaca sejarah adalah kegiatan suci yang dipecah menjadi berbagai keilmuan. Pada masa kolonial, pembaca sejarah menjadi penasehat politik kolonial. Pada masa kini, sejarah semakin dikerucutkan. Mudah mengatakan bahwa kita akan menghadapi kehancuran yang lebih hebat daripada masa Hindu-Budha, Islam dan masa kolonial itu sendiri. Namun, ini merupakan proses jangka panjang yang tidak akan difahami oleh program kurikulum yang dibentuk hanya untuk tiga periode politik.
Lagipula, sejarah berisi pertentangan-pertentangan dan seringkali bertentangan dengan apa yang disebut keteraturan. Keunikan akan selalu muncul disaat yang tidak terduga, maka pada level yang sangat konservatif, seorang peserta didik sejarah harus menyerap semua pengetahuan itu untuk benar-benar memahami keseluruhan pola dari pelajaran sejarah yang mereka dapatkan. Mereka harus membaca perlahan sebagaimana orang mengaji kitab kuning yang dulu dicemooh. Tapi disisi lain menghina hafalan sambil menuntut literasi digital yang tinggi.
Inilah yang menyebabkan belajar sejarah adalah kemewahan barang antik. Ia bukan barang etalase di toko grosir yang siap jual dan bisa dinikmati saat itu juga. Oleh karena itu belajar sejarah sebenarnya adalah pelajaran yang sangat mahal. Ia merupakan investasi jangka panjang yang tidak cocok jika diajarkan bagi semua sekolah di negeri ini yang notabennya sedang dicetak menjadi pekerja digital terampil.
Namun materi sejarah peminatan sangat membantu mereka yang memiliki cita-cita tinggi, bergaul secara global, memahami karakter manusia dari belahan dunia lain, dan membuat keputusan penting berdasarkan apa yang diajarkan masa lalu. Kombinasi antara profil pelajar Pancasila dengan mata pelajaran sejarah wajib yang indonesiasentris akan membuat panorama sejarah pelajar bergerak ke dalam. Penghilangan sejarah peminatan yang berkaitan erat dengan kedudukan Indonesia dalam konteks global dan sebagai bagian dari kesatuan umat manusia di planet bumi, akan hilang ditelan nasionalisme sempit. Seperti dalam tema ‘berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI’ yang justru menafikan bahwa teknologi bersifat estafet yang dibangun oleh manusia keseluruhan. Sangat berbalik dengan pidato Soekarno tahun 1960an, ‘memberikan Pancasila kepada dunia.’
Akrobat konseptual dalam kurikulum ini akan membuat kita mengulangi kesalahan yang sama, karena berlandaskan ambisi politik sesaat, sehingga kita akan mengulangi kesalahan yang sama, yang akan dicatat dalam sejarah. Mereka yang bermaksud menghilangkan peran sejarah dalam pendidikan negeri ini, tidak layak mendapatkan peringatan apapun dalam sejarah. Mereka berhak mengulangi kesalahan yang sama. Itu hak anda. Sedangkan membunyikan lonceng peringatan adalah tugas kami.
Jakarta, 30 Januari 2022
Iman Zanatul Haeri