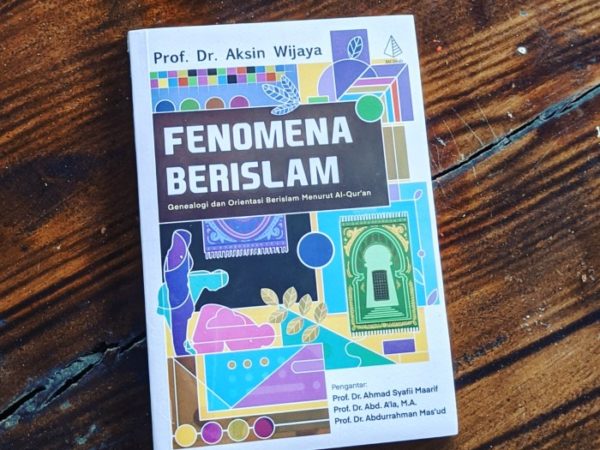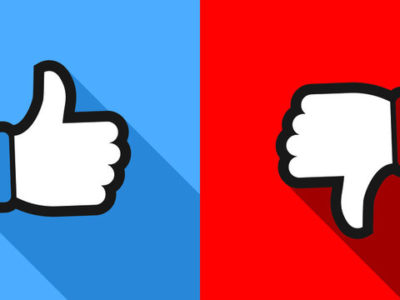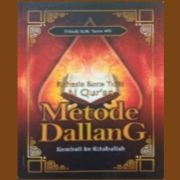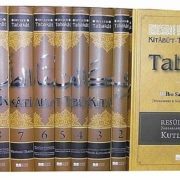Setiap orang adalah pelaksana dari prinsipnya sendiri. Itu artinya, pihak yang paling bertanggung jawab dari pikiran dan perkataan Anda adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Pun dalam hal menyinta, bukan tugas orang lain untuk menghormati dan menyayangi Anda, tapi tugas Anda sendiri. Inilah filsafat hidup yang (idealnya) dipegang teguh setiap manusia.
Setiap manusia menjalani hidup berdasarkan filsafat hidupnya. Sederhananya, setiap orang berpikir, bertutur dan tentu saja berbuat berdasarkan pandangan hidup atau prinsip yang selama ini dianggap benar.
Jelas kini bahwa filsafat hidup menentukan cara, tujuan dan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, tanpa prinsip, hidup adalah melangkah ke arah hilang arti, disorientasi. Hidup hanya merapatkan damba pada sikap putus asa, binasa—mautun fī hayātih (mati justru selagi masih hidup).
Demi alasan ini pula, Ramadan adalah puasa, puasa adalah menahan diri, kendalinya adalah kesadaran, sadar bahwa ada hak orang lain pada setiap yang kita punya, sadar bahwa orang lain adalah kita, mereka yang kurang beruntung hidupnya adalah tanggung jawab kita. Adalah dosa besar jika anak-anak kita belajar sampai sarjana sementara anak tetangga putus sekolah dan buta huruf, adalah mendustakan agama kalau anak-cucu kita sakit karena kebanyakan makan, sementara yatim-piatu dan anak-anak tetangga bergelimpangan sakit karena kurang makan, polio, stunting dan busung lapar. Adalah keliru kalau kita berprinsip bahwa, “toh nanti ada orang lain yang menolong, tidak harus saya.”
Nah, filosofi mautun fī hayātih (mati justru selagi hidup) adalah yang harus diinsyafi dengan puasa, artinya hidup sama dengan mati, tidak ada manfaat dan kontribusi apapun bagi kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan sakramen puasa selama Ramadan dan di luar Ramadan, kualitas hidup harus ditingkatkan menjadi hayātun fī hayātih (hidup bermakna selagi masih hidup), yakni sebisa mungkin hidup ini bermartabat dengan cara memberi manfaat.
Sebenarnya tanpa disadari, setiap orang memang terus mencari makna hidupnya (homo significant), jika tak kunjung mendapati, ia akan mengadopsi makna-makna yang telah ada pada orang tua, pada guru, juga pada orang lain, sebab kebaikan dan keburukan sama-sama membutuhkan keteladanan. Apakah selesai sampai di sini, Bro? Belum, kurang seru, bukan?
Setelah kita sampai pada level hidup yang berkualitas selagi masih hidup, masih tersisa sebilah tanya yang menusuk ke jantung kesadaran: bagaimana setelah mati? Nah!
Filsafat hidup berikutnya adalah, hayātun fī mautih (justru hidup dan semakin bermanfaat setelah mati). Siapakah yang sampai di level ini? Tentu saja para kekasih-Nya, para Nabi, para wali, para pejuang kemanusiaan dan kemerdekaan. Tengoklah makam para walisongo, batu nisan mereka menyedot jutaan pengunjung setiap hari nonstop 24 jam, semuanya mengaji, tahlil, istighosah dan berdoa. Tak hanya itu, di makam-makam penuh cahaya itu ada geliat ekonomi, geliat kebudayaan dan harmoni.
Pernahkah kita renungi bahwa mengapa para Wali yang telah meninggal ratusan tahun silam masih bisa membantu perekonomian kita saat ini? Inilah hayātun fī mautih yang mesti kita perjuangkan melalui puasa. Semoga bahagia dan mulia. [HW]