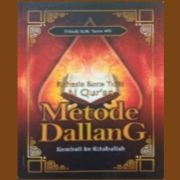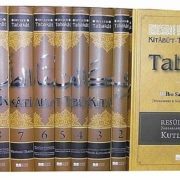Beberapa hari yang lalu, saya mendapat kiriman youtube dari sahabat saya, yang berisi orasi para pendemo berjubah putih. Beberapa menit kemudian, dia minta tanggapan saya atas isi youtube itu. Saya tidak langsung menjawab permintaannya, karena youtube seperti itu sudah banyak dan berkeliaran di media sosial, terutama youtube. Namun, pagi ini (5 Desember 2022), terlintas di benak saya untuk menjawab permintaan sahabat dari Bogor itu, lantaran saya merasakan ada yang aneh dari para pendemo itu. Dikatakan aneh, karena mereka menggunakan jubah putih dalam demonstrasinya yang secara sosiologis dan teologis merupakan simbol “kesucian”, tetapi di wajahnya tidak terlihat ada senyum yang menggairahkan, bahkan terlihat penuh amarah dan dari mulutnya keluar ungkapan kasar dan penuh ujaran kebencian, yang secara etika dan agama tidak pantas diekspresikan dan dilontarkan orang beragama.
Tanggapan saya ini tidak berkaitan dengan isi orasi mereka dan apa motivasi mereka melakukan demonstrasi dan menggunakan jubah putih. Saya ingin menyoroti wajah keberagamaan mereka, dan bagaimana sejatinya beragama, khususnya beragama Islam.
Kalau kita melihat beberapa gerakan Islam simbolis yang biasanya muncul pada setiap perhelatan akbar politik lokal dan nasional di Indonesia, ekspresi wajah mereka benar-benar terlihat garang, penuh amarah dan penuh dengan umpatan-umpatan kasar dan ujaran kebencian yang cenderung memecah-belah bangsa yang plural ini. Bukan hanya tidak sejalan dengan budaya Indonesia yang cenderung mengedepankan etika kesopanan, ekspresi keberagamaan seperti ini juga jauh dari nilai-nilai keislaman yang merahmati umatnya agar menyampaikan pesan perdamaian secara hikmah, nasehat yang baik bahkan terhadap mereka yang tidak setuju pun sejatinya disampaikan dengan dialog yang paling baik.
Beragama dengan penuh amarah dan kebencian seperti ini sejatinya tidak akan terjadi, jika ambisi politik dan berkuasanya tidak melebihi kualitas keberagamaanya. Karena kondisi itu, mereka menjadikan agama hanya sebagai tunggangan kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga keberagamaan mereka adalah keberamaan yang radikal sejalan dengan radikalismenya dalam berpolitik dan mengejar kekuasaan. Sikap radikal seperti ini pada gilirannya bisa memecah-belah anak bangsa. Untuk menghindari akibat yang tidak diharapkan itu, perlu diajukan keberagamaan yang merahmati yang mengajarkan nilai-nilai kedamaian yang penuh dengan cinta kasih, sebagai salah satu alternatif selain moderasi beragama yang sudah banyak dilakukan para akademisi, peneliti dan para pengambil kebijakan di negeri ini.
Pendekatan cinta kasih dalam beragama (agama cinta) biasa disuguhkan oleh para sufi besar. Hampir sebagian besar sufi menulis tentang cinta, suatu tema tasawuf yang terutama dipopulerkan oleh sufi wanita pertama, Rabiah al-Adawiyah. Abu Talib al-Makki menulis tentang cinta di dalam karyanya, Qutul Qulub, Al-Ghazali menulis tentang cinta di dalam karyanya, Ihya’u ulumiddin, Ibn Hazm menulis tentang cinta di dalam karyanya, Tuqul Hamamh, dan Ibn Qayyim menulis tentang cinta di dalam karyanya, Raudatul Muhibbinwa Nuzhah al-Musytaqin. Bisa dikatakan, cinta merupakan bagian dari nilai-nilai tasawuf. Bahkan, cinta di dalam tasawuf, bersama bidang ilmu kalam, filsafat, tauhid, ilmu pengetahuan, dan dzikir, dianggap bagian dari revolusi spiritual Islam sebagaimana ditulis Abul al-Afifi di dalam karyanya, al-tashawwufu: al-Thawrah al-Ruhiyah fi al-Islam.
Cinta itu merupakan pengalaman batin manusia, karena itu sulit dibahasakan dengan tulisan. Kendati demikian, cinta bisa diekspresikan melalui lisan dan fisik kendati tidak bisa mewakili ekspresinya melalui pengalaman hati. Cinta biasanya terjadi antara dua subyek yang saling membutuhkan dan saling memberi, tetapi tidak selalu demikian. Ada cinta seseorang yang berbeda jenis kelamin, misalnya seorang laki-laki mencintai perempuan, atau sebaliknya. Ada cinta orang tua kepada anaknya, dan cinta anak kepada orang tuanya. Ada cinta manusia kepada Alam semesta dan hewan, begitu juga sebaliknya cinta keduanya kepada manusia. Dan ada cinta manusia kepada Allah, dan cinta Allah kepada manusia. Cinta kategori pertama bisa dikatakan cinta syahwati (mawaddah); cinta yang kedua disebut cinta kasih saying (rahmah), cinta yang ketiga disebut cinta alami (hubbul hayah), dan yang keempat disebut cinta sejati (hubbul al-haqiqi). Cinta sejatinya terjalin dimana subyek yang mencintai hanya memberi, tetapi tidak membutuhkan sesuatu dari yang diberi. Dialah cinta Allah kepada hamba-Nya.
Bahwa ada sesuatu yang bernama cinta tidak hanya dinyatakan oleh manusia melalui hati dan akal pikiran. Al-Qur’an juga menyajikan tentang cinta dan hal itu tercermin di dalam sifat-sifat Allah. Di dalam al-Qur’an, ada dua bentuk sifat Allah secara umum. Pertama, sifat jalal, Allah menyifati diri-Nya dengan sifat-sifat keagungan (Jalal), seperti sifat Jabbar, Mutakabbir, Qahhar, Mu’izzun, Mudzillun, Sari al-Hisab dan sifat-sifat lainnya yang senada dengan sifat-sifat di atas. Kedua, sifat Jamal. Allah menyifati diri-Nya dengan sifat-sifat keindahan (Jamal), seperti sifat al-Rahman al-Rahim, Ghafur Rohim dan sifat lainnya yang sama dengan sifat-sifat di atas.
Kedua sifat itu membawa implikasi yang berbeda pada manausia. Sifat yang pertama, yakni sifat kebesaran-Nya (Jalal) membuat orang merasa takut kepada-Nya (siksa-Nya), dan mendorong manusia untuk tidak melakukan perbuatan dosa, dan senantiasa berbuat baik, bertaubat, ta’at dan beribadah kepada-Nya. Allah pun menyediakan siksa neraka bagi mereka yang berbuat dosa. Sedang sifat kedua, yakni sifat keindahan-Nya (Jamal) mendorong manusia untuk mencinta Allah, dan sebagai imbalannya, Allah mencintai manusia. Cinta balik antara manusia dengan Allah itu tercermin di dalam beberapa ayat al-Qur’an, seperti al-Maidah:2, al-Baqarah:160, al-Baqarah:222. Tentusaja, cinta Allah ditujukan kepada orang-orang yang baik, dan tidak melabuhkan cinta-Nya kepada orang-orang yang melampaui batas (al-Qur’an: 189) dan membuat kerusakan (al-Maidah:68) di muka bumi ini, seperti mereka yang mengeksploitasi alam, dan melakukan teror kepada umat manusia.
Memang berbeda pendapat di kalangan ulama’ terkait dengan cinta Allah kepada hamba-Nya, apakah bersifat majazi ataukah haqiqi. Ada yang berpendapat, cinta Allah itu bersifat majazi, karena cinta itu pada hakikatnya mencerminkan kebutuhan orang yang mencintai terhadap yang dicintainya, dan Allah sama sekali tidak membutuhkan manusia. Ada yang berpendapat, cinta Allah itu bersifat haqiqi, karena cinta hakiki itu tidak mengharuskan subyek yang mencintai menunjukkan kebutuhannya akan obyek yang dicintai.
Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas cinta merupakan sikap saling memberi sesuatu secara lebih kepada pihak yang saling mencintai, sehingga seringkali seseorang yang dimabuk cinta lupa akan dirinya dan hanya ingat sang kekasih yang dicintai. Para sufi yang dimabuk cinta kepada Allah pasti melupakan dirinya sendiri, sehingga ungkapan-ungkapannya mencerminkan seolah dirinya adalah Dia yang dicintai, misalnya ungkapan Ana al-Haq.
Kondisi cinta itu bergantung pada obyeknya. Obyek yang dicintai biasanya adalah yang mempunyai sifat indah, karena pada hakikatnya cinta adalah eskpresi atas keindahan. Kekal dan tidaknya cinta manusia bergantung pada kekal dan tidaknya keindahan. Cinta manusia kepada Allah tidak akan pernah pudar karena keindahan Allah yang Maha Indah itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Tetapi cintai Allah kepada manusia akan berubah karena sifat-sifat manusia senantiasa mengalami perubahan. Suatu waktu, manusia bisa menjadi orang baik, tetapi pada waktu yang lain juga bisa berubah menjadi jahat, melampaui batas dan membuat kerusakan. Pada saat itulah, cinta Allah berubah menjadi amarah kepadanya.
Sejalan dengan itu, manusia beragama sejatinya tidak hanya mencintai Allah karena ke-jalaman-nya semata, tetapi juga mencintai manusia karena ke-jamalan-Nya senantiasa menyinari diri manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki cinta-Nya. Begitulah sejatinya manusia jika mencintai. Dia akan memberi apa yang dikehendaki cintanya, melebih apa yang dibutuhkan dirinya. Karena Allah mencintai manusia, dan kita sebagai umat Islam mencintai Allah, maka cinta kita kepada Allah sejatinya juga mendorong kita untuk mencintai manusia karena manusia adalah ekspresi cinta-Nya. Karena Allah tidak membedakan-bedakan manusia, kecuali terhadap mereka yang melampaui batas dan membuat kerusakan, begitu juga sejatinya umat Islam mencintai manusia karena kemanusiaannya, kecuali kepada mereka yang melampaui batas dan membuat teror kepada manusia.
Karena itu, hindari sikap melampaui batas, membuat teror dan mengumbar kebencian atasnama Allah dan agama, karena sifat-sifat itu membuat murka Allah kepadanya. Mari kita jadikan diri kita sebagai simbol bukan hanya bagi sifat ke-besaran-Nya (jalal), tetapi juga dan terutama kita jadikan symbol bagi sifat ke-indahan-Nya (jamal) sebagai ekspresi keberagamaan kita. Kalau hanya sifat ke-besaran-Nya yang kita contoh, sembari mengumbar kalimat takbir dengan suara menggelegar dan meneror “Allahu Akbar”, Indonesia akan hancur. Sebaliknya, jika sifat ke-indahan-Nya yang kita pilih, Indonesia yang berbhinnika Tunggal Ika ini akan menjadi negeri yang baldatun wa rabbun ghafur.