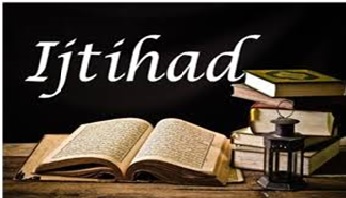Dalam sebuah forum komunitas pesantren yang belum lama digelar, seorang pembicara yang juga pengasuh pondok ternama di Jawa Timur me-lead narasinya dengan guyonan khas pesantren, “ini semua peserta dari pesantren kan, kalau dari pesantren berarti wes wareg gojlokan. Mentalnya sudah terbentuk dengan baik.” Ungkapannya pun diaminkan oleh peserta yang seluruhnya dari kalangan santri/alumni santri.
Dari peristiwa ini saja (yang penulis merasa nyaman tanpa menyebutkan komunitas dan pembicara) menggambarkan bahwa pesantren telah sekian lama menjadikan guyonan, wadanan dan gojlokan sebagai bahan-bahan lelucon receh. Dalihnya sebagai kawah condro dimuko, pembentukan mental. Sekarang ataupun dari masa lalu dalih itu tidak relevan ataupun beralasan.
Sebagai santri yang mondok dari orok, tepatnya awal tahun 2000, saya mengalami kekerasan verbal maupun fisik di lingkungan pesantren. Baik kekerasan verbal maupun non-verbal saya peroleh dari santriwan dan santriwati. Kekerasan itu sangat membuat saya tidak nyaman dan tertekan. Singkatnya, saya menyakiti diri sendiri agar teman santri tidak memanggil saya “tompel”.
Lain lagi, dengan ta’zir (hukuman) yang saya alami. Saya pernah dipermalukan di depan santri putra untuk menyapu halaman pondok pesantren putra, disaksikan oleh mereka dengan mengalungi kalung bertuliskan dosa yang saya perbuat. Untung saja ta’zir itu tidak membuat saya kehilangan kewarasan. Meski rasanya seperti ditelanjangi di hadapan seluruh santri putra. Apa yang terjadi dengan saya maupun Bintang, (mengutip Gus Hamid) merupakan ledakan gunung es yang sedikit sekali tampaknya di permukaan namun melimpah di dalam.
Kekerasan semacam itu terus terjadi, karena memang mendapat ruangnya di pondok pesantren, sebagian pemimpin pesantren juga telah menganggap gojlokan sebagai hal yang sangat biasa.
Lalu bagaimana menghentikan “gojlokan” dan kekerasan yang telah lama mengakar di pondok pesantren?
Kerja besar ini tentu tidak dapat dilakukan oleh pesantren sendiri, tanpa campur tangan pemerintah dan Lembaga Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Pesantren harus disadarkan dengan penuh bahwa kekerasan verbal seperti gojlokan dan fisik tidak boleh mendapatkan ruang di pesantren.
Diantaranya yang dapat dilakukan Komisi Perlindungan Anak, pemerintah dan pesantren yaitu melakukan kampanye tentang bahaya kekerasan secara massif dengan pendampingan Komnas Anak dan Perempuan, pemerintah harus berani mengucurkan dana, untuk mengkampanyekan anti kekerasan secara massif demi menghentikan dan mencegah kekerasan di lembaga pendidikan.
Selama ini, pesantren membiarkan riak-riak gojlokan kecil yang terjadi di pesantren. Pembina atau pihak yang berwenang di pesantren lebih banyak bersikap apriori jika terdapat santri lain meng-gojlok santri lainnya, seperti memanggil dengan panggilan yang tidak pantas, Wedus Gibas, Tompel, Kriwul, Kirun dan lainnya.
Santri, meski mendapatkan banyak insight tentang bahaya bullying, mereka tidak mampu serta merta menghapus budaya gojlokan dari ruang belajarnya sendiri. Pembina dan guru harus menajamkan pendengaran dan penglihatan dan memiliki sense of bullying untuk terus mengingatkan dan menegur santri yang gojlok menggojlok. Apalagi, main fisik.
Pesantren harus bergandengan tangan bersama-sama untuk melawan budaya busuk itu agar tidak terus melahirkan korban-korban lainnya seperti saya bahkan Bintang. Kampanye yang dilakukan pemerintah harus berfungsi sebagai penghayatan, pendalaman dan pengingat bagi kita semua warga santri atas bahaya bullying atau gojlokan di pesantren. Memberikan pembinaan leadership dan resolusi konflik di pesantren bagi Pembina, pendidik, guru dan pengasuh pesantren oleh pemerintah.
Tidak banyak pesantren lihai dalam melakukan penyelesaian masalah atas pelanggaran yang dilakukan santri. Pesantren biasanya akan membuat hukuman yang secara fisik santri lelah dan secara mental mereka malu. Sehingga biasanya menyapu halaman tapi di depan pondok pesantren putra jika santri putri. Sebaliknya, di halaman pondok putri jika yang melanggar santri putra. Atau dimasukkan kedalam air selokan kamar mandi. Dan berbagai taksiran fisik lainnya. Santri yang melakukan pelanggaran juga tidak lepas dari kekerasan verbal saat disidang.
Ta’zir yang berbau kekerasan, seharusnya bisa dialihkan pesantren dengan ta’ziran membaca buku dan meresumenya dalam waktu tertentu, menghafal atau Bisa juga berpidato di hadapan para santri. Tanpa menyebutkan ia sedang dita’zir.
Mbah Kiai Umar Mangkuyudan Surakarta punya cara yang unik dalam mengatasi santri ndableg. Santri yang paling ndableg akan dibacakan fatihah terbanyak, disusul santri-santri berikutnya. cara ini bisa diadaptasi di pesantren lain, selain berdampak pada aspek spiritual santri sebenarnya akan berefleksi. Ia akan merasa sungkan dibacakan fatihah secara khusus oleh seluruh santri.
Berkaca pada Mbah Umar, kemampuan meresolusi konflik menjadi pondasi yang sangat penting bagi pesantren, agar mampu menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang arif, santun dan membekas di dalam hati.
Pesantren harus bersikap lebih inklusif,dengan kemauannya untuk mengaplikasikan Pesantren Ramah Anak. Yang programnya telah diluncurkan oleh Kementerian Agama bersama dengan UNICEF, dengan Pesantren Hasannuddin di Kabupaten Gowa sebagai percontohannya.
Pesantren sering menganggap bahwa apa telah berjalan di pesantrennya telah ideal, terbukti dengan alumni-alumninya yang baik-baik saja bahkan sukses. Sehingga, seringkali sebagian pesantren menutup diri untuk belajar pada pesantren lain. Jarang sekali pesantren melakukan studi banding kepada pesantren lain karena hal itu.
Oleh karena itu, pesantren harus bersikap inklusif dan mau belajar kepada pesantren lain yang lebih dulu mengaplikasikan pesantren yang ramah anak. Mereka harus mengupdate regulasi maupun resolusi konflik dari pesantren lain.
Seandainya hal ini dapat dilakukan dengan baik, rasanya tidak akan lagi terdengar kekerasan menimpa adik-adik kita di pesantren, Semoga!. [HW]