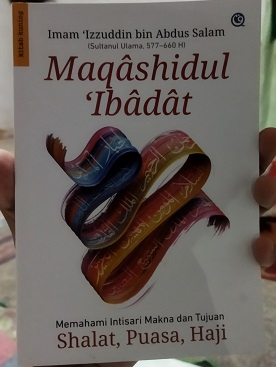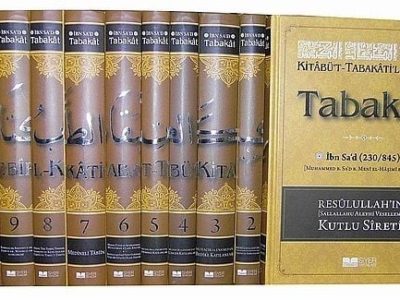Al-Anbiya: 36
وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًاۗ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ
wa iżā ra`ākallażīna kafarū iy yattakhiżụnaka illā huzuwā, a hāżallażī yażkuru ālihatakum, wa hum biżikrir-raḥmāni hum kāfirụn
“Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad), mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. (Mereka mengatakan), “Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?” Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pengasih.”
Beberapa cacatan dari ahli tafsir tentang ayat ini, antara lain:
Pertama: Sebagian mufasir menjelaskan latar belakang ayat ini diturunkan ketika Nabi Saw berjalan dan berjumpa dengan Abu Jahal yang tertawa sembari mengejek dengan perkataan, “Inilah nabi dari Bani Abd Manaf!”
Perkataan tersebut tidak bermakna bahwa Abu Jahal mengakui kenabian nabi Muhammad, melainkan olok-olokan semata untuk menyepelekan dan merendahkan Nabi Saw. Sebagaimana tersebut pada ayat di atas, wa iżā ra`ākallażīna kafarū in yattakhiżụnaka illā huzuwā (Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad), mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan…).
Huruf in pada kalimat in yattakhiżụnaka illā huzuwā adalah berfaedah nafiyah (negasi) untuk menunjukkan bahwa apapun yang perlakuan orang-orang yang diterima Nabi saat itu tak lain hanyalah ejekan semata.
Huruf in dengan makna negasi ini bisa kita jumpai juga, misalnya, pada surat al-Mujadilah: 2,
اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۤـِٔيْ وَلَدْنَهُمْۗ
“Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya.”
Kalimat in ummahātuhum ini merupakan bentuk negasi yang berarti “bukanlah ibu-ibu mereka”, illal-lā`ī waladnahum “kecuali yang telah melahirkan mereka”.
Kedua: Lalu Allah menjelaskan bentuk ejekan kepada Nabi pada penggalan ayat a hāżallażī yażkuru ālihatakum (…“Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?”…).
Kata yażkuru atau żikr bisa bermakna baik (pujian, sanjungan) atau buruk (celaan, kecaman), sebagaimana keterangan Imam az-Zamakhsyari. Jika suatu konteks dalam pembicaraan telah menunjukkan suatu makna yang terang, maka tak perlu ada penguatan untuk kata ini. Semisal apa yang dikatakan kepada seseorang, “Aku mendengar si A membicarakanmu (sami’tu fulānan yażkuruka)”. Jika si A yang dimaksud adalah temannya, maka yażkuruka bermakna “membicarakan hal baik tentangmu”, tetapi jika si A adalah musuhnya, makna yażkuruka berubah menjadi “membicarakan keburukanmu”.
Karena itu, ucapan orang-orang kafir tentang Nabi yang yażkuru ālihatakum bermakna “yang mencela tuhan-tuhanmu…”. Hal itu tak lain karena Nabi bukanlah orang yang menyetujui perihal ketuhanan yang disematkan pada berhala-berhala mereka. Jadi redaksi yażkuru yang dilakukan Nabi dalam konteks ini bermakna buruk (celaan, mencacat).
Kritik dan celaan yang dilakukan Nabi terhadap tuhan-tuhan mereka adalah menganggap tuhan-tuhan itu sebagai berhala yang dibuat dari batu semata, yang tidak bisa mendengar, melihat, memberikan manfaat atau mencegah bahaya.
اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۤءَكُمْۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ
“Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh (Allah) Yang Maha Teliti.” (QS. Fathir: 14)
Ketiga: Kata huzuwā adalah bentuk masdar yang bisa bermakna ism fa’il (subjek) atau ism maf’ul (objek). Hal ini untuk menunjukkan bahwa apapun yang datang dari Nabi Saw, baik ucapan, ajaran ataupun kepribadian beliau, akan senantiasa dijadikan bahan olok-olokan oleh orang yang mengingkarinya. Hal itu bisa dibuktikan dengan ayat berikut,
وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًاۗ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَاۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا
“Dan apabila mereka melihat engkau (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan (dengan mengatakan), “Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan (menyembah)nya.” Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.” (QS. Al-Furqan: 41-42)
Dengan demikian, lengkaplah sudah bentuk ejekan mereka terhadap Nabi Saw. Jika Nabi mengajak pada kebenaran tentang Allah, mereka anggap menyesatkan, ketika Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang tidak memberi manfaat atau mencegah bahaya tidak layak dipertuhankan, dianggapnya sebagai penista tuhan-tuhan sesembahan mereka.
Keempat: Alasan al-Qur’an menceritakan perihal orang-orang kafir menyebut Nabi telah mengejek tuhan-tuhan mereka dengan menggunakan redaksi yażkuru ālihatakum, hal ini untuk menggambarkan kekeliruan mereka dalam etika. Kepada berhala-berhala yang tak layak disembah mereka santun, sementara kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta mereka ingkar. Demikianlah tulis Imam Husain ath-Thibi dalam Futụh al-Ghaib.
Kelima: Imam ar-Raghib menjelaskan tentang makna żikr sebagai kondisi mental yang dimiliki manusia guna menjaga apa-apa yang diketahuinya. Hanya saja, lanjut beliau, żikr tidak sama dengan hifdz. Hafalan (hifdz) merupakan istilah untuk menjaga suatu pengetahuan yang diperoleh. Sementara mengingat (żikr) adalah menghadirkan pengetahuan tersebut ke dalam psikologis manusia. Secara sederhana, hifdz adalah tindakan rasional semata, sementara żikr merupakan aktivitas yang dapat mempengaruhi sisi psikologis manusia.
Secara umum, żikr dibagi menjadi dua: dengan hati dan lisan. Masing-masing keduanya juga dibagi dua: ada żikr yang bertujuan agar tidak lupa, boleh disebut mengingat kembali; ada pula żikr dengan tujuan menjaga ingatan yang sudah ada agar tak direnggut lupa. Semuanya disebut sebagai żikr.
Keenam: Penggalan dari ayat ini wa hum biżikrir-raḥmāni hum kāfirụn (…Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pengasih), bagi Imam ar-Razi, adalah kritik tajam kepada orang-orang kafir yang menghina Nabi karena mengatakan bahwa tuhan-tuhan (berhala) tidak dapat memberi manfaat dan menghindarkan mara bahaya; sementara itu mereka justru ingkar terhadap ar-Rahman, Dzat yang memberi nikmat, Maha Pencipta, Maha Menghidupkan dan Mematikan. Tentu tak ada tindakan yang lebih buruk daripada hal ini. Lanjut beliau, maka seluruh ujaran kebencian dan pencacatan yang mereka atributkan kepada Nabi akan berpulang pada mereka sendiri—tanpa mereka sadari.
Imam ath-Thibi menambahkan, pengulangan kata ganti hum pada ayat ini menunjukkan pengingkaran mereka dan celaan yang teramat sangat untuk mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekedar “tidak mempercayai sama sekali!”
Ketujuh: Tentang frasa żikr ar-raḥmāni, selain yang dimaksud adalah Allah itu sendiri, ada juga ulama yang menafsirkannya sebagai al-Qur’an dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum nabi Muhammad Saw. Demikian tutup Imam ar-Razi tentang ayat ini.
Kedelapan: Dalam sudut pandang Isyāri, ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan melihat makhluk yang dimuliakan Allah, baik para nabi atau wali, kecuali dengan pandangan ingkar dan merendahkan. Karena makhluk-makhluk mulia ini tidak mempertuhankan hawa nafsu, gemerlap dunia dan sejenisnya, sehingga mereka tampak buruk di hadapan orang kafir. Demikian kutip Syekh Najmuddin al-Kubra.
Dengan demikian, penolakan terhadap makhluk istimewa di sisi Allah memang merupakan sunnatullah yang telah berlangsung sejak dahulu. Ketentuan ini tidak terjadi di masa depan kecuali sebagai pengulangan demi pengulangan. Simpul Syaikh Ibn ‘Ajibah tentang ayat ini.
Al-Anbiya: 37
خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍۗ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ
khuliqal-insānu min ‘ajal, sa`urīkum āyātī fa lā tasta’jilụn
“Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya.”
Beberapa poin penting untuk dirangkum dalam ayat ini, antara lain:
Pertama: Perihal khuliqal-insānu min ‘ajal (Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa…), para ulama berbeda pendapat tentang kata insan (manusia), beberapa pendapat yang bisa dikutip antara lain: (a) Yang dimaksud adalah manusia secara umum, bahwa ciri utama manusia memang sering tergesa-gesa. (b) Kata manusia di sini dikhususkan pada nabi Adam, dengan sebuah riwayat bahwa Allah menciptakan nabi Adam As pada sore hari Jumat, saat ruh yang ditiupkan sampai ke bagian kepala beliau, belum sempurna sampai ke bagian bawah, nabi Adam berkata, “Wahai Tuhanku, segerakanlah penciptaanku ini sebelum matahari terbenam.” Sebab itu, komentar Imam Laits, Allah berfirman khuliqal-insānu min ‘ajal (Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa…). Riwayat lainnya yang mendukung pendapat ini dari Imam as-Sudi yang menceritakan bahwa ketika ruh sampai ke kepala nabi Adam, beliau bersin. Lalu para malaikat berkata, “Ucapkanlah Alhamdulillah!” nabi Adam pun melaksanakan saran tersebut. Kemudian Allah berkata kepada nabi Adam, “Tuhanmu mengasihimu”. Saat ruh sampai pada kedua mata beliau, beliau melihat buah-buahan di surga. Tatkala ruh sampai di perut, nabi Adam berhasrat untuk mengkonsumsi buah itu, lalu beliau segera melompat sebeluh ruh itu sampai ke kaki beliau. Itulah yang membuat keturunan beliau mewarisi sifat gegabah atau terburu-buru.
(c) Riwayat dari Imam Atha’, bahwa ayat ini turun untuk Nadzar bin Harits, sehingga yang dimaksud dengan kata insan (manusia) hanyalah dia semata, yang meminta diturunkan azab sesegera mungkin.
Imam ar-Razi mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, sebab konteks ayat ini ialah untuk mencela orang-orang yang memiliki sifat itu, dan tujuan itu akan tercapai jika kata insan diberlakukan secara personal.
Kedua: Beberapa perbedaan pendapat tentang kata min ‘ajal (dari ketergesa-gesaan) di antara para ahli tafsir, antara lain: (a) Ketergesa-gesaan sebagai sifat kondisi yang seringkali didapati pada manusia, karena salah satu kebiasaan orang Arab memang menamai sesuatu sesuai dengan ciri umum yang ada padanya. Pendapat ini juga dikuatkan dengan ayat lain,
…وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا
“…Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.” (QS. Al-Isra’: 11)
(b) Imam al-Akhfasy menyatakan bahwa min ‘ajal berarti sesuatu yang cepat sekali, hal ini tak lain karena firman Allah kun (jadilah!)—lalu manusia pun tercipta seketika. Bila dibandingkan dengan penciptaan langit-bumi yang memakan waktu sampai enam masa (fi sittah ayyām), tentu penciptaan manusia lebih cepat. (c) Sebagian memaknainya sebagai sifat lemahnya untuk melakukan kebaikan. (d) Pendapat Abu Ubaid yang mengatakan bahwa ‘ajal dalam bahasa Himyar bermakna tanah.
Ketiga: Penggalan akhir ayat ini sa`urīkum āyātī (Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku). Tulis Imam ar-Razi, terdapat beberapa tafsir tentang makna āyātī, antara lain: (a) Kebinasaan atau bencana di dunia dan azab di akhirat. Karena itu penggalan ayat selanjutnya adalah larangan memintanya untuk dipercepat, fa lā tasta’jilụn (Maka janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya), karena ia akan datang secara pasti dengan waktu yang ditentukan oleh Allah.
(b) Maknanya adalah dalil-dalil tentang keesaan Allah dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw. (c) Jejak peradaban terdahulu yang terdapat di Syam dan Yaman.
Bagi Imam ar-Razi, pendapat pertama lebih sesuai dengan rangkaian ayat yang sedang dibahas.
Keempat: Tentang rangkaian ayat yang menceritakan bahwa sifat dasariah manusia adalah tergesa-gesa (al-‘ajalah), lantas kenapa manusia dilarang melakukan sesuatu yang memang tendensi laten bagi mereka?
Imam ar-Razi menjawab, bahwa larangan ini diberlakukan untuk sifat terlalu tergesa-gesa atau gegabah (ifrāth al-‘ajalah). Di sisi lain, manakala potensi manusia memang demikian, sanggup menahan diri dari hal tersebut tentu menambah kesempurnaannya. Kita bisa sederhanakan argumen ini begini, tidak setiap yang diciptakan Allah berarti layak diikuti, sebagaimana Allah menciptakan Iblis agar kita menyelisihinya; Allah menciptakan hawa nafsu negatif supaya manusia bisa menahan diri; dan sudah barang tentu, jika Allah menciptakan sifat tergesa-gesa tidak berarti manusia lepas kontrol dan senantiasa menurutinya, bukan?!
Pertanyaan lain yang bisa dikemukakan ialah tentang ketergesa-gesaan orang kafir meminta azab bukan sesuatu yang hakiki. Artinya, mereka pada dasarnya tidak mempercayai azab yang diancamkan oleh Allah, dengan demikian hal ini hanyalah ketergesa-gesaan yang palsu, lalu kenapa harus dikritik dan dilarang dengan kalimat fa lā tasta’jilụn (maka janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya)?
Imam ar-Razi mengemukakan jawaban cerdas, menurutnya, isti’jal (meminta sesuatu dipercepat) dalam hal yang sudah diketahui saja dianggap tidak baik, apalagi terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Di sisi lain, jika yang mereka minta adalah ancaman azab di akhirat atau kebinasaan di dunia, hal itu mesti tercakup dalam kematian. Karena kematian adalah pintu menuju akhirat dan kebinasaan bagi kehidupan dunia. Dan kematian adalah hal yang mereka ketahui. Dengan demikian, isti’jal yang mereka lakukan masuk dalam kategori hakiki, sebab itu Allah pun melarangnya.
Kelima: Imam al-Qusyairi memberi garis demarkasi tentang al-‘ajalah dengan al-musāra’ah. Al-‘ajalah merupakan hal yang tercela, karena ia menginginkan sesuatu sebelum waktunya. Hal ini tak lain dari bisikan setan semata. Sementara musāra’ah adalah perkara terpuji, ia berarti melakukan sesuatu di awal waktu. Karenanya ia merupakan ciri dari taufik atau petunjuk dari Allah. [HW]