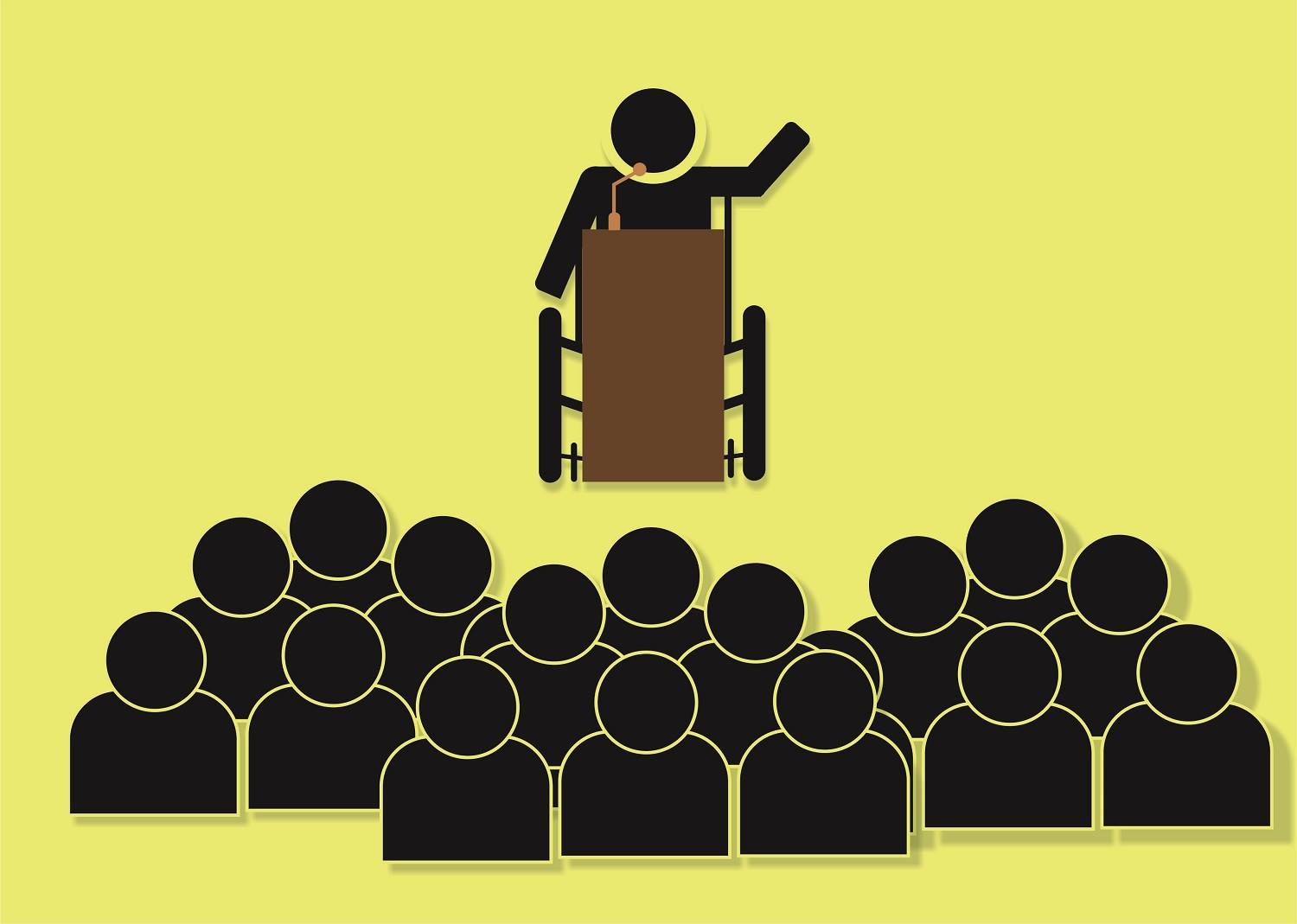Terus terang, baru kali ini saya menyaksikan pemandangan aneh yang begitu memilukan. Pengurus pondok membacakan pengumuman, bahwa pesantren libur tiga bulan: “waktu 30 maret sampai 2 juni…”. Sontak, riuhlah ribuan santri itu. Saling pandang, sesak dada, dan air mata pun jatuh membasahi pipi. Mereka kemudian menyeka air mata dengan kerudungnya. Seakan ada bahasa yang tak perlu diutarakan: “ini memang libur, tapi bukanlah libur yang kami inginkan”.
Itulah gambaran video pendek yang diunggah akun instagram @annawawiberjan_putri, yang juga direpost akun @annawawi_berjan pekan kemarin. Akun ini merupakan akun resmi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Gebang, Purworejo, tempat di mana dulu saya belajar ilmu agama sekaligus meneladani – secara empirik – akhlak seorang kiai.
Tak terasa, mata saya pun ikut berkaca-kaca. Berulang-ulang saya simak video itu, sambil menerka: kesedihan seperti apa sebenarnya yang dirasakan oleh mereka? Apakah sedih tidak bisa mengaji dalam waktu begitu lama? Sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang sudah membaur setiap harinya seperti pakaian dan badan? Ataukah sedih karena wabah corona ini mengacaukan jihad mereka di barak pesantren: menuntut ilmu agama. Saya tidak tahu kesedihan yang mana dari itu semua. Namun yang jelas, saya pun seakan merasakan kesedihan yang sama, di mana hal-hal yang selama ini telah menjadi rutinitas dan bahkan kebanggaan, tiba-tiba hilang begitu saja.
Semenjak kecil, baik di sekolah pagi ataupun madrasah sore di kampung dulu, begitu ada pengumuman libur, saya – dan juga teman teman – girangnya bukan main. Kami merayakannya dengan teriak kencang, berjingkrak-jingrak, menabuh-nabuh meja, atau lari berputar-putar. “Kami mendapatkan kebebasan,” pikir kami, waktu itu.
Hari libur, waktu itu, bisa kami gunakan untuk memancing ikan di sungai, bermain perang-perangan, menaikkan layang-layang, atau bermain sepak bola sampai terdengar bunyi kentongan dan bedug: “Tung!!! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Tung! Dunggggg!!!! Dunggggg!!!! Dunggggg!!!!” Tanda waktu magrib tiba. Saat itulah kami baru berakhir. Skor goal bisa mencapai ratusan, sebuah aturan sepak bola yang kami bikin sendiri, tak menggubris aturan FIFA. Intinya, kami begitu menikmati liburan, dengan teman-teman seumuran.
Namun, yang kulihat dalam video itu lain. Ribuan santri putri menangis begitu diliburkan. Dan kukira selain An-Nawawi banyak juga santri yang bersedih ketika harus libur dan dipulangkan, seperti Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Kebetulan, adikku yang nomor tiga, Naily Ulya Ulin Ni’mah, mondok sekaligus kuliah di sana. Tepatnya di Al-Amanah 2. Dengan memakai bus, adikku dan ribuan santri itu disemprot seperti tanaman cabe lalu dipulangkan ke berbagai daerah masing-masing dengan ketat. Tentu ini agar tak keluyuran dan berpotensi terpapar virus Covid19 yang tak kelihatan.
Memang, kadang kesedihan atau kehilangan itu menimpa kita saat yang kita miliki hilang. “Rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya,” begitu kata Mas Sabrang, vokalis grub band Letto, dalam lagunya: Memiliki Kehilangan. Artinya, kita merasa memiliki pesantren, merasa menikmati mengaji, bahagia dengan pertemanan, yang itu semua mesti dijeda untuk waktu yang agak lama. Dan kita pun menjadi sedih karena kehilangan itu semua.
Itu adalah pemaknaan “syariat”. Sedangkan dalam pemaknaan “hakikat”, kira-kira, kita takkan bersedih hati jika kita tak merasa memiliki. Jika kita merasa bahwa hidup dan semua yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah semata, maka kita takkan bersedih. Seperti tukang parkir, ia dititipi mobil mewah-mewah, dijaganya, begitu yang punya mengambil, ia sedikitpun tak bersedih hati.
Ketika ka’bah dikosongkan, umrah diundur, masjid diliburkan, tempat-tempat suci di-lock, mungkin Tuhan ingin mendidik kita: bahwa Dia bukan di tempat-tampat itu, melainkan ada di dalam hati kita, menaungi kita, bahkan sangat dekat dengan kita, seperti urat nadi, bahkan lebih dekat lagi, seperti dikabarkan QS. Qaaf: 16. Dia bukan di kemegahan dan gegap-gempita pesta, tetapi ada bersama anak yatim dan orang-orang miskin, begitu informasi dari QS. Al Maa’uun: 1-7, yang terekam lebih dari 14 abad lalu.
Maka, tak ada sesuatu yang menimpa kecuali di situ ada hikmah dan pelajarannya. Jika Ujian Nasional ditiadakan, sudah sangat tepat, karena kita sedang menghadapi ujian yang sesungguhnya: ujian kehidupan dan kemanusiaan. Bersama dengan kesulitan ini, sudah ada kemudahan-kemudahan, seperti yang ditegaskan secara berulang dalam QS. Al-Insyirah: 5-6. Sekarang, tugas kitalah untuk ikhtiar dan tawakkal. Sambil terus ber-istighfar dan merenungi kelakuan kita selama ini, di tengah keadaan yang serba ketar-ketir ini.
Akhirnya, saya menyadari kesedihan yang dialami para santri itu. Juga kegamangan jutaan umat manusia yang ada di bumi ini. Ini adalah perilaku yang wajar, meski baru sekali ini saya menemuinya seumur hidup. Maka, hanya kepada-Nya lah kita memohon, berharap dan bergantung, agar wabah Covid19 ini segera berakhir, dan kita menjalani hidup yang lebih ter-upgrade jiwa tauhid kita, empati sosial kita, kebersamaan kita, dalam menjalani titipan status khalifah di muka bumi yang sebentar ini.
Semoga para pemimpin dan paramedis yang berjihad di garda depan senantiasa diberi taufiq dan hidayah, sehingga menemukan kunci kemudahan yang sampai saat ini seakan belum ditemukan. Dengan perantara para kekasihmu, ya Allah, hilangkanlan wabah ini. Li khamsatun uthfi biha harral wabail hatimah: al-Musthafa wal Murtadla Wabnahuma wa Faatimah.