It was a fine morning when I finished reading this novel with a mixed feeling.
Troubled.
But contented.
But disturbed.
Pertama mengetahui novel ini pada Februari dari ulasan teman di komunitas perempuan membaca dan kurang tertarik. Membayangkan membaca kisah tentang gadis yang diperkosa dan ikhtiarnya menyembuhkan luka belum-belum membuat nyesek. Membayangkan tantangannya menghadapi dunia membuat pusing. Mending baca yang lain.
Yang bisa setidaknya membuat saya tetap cantik. Tidak jadi manusia selang air.
Awal April, sembari bercakap dengan Gus Dul Hamid tentang sastra pesantren, dengan seru beliau merekomendasikan novel Hilda, Cinta Luka & Perjuangan karya Muyassarotul Hafidzoh ini.
Oke, I will try.
Orang bilang jangan menilai buku dari kopernya, eh covernya. But seriously, ketika Hilda datang, saya mengamati sampulnya dengan seksama.
Sehelai bulu yang terbang tertiup angin namun tertahan oleh 2 tonggak, membentuk huruf H pada judul Hilda.
Hemmm… pertanda bagus.
Membuat saya penasaran, siapa dua tonggak yang mendampingi, membuat kuat jiwa Hilda yang rapuh setelah bencana menghantamnya?
Novel dibuka dengan baik, tokoh utamanya bertarung diatas panggung, tidak hanya melawan peserta debat namun juga melawan dirinya sendiri. Pergolakan batinnya melawan stereotyped views tentang how a girl must behaved, melawan traumanya sendiri juga. Full dari halaman 20 hingga 30 pembaca langsung disuguhi argumen lengkap plus rujukan berbagai sumber. Agak panjang namun diramu dengan cukup baik.
Sebagai karya sastra mubadalah saya temui banyak ilmu mengenai keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, cerita novel ini dirajut dengan rapih dengan ups and down tokohnya.
As I predicted tidak banyak scene yang membuat tersenyum. Momen bahagianya malah membuat nletik. Tapi ini saya rasa bukan karena penulisnya yang gagal. Tapi pembacanya ini yang cengeng.
Hanya ada dua hal di benak saya selesai membacanya -saat ini tentu, entah ketika suatu hari akan mengulang baca mungkin akan nemu lagi.
Pertama, what’s wrong with Hilda? Sementara trauma dan penyakitnya bisa terpicu dengan mudah -Hilda bisa histeris, hanya dari sentuhan lelaki Yang ingin menolong ketika kecelakaan.
Eh kok ketika ada pria compang-camping setengah gila memanggilnya berteriak-teriak ‘hilda, hildaku’, tokoh utamanya hanya bingung, tidakkah itu memicu ingatannya? Meski Hilda sudah terlindung dan tidak mendengar ketika si pria gila menceracau dan kemudian mengaku bahwa ia ayah dari anak Hilda, tidakkah itu memicu sesuatu di memorinya? Atau setidaknya otak cerdas Hilda bisa dong merasa penasaran dan menghubungkan titik menjadi gambar?
Apakah terjadi mekanisme pertahanan psikologis pada diri Hilda yang membuatnya -meski tetap ingat peristiwa perkosaan itu, namun ingatan akan sosok dan fisik jelas lelaki tersebut terhapus?
Kedua, tokoh utama pria yakni Wafa, digambarkan penulis sebagai wiraswasta mandiri, hidup berkecukupan, dari keluarga terhormat plus ganteng, putih, tinggi, bermata Indah, lentik.
Demi Yang Maha Sempurna dan segala yang diciptakan-Nya di dunia ini memang tanpa cela, saya setuju sekali bahwa at-thoyibuna lit thoyyibat, nanging ngunu yo mbok ojo ngunu. Kenapa sastra pesantren akhir-akhir ini sering meniru gaya utopian dimana karakternya physically flawless.
Dimana tempat bagi para pria brillian namun berkulit gosong atau setinggi pucuk teh dan setebal pokok pisang jika dunia impian para wanita dicekoki dengan rumpun bambu ramping?
Tidak heran masih banyak pria single meski jumlah wanita nyaris tiga kali lipat. Hehehe
Setelah membaca Hilda, secara keseluruhan, I like it. Empat jempol juga untuk layouter novelnya yang memisahkan tiap bab dengan quotes dan kutipan hikmah.
Jadi bingung milihnya.
Sama bingungnya ketika saya selesai membaca, tidak bisa menyimpulkan siapa dua tonggak yang menguatkan si sehelai bulu Hilda dan mendampinginya dalam ikhtiar menyembuhkan Luka. Apakah Ibunya dan Bu Nyai? Atau Ibunya dan Wafa?
Sepertinya tidak usah disimpulkan, saya akan nyeduh kopi manis saja. Karena di novel Wafa bilang:
“Al insan bila mahabbatin kal laili bila najmin
Wal mahabbah bila qoydin kal qohwati bila sakrin”

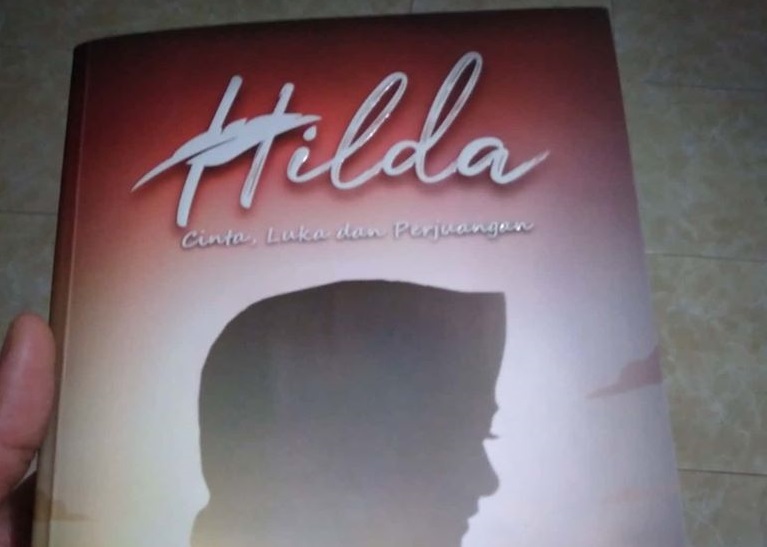












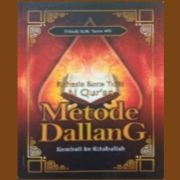

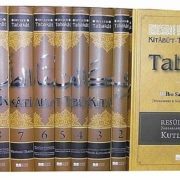







[…] Tayang pertama kali di pesantren.id […]