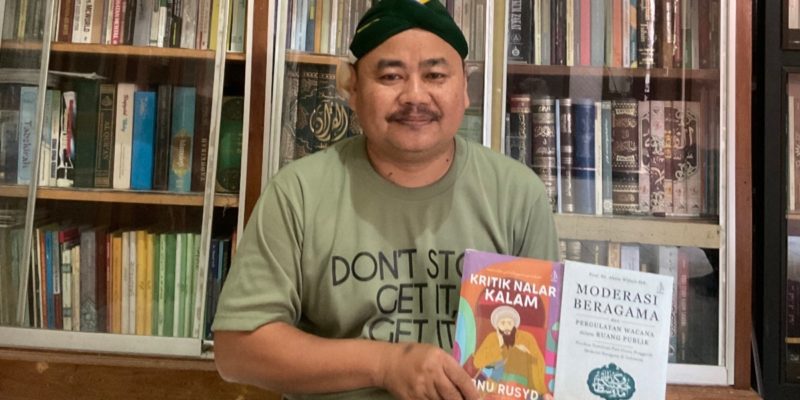Saya diminta oleh Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Dr. Islah Gusmian, untuk menjadi salahsatu pembicara dalam Konferensi Internasional “International Conference on Islamic Studies and Educational Research” ( ICISER) pada tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Syari’ah Hotel Solo. Karena di dalam AIM and Scope-nya terdapat topik terkait isu Islam dan moderatisme (Religious Moderation Issues), saya memilih membahas topik ini. Selain masih populer karena dipromosikan oleh Kementrian Agama RI sejak tahun 2019, topik ini saya kira penting dibahas karena ia menjadi salah satu pilar tegaknya kehidupan beragama yang rukun dan damai di Indonesia yang ber-Bhinnika Tunggal Ika ini, yang beberapa tahun terakhir masih muncul konflik bernuansa agama.
Tanpa menegasikan peran agama sebagai pencipta kedamaian dan harmoni sosial, konflik antar umat yang berbeda agama dan antar umat seagama yang berbeda pemahaman atas agamanya senantiasa mewarnai perjalanan hidup manusia di berbagai belahan negara, termasuk di Indonesia. Tentu saja, konflik bernuansa agama tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan agama dan pemahamannya, tetapi juga oleh faktor di luar agama, seperti kepentingan politik dan ekonomi yang memanfaatkan isu agama. Bisa dikatakan, politisasi agama dan komodifikasi agama turut serta mewarnai konflik bernuansa agama di masyarakat. Dari sekian faktor itu, yang mendasari argumen tulisan ini adalah konflik yang berlatarbelakang perbedaan agama dan pemahamannya atas agama, dan tulisan ini bermaksud menyuguhkan tawaran pemikiran untuk meminimalisir munculnya konflik tersebut, setidaknya secara epistemologis.
Beberapa pertanyaan yang dibahas secara deskriptif-kritis dalam tulisan ini adalah: Bagaimana agama (Islam) itu dipahami? Bagaimana sejatinya beragama itu? Bagaimana agama memandang dan menyikapi hubungan antara umat beragama? Dan bagaimana sejatinya umat beragama menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di Era Digital ini?
Problem Beragama
Ada dua kata kunci yang perlu ditegaskan perbedaannya untuk mengetahui bagaimana agama itu dipahami, yakni agama dan beragama. Istilah agama mengacu pada ajarannya, sedang beragama mengacu pada subyeknya. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak selamanya sejalan. Seseorang disebut tidak sejalan dengan agama, jika dalam beragama dia mengabaikan ajaran agamanya. Untuk mengetahui, apakah seseorang itu beragama sejalan dengan ajaran agamanya ataukah tidak, dan bagaimana sejatinya orang beragama, terlebih dulu saya akan mendeskripsi watak ajaran agam (Islam) itu sendiri, baru menjelaskan bagaimana seseorang beragama.
Pertama, Islam adalah agama moderat. Moderatisme Islam bisa dilihat dari penggunaan istilah, serta beberapa indikasi yang ditampilkan al-Qur’an. Istilah moderasi disepadankan dengan istilah wasathiyah dalam bahasa arab. Secara semantik, istilah wasathiyah mempunyai ragam makna, dan makna-makna itu sering digunakan, baik di dalam al-Qur’an maupun pemikiran Islam, yakni keadilan, istiqomah, kebaikan, keamanan, kekuatan, dan kesatuan.
Di dalam al-Qur’an, istilah wasathiyah dengan berbagai bentuknya disinggung sekitar empat kali, dan bentuk-bentuk itu dikaitkan dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam (al-Baqarah: 143) digunakan bentuk “wasathan”, dan dikaitkan dengan istilah ummat, sehingga muncul ungkapan “ummatan wasatha”; di dalam (al-Baqarah: 238) digunakan bentuk “al-Wustha”, dan dikaitkan dengan ibadah shalat wajib, sehingga muncul ungkapan “al-Shalat al-Wustha”; di dalam (al-Qolam: 28) digunakan bentuk “awsathun”, dan dikaitkan dengan perkataan suatu kelompok, sehingga muncul ungkapan “qala awsathuhum”; di dalam (al-Maidah: 89) digunakan bentuk “awsathun” sehingga muncul ungkapan “min awsathima”; dan di dalam (al-Adiyat: 4-5) digunakan bentuk “wasathna”, sehingga muncul ungkapan “fawasathna bihi”.
Al-Qur’an juga menampilkan beberapa ayat yang menunjukkan indikasinya pada ajaran bahwa yang tengah-tengah merupakan perkara yang paling baik (khairul al-umuri awsathuha), dan ayat-ayat itu berbicara tentang kasus yang berbeda-beda. Al-Qur’an (Al-Baqarah: 68) berbicara tentang Sapi Betina yang diperdebatkan orang-orang bani Israil; (al-Isra’:29) berbicara tentang sifat kikir yang disebut belenggu; (al-Isra’: 110) berbicara tentang suara yang sejatinya tidak terlalu nyaring dan terlalu pelan ketika mengerjakan ibadah shalat; (al-Furqan: 68) berbicara tentang larangan berlebihan dalam berberinfaq; (al-Baqarah: 201, al-Qashash:77) berbicara tentang keharusan menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat; (al-Jumu’ah: 9-10) berbicara tentang hubungan shalat jum’at yang merupakan urusan akhirat dengan mencari harta yang merupakan urusan duniawi; dan (al-Maidah: 87-88) berbicara tentang larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.
Indikasi moderatisme Islam juga ditunjukkan oleh penegasan al-Qur’an bahwa para nabi dan khususnya nabi Muhammad diutus untuk bersikap moderat “menegakkan keadilan” (al-Hadid: 25), dan pada saat yang sama, diperintah untuk mengatakan kepada kaum Ahli Kitab agar jangan berlebihan dalam beragama (al-Ma’idah:77). Sejalan dengan itu, ummat Islam yang menjadi ummat nabi Muhammad oleh al-Qur’an disebut sebagai ummat yang berada di tengah-tengah, “ummatan wasata” (al-Baqarah:143). Ummat yang berada di tengah-tengah itu oleh al-Qur’an disebut sebagai ummat yang paling baik “khairul ummah”, salah satu makna dari istilah wasathiyah, “kamu sekalian (wahai ummat Islam) adalah ummat terbaik (khairu ummah) yang dihadirkan Tuhan kepada umat manusia di dunia ini” (Ali Imran:110).
Kedua, sebagai agama yang “moderat”, Islam tidak selamanya dipahami secara moderat oleh para penganutnya. Ada kelompok yang memahaminya secara ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, dan ada kelompok yang memahaminya secara moderat.
Dalam sejarah gerakan Islam, kelompok yang selama ini disebut ekstrim kanan adalah Khawarij, Wahhabi dan Islamisme. Dikatakan ekstrim kanan, karena mereka cenderung “berlebihan” dalam beragama. Keberagamaan yang berlebihan itu terjadi karena mereka terlalu mengutamakan “menuhankan” teks (al-Qur’an dan hadis nabi), sembari mengabaikan akal dan konteks dalam memahami agama. Kebenaran tekstual yang mereka peroleh itu diyakini sebagai yang paling benar, sembari menyalahkan kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Mereka berprinsip “pendapat saya benar dan tidak mungkin salah, sedang pendapat orang lain salah dan tidak mungkin benar”. Mereka pun mempraktikkan keberagamaannya secara kaku, dan tidak jarang memaksakannya kepada pihak lain, sehingga bisa melahirkan kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik.
Di ujung sana, muncul kelompok beragama yang dinilai cenderung “mengabaikan” agama. Keberagamaan yang “abai” yang disebut ekstrim kiri ini mengutamakan akal dan konteks, sembari mengabaikan teks (al-Qur’an dan hadis nabi) dalam memahami agama. Kebenaran rasional dan kontekstual yang mereka peroleh itu seolah mengurangi nilai-nilai agama, berikut komitmennya dalam beragama. Mereka menganut prinsip berfikir “pendapat saya benar, begitu juga pendapat orang lain”. Umar bin Khattab, dan aliran rasionalis Islam abad pertengahan, Muktazilah bisa disebut sebagai wakil kelompok ini.
Sahabat nabi yang fenomenal itu dianggap, bukan hanya mengabaikan teks, tetapi juga mengabaikan ajaran normatif Islam. Beberapa di antaranya adalah: Umar menolak memberikan zakat kepada muallafati qulubihim yang secara normatif disebutkan di dalam al-Qur’an mendapat bagian zakat (al-Taubah: 60); menolak memberikan harta rampasan perang kepada mereka yang terlibat dalam peperangan melawan musuh yang secara normatif ditetapkan di dalam al-Qur’an (al-Anfal:1); dan tidak memotong tangan pencuri “di masa paceklik” yang secara normatif ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur’an (al-Maidah:38).
Sementara itu, Muktazilah mengutamakan bahkan “menuhankan” akal daripada teks (al-Qur’an dan hadis nabi) dan konteks. Menurut mereka, akal dengan sendirinya bisa mengetahui perkara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang zalim dan yang adil, tanpa bantuan wahyu Ilahi. Menurut mereka, nilai yang baik dan yang buruk terletak pada dirinya sendiri, bukan pada yang lain. Siapapun, termasuk Tuhan menurut mereka “wajib” berbuat baik, berbuat benar dan bertindak adil. Begitu juga, manusia dan Tuhan wajib menghindari perbuatan buruk.
Sedang kelompok moderat mengambil posisi yang tidak “berlebihan” dan juga “tidak abai” dalam beragama. Keberagamaan yang moderat itu lahir dari suatu metode yang memadukan secara dialogis antara teks (al-Qur’an dan hadis), akal dengan konteks. Kebenaran moderat yang mereka peroleh itu mengakomodir dua kecenderungan: kanan dan kiri. Mereka menganut prinsip berfikir “pendapat saya benar, tetapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tetapi ada kemungkinan benar”. Kelompok ini diwakili para pendiri mazhab pemikiran Islam, seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hambal dalam bidang fikih; Imam Asy’ari dan Imam al-Maturidi dalam bidang kalam; Imam al-Junaidi dan Imam al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Mereka semua dikenal dengan nama Ahlussunnah wa al-Jama’ah, yang dinilai sebagai mazhab jalan tengah.
Beragama Secara Moderat
Secara teoritis, masing-masing kelompok itu bisa bergeser dan berubah posisi. Kelompok ekstrim kanan bisa berubah menjadi ekstrim kiri dan moderat (terlepas dari prinsip berfikirnya yang kaku), begitu juga sebaliknya; kelompok ekstrim kiri bisa berubah menjadi moderat; dan kelompok moderat bisa berubah menjadi ekstrim kanan dan atau ekstrim kiri. Pergeseran ini sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam sebuah pemikiran, karena realitas yang mendasari lahirnya kelompok-kelompok itu senantiasa mengalami perubahan. Pergeseran itu terkadang membawa dampak positif misalnya, ketika kelompok ekstrim kanan dan kiri bergeser menjadi moderat, terkadang juga membawa dampak negatif, misalnya ketika kelompok ekstrim kiri dan kelompok moderat bergeser menjadi ekstrim kanan.
Kelompok ekstrim kiri dan kelompok moderat bisa berubah wujud menjadi ekstrim kanan jika terjadi pergeseran paradigmatik, dari rasionalisme dan moderatisme sebagai paradigma dalam beragama, bergeser ke rasionalisme dan moderatisme sebagai ideologi. Pergeseran itu bisa terjadi jika rasionalisme dan moderatisme beragama itu dibakukan sebagai ajaran formal Negara. Secara epistemologis, pergeseran ini tentu saja membawa dampak serius. Ketika masih dalam posisinya sebagai paradigma, rasionalisme dan moderatisme masih berproses terus menerus dan terbuka atas kehadiran yang lain. Tetapi ketika keduanya berubah wujud menjadi ideologi, ia berhenti berproses dan tertutup dari kehadiran yang lain.
Meminjam analisis Khaled Abou el-Fadl, pergeseran paradigma beragama itu dapat menyebabkan terjadinya pergeseran otoritas, yakni dari otoritas persuasif, dimana sebuah pemikiran diikuti karena adanya kesamaan epistemologis antara pihak yang mengikuti dengan pihak yang diikuti, ke otoritas koersif, dimana sebuah pemikiran diikuti bukan karena adanya kesamaan epistemologis antara keduanya, melainkan karena ada “paksaan” yang bersifat stuktural di dalamnya. Si A mengikuti pemikiran si B, bukan karena si A sepakat dan sejalan dengan pemikiran si B, melainkan karena si B itu adalah atasannya si A.
Implikasi lanjutan dari pergeseran itu adalah lahirnya kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik. Muktazilah yang menjadi simbol rasionalis Islam klasik dan sudah berubah wujud menjadi ideologi negara pada masa kekhalifahan Abbasiyah “memaksa” Ahmad bin Hambal untuk mengakui pemikiran “al-Qur’an itu diciptakan”. Ketika Ahmad bin Hambal tidak bersedia mengikuti paksaan itu (kekerasan wacana), tentu saja dia mendapat hukuman yang setimpal (kekerasan fisik) dari penguasa kala itu.
Untuk menghindari terjadinya pergeseran-pergeseran itu pada kelompok moderat khususnya, dan agar ia tetap menjadi paradigma, saya perlu menampilkan pemikiran Lukman Hakim Saifuddin, yang menjadi pelopor pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia, yang membedakan “moderasi agama” dengan “moderasi beragama”. Yang pertama berbicara tentang esensi agama, yang kedua berbicara tentang subyek yang beragama. Esensi agama menurut Lukman adalah memanusiakan manusia, sehingga persoalan keagamaan sejatinya diselesaikan dengan cara yang manusiawi. Diantara cara yang manusiawi itu adalah beragama secara moderat yang kini dikenal dengan nama “moderasi beragama”.
Moderasi beragama diartikan sebagai “ikhtiyar beragama yang tidak berlebihan, sehingga tidak melampaui batas”. Pengertian sederhana itu didasarkan pada asumsi bahwa selalu terjadi penafsiran yang bukan hanya berbeda, tetapi juga berseberangan di kalangan penafsir kitab suci agama, yakni penafsiran yang berorientasi pada teks semata, sembari melupakan kontek; dan penafsiran yang terlalu mengutamakan akal pikiran, sembari mengabaikan teks. Maka pengertian sederhana tentang moderasi beragama itu bersifat interpretatif, bukan konseptual
Dalam pengertiannya yang lebih luas, moderasi beragama didefinisikan sebagai “cara pandang, bersikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi yang merupakan kesepakatan Bersama”. Definisi ini menegaskan bahwa moderasi beragama digunakan dalam konteks kehidupan bersama, bukan individu. Dalam konteks kehidupan bersama, sejatinya seseorang beragama secara moderat.
Pengertian yang luas itu dijabarkan oleh Lukman: Pertama, frase “dalam kehidupan bersama”. Maksudnya, penguatan cara pandang, sikap dan praktik moderasi beragama itu manyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan individu. Moderasi beragama tidak mengintervensi kehidupan pribadi. Kedua, frase “mengejawantahkan esensi ajaran agama” dimaksudkan bahwa beragama harus bersifat substantif yang selalu mengedepankan esensi daripada ritual atau simbol. Ketiga, frase, “yang melindungi martabat kemanusiaan” menegaskan bahwa moderasi beragama dibangun di atas kesadaran bahwa esensi agama adalah menjaga martabat kemanusiaan. Keempat, frase” membangun kemaslahatan umum” menandakan bahwa praktik beragama harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan invidu. Nilai-nilai di atas harus selalu berlandaskan pada frase kelima, yakni prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi”. Atas prinsip yang terakhir itu, maka beragama tidak boleh melanggar ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar.
Esensi beragama yang moderat itu kemudian diacukan pada sembilan kata kunci: kemanusiaan, kemaslahatan, keadilan, berimbang, taat konstitusi, kometmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penghormatan atas tradisi, yang itu semua diturunkan dari definisi dan indikator-indikator moderasi beragama. Sembilan kata kunci beragama itu menurut Lukman merupakan pokok inti dari agama, dan seseorang disebut tidak moderat dalam beragama jika mengabaikan pokok inti agama itu sendiri. Ajaran inti agama itu dimiliki semua agama, baik agama bumi (ardi) maupun langit (samawi).
Tentu saja, kesembilan kata kunci moderasi beragama itu bukan harga mati karena moderasi beragama adalah sebuah proses yang tak akan pernah berhenti. Moderasi beragama merupakan cara, jalan yang menempatkan dialog sebagai proses utama dalam memahami agama. Dialog terus menerus itu merupakan tugas para penafsir agama. Pemahaman mereka sejatinya tidak hanya berhenti pada teks kitab suci agama semata, yang membuat pemahaman menjadi tektualis karena melepaskan peran konteks, juga tidak hanya bertumpu pada konteks pembaca, yang membuat pemahaman menjadi dekontekstualisasi karena melepaskan peran teks, melainkan bertumpu pada proses dialog terus menerus antara teks kitab suci dengan pembaca dan masyarakat penggunannya yang senantiasa mengalami proses perubahan.
Nilai penting watak dialogis itu adalah ketika agama sudah masuk ke dalam ruang publik. Pada saat itu, agama berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan yang harus diatasi, seperti hubungan antara ummat manusia yang seagama, sewarganegara dan yang berbeda agama. Begitu juga agama berhadapan dengan budaya lokal, bentuk negara dan komitmen kebangsaan yanag berbeda-beda yang tentu saja berbeda dengan kondisi saat agama itu hadir. Di sinilah nilai pentingnya menegaskan sisi dialogis dari moderasi beragama. Karena, Islam dikatakan sebagai agama yang moderat bukan hanya dalam arti ajarannya yang melarang ekstrim kanan (tafrit) dan ekstrim kiri (ifrat), tetapi juga wataknya yang bersifat dialogis.
Watak dialogis Islam itu bisa dilihat pada dialog Islam dengan peradaban-peradaban besar, seperti peradaban Arab, peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Barat dan tentusaja dengan peradaban Nusantara. Dialog Islam dengan peradaban-peradaban itu membuat Islam menjadi kreatif dan produktif. Dialog Islam dengan peradaban Arab melahirkan disiplin keilmuan kalam dan fikih; dialog Islam dengan peradaban Persia melahirkan disiplin keilmuan tasawuf; dialog Islam dengan peradaban Yunani melahirkan disiplin keilmuan flsafat Islam; dialog Islam dengan peradaban Barat melahirkan disiplin keilmuan sains Islam; dan dialog Islam dengan peradaban Nusantara melahirkan Islam moderat yang merahmati semua warga negara.
Kemampuan Islam dalam berdialog dengan peradaban-peradaban besar itu, yang mampu mensintensiskan dua atau beberapa hal yang tidak saling berhubungan, bahkan mungkin saling bertentangan, menurut Gus Dur, menandakan betapa Islam itu pada kenyataannya bersifat kosmopolit. Kosmopolitanisme Islam ini terjadi karena Islam mengandung nilai-nilai universal. Jika nilai-nilai universal Islam dipahami secara dialogis, moderatisme Islam itu bisa dikatakan sebagai moderatisme yang kosmopolit. Ia tidak hanya terbuka menerima kehadiran yang lain, tetapi juga berdialog dengan yang lain.
Begitu juga kelompok moderat sejatinya terbuka, dan berdialog dengan kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri, karena adanya dua kelompok itu menandakan, agama juga mengandung dua dimensi teks yang bersifat ekstrim itu, sebagaimana adanya kelompok moderat dalam beragama menandakaan bahwa di dalam agama terdapat dimensi teks yang bersifat moderat. Dimensi ekstrim kanan teks itu misalnya ayat-ayat al-Qur’an yang menegaskan bahwa “barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, zalim, dan fasik (al-Maidah:44-45, 47) sebagaimana dipegang teguh kelompok Khawarij, sedang dimensi ekstrim kiri teks misalnya ayat-ayat al-Qur’an yang menekankan adanya kebebasan memilih bagi seseorang, apakah beragama ataukah tidak (al-Kahfi:29 dan al-Naml:91-93), serta ayat yang menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama.
Dengan dua watak dialogis Islam itu, moderasi beragama tidak akan bergeser atau berubah menjadi ekstrim tengah, atau moderat yang ekstrim. Melainkan moderat yang kosmopolit, yang senantiasa terbuka dan berdialog dengan yang lain. Dengan demikian, moderasi beragama tetap menjadi paradigma, yakni cara memandang, bersikap dan mengkresikan agama dalam kehidupan bersama. Sebagai paradigma, moderasi beragama tetap terbuka dalam memandang, menyikapi dan hidup bersama penganut agama lain.
Memandang dan Menyikapi Penganut Agama Lain
Penting dicatat, keragaman alam beserta isinya ini merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah wujud menjadi tunggal atau seragam, termasuk keragaman manusia. Keragaman yang faktual itu kemudian dinormatifkan di dalam al-Qur’an, baik keragaman wujud manusia itu sendiri (Hud: 118, al-Rum: 22, al-Hujurat: 13), maupun keragaman keyakinan (Hud: 118, Yunus:99, al-Taghghabun:2, al-An’am: 149, al-Ra’du: 31, al-Maidah: 48). Sebagai makhluk beragama, seseorang tidak hanya harus menerima keberadaan dan wujud dirinya yang berbeda dengan yang lain, termasuk keyakinannya, tetapi juga menghargai keberadaan dan wujud orang lain, termasuk keyakinannya yang berbeda.
Al-Qur’an memandang, keyakinan keagamaan merupakan urusan masing-masing individu (Yunus:100, al-Isra’:15). Sebagai urusan pribadi, manusia diberi kebebasan memilih antara beragama ataukah tidak beragama (al-Kahfi: 29, al-Naml: 91-93, al-Rum: 44, al-Fatir: 39, al-Zumar: 41, al-Taghghabun: 2), serta memilih agama tertentu yang ada di dunia ini, baik agama langit (samawi) maupun agama bumi (ardi). Manusia diberi kebebasan memilih, karena beragama itu, meminjam istilah yang digunakan Abdulkarim Soros, merupakan al-hak al-lazim bagi seseorang, suatu hak yang dimiliki seseorang tanpa ada hubungan apapun dengan pihak lain. Dia mau melakukan apapun bergantung pada dirinya, dan orang lain tidak bisa ikut campur atas keputusannya. Saya mempunyai hak untuk duduk atau pergi dari kursi yang ada di depan rumah saya. Orang lain tidak mempunyai hak menilainya: boleh atau tidak boleh. Orang lain hanya dikenai keharusan menghargai (al-taklif al-lazim).
Sebagai al-hak al-lazim, beragama tidak boleh dipaksakan (al-Baqarah:256), karena keberagamaan yang dipaksakan akan melahirkan keberagamaan yang munafik. Al-Qur’an banyak berbicara tentang melarang menjadi munafik. Nabi Muhammad pun dilarang memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam (Yunus: 99-100). Tugas nabi Muhammad hanya menyampaikan ajaran Islam (al-Syura:48, al-Nahl: 82), mengingatkan (al-Ghasiyah: 21-22, Qaf: 48), memberi kabar gembira (al-Furqan: 56), dan memberi peringatan akan siksa neraka bagi mereka yang melanggarnya (al-A’raf:188, Hud:12). Mengapa demikian? Karena yang berhak memberi petunjuk pada manusia hanyalah Allah (al-Baqarah: 272, al-Kahfi: 5-7, al-An’am: 35, al-Nisa’: 88, al-Qashash: 56, al-Fatir: 8), sehingga paksaan dalam beragama tidak ada gunanya jika Allah belum menghendakinya untuk memberi petunjuk.
Atas dasar pandangan al-Qur’an itu, sikap umat Islam terhadap penganut agama lain sejatinya adalah berta’aruf (al-Hujurat: 13), mengajak dengan cara yang bijaksana (hikmah), memberi nasihat dengan cara yang baik, dan kepada mereka yang menentangnya, didorong untuk berdialog dengan cara yang paling baik (al-Nahl: 125, Saba’: 24-25). Al-Qur’an mendorong penganutnya untuk bersikap lemah lembut kepada mereka, tidak boleh menghina agama dan tuhan mereka. Al-Qur’an juga mendorong penganutnya untuk bertoleransi (al-Kafirun), dan bersikap adil kepada mereka (al-Mumtahanah: 8). Jika terhadap perbedaannya diharuskan untuk bertoleransi, terhadap kesamaannya dengan mereka sejatinya diadakan kerjasama demi kemaslahatan bersama, baik antar sesama penganut agama tertentu ataupun berbeda agama.
Menciptakan Kultur Moderasi Melalui Literasi Digital
Moderasi beragama yang terlihat ideal itu saat ini menghadapi tantangan ganda. Selain tantangan yang datang dari dalam umat Islam sendiri, yakni penganut agama yang ekstrim, baik kanan maupun kiri, juga datang dari luar, yakni pengaruh tegnologi digital. Tentu saja bukan tentang tegnologinya, melainkan perannya yang menggantikan manusia. Sebab, saat ini, tegnologi sudah menjadi kultur, “kultur digital” karena hampir segala tindakan dan komunikasi manusia bergantung pada tegnologi digital.
Tegnologi digital dengan berbagai perangkatnya bisa menggantikan posisi manusia, karena tegnologi ini sudah bisa berfikir dan memberikan solusi layaknya manusia. Seseorang yang mau bepergian, tidak perlu bertanya kepada manusia, kepada peta atau denah yang biasanya menjadi petunjuk arah bagi seseorang yang hendak bepergian ke suatu tempat yang belum pernah didatanginya. Mereka cukup menggunakan alat bernama GPS, yang dengan canggihnya bisa memberitahukan dan mengantarkan kita menuju tempat tujuan. Seseorang yang hendak mencari informasi tentang ilmu pengetahuan dan agama, tidak perlu bertanya kepada pakar dan ulama’. Cukup bertanya kepada Google dengan mengetik apa yang hendak dicari dan dipelajari. Google akan menjawabnya dengan sangat cepat, melebihi kecepatan manusia. Begitu juga seeorang yang hendak membuat tulisan, dia cukup menggunakan perangkat canggih bernama AI (Artificial Intelligence). Hanya dalam hitungan menit, tulisan anda akan jadi.
Kemampuan yang diberikan tegnologi digital itu tentusaja tidak gratis. Justru ia menjadi tantangan tersendiri. Sebab, masyarakat mulai meninggalkan pakar agama untuk mengetahui agama, dana beralih pada tegnologi digital. Dan pakar agama pun dianggap sudah mati, sebagaimana matinya pengarang dalam tradisi literasi. Sementara itu, informasi yang melimpah di internet itu banyak berisi sampah, hox, fitnah, ujaran kebencian, dan konten-konten Islam yang ekstrim. Ketika kita mengetik tema tertentu tentang Islam, yang muncul adalah konten-konten yang ekstrim itu, seperti jihad, mati sahid, bid’ah, dan sebagainya.
Sejalan dengan tantangan-tantangan itu, para penggerak moderasi beragama sejatinya tidak hanya mampu menguasai paradigma moderasi beragama, yang oleh Kementerian Agama RI sudah ditransformasikan melalui pendirian Rumah Moderasi Beragama (RMB) di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Swasta, dan Lembaga Keagamaan yang berada di bawah naungan Kemenag RI, serta memassifkan program wakrshop, FGD dan berbagai pelatihan, penelitian, penulisan buku melalui program Litabdimas, termasuk melalui KPM moderasi beragama. Mereka juga harus menguasai literasi digital. Mereka perlu dibekali, bukan hanya tentang bagaimana menguasai dan menggunakan tegnologi digital, tetapi juga tentang bagaimana mengisinya dengan konten-konten Islam moderat, serta mentransformasikannya kepada Masyarakat secara massif, sehingga beragama secara moderat menjadi kultur “kultur moderasi”, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Harapannya, ketika seseorang mengetik tema-tema tertentu tentang Islam di Google, yang muncul adalah ajaran Islam yang merahmati, yang memanusiakan manusia, yang menghargai perbedaan, yang menghargai budaya lokal, dan tentusaja berkomitmen dengan negara dan bangsa Indonesia yang ber-Bhinnika Tunggal Ika ini.
Dari sajian di atas bisa disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang moderat, dan karena itu, umat Islam sejatinya beragama secara moderat. Tetapi, moderat yang kosmopolit, bukan moderat yang ekstrim. Moderat yang kosmopolit, yakni moderat yang senantiasa menjadikan dialog sebagai wataknya, bisa dijadikan paradigma dalam beragama, karena ia tidak hanya terbuka menerima kehadiran yang lain, tetapi juga berdialog kreatif dan produktif dengan yang lain. Agar bisa diterima Masyarakat yang kini hidup dalam era kultur digital, para penggerak moderasi beragama sejatinya melek literasi digital, sehingga beragama secara moderat menjadi kultur, baik di dunia nyata maupun dunia maya.