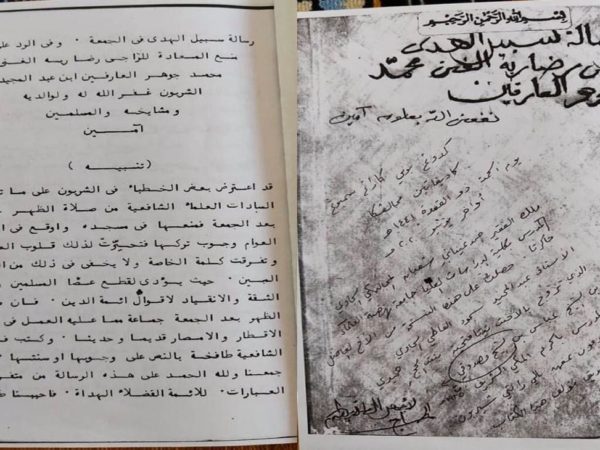Tulisan Gus Dur (2012:67) yang berjudul “Tuhan Tidak Perlu Dibela” menceritakan seseorang yang bernama X yang mengembara mencari kebenaran Islam yang ia pahami dengan Islam yang ia lihat, akhirnya di persimpangan jalan ia bertemu dengan seorang guru Tarekat yang menasehatinya dengan mengutip kata-kata Al-Hujwiri, “Bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau “Dia menyulitkan” kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang-orang menyerang hakikat-Nya. Yang ditakuti berubah adalah persepsi manusia atas hakikat Allah, dengan kemungkinan kesulitan yang diakibatkannya.”
Telah bertahun-tahun kata-kata itu melekat dibenak para pecinta Gus Dur, akan tetapi sangat sulit sekali menularkan kemelekatan tersebut terhadap orang-orang yang berada di luar lingkaran pecinta Gus Dur. Jangankan untuk memahaminya, untuk menerima kebenaran kata-kata tersebut alangkah sulitnya. Mungkin karena terbesit di hatinya, Gus Dur bukan berasal dari golongan yang ia kagumi, bahkan cenderung memiliki dendam tersendiri terhadap Gus Dur karena bersebrangan dengan golongan tersebut.
Golongan-golongan inilah golongan yang menempatkan Islam sebagai agama yang penuh formalisme dan bersifat ideologis, di mana golongan ini sejak awal telah dikritik oleh Gus Dur dalam tulisan dan ceramah-ceramahnya. Golongan ini menganggap Islam sebagai sesuatu yang patut dan harus dimonumenkan, tak tersentuh zaman dan bersifat transenden. Islam dipandangnya sebagai agama yang telah selesai penafsirannya, sehingga zaman awal-awal Islam lahir adalah zaman paling ideal untuk diimplementasikan di setiap zaman.
Tidak perlu lagi tafsiran Islam yang kontekstual karena dianggapnya hanya menjadikan Islam lemah, tidak perlu lagi bersusah payah menggali “makna” dari hukum syari’ah untuk menciptakan zaman ideal karena dianggapnya masa depan Islam yaitu zaman Nabi dan para Sahabatnya masih hidup, tidak dibutuhkan lagi ilmu-ilmu yang berada di luar Ilmu syari’ah dan tidak dibutuhkan lagi sistem kehidupan yang asal muasalnya berada di luar ajaran agama Islam, karena Islam itu sudah lengkap sehingga tidak perlu lagi repot-repot mencari kebenaran di luar Islam.
Dengan paradigma yang demikian, menjadikan mereka sangat reaktif terhadap sesuatu yang dianggapnya menyerang Islam. Islam yang dianggapnya agama yang mulia, sangat mudah sekali dinodai hanya dengan kata-kata yang menyerang kemuliaannya. Sebagai contoh Islam golongan ini, yaitu mereka yang “sangat reaktif” ketika Presiden Preancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa “Islam adalah agama yang tengah mengalami krisis dan disamakan dengan terorisme”, mereka dengan serta merta kehilangan nalar kritis dan akal sehat mereka.
Mereka gampang tersulut api amarah sehingga bertindak di luar akal sehat mereka. Mereka bukan hanya mengutuk tetapi juga menyatakan “boikot” produk yang berasal dari Perancis. Dengan harapan ekonomi negara Perancis menjadi lemah dan pembelaannya terhadap agama Islam diridloi oleh Allah. Tetapi anehnya, mereka melakukan boikot produk Perancis dengan memborong barang-barang tersebut dengan membakarnya secara cuma-cuma, akhirnya yang terjadi bukan “boikot” tetapi justru “pemborongan” produk Perancis secara besar-besaran.
Apabila kita pahami kata-kata Al-Hujwiri yang dikutip oleh Gus Dur dalam tulisannya, kita akan memahami bahwa seharusnya segala informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu “dilayani”. Cukup diimbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang “positif-konstruktif”. Kalau pun dari “serangan” yang dikeluarkan “dianggap” membahayakan cukup dijawab dengan jawaban yang mendudukan persoalan secara “dewasa” dan biasa-biasa saja, tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan dengan mencari-cari kesalahan yang lainnya.
Gus Dur pernah berkata, “Islam memang perlu dikembangkan. Tetapi tidak untuk dihadapkan pada “serangan” orang. Karena kebenaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan seseorang. Tuhan tidak perlu dibela, walaupun Dia tidak akan menolak untuk Dibela.” Islam bagi Gus Dur bersifat kosmopolitan, kebenarannya akan mudah diterima di mana saja. Bukan terletak pada “formalitas-formalitas” tertentu, tetapi ia dapat mengekspresikan dirinya dalam wujud yang paling mudah dikenali oleh pemeluknya.
Pembelaan kepada Tuhan yang “diformalitaskan” justru akan membuat batas bahwa Islam hanya dimiliki oleh suatu golongan tertentu saja. Kemudian dari hal tersebut melahirkan sikap fanatik yang membabi buta, ingin menghabisi segala sesuatu yang “berbeda” dengan kebenaran yang ia yakini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fitrah Islam yang rahmatan lil ‘alamin, di mana Islam yang seharusnya merangkul yang berbeda dan menjadikan perbedaan sebagai “anugerah” untuk membangun kekuatan.
Dalam tulisan Gus Dur (2006 :67-69) yang berjudul “Islamku, Islam Anda dan Islam Kita” beliau menjelaskan bahwa agama Islam dipahami oleh pemeluknya tidaklah tunggal. Karena agama Islam dipahami terbatas oleh ruang dan waktu si pemeluknya. Penafsiran dan pengalaman dalam menjalankan perintah agama menjadikan unsur utama dalam membentuk pemahaman keagamaan seseorang, itulah yang disebut Gus Dur sebagai “Islamku” dan “Islam Anda”.
Dalam pemahaman “Islamku” dan “Islam Anda” ini sangat bergantung kepada aspek yang sangat pribadi dari seseorang, sehingga pemahaman “Islamku” dan “Islam Anda” ini tak dapat dipaksakan kepada orang lain, karena ia bersifat sangat privasi dan cenderung eksklusif (baca: memiliki kekhasan tersendiri) untuk masing-masing individu. Berbeda dengan pemahaman tentang “Islam Kita”, yang mencoba mendialogkan pemahaman “Islamku” dengan “Islam Anda” yang memiliki kekhasannya masing-masing.
“Islam Kita” adalah sebuah upaya keprihatinan atas masa depan Islam yang pada perjalanannya terjadi benturan pemahaman yang dianggapnya “Islam yang lebih baik” antara “Islamku” atau “Islam Anda”. “Islam Kita” merupakan ruang dialog atas perbedaan yang terjadi untuk mewujudkan kehidupan Islam yang rahmatan lil ‘alamain. Sehingga “Islam Kita” ini bersifat kosmopolitan, tidak boleh diklaim oleh satu golongan saja tetapi pemahaman tentang Islam menjadi milik bersama.
Upaya dalam menciptakan ruang dialog untuk mewujudkan “Islam Kita” tidak boleh terjadinya tindakan yang represif dan anarkistis, serta menghormati perbedaan yang dimiliki oleh liyan. Persamaan pemahaman haruslah dilakukan melalui dialog-dialog di ruang terbuka yang dipenuhi kemufakatan dan membutuhkan waktu dalam prosesnya, tidak bisa dipaksakan dalam waktu yang sangat singkat.
Satu hal yang paling penting yaitu harus terciptanya ruang dialog dan komunikasi yang intens antara “Islamku” dan “Islam Anda”. Apabila ruang dialog yang diciptakan terjadi kemandegan, maka yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten menjalin dialog untuk mengikis perbedaan-perbedaan pemahaman yang terjadi. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selama 23 tahunnya. Selama puluhan tahun beliau berdakwah tidak sekalipun dianggapnya sebagai sebuah kegagalan dalam menciptakan ruang dialog dengan “orang-orang” di sekitarnya yang “berbeda”, hingga akhirnya beliau berhasil meyakinkan “Islam” bukan hanya “milikku” atau pun “milik anda”, tetapi Islam adalah “milik Kita”.
Semangat ini diwariskan kepada para Sahabatnya dalam menjalin perbedaan di antara mereka. Mereka selalu menciptakan ruang dialog yang intens untuk menghadapi perbedaan. Meskipun pada akhirnya terjadi perpecahan, tetapi mereka berhasil mewariskan semangat untuk menciptakan “ruang dialog” kepada generasi berikutnya. Hingga terciptanya madzab-madzab tak membuat Islam secara subtansi terpecah justru membuat Islam dipenuhi oleh perbedaan yang indah dan saling menyapa kebenarannya.
Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa golongan Islam yang bersikap represif tidak akan berlangsung lama keberadaannya, tetapi golongan Islam yang “mau dan mampu menciptakan ruang dialog”, merekalah yang mampu mempertahankan eksistensinya. Karena Islam yang rahmatan lil ‘alamin adalah Islam yang benar-benar menyebarkan “kasih sayang” dengan dialognya dan menjadi oase di tengah keringnya peperangan antar klaim kebenaran. []