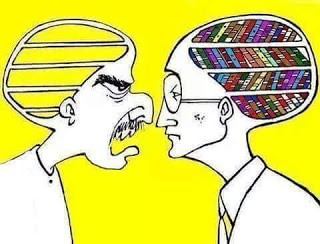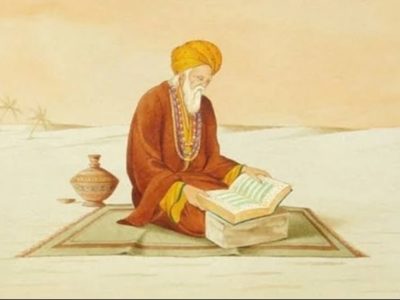Secara luas, jamak diketahui jika Shalawat Badar diciptakan oleh KH. Ali Manshur. Setidaknya sejak Muktamar ke-25 NU di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989). Saat itu, Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid, mengungkapkannya ke publik seraya menganugerahkan tanda jasa Bintang NU atas kontribusi almarhum Kiai Ali Manshur. Lalu, pernyataan tersebut diulang kembali saat beliau menjadi presiden Republik Indonesia dan membuka Muktamar NU di PP. Lirboyo, Kediri (2000).
Namun, tak banyak orang yang tahu, jika karya monumental tersebut diciptakan di Banyuwangi. Maklum saja, Kiai Ali bukanlah orang Banyuwangi asli. Beliau adalah putra KH. Manshur bin Siddiq yang berasal dari Jember. Di daerah seberang Gunung Kumiter itu, bayi bernama Ali Erkham itu lahir. Kemudian tumbuh besar di kampung ibunya di Rangel, Tuban. Di sini pula akhirnya jasad Kiai Ali terbaring untuk selamanya.
Di Tuban ini setiap tahunnya diperingati haul atas wafatnya Kiai Ali. Banyak peziarah yang juga mendatangi tempat ini. Dari sinilah, mungkin bayangan orang, akan mengira jika Shalawat Badar pun diciptakan di Tuban. Namun, ternyata tak demikian.
Kiai Ali ini dapat dikatakan bagian generasi NU yang digerakkan oleh KH. Abdul Wahid Hasyim untuk mengabdikan diri di Kementerian Agama. Saat itu, Kiai Wahid meminta tolong kepada keluarga besar NU guna membantu kementerian yang belum ada portofolionya itu. Tak ada bencmarking yang serupa dari kementerian di negara lain. Sehingga, dalam ijtihad membangun Kemenag itu, Kiai Wahid menggerakkan SDM terbaik NU untuk turut membantunya. Dari pusat hingga ke kecamatan. Termasuk di antaranya adalah pamandanya, KH. Achmad Siddiq Jember.
Dari karirnya di Kemenag itu, mengantarkan Kiai Ali berpetualang di sejumlah daerah. Di Sumbawa, Singaraja hingga di Banyuwangi. Di tempat yang terakhir ini, beliau mengabdi di Kemenag sedari 1959 hingga 1967. Sebagaimana di tempat-tempat lainnya, Kiai Ali selama di Banyuwangi juga aktif dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Bahkan, pada 1960, beliau dipercaya menjadi Ketua Cabang NU Banyuwangi.
Dinamika sosial-politik-keagamaan di Banyuwangi pada dekade 50-an hingga paruh pertama dekade 60-an tentulah berbeda dengan daerah lainnya yang pernah disinggahi oleh Kiai Ali. Baik di Jember, Tuban, Sumbawa, ataupun Bali. Politik ideologis yang terjadi selama masa Orde Lama itu, memang mempengaruhi keseharian masyarakat. Nyaris di seluruh sendi kehidupan.
Pada saat itu, partai-partai besar terlibat perseteruan yang sengit. Baik PKI, PNI, NU ataupun Masyumi (tahun 1960 partai ini dibekukan oleh pemerintah karena terlibat pemberontakan). Jika daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh Kiai Ali, memiliki konstilasi politik yang didominasi satu partai tertentu. Hanya di Banyuwangi yang konstilasinya saling berebut. Antara NU dan PKI.
Pada pemilu 1955, NU keluar sebagai pemenangnya. Berhasil memperoleh 160.989 suara. Bahkan, mampu mengantarkan satu tokoh terbaiknya ke Majelis Konstituante (KH. Harun Abdullah) yang saat itu ditentukan melalui pemilihan langsung.
Akan tetapi, prestasi tersebut tak bertahan lama. Dua tahun kemudian, saat digelar pemilu daerah untuk menentukan anggota DPRD Tk. I Jawa Timur dan DPRD Tk. II Banyuwangi, PKI berhasil mengambil alih pemenangnya. PKI berhasil mengantarkan 13 orang kadernya menjadi anggota DPRD Banyuwangi 1957. Sementara itu, NU hanya bisa mengutus 11 orang kadernya.
Kondisi yang demikian, sudah barang tentu menjadikan rivalitas NU dan PKI di bekas Kerajaan Blambangan ini, berlangsung sengit. Menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Di ranah pendidikan, umpamanya. Dari SMP, SMA, hingga universitas semua terjadi kontestasi. Ketika pelajar yang berhaluan komunis mendirikan organisasi, anak-anak NU tak mau kalah. Mereka juga menggerakkan IPNU-IPPNU.
Begitu pula di Universitas Tawangalun (Kelas jauh Fakultas Hukum dari kampus yang kini dikenal dengan UNEJ). Saat itu, PMII dihalangi berdiri karena banyak jajaran rektoratnya yang berhaluan komunis. Berbeda dengan CGMI yang justru mendapatkan karpet merah. Sampai-sampai Wakil Ketua PBNU Subchan ZE angkat suara soal itu.
Yang lebih panas lagi, tentu saja di bidang seni-budaya. Sebuah bidang yang menjadi ujung tombak dalam setiap kampanye politik. NU dan PKI terlibat persaingan yang sengit. Saat PKI dengan Lekra-nya menggalakkan seni angklung dengan nama Sri Muda, NU juga membuat Orkes Melayu Sinar Laut sebagai pesaingnya. Saat PKI menggunakan tari Gandrung, NU membuat pula tari Kuntulan. Ketika tokoh PKI Banyuwangi, M. Arief , berhasil mempopulerkan lagu Genjer-Genjer, NU kelabakan. Tak ada sebuah “lagu” yang bisa menjadi pemersatu warga Nahdliyin kala itu.
Di tengah situasi demikian, Kiai Ali datang ke Banyuwangi. Kemampuannya dalam ilmu arudl dan bahasa Arab yang mumpuni serta terbiasa membuat syair, menjadikan Kiai Ali lantas membuat shalawat yang menggambarkan dinamika zaman; Shalawat Badar!
Memang, Shalawat Badar diciptakan sebagai bagian dari spiritualitas Kiai Ali. Namun, tak bisa dipungkiri, situasi zaman tergambar jelas dalam syair dan pilihan diksi yang dipergunakan Kiai Ali di shalawat tersebut. Penggunaan kata “Badar” pada shalawat tersebut yang merujuk pada sebuah peperangan yang heroik antara 313 pasukan muslim berhasil mengalahkan seribu pasukan kafir Quraisy telah mengindikasikan demikian kuatnya nuansa kontestasi yang melatarbelakangi zaman penciptaan shalawat tersebut.
Hal ini juga diperkuat oleh kajian linguistik terhadap Shalawat Badar oleh RM Imam Abdillah dalam tesisnya yang berjudul “Puisi Keagamaan dan Politik: Studi Selawat Badar dan Politik Nahdlatul Ulama di Indonesia Masa Orde Lama”. Ia mengkaji 28 bait shalawat tersebut. Dari sana, ada beberapa kosakata yang berkaitan erat dengan keadaan zaman. Salah satu pada bait syair di bawah ini:
الهي نجيناواكشف # جميع اذية واصرف
مكاءدالعد والطف # باهل البدرياالله
Ilahii najjinaa waksyip # jamii’a adiyyatin washrif
Makaa’ida walthuf # biahlil badriyaa Allah
Lafadz “makaa’id” (مكاءد) yang berarti “tipu daya” dalam bait kedelapan tersebut, memiliki makna konotatif yang menyiratkan pada upaya “tipu daya” yang dilakukan PKI di masa itu. Salah satunya adalah doktrin tujuh setan desa. Di mana, mereka menganggap para pemilik tanah yang cukup luas dianggap sebagai setan yang harus direbut dan didistribusikan kepada rakyat. Dari doktrinasi yang demikian, banyak rakyat yang terperdaya sehingga melakukan aksi sepihak.
Aminuddin Kasdi dalam “Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur 1960-1965” mencatat perihal aksi sepihak PKI di Banyuwangi. Seperti yang dialami oleh H. Saleh dari Sumbersari, Srono. Salah seorang magersari-nya yang merupakan anggota BTI, Seran, tak mau membagi hasil panen sebagaimana kesepakatan semula. Seran menginginkan pembagiaan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (2001: 201-3).
Kejadian demikian hampir terjadi di berbagai tempat di Banyuwangi. Seperti di Genteng, Tegaldlimo, Cluring, Kalibaru, Rogojampi dan beberapa tempat lainnya.
Masih merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Imam Abdillah, lafadz lain yang memiliki makna konotatif pada konteks saat itu, adalah lafadz al-‘ashiin (العاصين). Secara harfiah, lafadz tersebut bermakna “orang-orang yang memberontak”.
Dalam sejarah republik, PKI tercatat dua kali melakukan pemberontakan. Selain pada 1965, juga pernah melakukannya pada 1948 di Madiun. Hal ini menimbulkan trauma yang cukup mendalam di benak kaum santri. Lebih-lebih pada masa itu, banyak kalangan kiai dan santri yang menjadi korban keganasan Muso cs. Pandangan yang demikian, besar kemungkinan, juga dialami oleh Kiai Ali Manshur. Sehingga ia mengabadikannya pada bait kesembilan sholawat tersebut.
الهي نفس الكربا # من العصين والعطبا
Ilahii nafsil kurba # minal ‘ashiina wal uthba
“Ya Tuhanku, lenyapkanlah kesusahan dan kerusakan akibat dari perbuatan orang-orang yang memberontak”.
Dari uraian di atas, kiranya dapat kita andaikan, jika Kiai Ali tak pernah ditugaskan di Banyuwangi, mungkin shalawat lainnya yang beliau anggit. Dengan demikian, jika saat ini shalawat tersebut mendunia, ada kontribusi Banyuwangi di dalamnya. (*)