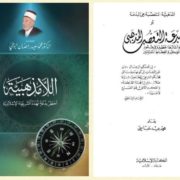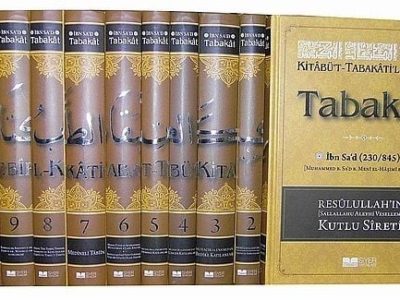Al-Anbiya: 34
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَۗ اَفَا۟ىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ
“Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau (Muhammad); maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?”
Beberapa kesimpulan ahli tafsir tentang ayat ini, antara lain:
Pertama: Setelah merampungkan perbincangan seputar kenabian, Allah menceritakan tentang perkataan kaum musyrik perihal nabi Muhammad Saw, bahwa sehebat apapun dakwah yang gencar dilakukan Nabi, pada akhirnya beliau akan meninggal dan orang-orang musyrik akan lepas dari semua seruannya, tentang hari kiamat, hari kebangkitan dan ajaran lainnya. Bahkan mereka sampai berkata, “Jika engkau memang benar, kapankah apa yang katakan akan terjadi?”
Lalu, ayat ini merupakan jawaban dari semua omongan mereka, peringatan dan sekaligus ancaman; di sisi lain, ayat ini juga diturunkan untuk menghibur Nabi Saw atas perkataan orang-orang musyrik yang tak bertanggung jawab itu. Demikianlah Syaikh Thabathaba`i memulai pembahasan ayat ini.
Tentang kalimat wa mā ja’alnā libasyarim min qablikal-khuld (Dan Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau (Muhammad)) terdapat tiga pendapat, tulis Imam ar-Razi dalam tafsirnya: (a) Imam Muqatil berkata bahwa ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa nabi Muhammad Saw tidak akan meninggal dunia, lalu turunlah ayat ini sebagai respon yang menyalahkan asumsi tersebut. (b) Sebagian orang kafir memprediksi bahwa Nabi akan meninggal, lalu mereka akan bahagia atas kematian tersebut. Bahkan mereka memang selalu mengharap keburukan akan menimpa Nabi, sebagaimana diceritakan al-Quran dalam ayat yang berbeda:
اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ
“Bahkan mereka berkata, “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya”.” (QS. Ath-Thur: 30)
Lalu Allah memperingatkan mereka dengan ayat ini bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang abadi, jika Nabi yang dicintai Allah saja bisa meninggal apalagi dengan orang-orang yang ingkar dan mendustakannya?!
(c) Ketika jelas bahwa nabi Muhammad adalah pemungkas para nabi, memungkinkan orang-orang beriman mengira bahwa seandainya Nabi meninggal tentu syariat yang dibawa beliau akan berubah, karena itu Allah menjelaskan dalam ayat bahwa keadaan nabi Muhammad serupa dengan para nabi terdahulu perihal kematian.
Kedua: Imam asy-Sya’rawi menunjukkan hal unik tentang ayat ini. Allah menceritakan bahwa Nabi akan dijemput kematian, sebagaimana tersurat dalam ayat,
اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۖ
“Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula).” (QS. Az-Zumar: 30)
Hal tersebut menunjukkan bahwa kematian merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya. Dalam ayat ini, menurut Imam asy-Sya’rawi, seakan Allah ingin berkata kepada Nabi, “Bahkan andaikata engkau meninggal, Wahai Muhammad, tak lain agar Kami menyegerakanmu memperoleh balasan terbaik atas beban dakwahmu yang begitu berat, dan engkau terlepas dari derita kehidupan dunia ini.” Demikianlah cara Allah menghibur (tasliah) Nabi Saw.
Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ayat ini berlaku dan sesuai dengan masing-masing pribadi: menjadi tasliah bagi Nabi Saw; sebagai kritik bagi orang mukmin yang berlebihan mencintai Nabi dan menganggapnya tidak akan meninggal; dan sekaligus mewujud ancaman mengerikan bagi orang kafir yang mengharap keburukan menimpa Nabi. Keunikan ini tak lain merupakan bentuk kecil dari sebagian mukjizat al-Quran yang sangat luar biasa.
Al-Anbiya: 35
كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤىِٕقَةُ الْمَوْتِۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗوَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.
Dalam ayat ini terdapat beberapa pandangan ulama, antara lain:
Pertama: Kata nafs (yang bernafas) dalam kalimat kullu nafsin żā`iqatul-maụt (setiap yang bernyawa akan merasakan mati) memiliki makna khusus, karena di dalam al-Quran kata nafs juga digunakan untuk Allah, semisal pada ayat,
…كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ…
“…Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya...” (QS. Al-An’am: 12)
…وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ
“…Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.” (QS. Ali ‘Imran: 28)
Atau manakala nabi Isa berkata kepada Allah,
…تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗاِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ
“…Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib.” (QS. Al-Maidah: 116)
Sekalipun pada ayat-ayat di atas Allah disebut sebagai nafs tentu tidak berarti Dia juga masuk dalam kategori kullu nafsin żā`iqatul-maụt (setiap yang bernyawa akan merasakan mati), karena kematian merupakan hal yang mustahil bagi-Nya. Sebab itu Imam ar-Razi mengatakan bahwa frasa kullu nafsin memiliki makna khusus.
Secara bahasa, kata nafs terdiri dari huruf n-f-s, yang memiliki makna dasar “keluarnya angin dengan cara apapun”. Dari kata ini muncul bentukan kata tanaffusa (bernafas) yang bermakna keluarnya udara dari rongga dada (paru-paru), demikianlah keterangan dari Maqāyis al-Lughah. Kata nafs juga diartikan sebagai “diri” karena setiap pribadi memang memiliki nafs masing-masing. Selain itu kata nafs bisa diartikan “darah” karena ketiadaan darah bisa membuat manusia mati. Karena begitu esensial, kadang sesuatu yang berharga juga disebut sebagai syai` nafīs.
Kedua: Pada hakikatnya kematian (al-maut) itu baik, demikian pendapat Imam asy-Sya’rawi, untuk menyegerakan ganjaran dan balasan terbaik kepada orang-orang saleh, dan untuk meniadakan keburukan dalam suatu masyarakat manakala yang meninggal adalah orang jahat. Kematian merupakan hukum semesta yang berlaku secara umum.
“Lalu bagaimanakah kematian dapat dirasakan?” persoalan mulai dimunculkan Imam asy-Sya’rawi. Kata żā`iqah atau żāuq adalah rasa sakit yang didapati manusia karena kematian. Namun demikian, jika memang manusia telah mati, bisakah ia merasakan sakit tersebut? Sementara “rasa” hanya diperoleh ketika manusia masih hidup. Imam asy-Sya’rawi menjawab, yang dirasakan oleh manusia merupakan permulaan kematian (muqaddimah al-maut), yaitu proses ketika kematian tengah menimpa seseorang.
Seirama dengan pendapat ini, Imam ar-Razi menganggap redaksi al-maut hanyalah metafora (majāz), karena maut bukan jenis makanan yang bisa dirasakan. Sebab itu makna al-maut adalah prosesi kematian yang sedang berlangsung, ditandai dengan rasa sakit begitu akut bagi seseorang yang sedang ditimpa olehnya. Rasa sakit ini tidak akan dirasakan sebelum dialami, sementara orang yang sudah mengalami akan dianggap sebagai mayyit (orang meninggal), dan mayyit tidak lagi merasakan sesuatu. Dengan demikian disimpulkan bahwa żā`iqatul-maụt terjadi ketika proses kematian sedang berlangsung.
Ketiga: Penggalan akhir ayat ini wa nablụkum bisy-syarri wal-khairi fitnah, wa ilainā turja’ụn (Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami), tak lain adalah untuk penyempurnaan kehambaan (ubudiyyah) di semua kondisi yang dialami manusia. Hal ini sesuai dengan makna dasar dari kata fitnah, sebagaimana ditulis Imam ar-Raghib, adalah proses pembakaran emas untuk memurnikannya.
Tidak seorang pun di dunia ini yang terlepas dari tanggung jawabnya (taklīf) sebagai seorang hamba. Ketika Allah menganugerahinya dengan kebaikan, wajiblah ia bersyukur; tatkala diberi keburukan, ia pun tetap menghamba dengan bersikap sabar. Hal ini sudah dicontohkan para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman, dengan seluruh kerajaannya, tetap bersimpuh sebagai hamba; nabi Yusuf yang begitu tampan-rupawan juga bersujud kepada Allah; nabi Ayyub dengan segenap ujian sakit yang membekapnya berpuluh-puluh tahun tetap setia untuk sabar; nabi Isa yang sangat fakir-miskin juga masih tunduk dan patuh pada semua perintah-Nya. Hal ini tentu bisa memberi kita hikmah bagi kita, bahwa kondisi apapun yang tengah meliputi kita, status sebagai “hamba” harus selalu dijaga.
Imam ar-Razi berkomentar, ujian (al-ibtilā`) tidak akan terealisasi tanpa tanggung jawab syariat (taklīf). Ayat ini menunjukkan tentang adanya taklīf, tetapi Allah Swt tidak sekedar memberi manusia perintah dan larangan semata, melainkan melengkapinya dengan kesulitan yang terdapat di dalam ujian itu dengan dua hal: (a) Kebaikan (al-khair), yaitu nikmat duniawi, kesehatan, kebahagiaan atau mendapat sesuatu yang diinginkan. (b) Keburukan (asy-syarr), bahaya duniawi berupa fakir, penyakit dan seluruh bencana yang menimpa manusia. Maka Allah jelaskan bahwa bersamaan dengan taklīf yang dipikul manusia, meraka juga diapit oleh dua keadaan di atas, tak lain agar manusia senantiasa bersyukur dengan anugerah dan bersabar saat menerima musibah, lalu semakin berlipat ganda lah pundi-pundi pahala mereka.
Kedua: Penamaan ujian (al-ibtilā`) yang terambil dari mafhum kalimat wa nablụkum (Kami akan menguji kamu) berdasarkan bentuk penjajakan kualitas manusia itu sendiri, sebab Allah telah mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia, bahkan sebelum hal itu benar-benar terjadi. Imam asy-Sya’rawi menjelaskan dan memberi analogi sederhana untuk persoalan ini. Bagi beliau, ujian pada dasarnya tidaklah buruk, tetapi keburukan tersebut bisa terjadi manakala akhir ujian itu mengantarkan pada kegagalan. Hal ini sama dengan ujian bagi seorang siswa di akhir semester, apakah hal tersebut buruk? Tentu tidak, bukan.
Tetapi, ketika Allah menguji seorang hamba, apakah Dia bermaksud mengetahui keadaannya? Tentu tidak, sebab Dia Maha Tahu segalanya. Ujian ini diberikan untuk menegakkan hujjah kepada seorang hamba, agar ketika mereka bertindak tidak baik dan masuk neraka, mereka tidak dapat mengajukan banding di hadapan Allah, sebab rekam jejak hidup mereka telah menunjukkan bahwa mereka memang layak dimasukkan ke neraka. Ini merupakan bagian dari sifat kebijaksanaan-Nya.
Ketiga: Tentang kalimat wa ilainā turja’ụn (…dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami), Imam ar-Razi menceritakan bahwa golongan at-Tasikhiyyah (orang yang mempercayai reinkarnasi) menjadikan kalimat ini sebagai dalil akan keyakinan mereka; atau golongan al-Mujassimah (antropomorfisme) yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari fisik, maka kembali pada Allah yang juga memiliki fisik. Imam ar-Razi memberikan komentar sederhana untuk persoalan ini, bahwa redaksi turja’ụn adalah bentuk metafor semata, bukan makna hakiki.
Untuk melengkapi jawaban Imam ar-Razi, kita bisa pakai komentar tentang ayat ini dari Imam asy-Sya’rawi, yang dimaksud semua hamba akan kembali pada-Nya adalah untuk diberikan ganjaran atas apa yang mereka perbuat, jika baik akan beroleh pahala dan penghargaan, apabila buruk maka mendapat siksa.
Keempat: Syaikh Najmuddin al-Kubra memberikan takwilnya terhadap ayat ini. Bagi beliau ujian yang dianggap buruk (asy-syarr) adalah apa-apa yang dibenci oleh manusia, seperti rasa takut, lapar, tak memiliki harta, kehilangan orang-orang yang berharga ataupun sumber pangan kehidupan, padahal itu semua merupakan sebab dari matinya hawa nafsu dan kehidupan bagi hati nurani manusia. Sementara ujian baik (al-khair) adalah sesuatu yang dihasrati manusia, semisal ketertarikan kepada lawan jenis, memiliki keturunan, harta benda, seluruh fasilitas yang dibutuhkan, makanan lezat nan bergizi dan lainnya; padahal itu merupakan sebab bagi tumbuh suburnya hawa nafsu dan hati yang mati. Maka orang-orang yang bisa bersabar untuk menahan keinginannya, akan dianugerahi nurani yang hidup dan ketenangan jiwa, ia pun berhak untuk kembali ke hadirat Allah dengan satu tarikan (jadzbah),
يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُۙ. ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
“Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya.” (QS. Al-Fajr: 27-28)
Dengan demikian, apa yang mulanya diasumsikan buruk tiba-tiba menjadi kebaikan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang berbeda,
…وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ….
“…Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu…” (QS. Al-Baqarah: 216)
Sementara orang-orang yang tak sanggup bersabar dengan hal yang dibenci dan condong memenuhi kenyamanan syahwat semata, tanpa mensyukuri nikmat yang dirasakannya dengan menunaikan kewajiban sebagai hamba, maka baginya azab yang pedih. Lalu apa yang ia anggap sebagai kebaikan seketika berubah menjadi keburukan. Hal itu sebagaimana tersirat dalam al-Quran,
…وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ…
“…dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu…” (QS. Al-Baqarah: 216)
Karena sifat lemah dan ketidaktahuan yang diderita manusia hingga membuatnya tidak benar-benar bisa membedakan antara yang benar dan keliru, seharusnya mereka mengembalikan dan menggantungkan segalanya kepada Allah semata, wa ilainā turja’ụn (…dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami)
Wallahu a’lam. [HW]