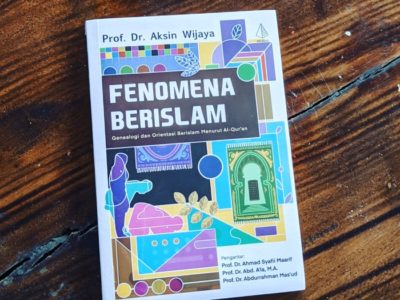“Ketidaktahuan menyebabkan rasa takut, ketakutan menyebabkan kebencian, kebencian menyebabkan kekerasan.” Ibnu Rusyd
Kebodohan masih menjadi musuh besar bukan hanya manusia tapi juga peradaban. Hal ini bukan petuah receh. Sebab bilamana seseorang hendak menghancurkan suatu lembaga, institusi, agama, dan negara. Maka persuburlah orang-orang bodoh. Dengan cara yang beragam.
Kebodohan, setidaknya akan melahirkan rasa takut atau jika ia membesar akan menjadi paranoia. Ketidaktahuan dan keengganan kita untuk memberantas kebodohan telah mengantarkan kita pada kondisi phobia terhadap simbol dan visualisasi. Sebagai misal, keparanoiaan itu tergambar dari ketakutan terhadap simbol PKI—isu yang selalu digoreng tapi tak pernah masak—atau hal-hal yang berbau Barat yang dianggap sebagai sesat.
Umpatan pun terlontar. Mengalir tak cuma dari tempat-tempat umum. Namun lebih jauh dati itu dan yang membuat hati tersayat serta kepala tak habis pikir ialah hal semacam itu terjadi di rumah ibadah—khotbah pengkafiran semakin lantang, dakwah tak lagi berbasis etis; kepentingan lebih seksi untuk digarap ketimbang dakwah dengan hasanah.
Ujaran-ujaran kebencian setidaknya belakangan ini begitu memekakkan telinga. Kita lantas sulit menenangkan hati di tengah kegaduhan politik dan sengkarut pandemi yang belum mau menemui fajarnya. Dalam masa krisis yang mestinya tiap orang bergandeng tangan dan saling menguatkan, lantas –oleh sebagian orang—digarap untuk mencari panggung demi membenarkan fatwanya, dengan cara apa pun.
Ketika kebencian itu menguat dan bertumbuh di subur pada personal seseorang, maka tidak mengherankan bila kemudian yang terlahir adalah kekerasan.
Apa yang disebut kekerasan bukan semata dalam bentuk fisik yang tergambarkan dengan sabotase, perusakan, pembakaran, pembubaran dan lain sebagainya. Namun kekerasan bisa berarti pula kekolotan dalam berpikir. Setidaknya—hemat saya—ini terjadi dari krisis literasi, kecetekan minat membaca menjadi bumbu utama tumbuh suburnya kebodohan.
Setidaknya, bila kita mau menoleh lebih halus terhadap sejarah bangsa: kemerdekaan yang kita raih adalah berkat lahirnya golongan intelektual yang rakus membaca. Bagaimana Cokroaminto dan kawan-kawan serta para muridnya yang diantaranya adalah Soekarno dan Hatta adalah seorang yang gemar membaca—selain berdiskusi. Tanpa jasa-jasa mereka, kemerdekaan bangsa rasa-rasanya hanya sebatas utopia yang bergantung di depan mata kita, pada saat itu.
Namun, apakah lantas dengan merdekanya Indonesia turut membuat bangsanya tercerdaskan? Tentu itu soal lain. Apalagi bila kita kembali ke pembahasan di atas.
Meskipun demikian, dakwah mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap digalakkan. Kita tentu butuh lebih banyak aktivis, relawan, dan pegiat literasi untuk merealisasikannya.
Dengan merambahnya pegiat literasi, maka ruang publik dan diskusi-diskusi baik di media maya atau pun media nyata akan lebih berbobot. Kita akan cenderung menyaksikan ide mengalir dan gagasan terus lahir. Keterbukaan terhadap literasi akan membuat pribadi memiliki sikap ‘Open Minded’ atau berpikiran terbuka.
Ketika kondisi ini sudah kita raih, maka kebodohan akan sayu dan mati. Kekolotan dan kekerasan lantas menipis dan pudar seiring semakin menebalnya kecerdasan kehidupan bangsa. [HW]