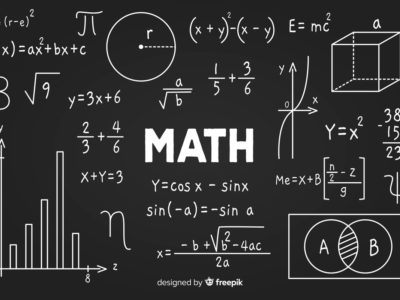Mengapa para elit? Tatkala Romawi (contoh kasus) pada abad-abad awal Masehi sedang giat membangun, ongkosnya adalah darah, biayanya adalah tumbal (ke)manusia(an) di mana 600 budak dibakar hidup-hidup oleh kaisar Nero untuk menerangi jalan, bahkan penasehat dan guru spiritualnya sendiri, Seneca, di hukum mati? Untuk apa di Colosseum diadakan pementasan raksasa berupa baca puisi dan pertunjukan pembunuhan melalui gladiator, budak dengan budak—kadang sahaya pekerja dengan sahaya pemuas nafsu sesama pria—diadu di tengah palagan dalam pertarungan bebas sampai mati, lalu diadu lagi dengan binatang buas, sampai terbunuh dan terpelanting kepalanya menyusur tanah? Kemudian hadirin bersorak sembari tepuk tangan, untuk apa? Mengapa acara sabung nyawa ini justru mendapatkan fiat, meski tentu faktitius, dari istana?
Anda tahu, kesenian macam ini hanya alibi demi menyampaikan pesan bahwa Nero tidak bersalah, kesenian adalah alat propaganda penguasa demi membungkus muslihat politisnya di satu sisi dan menarik simpati rakyat di sisi lain, ini terjadi selama Orde Lama dan Orde Baru. Anda tentu masih ingat lembaga-lembaga kesenian, kebudayaan dan bahkan agama yang didirikan pemerintah dan tentu saja dibiayai uang rakyat demi melindungi aristokrasi sebagaimana mitos Nyi Roro Kidul versi keraton Mataram. Perhatikan pula misalnya, di negeri kita, setiap menjelang pemilu dan pilkada, kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan air mata sosial lainnya justru menjadi komoditas untuk “dijual” sebagai bahan kampanye para Caleg, calon kepala daerah, juga Capres-cawapres, di samping isu SARA. Anda masih mau beli jualan mereka?
Skenario ini pula yang dulu digunakan sang Kaisar sebagai manipulasi dan gincu politik. Apa gerangan? Bagaimana grand design-nya? Keadaan tak stabil, krisis ekonomi dan kesenjangan sosial di Romawi kala itu dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dan kesibukan rakyat, lantaran itu pula dikambing-hitamkanlah umat Kristiani sebagai pembakar kota Roma yang harus dibantai dan dicincang sementara kaisar Nero dengan asyiknya justru sembari bersendawa membaca puisi, menyeringai dan terbahak menikmati pertunjukan gladiator di altar muslihat para aristokrat. Apa harus saya jelaskan salinan peristiwa ini di Indonesia? Bukankah bangsa manusia sangat piawai mereplikasi dirinya serta menduplikasi kepalsuannya demi selangkangan politik? Bukankah manusia dahulu berasal dari sungai yang sama, sungai DNA, dan belakangan sungai digital dan sungai big data? Masih ingat betapa UMKM kita babak-belur gegara big data dan hilir-mudik jual-beli online kita dibajak, dicolong, dan ditiru dengan produk sejenis yang jauh lebih murah dan lantas kita mengimpor barang-barang kebutuhan kita yang tadinya adalah ide kreatif dari UMKM kita sendiri?
Apa dan siapakah sejatinya kambing hitam itu? Dalam perspektif politik, René Girard mencoba mengurai benang kusut untuk kemudian mencari benang merah pada upacara korban dan mekanisme pertikaian agama-agama asli dan agama besar serta apapun saja yang lalu dimonumenkan menjadi “agama”, kemudian disembah dengan penuh gairah dan syahwat. Bukankah masih terang dalam ingatan Bangsa ini betapa ormas-ormas terlarang berikut baliho-balihonya disembah, lebih tepatnya dijual oleh para oligark politik, demagog ekonomi, pengasong intoleransi kepada kita, terutama di jagat maya?
Pendek kata, secara psikologis, manusia selalu butuh outlet pelampiasan kekecewaan terhadap hidup dan realitas sosial yang dirasa tidak berpihak kepada diri dan kawanannya. Nah, kekesalan yang sesungguhnya berasal dari ketidakmampuan mengatasi persoalan internal lalu dicarikan pelampiasannya dengan membangun mekanisme korban eksternal, misal: jika jalanan macet total dan Anda sedang terburu-buru, sementara orang berduit seenaknya menyewa patwal agar terhindar dari kemacetan, siapa yang Anda salahkan? Ketika gagal melamar seorang gadis pujaan selebgram pula yang sudah operasi plastik belasan kali, siapa yang Anda salahkan? Inilah frustasi agresi.
Manusia lebih senang dikagetkan, ia lebih memilih untuk dicemaskan, bukan semata demi membangun manajemen konflik, tetapi demi menemukan kambing hitam. Masih ingatkah Anda dengan jutaan tumbal genosida dan pengkambing-hitaman bangsa Yahudi di zaman Hitler? Bagaimana pula kaisar Titus II pada tahun 70 M membantai budak-budak Yahudi lalu terjadi diaspora yang kelak melahirkan gerakan zionisme melalui Theodor Herzl? Pun juga khalifah-khalifah dari berbagai dinasti (Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah dan Utsmaniyah) yang kerap menumpahkan darah dengan dalih tahkim atau arbitrase? Bagaimana pula syeikh Siti Jenar manjadi tumbal laiknya Al-Hallaj sang Martir? Pernahkah kita memikirkan seandainya “akidah” penguasa waktu itu justru sama dengan Siti Jenar, maka sudah barang tentu Walisongo lah yang akan dieksekusi mati?
Namun demikian, sebagaimana Ibnu Khaldun, René Girard menyebutkan bahwa semakin kritis peradaban suatu bangsa semakin halus dan canggih pula hegemoni dan pengkambing-hitaman. Manakala rakyat kian berdaulat, manipulasi politis kian sulit dilakukan terang-terangan. Oleh karenanya, kecerdasan, kearifan dan sikap kritis harus menemukan oksigen dan udara bebas sebanyak mungkin, bukan lantas diberangus dan atau dibelenggu oleh otoritas negara dan agama, lewat para buzzer misalnya. Dan, ini mutlak hanya dengan mempelajari, mendialogkan dan mengalami filsafat dalam arti yang sesungguhnya. Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi, amanat UUD 1945? Bukankah dahulu para pemuda dalam sumpahnya tidak ingin beragama satu, tidak menghasrati kebudayaan dan tafsir yang satu, mereka ingin Bahasa, Bangsa dan Tanah Air yang satu: Indonesia!
Lantas, kecerdasan macam apakah yang dibutuhkan Bangsa ini demi mengatasi krisis pengkambing-hitaman, Kisanak? Sikap kritis yang bagaimanakah yang harus dibangun dan lalu disebarluaskan? Perlukah narasi besar alternatif agar budaya kambing hitam setidaknya bisa direduksi dari cakrawala keindonesiaan kita, sehingga keterlanjuran kultur mencari-cari “siapa” yang salah digantikan oleh cara berpikir “apa” yang salah? (bersambung). []