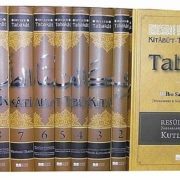Adalah Jurgen Habermas, filsuf generasi kedua Mazhab Frankfurt, penerus teori kritis Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Habermas amat prihatin dan mencemaskan teori kritis yang dipaparkan oleh para pendahulunya itu yang justru berakhir secara kontra produktif, pesimis dan mengalami banyak kebuntuan dan kerapuhan pada sekian aspek terapan.
Habermas lantas membangkitkan kembali teori itu dengan paradigma baru, cakrawala yang lebih manusiawi. Ia mengajak umat manusia—di tengah pusaran arus kambing hitam tersebut—agar hijrah dari sekadar memiliki kecerdasan instrumental menuju kecerdasan emansipatoris. Apa sebab?
Kecerdasan instrumental—yang selama ini diajarkan kurikulum dari PAUD hingga Perguruan Tinggi—adalah rasionalitas kaku, kecerdasan ala tukang, dan sikap kritis yang hambar, bersemayam di menara gading kepongahan, tercerabut dari akar kemanusiaan. Kecerdasan ala tukang ini, cuma mengkaji kehidupan secara banal, mekanistik, pragmatis, teknokratis, dan selalu potong kompas, lahirlah yang namanya generasi shortcut, terutama di era digital dan medsos ini.
Kecerdasan instrumental (dan apapun nama akademisnya) menganggap segala sesuatu sebagai sarana mencapai tujuan, kadang, segala sesuatu adalah tujuan itu sendiri, praktis, tujuan selalu berubah-ubah. Dan, celakanya, oleh karena semuanya (termasuk manusia) adalah instrumen, maka tujuan apapun meniscayakan dan menghalalkan segala cara. Belakangan, Tuhan juga dijadikan alat kampanye, agama adalah pijakan untuk berkuasa, berdiri dengan menginjak kepala para jelata.
Secara gampang begini, seorang insinyur atau teknokrat yang cuma memiliki kecerdasan instrumental dan berkepribadian tukang hanya akan berpikir sempit, dangkal dan asal kerja mengenai teknokrasinya. Konsekuensinya, ia tak mau ambil pusing dan menyiksa otaknya untuk mendialogkan teknologi dengan kehidupan, dengan jagad nilai, dengan kemanusiaan, dengan kalkulasi tumbal dan korban manusia, korban ekologis serta kerusakan ekosistem. Yang penting, asal tujuan teknologi dikalkulasi secara teknis, langsung eksekusi. Soal teknologi dan modernisasi menuntut adanya tumbal, ya itulah ongkos sejarah, itulah resiko yang nanti bisa “dicari” sama-sama dalam ruang seminar dan sidang-sidang anggota dewan sembari liburan ke luar negari mengenai apa dan “siapa kambing hitamnya”. Yang terpenting, teknologi tercapai sesuai pesanan dan anggaran, tentu saja setelah di-mark up dan lalu disunat.
Sedangkan kecerdasan emansipatoris lebih merupakan ramuan dari kecerdasan akal budi, kejernihan nurani, keheningan rohani dan kebeningan sikap kritis yang kemudian dikonfrontir dengan realitas sosial, kesenjangan moral sebagai dampak dari kemajuan semu dan teknologi palsu. Pergulatan ini lalu diekstraksi menjadi sebuah “gugatan” untuk terus setia bertanya mengenai apa sumbangan kecerdasan bagi kemanusiaan? Apa sumbangsih dialog-dialog lintas nilai dengan penyejahteraan sesama, peningkatan kualitas dan taraf hidup orang banyak? Bukankah selama ini kemajuan hanyalah mitos yang terus meninabobokan rakyat miskin? Siapa yang labih diuntungkan oleh infrastuktur perkotaan, mall, pabrik-pabrik, industri? Bahkan jalan raya, tempat hiburan, sekolah dan rumah sakitpun hanya milik sebagian kalangan, yang pasti bukan kaum miskin. Cukuplah si miskin yang tersebar di 27.000 desa lagi terbelakang itu ditakut-takuti dengan neraka, sembari sesekali dihibur hatinya dengan iming-iming surga. Inilah yang terus digugat oleh kecerdasan emansipatoris ala Habermas.
Jika demikian, membangun manusia adalah membangun harkat martabatnya serta memuliakan kedudukannya, sementara itu pembangunan dan industri yang tidak manusiawi, menindas dan dehumanistik harus segera disudahi. Jika tugas-tugas manusia sudah bisa digantikan oleh mesin-mesin, terutama setelah dicanangkan kecerdasan artifisial, maka tantangan manusia modern adalah bisakah ia tetap menjadi manusia? Bisakah ia mempertahankan kemanusiaannya di tengah ancaman zaman digital ini, di tengah gelegak gila politik dan politik gila ini, di tengah politisasi agama dan Kitab Suci, di tengah kepungan intoleransi dan cyber crime yang merajalela?
Pada episentrum inilah kecerdasan emansipatoris terus berproses menjadi kecendikiawanan yang menggugat rasionalitas dalam sumbangsihnya bagi kemanusiaan, bukan kecendekiawanan menara gading yang hanya omong soal kemiskinan di ballroom hotel bintang lima. Hal ini tentu saja agar manusia lebih manusiawi, lebih emansipatif dan emansipatoris.
Habermas lalu menggagas dan melokomotifi pentingnya dialektika pemikiran emansipatoris melalui dialog lintas disiplin, lintas genre, lintas khazanah dan perbedaan. Dialog interaktif, diskusi bebas, debat rasional sebagai tradisi, sebagai aksi komunikasi agar setiap orang tercerahkan akal budinya, dibangkitkan kesadaran kritisnya, digoyang-dibongkar sekat mitos-mitosnya yang selama ini mengekang, dijungkirbalikkan logika sumbu pendek dan cuti nalarnya yang selama ini membakar diri dan kehidupan sekitar.
Pendekatan Habermas ini dikenal dengan The Theory of Active Communication yang output-nya adalah enlightening process atau proses pencerahan yang tidak hanya rasional, tetapi juga membangun pandangan jagad (weltanschauung) menuju ke(le)luasan cakrawala visi sebagai manusia, bukan semata sebagai alat pembangunan yang sangat dehumanistik dan menciderai kemanusiaan. Walhasil, pembangunan harus membumi dan manusiawi, harus mencium tanah dan jauh dari pongah. Pembangunan harus dilandasi semangat sujud, mecium tanah, tidak tercerabut dari Tanah, dan Air. Semoga. []