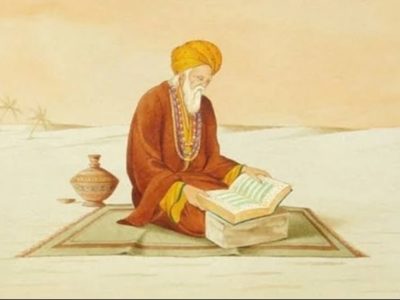Saya mau membuat pengakuan jujur: bahwa saya sebetulnya tidak terlalu mengenal sosok Agus Sunyoto (saya biasa memanggilnya: Mas Agus, dan panggilan ini akan saya pakai seterusnya dalam tulisan ini) secara pribadi. Persinggungan saya dengan sosok ini hanya bersifat selintas, kasual, dan sambil lalu saja. Saya juga tidak membaca secara mendalam tulisan-tulisan Mas Agus. Beberapa bukunya saya baca, terutama mengenai sejarah Wali Songo. Saya mengikuti sebagian kecil dari ceramah-ceramahnya, baik secara langsung atau melalui YouTube. Jika saya tidak membaca tulisan-tulisan Mas Agus, itu bukanlah karena pikiran-pikirannya tidak menarik, melainkan karena perhatian intelektual dan minat “akademis” saya tidak banyak bersinggungan dengan tema-tema yang menjadi pokok pembahasan dia. Dalam akhir hayatnya, misalnya, Mas Agus banyak berbicara mengenai sejarah Majapahit dalam “sudut pandang” yang khas. Saya kurang (atau mungkin “belum”) memiliki minat dalam tema-tema mengenai “sejarah kuno” semacam ini. Inilah yang menjelaskan kenapa saya tidak banyak membaca tulisan Mas Agus. Tetapi saya “terpaksa” menulis tentang sosok ini karena, pertama, saya diminta teman-teman yang menyiapkan sebuah buku untuk mengenang 100 hari wafatnya Mas Agus; dan, kedua, sebagai penghormatan terhadap sosok yang saya anggap penting dalam NU.
Dan ini, terus terang, yang membuat saya agak kesulitan menulis semacam “memoar kecil” mengenai sosok ini, karena tidak ada “persinggungan” yang mendalam antara dia dengan saya. Saya pernah “sowan” ke rumahnya di Malang, dan berbincang-bincang (tidak lama) mengenai banyak aspek dalam sejarah. Dari percakapan yang hanya sebentar itu, saya punya kesan: Mas Agus menyimpan semacam “api” dalam dirinya. Api ini tampaknya yang mendorongnya untuk menulis semacam “sejarah alternatif.” Saya juga tidak yakin apakah istilah “alternatif” di sini tepat. Juga saya bertanya-tanya pada diri sendiri: alternatifnya dalam aspek apa? Aspek tema? Pendekatan? Atau model penulisan/historiografinya? Saya, terus terang, tidak tahu jawabannya.
Tetapi, dari pelbagai diskusi dengan teman-teman, dan dari kesan sekilas saya berbicara dengan Mas Agus, atau mendengarkan sebagian ceramah-ceramahnya (sekali lagi: saya tidak banyak mengikuti ceramah dia), saya punya kesan bahwa aspek “alternatif” dalam sejarah yang ditulis oleh Mas Agus itu tampaknya terletak dari segi pendekatan; juga tema yang ia pilih. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan secara “substantif” apa pendekatan yang dipakai oleh Mas Agus dalam menulis sejarah, tetapi saya menduga: dia kurang cocok dengan sejarah, atau lebih tepatnya: historiografi, sebagaimana dipraktekkan di kalangan sejarawan yang “mainstream” di Indonesia. Saya menduga, Mas Agus kurang “sreg” dengan model penulisan sejarah arus-utama ini karena, antara lain, versi ini kurang memberikan perlakukan yang “adil” kepada masyarakat Islam “tradisional” (jika istilah ini bisa kita pakai, meski harus dengan sikap hati-hati) yang sangat dia akrabi. Kita tahu, sejarah Indonesia memang ditulis dengan “bias modern” yang sangat kuat. Apa yang saya maksud dengan “bias modern” di sini adalah kecenderungan untuk memberikan perhatian yang lebih, dan “favoritistik,” kepada sektor masyarakat modern yang umumnya, secara geografis, terletak di daerah perkotaan. Sejarah yang berkenaan dengan sektor pedesaan yang tradisional kurang banyak diperhatikan.
Ini jelas terkait dengan asumsi epistemologis dalam historiografi modern. Misalnya, ada asumsi bahwa apa yang layak ditulis sebagai sejarah dan diketengahkan kepada publik adalah hal-hal yang berkenaan dengan segi-segi kehidupan di kota; sebab, di kota lah segala dinamik perubahan terjadi. Kehidupan di desa dianggap tidak menyimpan “tambang data dan sejarah” yang layak ditulis. Di sana, kehidupan berjalan “statik,” tidak ada perubahan dinamis yang layak diperhatikan. Di sektor pedesaan ini, tak ada “sejarah” yang menarik; atau jika ada sejarah di sana, ia tidaklah semenarik “sejarah” tentang kota.
Dalam dunia penulisan berita, kita mengenal apa yang disebut “news-worthiness,” kelayakan sebuah peristiwa untuk diangkat sebagai berita dan diketengahkan kepada khalayak luas. Saya kira ada asumsi umum, meskipun sekarang sudah dikoreksi (walaupun koreksinya masih terbatas!), dalam historiografi modern bahwa kehidupan di desa, atau dinamik sosial-kebudayaan yang berlangsung di ruang sosial yang tradisional, tidak banyak peristiwa yang mengandung semacam “news-worthiness.” Karena itu, “historical gaze,” atau mata kesejarahan yang dipunyai oleh para sejarawan tidak banyak melayangkan pandangannya ke sektor ini.
Aspek lain yang problematis dalam historiografi modern adalah adanya (ini istilah saya sendiri yang belum tentu tepat!) “materiality bias,” yaitu cenderung mendefinisikan “sejarah” sebagai peristiwa yang disokong oleh bukti-bukti “material.” Ini bisa berupa tulisan, inskripsi, prasasti, koin, dan artefak-artefak material lain yang bisa dilihat secara kasat mata. Meskipun sudah ada jenis historiografi yang menggunakan “kesaksian lisan” turun-temurun sebagai bukti (disebut “sejarah lisan”), tetapi, secara ontologis, sejarah yang demikian itu, yang didasarkan pada bukti-bukti yang “non-material” (sebaliknya, hanya melalui ingatan saja), cenderung dianggap “less historical,” kurang bernilai secara sejarah. Kedudukannya pun, dalam hirarki historiografi, dianggap lebih rendah. Buktinya kurang kuat! Bias semacam ini cenderung merugikan masyarakat yang tidak memiliki tradisi tulis yang kuat; masyarakat yang merawat “ingatan kolektf” mereka bukan melalui catatan tertulis, tetapi tradisi lisan yang dikisahkan secara turun-temurun. Akibat dari bias-bias semacam ini, penulisan sejarah “resmi” cenderung “valorizing,” memenangkan sektor modern yang memang sudah mengenal budaya tulis dalam derajat yang canggih.
Apa yang disebut sebagai “sejarah Indonesia,” misalnya, jelas amat banyak dipengaruhi oleh bias-bias semacam ini. Segi-segi sejarah yang berlangsung di ruang sosial yang non-modern kurang mendapatkan perlakuan yang adil. Karena sejarah resmi ini diajarkan di lembaga pendidikan modern secara massal, maka “sejarah resmi” semacam ini kemudian membentuk “ingatan kolektif” yang eksklusif (artinya: tidak inklusif). Sebab ia ditulis dengan “historical gaze” yang terarah kepada sektor sosial tertentu, mengabaikan sektor yang lain. Narasi mengenai masyarakat pesantren dan peran-perannya dalam sejarah kebangkitan nasional, misalnya, tidak begitu menonjol dalam sejarah resmi ini. Dan kita tahu, setiap bentuk eksklusivitas pastilah akan berujung kepada ketidak-adilan.
Meskipun tidak bisa memastikan, tetapi saya memiliki dugaan bahwa Mas Agus bergumul dengan problem-problem historiografis semacam ini. Dan inilah tampaknya yang mendorongnya untuk “keluar” dari sejarah resmi, dan mencoba mengeksplorasi wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Misalnya, salah satu warisan penting dia adalah penulisan sejarah Wali Songo. Saya kira, dengan warisan yang satu ini saja, Mas Agus sudah meninggalkan “monumen historiografi” yang penting.
Saya kira, ada banyak orang yang “salah paham” mengenai sosok Agus Sunyoto ini. Semoga saya keliru dalam dugaan ini. Dan salah paham ini bisa datang dari dua belah pihak sekaligus: yaitu masyarakat nahdliyyin sendiri, atau di luarnya. Apa yang saya maksud dengan “salah paham” di sini ialah adanya anggapan bahwa Mas Agus menulis “sejarah” dalam pengertian “hagiografi” sebagaimana banyak kita jumpai di dalam masyarakat kita, terutama masyarakat pesantren. Hagiografi adalah sejarah yang ditulis hanya dengan tujuan untuk “mensucikan” tokoh tertentu, tanpa kesadaran kritis mengenai validitas data-data pendukungnya, dan cara mem-verifikasi-nya. Sekarang ini, misalnya, banyak kita jumpai buku-buku yang ditulis oleh “sejarawan pertikelir” mengenai kiai ini atau itu, pondok ini atau itu, tanpa dibarengi dengan kemampuan untuk nenapis data, dan mem-verifikasi-nya. “Sejarah” dalam pengertian populer ini direduksi hanya semata-mata sebagai proses memindahkan kesaksian populer dalam masyarakat kedalam sebuah tulisan. Tulisan semacam ini sebetulnya tidak bisa disebut “sejarah” dalam pengertian yang ketat. Ini hanyalah semacam “tutur tinular.” Mas Agus tidak menulis sejarah semacam ini. Bagaimanapun, dia adalah sosok sejarawan yang terdidik secara profesional dalam penulisan sejarah sebagaimana dikenal di perguruan tinggi modern. Dengan kata lain, dia memiliki latihan akademis sebagai sejarawan, bukan sekedar seorang penulis yang rajin mengumpulkan tuturan-tuturan yang berkembang di masyarakat, lalu meramunya menjadi sebuah “kisah.”
Mas Agus, dengan kata lain, menulis sejarah dengan kesadaran penuh tentang problem-problem dalam historiografi yang mapan dan dominan. Kesadaran ini yang membawa dia ke semacam “terra incognita,” wilayah yang jarang dijelajahi oleh sejarawan “resmi” yang lain. Narasi dia tentang “agama Kapitayan,” misalnya, adalah bentuk “perlawanan” terhadap “narasi resmi” mengenai sejarah pengislaman tanah Jawa. Dalam berbagai kesempatan (termasuk dalam perbincangan secara personal dengan saya, baik di rumahnya atau di tempat lain), ia sering mengulang-ulang poin penting ini: Bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Jawa sejatinya sudah memiliki “tradisi tauhid” sebagaimana dikenal dalam agama Kapitayan. Inilah, menurut dia, yang menjelaskan kenapa Islam bisa diterima dengan gampang oleh masyarakat Jawa. Kita boleh setuju atau tidak dengan interpretasi Mas Agus ini. Tetapi yang lebih penting adalah usaha dia untuk menampilkan interpretasi alternatif terhadap proses Islamisasi di Jawa.
Gagasan lain yang menurut saya menarik adalah interpretasi Mas Agus tentang aspek kecil dalam sejarah Wali Songo, terutama sosok “nyentrik” bernama Syekh Siti Jenar. Dia menegaskan (dan saya tidak tahu, dari mana sumbernya dia memperoleh data ini) Syekh Siti Jenar lah sosok pertama dalam sejarah Jawa yang mengenalkan konsep tentang “ingsun” sebagai pronomina atau “dlamir” untuk orang pertama. “Ingsun” maknanya adalah “saya” dalam bahasa Jawa. Sebelum istilah ini dikenalkan oleh Sykeh Siti Jenar, orang Jawa menggunakan istilah “kawula” atau “kula” untuk menunjuk dirinya sendiri. Dua istilah itu maknanya sangat merendahkan, “derogatory”: “kawula” adalah budak. Praktek linguistik ini menandakan kuatnya kultur feodalisme yang merendahkan rakyat kecil. Syekh Siti Jenar mencoba melakukan semacam “revolusi kebudayaan” dengan mengubah bentuk kesadaran subyektif masyarakat Jawa; yaitu, dengan mengenalkan konsep tentang “aku”/“ingsun” yang otonom, bukan budak para raja atau bangsawan. Dalam masyarakat Banyumasan, praktek menyebut diri dengan “ingsun” ini masih berlaku umum hingga sekarang; berbeda dengan kawasan Jawa yang berada dalam pengaruh keraton Jawa yang lebih kuat. Dalam masyarakat Jawa yang terakhir ini, kata “kawula” lebih populer ketimbang “ingsun”.
Dalam komunitas pesantren Jawa, kosa-kata “ingsun” ini masih dipertahankan dalam tradisi memaknai (atau, dalam tradisi santri Sunda, “ngalogat“) kitab kuning yang berbahasa Arab. Biasanya, kata “ingsun” dipakai untuk menerjemahkan kata ganti orang pertama: ana atau -tu/-ni. Apakah ini ada kaitannya dengan warisan ajaran Syekh Siti Jenar yang masih dipertahankan oleh komunitas santri, saya kurang tahu. Tetapi, jika interpretasi Mas Agus ini benar, ia jelas merupakan “data kultural” yang amat menarik.
Dalam sebuah percakapan personal dengan saya, Mas Agus pernah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, pada dasarnya, adalah membangun kesadaran tentang “masyarakat sipil” yang mandiri dalam masyarakat Jawa. Dalam interpretasi semacam ini, kita melihat semangat Mas Agus untuk melihat sejarah dari sudut yang tidak “lazim.” Dengan kata lain, sudut pandang yang dipakai oleh Mas Agus adalah kaca-mata alternatif.
Dalam ujung hayatnya, Mas Agus banyak bicara mengenai sejarah Majapahit. Ketika berkunjung ke rumahnya di Malang beberapa tahun yang lalu, saya sempat bertanya: Apakah “njenengan” paham bahasa Jawa kuno yang disebut Kawi? Mas Agus memberikan jawaban afirmatif. Sasya penasaran, dari mana Mas Agus belajar bahasa Kawi. Dia menjawab: otodidak. Pertanyaan ini sengaja saya ajukan karena saya ingin tahu sumber-sumber yang dipakai oleh Mas Agus untuk memahami sejarah Majapahit: apakah sumber primer berupa kakawin, misalnya, atau sumber sekunder. Kita tahu, sumber-sumber tentang Majapahit ditulis dalam bahasa Kawi. Ketika saya mendapatkan jawaban bahwa Mas Agus menguasai bahasa ini, saya senang sekali, dan berkesimpulan bahwa dia tidak “sembarangan” dalam menelaah sejarah Majapahit. Dia merujuk kepada sumber primernya. Meskipun saya tidak tahu, seberapa jauh penguasaan Mas Agus atas bahasa Jawa kuno ini. Tetapi, saya yakin bahwa Mas Agus mencoba memahami sejarah Majapahit dengan sungguh-sungguh melalui sumber-sumber primer. Dan ini, sekali lagi, menunjukkan sikap dia sebagai sejarawan profesional, meski dengan interpretasi yang tidak “lazim.”
Salah satu interpretasi dia yang menarik tentang Majapahit (meski interpretasi ini tidak terlalu orisinal, menurut saya) adalah adanya kebijakan yang secara sadar diterapkan oleh kerajaan Jawa kuno itu untuk menghormati keragaman keyakinan, sebagaimana dilambangkan dalam jargon: “bhinneka tunggal ika.” Dalam sebuah percakapan personal, dia menegaskan, bahwa prinsip inilah yang membedakan masyarakat Jawa dengan masyarakat Arab. Dengan kata lain, dalam masyarakat Jawa telah dikenal kesadaran yang mendalam tentang pentingnya menghargai keragaman keyakinan; “truth claim” atau klaim kebenaran tidaklah sekuat dalam kebudayaan Arab. Di sini, saya memang melihat adanya kesadaran yang kuat pada Mas Agus tentang “identitas Jawa” berhadapan dengan kearaban. Saya menduga, pandangan Mas Agus ini mencerminkan “sikap populer” yang dominan dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana masyarakat nahdliyyin secara sadar ingin mengembangkan semacam identitas Islam yang khas nusantara vis-a-vis Islam yang dibentuk oleh kebudayaan Arab. Ada semangat “perlawanan” yang tersembunyi dalam interpretasi dia terhadap sejarah Majapahit: sejarah Majapahit yang dilihat ulang sebagai basis pembentukan identitas Jawa yang lebih positif karena menghargai perbedaan, dan kurang dibebani dengan obsesi pada “truth claim.” Jika ada sesuatu yang orisinal pada Mas Agus, saya kira ya terletak dalam aspek ini: aspek menegaskan adanya “agency” pada umat Islam yang ada di luar kawasan Arab.
Dengan kata lain, karir historiografi Mas Agus menandakan satu hal penting: ia menulis sejarah dari pinggiran, dari wilayah yang jarang dirambah oleh orang lain. Juga pendekatan yang ia pakai: pendekatan alternatif. Karena menulis sejarah dari pinggiran tidak akan bisa “dieksekusi” dengan sebaik-baiknya jika masih menggunakan pendekatan yang dominan. Pendekatannya haruslah alternatif.
Saya ingin menutup kenangan kecil ini dengan menunjukkan hal lain yang “khas” pada Mas Agus. Semangat dia untuk menempuh historiografi alternatif ini tampak juga dalam tampilan lahiriah dan cara berpakaian. Pertama, ia selalu tampak dengan tampilan fisik yang unik: ia memiliki jenggot dan kumis yang jelas berbeda sekali dengan “jenggot salafi.” Ia selalu memakai kopiah ke manapun ia pergi. Ia memakai pakaian yang amat sederhana. Dan ia pun hidup dengan gaya hidup yang “semenjana,” sedang-sedang saja, bahkan cenderung sederhana sekali. Orang yang duduk di samping Mas Agus tidak akan merasakan “aura pretensi” apapun. Dia tidak tampak ingin dilihat sebagai seorang kiai, intelektual, cendekiawan, dosen, atau apapun. Ia tampil tanpa beban apapun. Bagi saya, ini adalah sikap “kerohanian” yang amat patut diapresiasi. Tampilan fisik semacam ini bagi saya bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak dan kebetulan saja. Ini jelas ada kait-mengaitnya dengan wawasan “epistemologis” Mas Agus yang ingin menempuh jalur alternatif dalam penulisan sejarah.
Dalam banyak kasus, saya sering melihat kaitan (meskipun ini sulit dibuktikan) antara wawasan teoritis seseorang dengan cara ia berpakaian, bertindak, dan berbicara di depan khalayak ramai. Seseorang yang memiliki “passion” pada kekuasaan dan politik, misalnya, cenderung (meski ini tidak “muttarid,” berlaku dalam semua kasus) akan tampil dengan gaya hidup dan berpakaian tertentu. Saat berbicara dan bercakap-cakap dengan Mas Agus pun, saya tidak merasakan adanya “pretensi” tertentu. Dia memiliki “strong opinion,” pendapat yang solid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, tetapi dia tidak cenderung memaksakan pendapatnya itu, atau mendakwahkannya secara “misionaris” kepada orang-orang lain. Ketawadlu’an intelektual semacam ini amat memikat saya. Jujur saja, saya selalu memendam rasa “jengkel” pada pemikir atau intelektual yang “pretensius,” apalagi arogan.
Dengan kata lain, sikap keilmuan Mas Agus dalam bidang sejarah tidak saja berhenti sebagai “posisi teoritis” saja, melainkan “tembus” ke dalam laku kehidupan sehari-hari. Karena itu, di mata saya, Mas Agus bukan sekedar seorang “ilmuwan” dan “sejarawan” dalam pengertian yang kita kenal di kalangan academia. Dia menulis sejarah sebagai ilmu dan sebagai laku sekaligus. Ini adalah “etos kesarjanaan” yang jelas tidak asing bagi orang-orang yang pernah menjalani pendidikan di pesantren. Theoria dan praxis, ilmu dan amal bersatu, bukan dua hal yang dipisahkan. Bagi Mas Agus, menulis sejarah juga bukan semata-mata tindakan ilmiah belaka, tetapi “tindakan etis.” Apa yang saya maksud dengan tindakan etis di sini ialah sesuatu yang dikerjakan dengan tanggung-jawab moral-etis tertentu.
Dengan kata lain, menulis sejarah mengandung sebuah “misi moral,” bukan semata-mata menafsirkan peristiwa sosial dengan sikap yang (seolah-olah) “obyektif.” Tanggung jawab moral di sini ialah: membela orang-orang yang lemah, dan memberdayakan mereka. Ini, tiada lain, adalah perwujudan langsung dari ajaran “ingsun” yang diwedarkan oleh Syekh Siti Jenar sebagaimana dipahami oleh Mas Agus. Menulis sejarah adalah menulis narasi dengan tujuan pokok: menanamkan kesadaran “ingsun” yang otonom dan merdeka pada komunitas yang selama ini dipinggirkan atau dipandang bukan sebagai sumber yang layak untuk penulisan sejarah. []
(Catatan: Tulisan ini saya buat untuk momen peringatan 100 hari wafatnya Mas Agus Sunyoto, sejarawan NU yang penting. Dia wafat pada 27/4/2021 yang lalu. Terlalu panjang karena ditulis untuk sebuah buku bunga rampai kenangan dari sahabat-sahabatnya. Saya muat di dinding FB saya ini sebagai dokumentasi saja. Kalau ada yang tertarik membaca, ya jelas saya bersyukur, sekaligus “mbatin“: “Yang mau baca, pasti lagi punya banyak waktu senggang, dan duitnya banyak”).