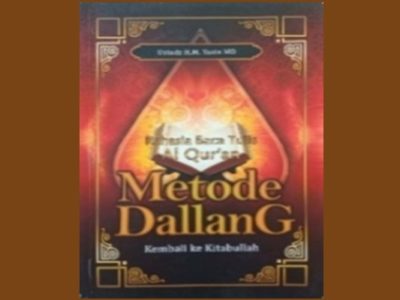Tak satupun dari sisi kehidupan dan pola-pola hubungan (dengan Tuhan, sesama manusia, flora-fauna dan bahkan seluruh semesta) yang tak dicontoh-teladankan oleh Baginda Nabi. Mulai dari berpikir, bertindak, bertutur, bergaul, berumah tangga, berniaga, dan bahkan membangun peradaban serta kamanusiaan. Satu catatan yang harus digarisbawahi, beliau tampil di rumah, di pasar, di masjid, di pergaulan sosial, dan dalam segala aspek kehidupan sebagai manusia, bukan sebagai malaikat!
Di ranah pekerjaan, misalnya, pada masa kecil Nabi Muhammad serta kabanyakan para Rasul adalah gembala. Itu artinya, sebelum memimpin umat manusia, kita harus belajar memimpin binatang, bukan hanya di luar tapi terutama di dalam diri. Pantaslah jika dalam Islam ada syariat untuk Qurban dan Aqiqah, semata agar kita belajar menyembelih sifat-sifat dan kecenderungan binatang dalam diri dan bangsa ini, lebih-lebih ketika dipercaya memimpin dan mengemban amanah.
Direportase dalam kitab Fathul Bari, Nabi memelihara kambing untuk latihan tawadhu’ (low profile), agar hatinya terbiasa mengatur suatu urusan, dan meningkat dari sekadar mengatur kambing kepada mengatur umat. Tata kelola semacam ini belum menjadi kurikulum dalam lembaga-lembaga pendidikan kita, bukan? Inilah nilai-nilai leadership yang diteladankan kanjeng Nabi.
Sementara itu, dikisahkan pula dalam Maulid Barzanji bahwa pada usia ketiga puluh beliau bersama penduduk Mekah membangun kembali Ka’bah setelah diterjang banjir bandang. Mereka bersengketa mengenai peletakan Hajar Aswad. Masing-masing suku dan kabilah berharap mendapat kemuliaan dengan mengangkat batu surgawi itu.
Mulailah terjadi selisih paham dan ketegangan lantaran semua pihak merasa paling berhak. Peristiwa ini nyaris berujung pertikaian dan adu pedang. Panas, belum lagi karena Mekah kala itu sedang dilanda krisis ekonomi.
Akhirnya, mereka menginsyafi pertikaian itu dan menyerahkan urusan Hajar Aswad kepada sosok paling terpercaya dengan integritas moral (Al-Amin) yang telah teruji dan tak pernah berdusta, siapa lagi kalau bukan Muhammad Saw, sang empunya pendapat yang benar dan paling toleran. Mereka bersepakat memutuskan perkara itu kepada orang yang pertama masuk dari pintu Masjidil Haram esok harinya. Ternyata baginda Nabi adalah yang pertama kali masuk. Maka mereka berujar, “Inilah orang yang kami percaya. Kami semua menerima dan rela.”
Lantas Baginda meletakkan Hajar Aswad itu di selembar kain serban, kemudian beliau mengajak semua kabilah untuk mengangkatnya bersama-sama ke sudut Ka’bah dan beliau meletakkannya dengan kedua tangannya yang mulia di tempat semula Nabi Ibrahim As menempatkanya.
Walhasil, tak satupun kepala suku dan kabilah merasa keberatan, semua merasa mendapat kehormatan dan kemuliaan mengangkat sang batu hitam. Inilah bukti pekerti mulia Baginda Nabi, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Kecerdasan macam apakah yang dimiliki Muhammad Saw—yang belum diangkat jadi Rasul waktu itu—sehingga bisa mendamaikan pertikaian yang nyaris berujung pada perang saudara?
Inilah kecerdasan profetik yang harus sering-sering kita asah dan kita duplikasi untuk keindonesiaan dan kemanusiaan.
Paman kinasih beliau, Abu Thalib, meninggal dunia pada pertengahan bulan Syawal tahun kesepuluh dari kenabian. Tak pelak, kaum pagan Mekah merasa mendapat angin segar untuk melancarkan teror, intimidasi, dan ancaman bertubi-tubi. Tiga hari kemudian sang isteri tercinta, Sayyidah Khadijah al-Kubra berpulang ke haribaan Ilahi, maka semakin deraslah gelombang cobaan dan prahara siksaan atas baginda Nabi dan para pengikutnya. Betapa tidak, dua pembela dan pelindung utama telah tiada, kini sang Nabi sebatangkara berjuang menegakkan panji agama.
Beliau bergegas menuju Thaif, mengajak bani Tsaqif, namun apa boleh dikata, mereka tak menggubris. Alih-alih menerima, penduduk Thaif malah memprovokasi dan mencari, mencerca dan menghina, bahkan mereka yang tak terpelajar dan hamba sahaya sekalipun mencaci-maki dengan kata-kata serapah, melemparinya dengan batu dan kotoran, sampai-sampai darah mengucur hingga melumuri kedua sandal kanjeng Nabi.
Sejurus kemudian beliau kembali ke Mekah dengan perasaan sedih, bukan karena prilaku bengis mereka, tetapi karena hidayah tak kunjung datang mengetuk setiap hati. Malaikat penjaga gunung sempat memohon izin kepada Nabi Saw untuk menghancurkan semua penduduk Thaif yang kepala batu itu.
Namun lagi-lagi tak tampak kemarahan seirispun dari roman wajah sang Nabi, beliau malah mendoa, “Sungguh, aku berharap agar kelak Allah SWT memberi mereka keturunan berupa pribadi-pribadi yang sudi mengurusi agamaNya.”
Tindakan Muhammad Saw sebelum menjadi Rasul ini jelas tindakan cerdas yang menyelamatkan bangsanya dari pertumpahan darah. Sekali lagi, kecerdasan dan kesabaran apakah yang membuat baginda Nabi mengambil tindakan strategis padahal wahyu belum turun kepadanya?
Itu artinya, beliau memang memiliki kecerdasan dan kesabaran profetik, dijaga langsung oleh Allah SWT dalam segala prilakunya. Kecerdasan nabawi (fathanah) inilah yang seharusnya kita jadikan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan, yakni bagaimana santri dan mahasantri, murid dan mahamurid memiliki cara berpikir dan untuk kemudian pola sikap sebagaimana Nabi. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ ala alihi wa shahbihi wa sallim.