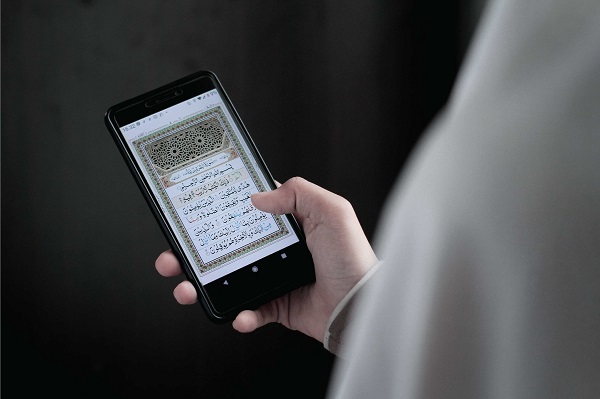Siapa kiranya mau menolak bila dirinya diberikan predikat ‘benar’ atau posisinya berada di titik ‘benar’ atau terlebih lagi bila apa yang dikatakan dan dilakukan mengandung (nilai) ‘kebenaran’. Tentu hal ini secara alamiah mampu diterima dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa adanya penolakan dari individu tersebut. Karena hal itu terasa manis dan membahagiakan, dan terutama bila boleh sedikit meninggi hal itu terasa begitu membanggakan.
Tiap orang menyimpan –yang pikirannya waras- asa agar apa yang dilakukan dan dikatanya tidak salah, baik hal itu sebentuk ucapan atau buah prilaku tampilan kesehariannya dalam bilik-bilik komunitas, sosial, organisasi, atau hal paling sederhana adalah ketika mendapati dirinya menjalin asmara dengan seorang tercinta. Sebaliknya, penyematan –baik langsung maupun tidak- ‘kesalahan’ atau ‘salah’ terhadap dirinya dari individu yang lain tentu terasa menyakitkan apalagi penyematan tersebut dilakukan oleh orang lebih dari satu. Alih-alih hidup ini menjalani risalah Tuhan, yang terjadi malah trauma karena psikisnya tergores tak siap menerima kenyataan sebenarnya.
Terlepas dari manusia siap ataupun tidak, kebenaran sejatinya bersifat primordial atau mendasar. Kebenaran tak terkikis barang secuilpun oleh perlakuan kotor manusia yang menolak atau melawan bahkan menutup kebenaran dengan cara membengkokkannya, memotongnya, atau dengan hal keji berupa kebohongan.
Kebenaran demikianlah yang selama ribuan abad diperjuangkan oleh para tokoh, yang dengan kegigihannya harus berakhir martir atau syahid. Ia terpaksa dihukum mati oleh instansi atau organisasi tertentu sebab mendobrak tatanan mapan yang dianut instansi atau organisasi tersebut. Di ingatan kita –semoga anda masih mengingatnya- tergambar jelas bagaimana Galileo harus martir karena mendobrak dominasi gereja (teologi) dengan pernyataannya bahwa bumi adalah benda bulat yang ia faktakan berdasarkan sains/berdasarkan kebenaran ilmiah, namun dalam hal ini gereja (teologi) merasa terhina karena pernyataan Galileo itu menyalahi nash atau teks yang dipunya (gereja).
Demikian sepenggal kisah pejuang kebenaran, tak mudah memang, rumit, dan berakhir meregang nyawa adalah satu keniscayaan logis. Namun pun begitu, kebenaran mesti diusahakan. Apalagi menyangkut manusia, si makhluk ringkih, rapuh, lemah, terbatas, dan begitu rentan terhadap kealpaan serta tipu daya. Apalagi bila menyandingkannya dengan kemajuan teknologi, begitu jamak dijumpai manusia tak siap menerima kebenaran.
Semakin majunya zaman ternyata tak menjadi jaminan kedewasaan manusia dalam bersikap juga semakin maju. Bahkan acap ditemui malah dalil-dalil agama kerapkali dijadikan alat untuk memaksakan tindakannya atas nama kebenaran dan pendakuan pemegang tongkat ‘benar’ dan ‘kebenaran’. Mereka tak peduli dengan hukum alam bernama ‘pluralitas’. Tak hanya itu, ketakterimaan terahadap kebenaran juga sering ditampilkan dengan alat kekuasaan yang dipunya untuk membungkam kebenaran tersebut. Miris memang!
Dikisahkan dulu seorang raja hidup dalam gelimang harta dan pangkat adiluhung. Ia jauh dari kata ratu adil dan begitu otoriter terhadap rakyatnya, namun di wilayah kekuasannya pula hidup seorang manusia alternatif atau dalam Islam disebut sebagai sufi.
“katakan padaku satu kebenaran, Guru” pinta sang sultan sopan
“apakah kau yakin atas permintaanmu itu, Sultan” jawab si sufi landai
“tentu” sergahnya
“baiklah, kalau begitu” si sufi mengambil nafas bijak dan coba menenangkan dirinya
“menurutmu, kira-kira berapa harga diriku ini bila diukur dengan nominal uang?” tanya sultan pada sufi
“sebentar” si sufi berpikir sejenak, lalu ia menjawab pelan “ ya, kira-kira sejuta lah” jawab sufi terkait harga diri sultan
“wah sembarangan kamu, sejuta?!. Bajuku saja ini harganya sejuta!” tolak si sultan pada pernyataan sufi
“loh la iya, aku hanya bisa melihat itu sebagai satu-satunya yang berharga dari dirimu”
“kurang ajar!” sultan pun geram dan mukanya merah padam
“bukankah tadi kau yang memintaku menyatakan kebenaran? Dan kau sendiri yang menyatakan siap diri untuk mendengarnya? Namun mengapa sekarang yang muncul justru amarahmu?” tanya tegas si sufi pada sang sultan.
Kebenaran kendati terkesan biasa saja, bahkan sekali. Namun menerimanya bukanlah pekerjaan sepele. Apalagi kebenaran itu tidak sesuai yang dengan kehendak serta hasrat keinginan dalam diri. Sebagaimana fitrah lumrah manusia menghendaki kebenaran, akan tetapi bukan menempuhnya dengan cara bijak tapi malah cara itu ditempuh dengan jalan-jalan pilu berupa menghindari kenyataan, tak mau menerima fakta bahkan menyerang balik si pengucap kebenaran.
Seorang aktivis sejati sekaligus pejuang kemanusiaan bernama Gie pernah mengatakan bahwa umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran karena kebenaran itu seringkali menyakitkan, kalimat itu rasa-rasanya begitu pas disematkan kepada dia manusia modern. Padahal jauh sebelum Gie, kakek kita bernama Socrates lebih dulu mengungkapkan bahwa don’t be angry with me, if I tell you the truth. Atau terlepas dari keduanya, Islam pun mengajarkan bahwa katakanlah kebenaran walaupun itu menyakitkan.
Namun alih-alih mengaca pada dalil-dalil di atas sebagai pijakan hidup, manusia justru kerap berdalih dengan macam-macam alasan dan cara. Padahal kebenaran adalah kebenaran, ia akan tetap ada dan abadi bagaimanapun cara manusia mendiskreditkannya. Bahkan dengan cara kolektif kelompok sekalipun.
Ajaran Islam yang mengajarkan untuk mengatakan kebenaran itu memiliki dua dimensi, setidaknya. Pertama, adalah sebagai perintah bahwa selaku muslim, dalam melihat hal-hal yang melenceng dan membelok mesti diluruskan demi tegaknya kebenaran. Kedua, adalah sebagai fakta bahwa betapapun kebenaran dikehendaki dan dihasrati oleh manusia, namun kenyataannya tidak selalu selaras dengan kehendak juga hasratnya, lebih jauh manusia harus melihat itu sebagai kenyataan yang terjadi dan ada.
Lalu, mengapa kita harus menyampaikan kebenaran? Bila pada kenyataannya kebenaran itu sendiri menyakitkan dan kerap melahirkan permusuhan. Mengapa harus menerima kebenaran? Bila pada kenyataannya kebenaran itu sendiri mangkir dari kehendak pribadi. Bukankah itu menyedihkan sekali?
Setidaknya ada beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk relatif, tidak bersifat mutlak layaknya Tuhan. Sehingga menjadi wajar bila perkataan, perbuatan manusia sekali waktu adalah sebuah kesalahan. Kedua, dengan (minimal belajar) menerima kebenaran berarti manusia juga (belajar) menjadi personal dewasa, yang tidak memutlakkan diri dan kehendaknya, yang tidak menutup kritik atau saran dari kerabat sebagai bentuk koreksian terhadap kekurangannya.
Beranjak dari hal tersebut, betapapun kebenaran layak dilayangkan, namun etika dan attitude-pun mesti tetap diperhatikan. Jangan sampai dengan dalih menyampaikan kebenaran lalu kemudian jalan yang ditempuh asal-asalan dan malah sembrono. Kebenaran harus tetap disampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana, terlebih kebenaran pun mesti dilihat konteks kejadian yang ada. Tentu tak benar bila dengan dalih menyatakan kebenaran, lalu manusia mengatakan “hai, ndut, tem-item” kepada temannya sendiri meskipun secara fakta demikian adanya. Alih-alih menyampaikan kebenaran, yang ada justru penghinaan.
Baiklah, pembaca yang budiman, apalagi yang membaca sampai akhir. Doa hamba, menyertai anda.
Menjalani hidup di alam semesta ini kita akan menemui hal yang kompleks yang setiap pribadi harus siap dengan segala kenyataannya, apalagi itu terkait kebenaran. Meskipun rasanya lagi-lagi pahit dan menjemukan. Tapi penerimaan terhadap kebenaran yang demikian tak serta merta menjadikan manusia nista atau hinda-dina. Justru sebaliknya, penerimaan terhadap kebenaran adalah bukti bahwa ia dewasa dan mampu mengenal sifat kemanusiaan yang melekat pada dirinya yaitu sifat potensial berbuat khilaf, salah, alpa, dan lain sebagainya.
Akhirnya
Kebenaran diakui ataupun tidak masih menjadi dilematis dalam penerimaan kita sebagai manusia. Mengapa? Mari kita lihat secara metafor, banyak manusia yang mendaku sebagai pecinta pelangi, namun di saat yang sama ia mencaci-maki guntur yang acapkali mengawali kemunculan pelangi. Berapa orang yang mendaku mencintai mawar, namun tak siap dengan konsekuensi duri yang melekat pada tangkainya. Lalu, sejauh mana manusia mencintai senja bila pada akhirnya ia menangis tersendu dan terlunta-lunta ketika magrib melenyapkan merahnya. Kebenaran dan kesalahan serupa dua lajur jalur kereta yang saling berdampingan. Keduanya akan ada sepanjang perjalanan umat manusia. Sebagai makhluk budiman, manusia bisa memilih melakukan kebenaran atau sebaliknya, menerima kebenaran atau malah menyangkalnya dengan perilaku pembenaran. [HW]
Salam kreatif.