Perempuan adalah sosok manusia multidimensi yang tak akan pernah habis dibicarakan dan didiskusikan dari pelbagai perspektif, seperti: sosiologi, psikologi, budaya, filsafat, dan lain sebagainya. Sebab, ia kerap diposisikan sebagai makhluk nomor dua, direndahkan, dan tidak dihargai dalam kancah kehidupan sosial-politik. Bahkan, ketika dihadapkan dengan seorang laki-laki, perempuan tidak lebih hanya sekadar pelengkap penderitaan. Juga lebih banyak dijadikan obyek ketimbang subyek. Dari perspektif sejarah, perempuan kerap menjadi korban mitologi, ketidaknyamanan saat hamil, dan rasa sakit yang dialami ketika melahirkan. Hal tersebut dianggap sebagai hukuman atas dosa pertama (dosa Hawa).
Itulah mengapa dari zaman dahulu hingga sekarang muncul tindakan misoginis terhadap seorang perempuan. Tindakan tersebut, tampaknya mendapat momentumnya karena ditopang oleh doktrin teologis tak terkecuali di dalam Islam. Dimana sebagian para pemikir Islam dan ulama kerap memosisikan kaum laki-laki (superior) daripada kaum perempuan (inferior), baik dalam persoalan kepemimpinan agama maupun spiritual dan lain sebagainya.
Padahal, dalam ajaran Islam, kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama, artinya Islam tidak memihak di antara salah satunya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah bahwa “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah”. (QS. Al-Hujarat: 11)
Ayat ini mengindikasikan bahwa Islam sejak kedatangannya, merupakan agama yang sangat menjaga harkat dan martabat kaum perempuan dengan berpegang pada prinsip persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan sosial.
Berlandaskan pada ayat tersebut, maka dalam tradisi pemikiran filsafat Islam, antara kaum perempuan dan laki-laki diposisikan setara sepanjang ia mempunyai kemampuan lebih (kemampuan intelektual bukan jenis kelamin). Al-Farabi (670-950 M) misalnya, salah satu tokoh besar dalam filsafat Islam dan juga dikenal sebagai mahaguru filsafat. Ketika berbicara tentang puisi, Al-Farabi menyatakan secara tegas dan lugas bahwa, kriteria unggulan dari sebuah puisi tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikan, baik laki-laki atau perempuan. Akan tetapi sejauh mana keindahan dari susunannya.
Pun juga, pandangan Al-Farabi perihal kedudukan seorang perempuan dapat dilihat dalam kitabnya Mabadi’ Ara al-Madinah al-Fadhilah. Tatkala ia memberikan kriteria untuk memimpin sebuah negara. Di antara kriteria yang diajukan oleh beliau adalah sehat jasmani, kesempurnaan intelektual, memiliki girah terhadap ilmu pengetahuan, bermoral baik, dan mampu melahirkan peraturan yang tepat.
Jika diteliti secara saksama, tampaknya kriteria yang diajukan tersebut berdasarkan pada hal-hal yang bersifat intelektual dan spiritual. Artinya, Al-Farabi tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu (harus laki-laki seperti kebanyakan fikih pada umumnya) untuk menjadi pemimpin sebuah negara selama ia mampu memenuhi kriteria tersebut.
Selain Al-Farabi, filosof muslim yang menaruh minat secara serius terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang lebih dikenal sebagai komentator Aristoteles terkemuka adalah Ibnu Rusyd (1126-1198 M). Pandangannya tentang kedudukan perempuan ia lontarkan tatkala mengomentari argumentasi Plato dalam karyanya Republic, yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak lain adalah makhluk imitasi.
Ibnu Rusyd secara tegas menolak argumentasi Plato tersebut, dengan menganggap bahwa hal itu tidak benar dan menyesatkan. Sebab, bagi Ibnu Rusyd, perempuan tidak sekadar makhluk yang pintar berdandan, melainkan juga mempunyai kemampuan berbicara (beretorika) yang baik dan memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni.
Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan hukum (fikih), tampaknya Ibnu Rusyd tidak secara tegas dan lugas (sangat berhati-hati) dalam membicarakan masalah perempuan. Dalam kasus perempuan menjadi imam salat misalnya, Ibnu Rusyd yang juga ahli fikih tak memberikan hukum secara tegas tentang hal tersebut. Sebab, bagi beliau, hal itu tak ada aturannya dalam nash. Begitu pun dalam urusan seorang perempuan tatkala menjadi hakim.
Meskipun demikian, Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid memberikan penjelasan bahwa hal tersebut bersifat ikhtilaf (terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama). Al-Thabari (836-922 M) misalnya, salah seorang ulama yang memperbolehkan seorang perempuan menjadi imam salat bagi makmum laki-laki dan menjadi hakim. Itu artinya, meskipun dalam ranah fikih, Ibnu Rusyd tidak memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dari seorang laki-laki.
Maka dari itu, sedari awal tradisi pemikiran filosofis hadir untuk mendobrak pola pikir perihal kedudukan seorang perempuan lebih rendah daripada seorang laki-laki, baik di lingkungan ulama atau pemikir Islam maupun sosio-kultur yang berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan argumentasi rasional dan tetap berpegang pada prinsip nilai-nilai keislaman sebagaimana Al-Farabi dan Ibnu Rusyd. []






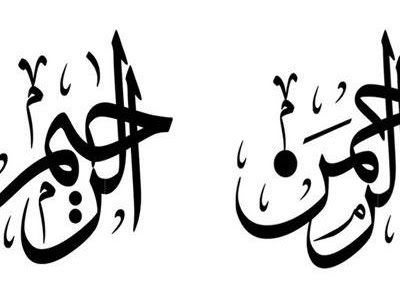

















[…] Kiai Sahal bagi pendidikan perempuan ini, tentu saja bukan yang pertama kali beliau lakukan. Jauh sebelumnya, kita dapat melihat […]