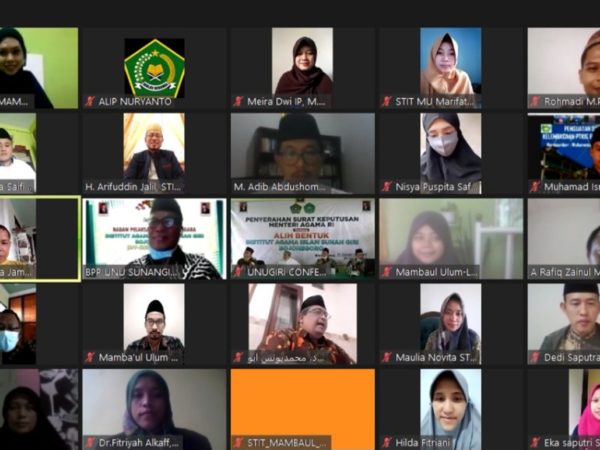Menarik pernyataan Pak Jokowi terkait Indonesia tidak mengalami resesi seks. Beliau juga mengutarakan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini di angka 2,1. Kemudian laju angka pernikahan yaitu 2 juta dan yang hamil 4,8 juta. Artinya Indonesia tidak mengalami resesi seks. Tentu saja, pernyataan Jokowi merupakan counter atas maraknya anggapan liar yang menunjukan Indonesia akan terkena resesi seks.
Berkembangnya resesi seks di beberapa negara nyatanya menjadi ancaman yang kompleks, sebab menimbulkan kekawatiran demografi yang berujung kepada lemahnya perekonomian negara atau politik kebijakan negara. Beberapa strategi alternatif telah digagas oleh negara yang tengah mengalami resesi seks, seperti China yang mulai merevisi kebijakan cuti hamil dengan dalih patronasi pra dan pasca kelahiran. Begitu juga dengan Jepang upaya meningkatkan tunjangan pengasuhan anak sampai selesai pendidikan.
Perlu dimafhumi bersama, resesi seks muncul tidak dalam ruang yang kosong, melainkan terdapat faktor yang mempengaruhinya. Kitchener dalam risetnya mengemukakan tiga alasan terjadinya resesi seks khususnya di Amerika First, the younger generation gets their pleasure in other ways. Second, teens are less likely to be in long-term relationships. Third, the sexual treatment of women is done painfully. Penulis pribadi setuju dengan pendapatnya Kitchener, kecenderungan generasi yang memprioritaskan karir, peningkatan kekerasan turut andil mengkonstruk pemikiran seseorang dalam ihwal seksual.
Akan tetapi terlepas dari jawaban Pak Jokowi yang menyandingkan data ratio pertumbuhan penduduk, ada beberapa hal yang perlu dicermati secara komprehensif, yaitu mengapa Indonesia “tidak/belum” mengalami resesi seks dalam konteks waktu yang singkat?
Kekaburan Makna “Resesi Seks”
Perlu dimengerti bahwa sejatinya istilah resesi seks tidak memiliki istilah yang pasti. Hanya saja Jake Novak menggambarkan resesi seks adalah “the drop in sex rates and marriage rates”. Begitu juga dengan Kate Julian yang mengistilahkan resesi seks mirip dengan “a having less sex”. Akan tetapi dalam konteks Indonesia istilah ini mengalami kekaburan sehingga memiliki istilah yang kontras.
Sebagai contoh, beberapa media masa memberikan pemahaman bahwa resesi seks sebagai sikap keenggenan pasangan untuk memiliki anak atau memiliki sedikit anak. Begitu juga dengan beberapa stakeholder yang mengkonjungsikan resesi seks dengan perkawinan yang semakin meningkat. Apabila pemaknaan ini yang dipahami maka jatuhnya adalah intercouse yang masih sama tetapi tidak menyebabkan kehamilan yang berujung hadirnya seorang anak. Apabila seperti ini jelas pemaknaan resesi seks kuranglah tepat.
Merujuk kepada pendapat Jake Novak dan Kate Julian, resesi seks dimaknai sebagai kurangnya hasrat seksual seseorang sehingga mengurangi angka pernikahan. Hanya saja ketika disandingkan dengan konteks pemahaman umum masyarakat maka resesi seks itu tidak akan terjadi. Mengingat tidak mungkin seseorang tidak memiliki hasrat seksual sama sekali.
Tetapi, jika pemahaman ini merujuk pada kurangnya hasrat seksual yang implikasinya terhadap penurunan jumlah anak -sebagai mana yang terjadi di beberapa negara- maka alangkah tepatnya jika dikatakan sebagai resesi reproduksi. Istilah ini mungkin lebih relevan karena menggambarkan kurangnya jumlah anak yang dihasilkan dari fersilitasi. Jadi harus ada koreksi dan interpretasi kohesif terhadap kata “resesi seks”.
Sejumlah Perspektif Masyarakat
Perlu dipahami bahwa kekhawatiran terhadap resesi “reproduksi” adalah berkurangnya jumlah orang yang aktif prokreasi. Sehingga angka kelahiran terus menurun dan berujung kolaps. Berkaitan dengan ini, dalam konteks masyarakat Indonesia nampaknya masih skeptis jika Indonesia mengalami resesi “reproduksi” dalam konteks waktu saat ini atau singkat.
Penyebabnya adalah masyarakat Indonesia masih memandang memiki anak/bayi dalam beragam persepktif, seperti agama, sosiologi-antropologi, ataupun juga psikologi. Dalam perspektif agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki corak hidup ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam konteks ini masyarakat sangat paham sekali bahwa anak adalah fitrah (wa battssa minhuma rijalan kastiran wa nisa’a [an-Nisa (4):1]). Bahkan terdapat adagium berbau agama yaitu banyak anak banyak rezeki. Perspektif ini yang mengkontruksi pemikiran masyarakat tentang memiliki bayi/anak sehingga menimbulkan pemahaman seakan-akan mempunyai anak adalah suatu kewajiban. Sebab itu isu childree sempat menjadi pros and cons di masyarakat.
Kemudian dari sisi sosiologi-antropologi, anak dipahami sebagai entitas sosial. Mungkin di beberapa masyrakat sering didapati anggapan miring atau sinis sinis dengan pasangan yang tidak kunjung mempunyai anak, terlepas dari keputusan pasangan punya anak atau tidak. Anak di ranah sosial tergambar sebagai eksistensi dari pasangan. Tanpa adanya anak pasangan akan kurang dihargai bahkan dalam beberapa daerah menunjukan strata sosial berada di golongan liyan. Anak juga dipandang sebagai generasi penerus keluarga, sebab dengan banyaknya suku yang masih mengaplikasi sistem bilateral, matrilineal, atau patrilineal.
Sedangkan perspektif psikologis, anak dipahami masyarakat Indonesia sebagai penenang hati dan penyejuk jiwa. Bahkan dalam penelitianya Deatone (2014), pasangan yg memiliki anak memiliki tingkat bahagia yg tinggi dibanding tidak mempunyai anak. Di satu arus juga anak dipandang sebagai perekat relasi antara suami dan istri.
Kemungkinan Kedepan
Kendati demikian, seiring gelombang inklusifitas masyarakat sangat memungkinkan terjadi resesi “reproduksi”. Pendidikan yang mapan, mengedepankan karis, etos kerja yang tinggi turut andil dalam mendukung pemikiran masyarakat kedepanya. Hal ini bisa tergambar dari menurunya angka kelahiran di Indonesia dari sejak tahun 1960 sampai 2020 yang ditopang dengan propaganda program Keluarga Berencana (KB).
Meski terdapat sikap skeptis hadirnya resesi “reproduksi” dalam jangka waktu yang pendek, nampaknya perlu adanya tindakan preventif. Hasil riset yang dilakukan oleh peneliti seperti Kitchener tidak boleh dinafikan keberadaanya. Gelombang inklusifitas juga harus dipandang dan tetap menjadi utuh dari keasadaran masyarakat. Setidaknya kemungkinan kedepan terjadinya resesi “reproduksi” bisa diantisipasi.
Terakhir, mengontrol angka kelahiran dan tetap menjaga replacement level di Indonesia pada angka ideal seperti ratio 2,1 juga harus ditindaklanjutkan oleh pemerintah. Tidak cukup disini, literasi yang intensif ditengah gelombang inklusifitas juga harus mulai di gerakan secara berkala, mengingat kemungkinan tantangan kedepan jauh lebih besar dari pada saat ini. Khusunya dalam permasalahan demografi.