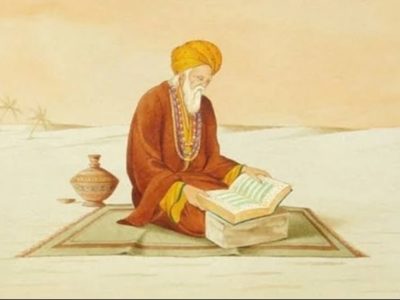Tak bisa di pungkiri, bahwa dari kecakapan intelektualnya, kita dapat melihat bagaimana usaha al-Ghazali merenungi lautan pengetahuan dan mencari tempat berpegang. Dilukiskannya, bagaimana kesan dan perasaannya melihat masyarakat yang ada disekelilingnya. Makanya, ia mempelajari madzhab-madzhab yang ada dalam setiap aliran-aliran.
Kita tahu, secara historis, al-Ghazali memiliki naluri gemar mencari kebenaran dan berusaha membebaskan dirinya dari taqlid atau pendapat yang berbeda-beda, serta aliran-aliran yang beraneka ragam. Ia ingin mengetahui perbedaan kebenaran dan kebatilan (lantaran perbedaan aliran), mengumpulkan dan memperbandingkan satu aliran dengan aliran lainnya (akhirnya merenungkan untuk mencapai pengetahuan sebenarnya).
Sudah mafhum, al-Ghazali adalah salah seorang filosof muslim yang dianggap sebagai intelektual produktif. Ia juga dikenal sebagai pembela paham Sunni dan sekaligus paham Asy’ariyah mengenai ketuhanan.
Fazlur Rahman mengatakan, al-Ghazali adalah orang yang pertama mempertemukan antara sufisme dan kalam dengan syari’ah, yang sebelumnya dua aliran ini bertentangan karena perbedaan dasar pendekatan yang dipakai. Inilah sintesa yang di capai al-Ghazali terletak dalam dasar spritual hingga membawanya ke dimensi religius asal.
Alih-alih mempertemukan, ia justru menemukan penyimpangan (anomali) dalam ilmu kalam, namun tidak menolaknya. Hanya saja, ia menggaris bawahi keterbatasan-keterbatasannya sehingga berkesimpulan bahwa kalam tidak dapat mengantarkan manusia menuju Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan jalan sufilah seseorang bisa mendekatkan diri terhadap-Nya.
Ada yang mengatakan bahwa al-Ghazali memperoleh pengetahuan tentang hakikat realitas dengan dua cara. Pertama, kemampuan insaniah bahwa ilmu yang diperolehnya melalui kemampuan manusiawi berupa indera dan akal. Kedua, al-Ghazali memperolehnya karena anugerah Tuhan (memberikan cahaya keilmuan ke dalam hatinya).
Pengetahuan seperti ini adalah suatu perolehan ilmu yang bersifat irrasional atau bersifat sufistik. Bahkan, al-Ghazali sendiri dalam bukunya menjelaskan bahwa pemahaman didapatinya bukan melalui dalil-dalil yang kuat, melainkan karena cahaya yang disusupkan Allah swt. ke dalam hatinya.
Masih tentang pengetahuan. Jika mengacu pada dua perbedaan pandangan tajam, memang betul al-Ghazali memperoleh pengetahuan melalui jalan sufi yang Esoterik. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu kitabnya, pengetahuan di cari tidak hanya menghasilkan rasa tahu pada dirinya, tapi juga menghilangkan keragu-raguan dalam pikirannya.
Namun demikian, dari perjalanan intelektual yang dilakukan al-Ghazali, tetap saja ternyata ia pernah mengalami kekacauan pada dirinya. Kekacauan itu adalah rasa keraguan yang terjadi pada dirinya sehingga mengganggu pula pada fisiknya.
Ia mengalaminya selama dua bulan dan selama masa itu dia “skeptis” terhadap kenyataan, tetapi tidak terhadap ucapan dan doktrin. Adalah fase dimana ia harus bertahan terhadap keraguan yang dialaminya sangat kental karena wilayah rasionalnya dihadapkan pada manifestasi keyakinan dari wilayah intuisif.
Dengan demikian, tak heran ketika ia sembuh dari penyakitnya bukan melalui argumen-argumen rasional atau bukti-bukti logis, tetapi disembuhkan oleh Allah swt. melalui jalan cahaya-Nya, sehingga jiwanya kembali sehat dan normal.
Yang jelas, bagi al-Ghazali sendiri, doktrin mistik yang berkaitan erat dengan ide pembimbing moral, secara keseluruhan tidaklah semua hal itu merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi beliau semata-mata mengalirkan doktrin mistik dari tokoh-tokoh dan para pendahulunya.
Berkaitan dengan profesinya sebagai pemikir, al-Ghazali mengkaji secara mendalam dan kronologis, dan hasil pemikirannya termuat dalam kitab seperti Al-Munqidz min ad-Dhalal, Faishal al-Tafriqah, Ihya’ Ulumuddin dan kitab-kitab lainnya. Al-Ghazali, mengkaji pemikiran mutakallimin dari berbagai aliran. Pun, mempelajari buku yang berkaitan dengan masalah teologi dan dikajinya secara kritis, sehingga memahami argumen apa yang dijadikan para mutakallimin sebagai dasar akidah aliran mereka.
Al-Ghazali melihat kerja para mutakallimin itu hanya sibuk mengumpulkan argumen-argumen lawan pahamnya untuk di bantah dengan argumen sendiri yang dianggap lebih rasional (mengunggulkan logika). Kata al-Ghazali, kalam hanya berpotensi untuk membentengi secara rasional akidah yang benar, dalam hal ini bersumber dari al-Qur’an dan hadits dari gangguan ahli bid’ah.
Malangnya, seusai mengkaji ilmu kalam, al-Ghazali justru mendapatkan bahaya yang timbul dari ilmu kalam ini lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebab, ilmu itu lebih banyak mempersulit hal yang menyesatkan dari pada mendefinisikan secara mudah dan menyingkapkan secara jelas.
Sebenarnya, jika di telisik, tujuan dari pengkajian itu adalah untuk memelihara akidah umat dari pengaruh bid’ah. Misalnya, aliran Mu’tazilah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha’, dimana aliran ini mendapat pengaruh kuat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Aliran ini sangat menggunakan kekuatan akal (rasional). Inilah yang dikritik dan ditentang oleh al-Ghazali.
Beliau berusaha untuk mengendalikan serta mengarahkan akidah umat Islam kepada akidah yang dianut oleh Rasulullah saw. Terlebih, beliau menyerukan untuk mengekang orang-orang awam dari belajar ilmu kalam, meskipun masyarakat awam puas dengan bertaqlid dan tidak mampu melakukan perdebatan teologis (kalamiah).
Menariknya, Ibnu khaldun mendukung pendapat al-Ghazali, dan pendapat bahwa studi-studi teologis harus di batasi untuk kalangan khusus. Namun, di akhir kehidupannya al-Ghazali justru berbalik. Ia di dominasi oleh kecenderungan Sufi dan mulai mengkritik studi-studi rasional yang sebelumnya pernah di telaahnya.
Meski mengekang orang awam untuk mempelajari ilmu kalam, al-Ghazali tetap mengakui pentingnya eksistensi kalam. Baginya, kalam bisa menjadi obat terakhir terhadap penyakit yang diderita oleh orang awam yang tidak bisa lagi diobati dengan cara lain.
Rupa-rupanya, hal ini dibenarkan dengan dasar tuntunan al-Qur’an surah An-Nahl: 125 yang membenarkan metode mujadalah dengan cara terbaik terhadap orang itu.
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl:125).
Di sini, diharapkan bisa berfungsi sebagai cara dan jalan yang lebih baik. Akan tetapi, al-Ghazali menegaskan bahwa, adanya makna penting kalam tidak berarti membuka pintu lebar bagi kalam untuk memasuki masyarakat Islam.
Konsepsi al-Ghazali tentang kalam yang komprehensif menyatu dengan dirinya, yaitu dengan perkembangan intelektual dan spritualnya sejak dia menggeluti dunia pengetahuan sampai akhir hayatnya. Dengan banyaknya karya tulis yang lahir dalam situasi perkembangan intelektual dan spiritual yang berbeda-beda kala itu, tentulah tak mudah memahami kalam yang berasal dari al-Ghazali dengan keutuhan pribadinya.
Syahdan, yang menarik dari al-Ghazali adalah ia digolongkan sebagai salah seorang yang paling menentukan jalannya sejarah Islam dan bangsa-bangsa Muslim. Bahkan, dalam bidang pemikiran dan peletakan dasar ajaran-ajaran Islam, al-Ghazali ditempatkan pada urutan kedua setelah Kanjeng Nabi. Ia adalah seorang pemikir yang tidak saja mendalam, tapi juga sangat subur dan produktif dengan karya-karya.
Akan tetapi, di balik kehebatannya, al-Ghazali tetaplah manusia biasa yang juga berbagai kelemahan. Salah satunya kelemahan sikapnya terhadap ilmu kalam. Mungkin karena ia memiliki semangat intelektual yang amat tinggi, mendorongnya untuk mengkaji apa saja yang ada pada lingkungannya.
Di samping itu, al-Ghazali sering menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Ia sendiri melukiskan riwayat pengembaraan intelektualnya dalam bukunya al-Munqidz min al-Dhalal yang ditulisnya pada saat menjelang wafatnya. Banyak pengkaji melihat ketidakkonsistenan al-Ghazali justru karena petunjuk kehebatan intelektualnya yang selalu mencari dan terus menerus ingin tahu.
Salah satunya sebagaimana di ungkap oleh Cak Nur, yaitu terhadap ilmu kalam itu. Mungkin karena menganut mazhab Syafi’i, al-Ghazali, dalam bukunya, Iljam al-Awam an Ilm al-Kalam tampak menentang ilmu kalam. Tetapi bukunya yang lain, al-Iqtishad fi al-I’tiqad, al-Ghazali memberi tempat kepada ilmu kalam al-Asy’ari.
Sementara itu, dalam karya utamanya yang cemerlang, Ihya’ Ulumuddin, al-Ghazali dengan cerdas menyuguhkan semacam sinkretisme kreatif dalam Islam, sambil tetap berpegang pada ilmu kalam al-Asy’ari. Ini tak mengherankan. Sebab, al-Ghazali di usia mudanya, dikenal sebagai murid utama al-Juwaini yang juga dikenal sebagai Imam al-Harmain (salah seorang terbesar dari kalangan para Mutakallimun Asy’ari).
Hingga akhirnya, al-Ghazali aktif mengembangkan Asy’arisme ketika selama delapan tahun menjabat sebagai guru besar pada Universitas al-Nizhamiyah, Baghdad. Sebenarnya, jabatan al-Ghazali adalah guru besar ilmu fiqh mazhab Syafi’i. Sedangkan di Universitas al-Nizhamiyah mengikuti mazhab pendiri dari sponsornya, Nizam al-Mulk, dan menjadi partisan mazhab Syafi’i.
Tentunya, di samping menganut mazhab Syafi’i di bidang fiqh, Nizam al-Mulk juga menganut, malah mengagumi ilmu kalam al-Asy’ari. Ada yang mengatakan bahwa hal ini terjadi mungkin karena Abu al-Hasan al-Asy’ari sendiri adalah seorang penganut mazhab Syafi’i yang baik.
Hal lain karena, dengan melihat tema pikiran al-Ghazali, yang merupakan sinkretisme kreatif. Sebagaimana dimaksudkan oleh pendirinya, Asy’arisme bertujuan mengambil jalan tengah di antara paham Jabariah dan Qadariah, serta di antara ketegaran kaum Hanbali dan kebebasan berpikir para filosof.
Fazlur Rahman mengatakan, penyelesaian teologis yang diajarkan oleh al-Asy’ari dan al-Maturidi) terlepas dari berbagai nuktah pada sistem mereka yang menjadi sasaran kritik kaum Hanbali, seperti Ibn Taimiyah benar-benar merupakan definisi menyeluruh tentang Islam, yang membungkam paham Khawarij dan Mu’tazilah, dan menyelamatkan umat dari bunuh diri.
Maksud bunuh diri adalah tak berdayanya Islam untuk bertahan. Mengapa demikian? Karena ketidakmampuan intelektual para pemimpin Islam dalam menghadapi dan menjawab tantangan gelombang Hellenisme yang melanda Islam saat itu.
Dari sini kita bisa membaca bahwa, al-Ghazali mempunyai pendapat yang konstan dalam menilai kalam, meski dalam perkembangan spiritualnya berbeda. Pertama, kalam tidak boleh diberikan kepada orang awam; kedua, kalam bisa dimanfaatkan dalam keadaan yang sangat mendesak, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum; ketiga, ahli kalam tetap diperlukan dalam suatu masyarakat Islam.
Ringkasnya, sehubungan dengan kalam dapat diambil tiga poin. Pertama, bahwa tujuan kalam adalah untuk melindungi akidah Islam dari penyimpangan yang dilakukan oleh ahli bid’ah. Kedua, kalam tak sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya. Sebab, kalam gagal jika berhadapan dengan para skeptik atau dengan para filosof. Ketiga, bahwa kalam tidak mungkin memenuhi kebutuhan dahaga intelektual dan spiritual al-Ghazali.
Sebagai penutup, usaha manusia untuk mencari hakikat pengetahuan, maka diperlukan pengetahuan dan keyakinan yang meyakinkannya. Adalah satu keyakinan matematis seperti keyakinan bahwa, angka 10 lebih besar dari pada angka 3 (dan ini tak bisa di bantah). Keyakinan yang (meyakinkan) seperti ini tak akan bisa dimilikinya, kecuali dengan perantara panca indera dan pengetahuan dasar dari akal. Wallahu a’lam bisshawaab. []