Santri dan mahasiswa merupakan dua elemen vital bangsa yang memiliki intensitas dialektikanya masing-masing. Keduanya memiliki corak dan karakter yang relatif berbeda. Namun, sama sekali tidak ada kontradiksi antara mereka, bahkan di sana terjadi sinkronisasi. Dalam artian, relasi antara mahasiswa dan santri tertanam simbiosis mutualisme, relasi yang saling menguntungkan.
Namun, di balik eksistensi dan peran keduanya sebagai bibit unggul bangsa terjadi kekacauan berpikir masyarakat dalam merespon. Karakter yang berbeda tersebut—di beberapa realitas—justru disikapi dengan keliru. Mahasiswa dan santri bukan lagi dianggap sebagai kemajemukan (baca; kekayaan) intelektual, melainkan diklasifikasikan dengan mengunggulkan yang satu terhadap yang lain.
Dalam disiplin keilmuan, hal tersebut dinamakan dengan dikotomi. Sebuah fenomena yang sering terjadi. Namun, dikotomi yang terjadi sekarang bukan hanya dalam disiplin keilmuan saja, bahkan lebih luas dari itu. Yang dijangkiti bukan cuma aspek keilmuannya, namun juga menjalar pada aktornya (pelakon keilmuan, seperti santri dan mahasiswa).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikotomi diartikan sebagai pembagian antara dua kelompok yang saling bertentangan. Di sinilah masalah itu bisa dijumpai. Sebagian masyarakat—bahkan tokoh agama sekalipun—kerap membeda-bedakan santri dan mahasiswa, berikut keilmuan antara keduanya. Diskursus ihwal santri dan mahasiswa melumer sebagaimana dikotomi yang terjadi antara ilmu agama dan ilmu umum.
Padahal, diakui atau tidak, dikotomi-dikotomi semacam itu merupakan indikator dari pemahaman-pemahaman yang rigid dan kerancuan berpikir. Menganggap perbedaan mahasiswa dan santri sebagai masalah adalah masalah, masalah yang timbul dari pemikiran yang tidak kompherensif. Sebab, sebagaimana disebut di awal, mahasiswa dan santri memiliki eksistensi dan urgensitasnya masing-masing.
Faktor Lahirnya Belenggu Dikotomi
Tentu, klasifikasi antara santri dan mahasiswa tidak pernah lepas dari fakitor yang selama ini membelenggunya. Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan stigmasi di kalangan masyarakat sekaligus mengundang klasifikasi keliru antara keduanya. Layaknya suatu kerajaan (kingdom), faktor adalah raja yang harus secepatnya disingkirkan terlebih dahulu. Hingga unit-unit dari kingdom tersebut lebih mudah dibuang.
Maka, untuk itu, mula-mula kita harus tahu dan paham faktor apa saja yang menjadi penyebab atas ini (dikotomi).
Pertama, perbedaan fokus keilmuan yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan di depan, sejak awal, dikotomi keilmuan lahir terlebih dahulu.
Masyarakat bahkan tokoh agama sekalipun masih ada yang menganggap ilmu-ilmu itu (agama dan ilmu umum) berbeda. Seperti halnya ketika masyarakat lebih mengunggulkan ilmu agama dari ilmu umum, dan sebaliknya. Bahkan, beberapa di antara mereka menganggap ilmu umum bukanlah ilmu yang urgen, bukan ilmu yang diajarkan oleh teks nash. Betapa rigidnya argumen semacam itu.
Dikotomi keilmuan yang ada kemudian menjalar kepada masing-masing subjeknya. Santri sebagai subjek dari ilmu agama, dan mahasiswa yang cenderung fokus pada ilmu umum. Di sini kemudian dikotomi itu menjangkiti keduanya. Masyarakat seringkali membanding-bandingkan keduanya hanya karena background keilmuan keduanya berbeda.
Kedua,sikap egosentris masing-masing. Kadang, dikotomi itu justru lahir dari internal keduanya. Masing-masing—dengan fanatiknya—merasa lebih unggul. Kefanatikan itu yang juga kemudian menyeret mereka pada kontradiksi yang berkelanjutan. Ego dari setiap keduanya mahasiswa dan santri bertarung untuk mendapatkan posisi.
Tak ayal, beberapa kali kita mendengar beberapa santri yang memandang miring mahasiswa, seperti menjudge mahasiswa tidak paham agama misalkan. Sebaliknya, mahasiswa memandang remeh para santri dengan alasan kolot, tidak berkemajuan, dan terbelakang. Lebih-lebih jika yang bertemu adalah santri salaf dan mahasiswa negeri.
Belenggu-belenggu itu justru yang dibangun sendiri oleh keduanya. Meskipun tidak semua, saya yakin sebagian dari mereka tertanam pikiran-pikiran semacam itu. Maka perlunya, kita (dengan peran masing-masing) tidak selalu fanatik dengan atribut yang kita sandang. Artinya, juga harus memberi peluang terhadap peran-peran pemuda di sekitar, dengan latar belakang yang berbeda.
Menilik Peran Keduanya
Mahasiswa dan santri memiliki kontribusi yang besar, bahkan sejak pra-berdirinya bangsa. Ini juga mengindikasikan bahwa urgensitas peran keduanya memang tidak luput dari lembar historis. Baik mahasiswa atau santri sama-sama dianggap penting.
Segala lini perjuangan, meski dalam lintas generasi, tidak pernah alpa diisi oleh keduanya. Mahasiswa dan santri dianggap sudah memiliki kredibilitas dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, tinggal bagaimana mereka menyikapi. Tentu, dikotomi yang selalu menjadi problematika secepatnya dibuang jauh-jauh.
Lengsernya Soeharto misalkan. Punuk kekuasaan Orde Baru berhasil tumbang setelah menerima beberapa perlawanan dari berbagai macam pihak, salah satunya adalah mahasiswa. Tahun 1998 itu diwarnai kecaman mahasiswa (khususnya pers kampus). Mahasiswa melakukan kritik yang kritis untuk menggempur arogansi pemerintah. Baru setelah itu Orba rapuh, angina segar reformasi pun terhirup.
Dalam isu kontemporer, justru aliansi mahasiswa secara massif menggelegar di berbagai sudut. Tidak lain adalah sebagai bentuk mengupayakan keadilan. Meskipun beberapa dari mereka masih melakukan tindakan yang represif. Namun, diakui atau tidak, tak sedikit dari kebijakan baru harus bertekuk lutut di bawah perlawanan mahasiswa. Sebagai contoh kecil adalah kasus RUU KUHP kemarin.
Mengutip dari postingan mas Aguk Irawan Mn di laman Facebook-nya, pada tahun 1512, sejak NKRI masih memiliki nama kerajaan Demak. Pati Unus yang merupakan seorang santri memimpin 10.000 pasukan. Pasukan-pasukan tersebut terbagi ke dalam 100 kapal. Hal itu dilakukan kala Pati Unus dan pasukan hendak menyerang tentara Portugis. Sampai akhirnya, di tahun 1802, terjadi perang besar yang kemudian disebut dengan pemberontakan Cirebon.
Kemudian semangatual pergerakan santri tetap eksis pasca kemerdekaan. Seperti suatu hari sacral yang sampai saat ini masih sering dikenang dalam kabung, tragedi 10 November. Resolusi jihad yang menggelegar saat itu berhasil menghapus keraguan bangsa lain atas kemerdekaan Indonesia. Hingga sampai saat ini—santri dengan atributnya—tetap eksis. Bahkan di tulisan saya sebelumnya ‘Pesantren Salaf Hari Ini’ dibahas bagaimana euforia pesantren bisa memegang punuk eksistensi saat ini.
Ini yang perlu dipahami bersama. Bolehlah mengatakan santri dan mahasiswa dianalogikan ke relasi antara minyak dan air. Kalian bisa mengatakan keduanya sulit disatukan (mneski faktanya mudah, sangat mudah). Namun, yang perlu disadari, minyak dan air bisa bersatu dalam satu wajan untuk menciptakan masakan yang lezat. Kalian boleh mengatakan santri dan mahasiswa memiliki diskursus keilmuan yang relative berbeda. Namun, kombinasi keduanya sangat mungkin untuk menjadi hal yang urgen dalam menyongsong kemerdekaan. Wallahu a’lam… [BA]







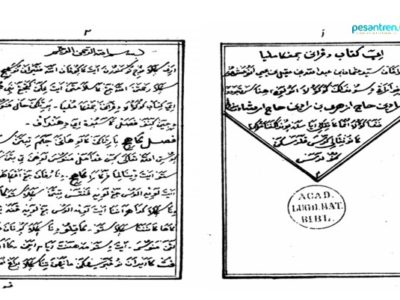
















[…] Source link […]