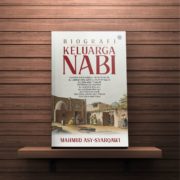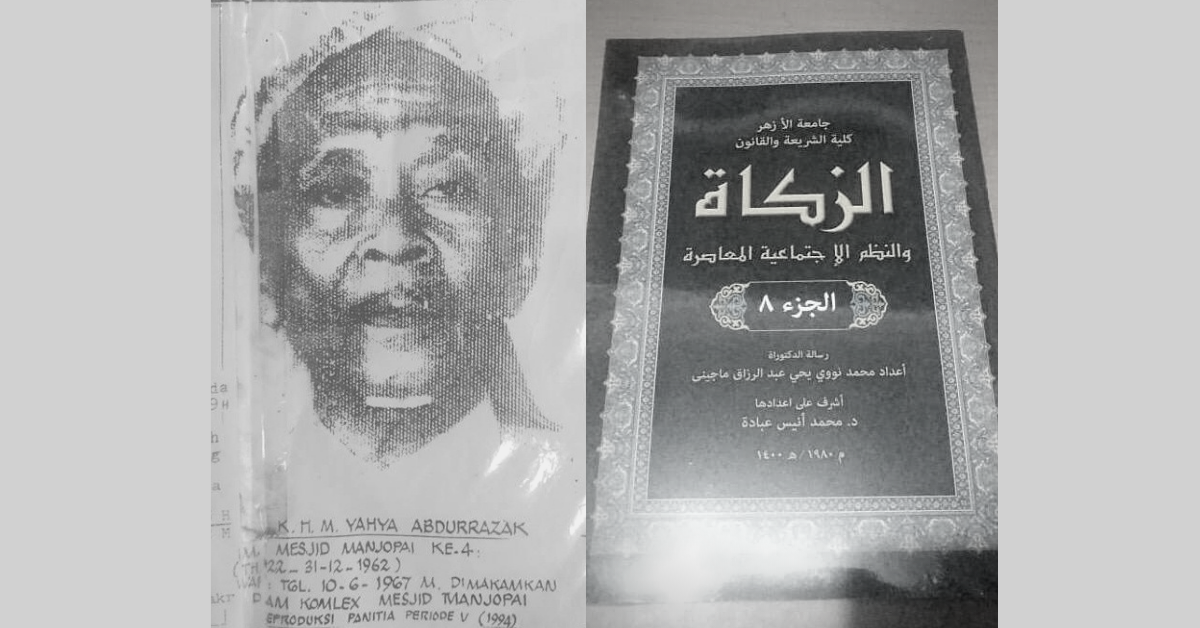Judul di atas bukan bermaksud menggeneralisasi seluruh kiai yang ada di kampung. Bacaan khas kiai kampung yang dimaksud di sini adalah model bacaan orang-orang dulu, sebagai contoh ‘ain (ع) dibaca ngain. Semoga dari sini pembaca bisa menangkap apa yang kami maksud, aamiin!. Saat ini, bacaan model tersebut nampaknya jarang ditemui. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah TPA/TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) baik di kota maupun di desa; dan nampaknya hampir setiap orang pernah mengenyam pendidikan TPA/TPQ.
Kendati demikian, beberapa kiai sepuh (tua) memang masih ada yang membaca Al-Qur’an dengan model khas termaktub. Lantas, bila kiai sepuh ini menjadi imam shalat jama’ah, apakah model bacaannya tersebut berpengaruh pada diterima/tidaknya shalat?. Dalam kita Fath al-Qarib karya Ibn Qasim al-Ghazi dijelaskan.
(وَلَاقَارِئٌ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ اْلفَاتِحَةَ أَيْ لَايَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ (بِأُمِّيْ) وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيْدَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ
“Seorang qari’, yakni orang yang benar bacaan al-Fatihahnya, tidak sah bermakmum pada seorang ummi, yakni orang yang cacat bacaan huruf atau tasydid dari surat al-Fatihah”.
Mengacu pada paparan tersebut, mungkin beberapa di antara kita langsung menyimpulkan bahwa shalat jamaah yang dilaksanakan di kampung-kampung dengan diimami oleh seseorang yang model bacaannya khas kiai kampung itu tidak ada yang sah. Tapi, alangkah baiknya bila kita tak tergesa-gesa dalam menilai terlebih dahulu. Seperti diketahui, setiap teks akan melahirkan konteks dan tidak ada konteks yang bisa terlepas dari teks. Pemahaman tekstual akan memberikan implikasi pemahaman yang cenderung kaku dan sempit. Oleh sebab itu, pemahaman kontekstual juga diperlukan supaya pemahaman yang didapat sesuai dengan yang dikehendaki penulis teks.
Apa yang tertulis dalam kitab Fath al-Qarib di atas akan relevan bila keadaan antara qari’ denga ummi itu sama (setara). Maksudnya gini, dalam suatu wilayah terdapat orang yang cara membaca Al-Qur’annya khas kiai kampung. Namun, ternyata warga lainnya kurang mahir dalam membaca Al-Qur’an. Dalam kasus ini, satu orang tadi merupakan qari’, sementara warga lainnya adalah ummi. Bila kasusnya berbeda, maka akan berbeda pula implikasi hukumnya.
Misalnya, ada seorang musafir muda yang datang (lewat) ke wilayah tadi. Ketika ikut shalat berjamaah, tentu ia mendengar bacaan imam khas kiai kampung tadi. Musafir muda ini kaget dan langsung menganggap shalat jamaahnya tidak sah. Hal ini disebabkan karena ia merasa bacaan Al-Qur’annya jauh lebih baik dibandingkan sang imam. Pada shalat jamaah berikutnya, musafir muda tersebut tak mau lagi mengikuti apabila bacaan imamnya masih khas kiai kampung. Karena menganggap shalat jamaahnya tidak akan sah, ia lantas shalat munfarid (sendiri) selama mampir di wilayah tersebut.
Kasus musafir muda di atas menurut saya adalah salah satu praktik dari―meminjam istilah dari Ustaz Ahong―otak cingkrang. Hal ini ditandai dengan sikapnya yang mengklaim bahwa dirinyalah yang paling benar, sementara yang lain salah. Praktik otak cingkrang seperti ini banyak terjadi pada anak muda khususnya yang menyatakan diri sedang (baru) ‘hijrah’. Mereka sering meragukan diterimanya shalat jamaah yang bacaan imamnya khas kiai kampung; yang lebih ekstrem lagi bila mereka sampai menganggap bahwa imam yang bacaannya khas kiai kampung itu masih berada dalam masa jahiliyyah. Sudah tentu hal tersebut sangat-sangat kelewatan.
Perkara apa saja, termasuk ibadah, Islam selalu mengedepankan akhlak. Contoh, dalam sudut pandang fiqh aurat laki-laki itu di atas pusar hingga di bawah mata kaki. Bila seorang laki-laki shalat dengan hanya menutup auratnya tersebut, maka shalatnya sah. Namun, hal itu tentu kurang pantas bila dilihat dari kacamata akhlak. Oleh sebab itu, ketika shalat, semua laki-laki akan menutup aurat sebagaimana yang biasanya kita lihat. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sebenarnya selalu mengedepankan akhlak.
Dalam kasus musafir muda tadi, pendapatnya tidak bisa serta-merta dibenarkan. Sebab, ia menganggap bahwa ibadah orang lain tidak sah dan hanya ibadah dirinya yang sah. Terkait hal ini Gus Baha’ pernah menyatakan, “Saya tidak setuju dengan para ulama yang selalu mengatakan kalau ibadah kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Logikanya tidak seperti itu. Kita mau ibadah saja sudah luar biasa, sudah harus bersyukur. (Sebab) orang seperti kita masih diberi rahmat untuk melakukan ibadah”.
Lantas, bagaimana dengan shalat seseorang yang bacaannya khas kiai kampung? Diterima atau tidak?. Perkara diterima atau tidak, itu urusan Allah swt. Toh, Allah sendiri pernah menyatakan bahwa Ia tidak membebani hambanya melebihi batas kuasanya. Kasus musafir muda tadi mengajarkan kita untuk sesuatu yang penting; sesuatu yang menjadi peribahasa jawa yakni, “Ojo rumongso biso, nanging bisoho rumongso”. []