Salah satu penyakit kronis yang merebak beberapa tahun belakangan dari kaum urban, wa bil khusus para imigran internet yang kerap berselancar di dunia maya (dumay) dan memang “berhabitat” di berbagai jejaring media sosial (medsos) adalah pemutlakan paham dan pemberhalaan pendapat, terutama dalam beragama dan berpolitik: busuk, anyir dan berlendir.
Virus absolutisme tak lain merupakan pola pikir yang lamat-lamat menjadi pola sikap serba mutlak, sehingga cenderung intoleran dan bahkan menolak sama sekali pikiran dan paham di luar diri dan kelompoknya. Anda ingin tahu: apa saja jualan dan gorengan mereka yang telah mengidap kanker absolutisme stadium 4?
Tidak ada lagi selain 4-T, yakni: (1) ideologi takfiri alias gemampang teriak kafir-thoghut-PKI-Yahudi secara membabi buta kepada siapapun yang berbeda, (2) tasyriki atau sangat rajin menuduh syirik-liberal ke segala penjuru, (3) tabdi’i alias kerap membid’ah-bid’ahkan seenak perut, serta (4) tasykiki atau menyebar propaganda negatif dan berita bohong lewat buzzer-buzzer bayaran dan ustadz-ustadz sewaan dengan politisasi masjid agar timbul keraguan, kebencian, sentimen bermuatan SARA, kekacauan nasional dan pada gilirannya berjamaah menjadi pengikut meraka. Narasi-narasi sampah semacam inilah yang gentayangan di jagad medsos setidaknya satu dekade terakhir, tepatnya sejak era Menkominfo zaman SBY.
Wabah absolutisme ini tak hanya menjangkiti kaum puritan, kalangan Islam fundamental dan radikal yang bebal 24 karat tapi ramai-ramai berpolitik secara jahiliyah dan menjadi aktivis medsos secara barbar, namun demikian juga melanda sebagian besar generasi milenial yang sebelas-dua belas dengan mereka, yakni miskin literasi, fakir wawasan, tuna pustaka dan defisit akal sehat tetapi merasa tahu segala-galanya. Siapakah mereka?
Bani micin, pasukan otak cingkrang, kaum cuti nalar, gerombolan defisit otak, generasi sumbu pendek, paguyuban pemuja ketiak bidadari, konsorsium tukang kawin bermodal jenggot dan jidat, masyarakat daun kering, komunitas pentol korek dan apapun saja sebutan bagi para skriptualis karatan khas Wahabi, eks DI-TII, eks HTI, JAD, ISIS lokal, jihadis, jidatis, cingkrangis, hijrahis, pasukan nasi bungkus (panasbung), ormas radikal yang kalau lapar ngamuk-ngamuk dan nyusahin Negara, ormas tandingan garis lurus dan partai politik pemuja pan-islamisme Hasan al-Banna yang nalarnya telah membusuk dan menjadi fosil, sehingga tidak ada yang mereka banggakan selain kedunguan sampai ke ubun-ubun dan jahiliyah 14 turunan. Kabar buruknya, karena mereka sulit tertawa dan bahagia, maka tugas tertawa dan menertawakan itu mereka bagi rata ke seluruh rakyat Indonesia. Sayapun ikut menertawakan mereka, bukan lucu, tapi muak!
Mereka lazim menganut paham “hitam-putih” dalam beragama dan bahkan bernegara, sehingga tidak mentolerir “warna-warni” yang lain dan enggan membiarkan orang lain riang-gembira dengan warnanya masing-masing. Mereka karena pemahaman agamanya sebatas simbol kerap uring-uringan, bersungut-sungut, marah, alergi, ayan, kejang-kejang dan ketakutan dengan lambang tertentu, logo, geometri, gambar, seperti salib, segitiga, arca, relief, dll. Banalitas semacam ini yang menjadi biang keladi kemunduran umat Islam, meski mereka teriak paling beragama dan memang menggalakkan politik agama, karena merekalah pengasong firman Tuhan dan pengecer hadits Nabi demi syahwat politik yang na’udzu billah.
Dalam hemat saya (yang tak terlalu hemat), kanker ganas absolutisme dipicu oleh kurang matangnya seseorang setidaknya (1) dari segi intelektual, mengalami kemunduran fungsi nalar permanen, karena pengetahuannya “itu-itu” saja dan ironisnya, malah terjebak memberhalakan pemutlakan pendapat, sehingga sikapnya ya “gitu-gitu aja”; juga (2) masih amatir dari sisi emosional dan mental, sehingga menganggap hal-hal baru dan orang lain sebagai ancaman bagi “kemapanan” yang selama ini disembahnya; serta (3) rendahnya spiritualitas, eksesnya, terjebak pada atribut-atribut formal nirfaedah yang belakangan menjadi komoditas politik.
Sebagai pembaca yang cerdas, tentu anda bertanya bagaimana cara menangkal gelombang absolutisme, tsunami hoaks, badai pemutlakan pendapat dan prahara pemberhalaan paham agar bahtera besar bernama NKRI tidak karam?
Tentu saja dengan rendah hati terus belajar, melakukan pengayaan intelektual, merentangkan pikiran, memperluas cakrawala (1) keilmuan, horison (2) keindonesiaan, dan terutama khazanah (3) keislaman. Kabar baiknya, pondok pesantren menghamparkan ketiganya dengan pendidikan berbasis pekerti, local genius, dan budaya Nusantara melalui kitab kuning yang sangat ketat, bukan belajar agama secara instan seperti para bromocorah dumay dan begundal-begundal medsos itu, mengapa?
Karena internet tidak bisa menggantikan peranan guru dan gawai tidak bisa memberikan geneologi (sanad) ilmu! Jangan lupa, manusia bukan mesin, big data bukan big norak dan apalagi big barokah, teknologi bukan untuk disembah! Untuk beragama dan bernegara secara sinergi butuh proses. Proses adalah ketekunan, kesabaran dan kedisiplinan. Mengabaikan proses adalah mengacuhkan kualitas. Ingat, menelan “karbit” bukan solusi. Karbit, Anda tahu, ditelan menjadi racun, dimuntahkan manjadi api. Karbitan adalah kematangan yang palsu dan amatir.
Saran terbaiknya adalah: jangan menjadi “umat beragama oplosan” yang belajar agama hanya dari Al-Qur’an dan Hadits terjemahan lalu dioplos dengan bumbu politik populis! Jangan menjadi “muslim karbitan” yang merasa telah matang padahal sangat mentah, merasa telah sampai padahal baru melangkah, itu pun latah, merasa telah paripurna padahal belum berbuat apa-apa selain pongah!
Tak ayal, spiritualitas membutuhkan sosok pembimbing rohani (mursyid), spiritualitas tak bisa dibeli lewat penampilan formal semata dengan menggunakan daster rangkap tiga dan gamis motif polkadot, memakai serban sebesar parabola, mengenakan cadar layaknya Ninja lantas mengklaim telah hijrah, memaksakan diri impor jenggot dan berjidat biru, sementara prilaku tak ubahnya sobat gurun yang masih primitif (badawah) dan mabok kencing onta. Spiritualitas berangkat dari disiplin ilmu secara berjenjang, disiplin menjalankan akidah dan syariat secara ketat, serta disiplin moral untuk mencapai derajat manusia paripurna (insan kamil).
Jelaslah kini bahwa pengayaan intelektual, penempaan aspek emosional dan labih-lebih pendakian spiritual yang berbasis mie instan tak cukup diri untuk berislam dan berindonesia. Alih-alih mendamaikan dan harmoni dalam kebinekaan sebagaimana dicita-citakan para pendiri NKRI, keganasan kanker bernama absolutisme justru diprakarsai oleh tarbiyah-tarbiyah gadungan ala HTI-PKS di kampus-kampus juga media-media Wahabi dan salaf palsu yang sangat masif dekade belakangan ini. Mereka hanya memproduksi pemahaman Islam yang kaku, intoleran, dangkal, tidak memiliki pondasi epistemologi yang ajeg, kering dan tentu saja gampang dibakar oleh para srigala politik, para demagog khilafah, para oligark kekuasaan dan tentu saja para predator bisnis.
Mari melék kitab kuning, sebuah lanskap keislaman yang menjadi primadona kaum sarungan yang sangat kaya dengan dinamika pertarungan intelektual di mana ragam perbedaan pendapat (dalam berbagai disiplin) dirayakan sedemikian terbuka dengan argumentasi-argumentasi ilmiah tetapi tetap menjunjung tinggi pekerti mulia, toleran dan harmoni sebagai sesama anak Bangsa. Alfatehah untuk para Ulama Nusantara. Nah, kopi pahitnya mana?




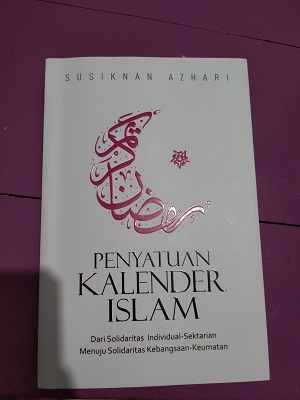



















[…] lebih dan pengetahuan yang sempurna. The greats Books dalam koridor pesantren ialah kitab-kitab kuning yang telah terklasifikasikan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti tafsir, fiqih, hadis, […]