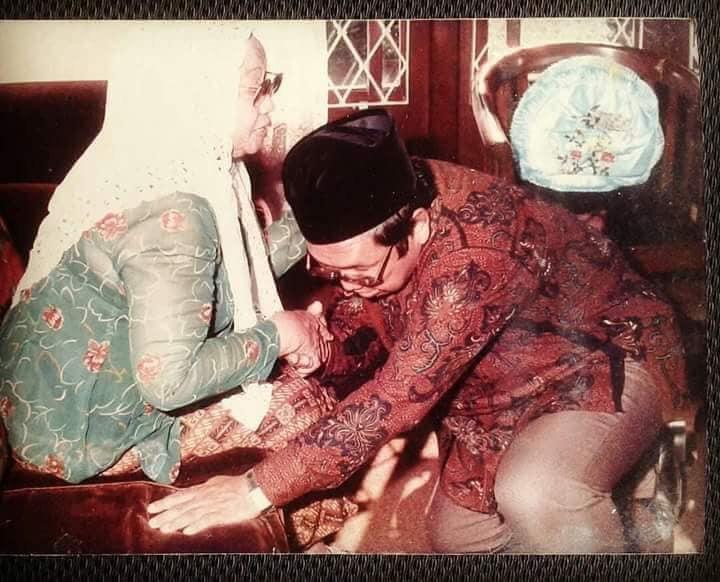Al-Anbiya: 46
وَلَىِٕنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ
Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, “Celakalah kami! Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi (diri sendiri).”
Pendapat yang beredar di kalangan para ahli tafsir, antara lain:
Pertama: Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah bahwa ancaman yang dikabarkan oleh Nabi Saw tidak akan digubris, kecuali jika orang-orang kafir merasakan sedikit saja tentang azab yang dijanjikan tersebut.
Kata massat-hum berarti sentuhan ringan, sementara nafḥat adalah semilir angin yang begitu lembut (ar-rīh al-layyinah). Jika dibuat permisalan, ia ibarat aroma bunga mawar yang menerpa hidung, bukan substansi bunga mawar itu sendiri. Bahkan dalam al-Kasysyāf, Imam az-Zamakhsyari menyebutkan ada tiga bentuk mubālāghah (makna superlatif) pada kata massat-hum nafḥat: (a) kasa massa yang berarti sentuhan kecil; (b) kata nafḥat karena mengandung makna al-qillah (sedikit sekali); dan (c) kata nafḥat yang juga mashdar li al-marrah (bermakna satu kali). Ini semua untuk menunjukkan bahwa azab yang diterima oleh orang-orang kafir hanyalah hembusan kecil min ‘ażābi rabbika (azab dari Tuhanmu) yang mereka jumpai pada kali pertama, dan pada saat itu layaqụlunna yā wailanā innā kunnā ẓālimīn (pastilah mereka berkata, “Celakalah kami! Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi [diri sendiri]”). Demikianlah pendapat kebanyakan ahli tafsir.
Kedua: Ungkapan spontan yang mereka katakan yā wailanā (Celakalah kami!) muncul dalam jiwa mereka, setelah mereka merasakan hembusan azab yang akan segera mereka terima. Lalu, mereka menyadari dan membuat pengakuan tentang kezaliman yang mereka lakukan innā kunnā ẓālimīn (Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi)! Begitu yang tersebut dalam tafsir Imam asy-Sya’rawi.
Sementara itu, kezaliman terbesar yang mereka lakukan boleh jadi berbentuk kemusyrikan, sebagaimana disuratkan dalam al-Quran:
…اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ
… sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Lukman: 13)
Atau berupa kekafiran,
…وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
… Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 254)
Ketiga: Jika memang makna zalim berpotensi mengarah pada syirik maupun kufur, bagaimana dengan nabi Adam As ketika mengaku sebagai orang yang zalim,
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
Keduanya (Adam dan Hawa) berdoa, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al-A’raf: 23)
Atau nabi Yunus As yang menyatakan dirinya sebagai orang zalim,
وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ
Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, ”Tidak ada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Anbiya`: 87)
Bagaimanakah makna zalim yang dimaksud?
Jawaban tentang pertanyaan ini sangat beragam, tapi sebagaimana dalam akidah Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah yang menyatakan para rasul memiliki wajib sifat amanāh, yaitu terjaga dari sesuatu yang makruh ataupun haram, tentu mereka tidak akan syirik dan kafir. Adapun pendakuan dalam doanya tidak lain, sebagaimana kaidah dalam ilmu tasawuf, bahwa:
حسنات الأبرار سيأت المقربين
“Kebaikan orang-orang pada umumnya adalah keburukan bagi orang yang dekat kepada Allah”
Sehingga, perasaan dan pengakuan diri sebagai orang zalim, bagi para rasul, bukan berarti mereka demikian adanya. Hal tersebut tak lain ialah adab dan bentuk kerendahan hati para utusan Allah tersebut di hadapanNya ketika telah melakukan suatu kesalahan, sekalipun hal itu merupakan kekeliruan yang kecil sekali. Wallahu a’lam.
Al-Anbiya: 47
وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔاۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَاۗ وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ
Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.
Beberapa hal yang penting disampaikan dari para mufasir:
Pertama: Dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan perihal yang terjadi di hari kiamat merupakan keadilan, sekalipun mereka telah berbuat zalim di dunia, di akhirat tidak satupun dari orang-orang kafir yang dizalimi. Imam ar-Razi menulis tentang makna wa naḍha’ul-mawāzīnal-qisṭha (dan Kami akan memasang timbangan yang tepat). Kata wa naḍha’u sebagai “Kami mendatangkan” (ihdhāru-hā), kata al-qisṭha sebagaimana dikutip dari Imam al-Farra` sebagai sifat bagi al-mawāzīn (beberapa timbangan), sekalipun kata al-qisṭha berbentuk tunggal dan kata al-mawāzīn berupa kata plural, namun hal ini tidak menjadi soal dalam kaidah bahasa Arab. Sementara Imam az-Zajjaj memaknaninya sebagai al-mawāzīn dzawāt al-qisṭha (timbangan yang memiliki nilai keadilan).
Kemudian, frasa liyaumil-qiyāmati dimakanai fi yaumil-qiyāmati (pada hari kiamat) oleh Imam al-Farra`; ada juga yang memaknainya dengan li ahl al-qiyāmah (untuk orang-orang yang berada di hari kiamat).
Kedua: Imam asy-Sya’rawi menyebutkan bahwa pengalihan pembicaraan dari tema keingkaran, pendustaaan terhadap rasul dan ketakpercayaan mereka terhadap wahyu, terhadap topik seputar perhitungan dan timbangan amal, ialah untuk menyadarkan dan mengalihkan fokus mereka terhadap konsekuensi hal-hal yang mereka perbuat ialah berpulang pada kebaikan mereka. Bahwa segala sesuatu akan diperhitungkan, ditimbang dan dikalkulasi. Hal ini seakan ungkapan nasehat bahwa kasih sayang Allah selalu menghendaki kebaikan dan kebahagiaan untuk mereka.
Kata al-mawāzīn adalah bentuk plural dari kata al-mīzan, yaitu alat ukur untuk menimbang sesuatu berdasarkan tingkat kepadatan atau massanya (al-wazn), sebagaimana jarak tempuh suatu perjalanan yang diukur dengan al-qiyās. Saat ini, para ilmuan sudah menetapkan standar internasional untuk tiap-tiap ukuran. Misalnya, ukuran Meter dengan sesuatu yang terbuat dari platinum agar mencegahnya dari perubahan, sebagaimana yang ada di kota Paris; begitu pula dengan Yard. Para ilmuan juga menjadikan pengukur berat dari besi untuk menandai Kilo ataupun Liter.
Imam asy-Sya’rawi menceritakan bahwa pada zaman dahulu, orang-orang menjadikan satuan berat dari potongan batu. Seiring berjalannya waktu, acuan batu itu berubah dan berkurang karena terlalu sering digunakan, karenanya akurasi suatu ukuran menjadi jauh dari kata presisi.
Kembali pada penjelasan tentang ayat di atas, dalam hal ini, Imam asy-Sya’rawi memiliki pandangan yang unik, bahwa seluruh mahluk akan ditimbang secara bersamaan dalam satu waktu. Hal ini sebagaimana riwayat bahwa Sy. Ali pernah ditanya, “Bagaiamana Allah menghitung amal seseorang dalam satu waktu?”
Lalu Sy. Ali menjawab, “Tentu sebagaimana Dia menganugerahi rezeki terhadap seluruh mahluk dalam waktu yang bersamaan. Hal ini tampak sulit juga bagi kita (mahluk), tetapi begitu gampang dan mudah bagi Allah Swt!”
Sementara itu kata al-qisṭha adalah bentuk mashdar yang bermakna “adil”. Untuk menunjukkan makna keadilan yang lebih besar, maka tidak dikatakan kepada seorang hakim dengan redaksi “anta al-‘ādil” (engkau seorang yang adil), melainkan “anta al-‘adl” (engkaulah keadilan). Karena itu kita mengatakan dalam al-Asma` al-Husna bahwa Allah al-Hakm al-‘Adl.
Secara bahasa, kata dengan huruf q-s-th berikut variannya memiliki makna yang beragam, bahkan mengandung makna yang bertentangan (antonim) di dalamnya. Hal ini sebagaimana kata az-zauj yang bisa berarti “suami” ataupun “istri”; kata al-‘ain yang dapat bermakna “mata”, “sumber air”, “mata-mata” bahkan “emas-perak”. Demikian pula makna al-qisth (harakat kasrah pada huruf qāf) yang berarti “adil”, sebagaimana firman Allah:
…وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
…Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Ma`idah: 42)
Ataupun al-qasth (harakat fathah pada huruf qāf) yang justru bermakna zalim, sebagaimana tersebut pada ayat berikut:
وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًاۙ
Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran (zalim), maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam. (QS. Al-Jinn: 15)
Ketiga: Imam ar-Razi merangkum makna al-mawāzīn menjadi dua: (a) yang dimaksud dengan al-mawāzīn adalah keadilan itu sendiri—makna majāzi, pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam adh-Dhahhak. Sehingga makna timbangan yang adil adalah manakala seseorang diliputi oleh kebaikan dibanding keburukannya, maka menjadi beratlah timbangan amal baiknya,
وَالْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ِۨالْحَقُّۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Maka barangsiapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang yang beruntung. (QS. Al-A’raf: 8)
Sementara jika keburukan yang mendominasinya, maka dianggap ringanlah timbangan amalnya,
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ
dan barangsiapa ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami. (QS. Al-A’raf: 9)
Dan (b) pendapat para imam salaf bahwa Allah Swt meletakkan timbangan dengan makna hakiki, untuk menimbang amal-amal manusia.
Imam ar-Razi juga menceritakan sebuah riwayat tentang nabi Daud As yang meminta kepada Allah agar diperlihatkan tentang timbangan amal. Takkala permintaan itu dikabulkan, seketika beliau pingsan. Setelah siuman, beliau bertanya, “Oh Tuhanku, siapakah yang sanggup memenuhi timbangan kebaikan yang [besar] seperti itu?”
Lalu Allah menjawab, “Jika Aku ridha terhadap seorang hamba, maka Aku akan memenuhi timbangan kebaikannya sekalipun dengan sedekah satu butir kurma!”
Keempat: Imam ar-Razi dan Imam asy-Sya’rawi memberi ulasan perihal ayat yang tampak kontradiksi dengan yang sedang dibahas saat ini, yaitu:
اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاۤىِٕهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا
Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan (tidak percaya) terhadap pertemuan denganNya. Maka sia-sia amal mereka, dan Kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat. (QS. Al-Kahfi: 105)
Pada surat al-Kahfi: 105 ini menyiratkan pemahaman bahwa orang-orang kafir kelak di hari kiamat tidak akan ditimbang amal baiknya, berbeda dengan al-Anbiya: 47 yang menyatakan sebaliknya.
Dalam menjawab ini, Imam ar-Razi mentakwil makna pada al-Kahfi: 105, bahwa yang dimaksud “…Kami tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat” adalah bahwa Allah tidak mengagungkan dan memuliakan mereka, sehingga sekalipun setiap amal mereka ditimbang, seakan tidak ditimbang—karena mereka diabaikan dan dianggap tidak memiliki kebaikan sama sekali!
Di sisi lain, Imam asy-Sya’rawi menceritakan perihal yang mempertanyakan ayat ini adalah orang-orang orientalis. Tetapi, beliau memberikan toleransi terhadap anggapan tersebut, sebab mereka sangat lemah dalam masalah ilmu kebahasaan sehingga sulit memahami makna al-Quran kecuali secara tekstual semata.
Seandainya kita merenung, ajak Imam asy-Sya’rawi, bahwa huruf lām pada kalimat lā nuqīmu lahum (di surat al-Kahfi: 105) memiliki fungsi li al-milk wa al-intifā’ (bermakna kepemilikan dan sesuatu yang memberi manfaat), tentu kita bisa mengurai persoalan yang ada. Jadi memaknai fa lā nuqīmu lahum yaumal-qiyāmati waznā sebagai “Kami tidak memberikan [manfaat] penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari Kiamat”. Demikianlah menyelesaikan problem kontradiksi dua ayat di atas.
Kelima: Tentang kalimat fa lā tuẓhlamu nafsun syai`ā (maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit), Imam ar-Razi begitu baik dalam membuktikan bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, sekaligus menolak konsep ta’dīl[1] kaum Muktazilah. Bagi Imam ar-Razi, aẓh-ẓhlam adalah berbuat sesuatu (at-tasharruf) pada hal yang dimiliki atau dikuasai oleh orang lain; dan hal itu tentu tidak pernah terjadi pada Allah—karena segala sesuatu memang milikNya dan dikuasai olehNya. Pembuktian secara rasional ialah bahwa berbuat zalim kepada seseorang boleh jadi dikarenakan ia “tidak mengetahui” (al-jahl) atau karena ia sedang “terdesak” (al-hājat) untuk berbuat tersebut. Sementara “ketidaktahuan” dan “terdesak” adalah dua hal yang mustahil bagi Allah; sesuatu yang meniscayakan hal mustahil pasti mengantarkan pada kemustahilan. Dengan demikian, kezaliman tidak akan mungkin dilakukan oleh Allah terhadap hambaNya.
Keenam: Sementara firmanNya wa in kāna miṡqāla ḥabbatim min khardalin atainā bihā (sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya [pahala]) ditafsirkan oleh Imam asy-Sya’rawi dengan cukup menarik. Bagi beliau kata miṡqāla ḥabbatim min khardalin (biji sawi) menunjukkan kuantitas yang kecil dari sisi bentuknya, sementara kata miṡqāla (berat) menunjukkan massa atau kualitas yang lebih substansial. Dengan demikian suatu amal, harus mengandung keduanya, zahir yang baik (sesuai syariat) dan batin yang murni (ikhlas).
Sementara Imam ar-Razi mengungkap suatu makna yang luar biasa perihal kata ḥabbat yang lebih besar dibanding khardal tapi keduanya disandingkan sedemikian adanya, sehingga ayat ini bisa dimaknai seperti ini: sekalipun ada suatu amal, entah kecil atau besar, yang muncul dari sesuatu yang tak kalah kecilnya, Allah berjanji untuk tidak menyia-nyiakannya, semua akan mendapat balasan dariNya.
Ketujuh: Kalimat penutup dalam ayat ini, wa kafā binā ḥāsibīn (dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan) bertujuan memberi peringatan (at-tahdzīr) bahwa yang akan menghitung amal memiliki pengetahuan yang detail, tanpa ada yang samar sedikitpun bagiNya, mempunyai kekuasaan tanpa titik lemah sama sekali, hal ini agar seseorang yang berakal tak henti-hentinya merasa takut (al-khauf) kepadaNya.
Sementara bagi Imam asy-Sya’rawi, melakukan perhitungan bukanlah suatu yang mudah—bagi mahluk, lebih-lebih untuk menemukan akurasi yang tepat. Bahkan neraca modern sekalipun belum tentu menjamin hal itu, karena jika terdapat sedikit saja kekeliruan teknis, ketimpangan akan terjadi. Sementara itu, ayat ini menjelaskan agar wa kafā binā ḥāsibīn (dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan), karena neraca dari Allah tak pernah berubah dan Dia juga tidak pernah lupa akan apapun yang diperbuat oleh manusia. Wallahu a’lam. [HW]
[1] Keadilan Tuhan bagi Muktazilah adalah Tuhan memberi balasan surga kepada orang yang baik dan membalas neraka kepada orang yang buruk, tanpa bisa merubah hukum tersebut. Berbeda dengan Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah yang menganggap bahwa Allah menganugerahkan surga semata karena fadhilahNya dan memasukkan orang-orang buruk ke neraka dengan keadilanNya, tanpa tanpa tuntutan apapun atas yang Tuhan berikan.