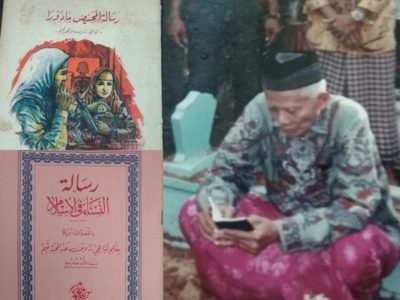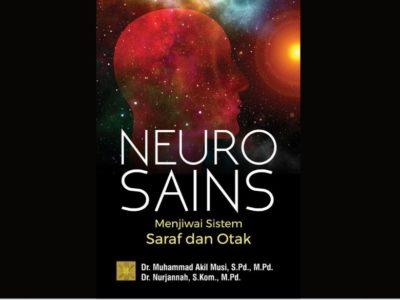Terhadap apa yang berhubungan dengan perempuan selalu menarik untuk dikaji dan terus ditafsir lebih lanjut. Hal ini, dalam hemat saya (yang tidak terlalu hemat), lantaran perempuan adalah pancaran dari Tuhan yang paling lengkap dan indah. Sementara para lelaki, tak lebih dari sekadar penafsir akan keindahan dan keluhuran perempuan, itupun acapkali ugal-ugalan dan salah tafsir!
Adalah Simone de Beauvoir (1908-1986), filsuf perempuan dan tokoh feminisme Prancis dalam bukunya Le Deuxième Sexe atau The Second Sex (1949) yang pernah melontarkan protes kerasnya terkait perlakuan terhadap perempuan di tengah masyarakat Eropa dengan kalimat: “One who is not born is the Other, but woman.” Ya, perempuan tidak terlahir, melainkan dicetak, dibentuk. Itu artinya, perempuan tertindas dan terpenjara sekaligus terdepak dari kesetaraan. Perempuan adalah sang “liyan” yang tidak hanya berbeda, tetapi juga sengaja dibeda-bedakan secara diskriminatif oleh lelaki, baik lelaki secara personal, maupun lelaki dalam bentuk sistem dan nilai.
Dalam pandangan de Beauvoir, perempuan tak punya hak atas dirinya, atas tubuh dan pikirannya, bahkan kesantunanpun harus “menyesuaikan” dengan keinginan lingkungan dan komunitas, dalam hal ini, siapa lagi kalau bukan lelaki?!
Perempuan dalam The Second Sex seolah tak punya “kehadiran”, sebab yang memberi “makna” adalah lelaki. Ia tak punya kebebasan, kesetaraan dan keluhuran martabat sebagai manusia. Seonggok tubuh perempuan tak lain adalah obyek pelampiasan nafsu, kekesalan, kekecewaan, dan kekejian maskulinistik yang jumawa.
Filsuf perempuan ini sekali lagi telah menegur kita bahwa di Eropa saja, masih banyak perempuan yang terkungkung dan menjadi The Second Sex, baik secara ekonomi, politik, budaya, dan terutama pendidikan. Perempuan seakan terus berada di pinggiran sejarah, di tepian keseharian lelaki. Inilah yang menyebabkan perempuan rentan mengalami perbudakan, penganiayaan, intimidasi dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga, juga oleh nilai-nilai yang terus dikembangkan secara budaya.
Bukti konkret dari narasi de Beauvoir adalah para nakerwan (Tenaga Kerja Wanita) atau TKW yang kerap pulang ke Indoensia dalam keadaan TKO alias Total Knock Out. Masih ingat Sumiati? Ia dianiaya majikannya di Arab Saudi dengan kaki hampir lumpuh, bibir digunting, muka sembab dan bonyok, belum lagi caci-maki, hujatan dan tentu saja pelecehan seksual. Derita sumiati ini terjadi persis ketika umat Islam sedang merayakan hari raya Kurban sekian tahun silam.
Untuk menyebut beberapa kasus saja, Mei 2004 di Malaysia, Nirmala Bonet, nakerwan asal Kupang NTT disetrika majikannya dan disiram air panas, dicambuk dan terdapat luka bekas sayatan pisau di wajah. Juni 2005, Binti Salbiyah asal Madiun, dipukuli dan disiksa majikannya di Singapura hingga kedua tangan lumpuh total. Mei 2007, Mita Retningsih asal Sumedang mengalami kelumpuhan karena patah tulang punggung setelah melompat sari lantai tiga rumah majikannya di Jeddah, Arab Saudi lantaran tak tahan lagi disiksa, juga Tina Rayahu asal Garut, depresi berat dan harus dirawat di RSJ karena terlalu lama disiksa dan dianiaya, belum lagi Ceriyati atau yang populer dengan Shamelin, bahkan beberapa penyumbang devisa Negara itu diperkosa, dibunuh dan atau dihukum mati meskipun majikan mereka yang bersalah.
Dalam situasi seperti ini, apakah perempuan masih punya makna “kehadiran” sebagai subyek di tengah masyrakat yang mulai canggih dan beradab?
Simone de Beauvoir yang meninggal pada 1986 setelah menderita pneumonia dan dimakamkan di sisi Jean-Paul Sartre di Pemakaman Montparnasse, Paris secara blak-blakan mengkritik nama-nama besar dalam lanskap filsafat. Menurut de Beauvoir, para filsuf klasik sejak Plato(n), Aristoteles, sampai Heidegger, juga terutama Hegel, Kant, dan Marx telah menenggelamkan perempuan dalam kubangan misterius “sistem rasional”. Dalam polis Yunani, perempuan bukan warga negara, sebab polis adalah negara para lelaki. Perempuan hanya ada di kerumunan para budak, sama sekali tak ada rasionalitas dalam eksistensi makhluk mulia bernama perempuan.
Seluruh bangunan filsafat Aristotelian—dalam pembacaan saya—juga tak menjangkau perempuan. Buktinya? Dalam mukadimah Metafisika-nya, Aristoteles menyebut bahwa kecenderungan alami manusia adalah ingin mengetahui. Dan frase ini, ironisnya, tidak mencakup perempuan, sebab tugas mereka hanya melahirkan, tidak lebih! Itu artinya, perempuan tak layak mendapatkan pendidikan sebagimana lelaki, bahwa melahirkan adalah tugas mulia seorang perempuan, hal ini sudah sangat fitrah dan alami, tapi hak sebagai warga negara acapkali terabaikan.
Siapa lagi? Hegel. Ia malah secara angkuh dan jumawa mengatakan bahwa tidak ada rasionalitas dalam diri perempuan. Filsafat transendental Hegel yang tidak membumi ini kelak dikritik secara tajam oleh muridnya, Kierkegaard, lantaran sang guru telah menafikan eksistensi manusia dalam sejarah!
Kant bagaimana? Setali tiga uang dengan Hegel. Ia membongkar epistemologi Aristotelian yang memiliki keterikatan pada obyeknya dan lantas mendeklarasikan pengetahuan secara murni milik ajal budi, milik laki-laki.
Dalam tutur budaya Jawa, perempuan itu hanya 3-M, yakni: masak, macak (bersolek) dan manak (melahirkan). Juga ujar-ujar lama yang masih sayup-sayup terdengar dari alam bawah sadar bahwa perempuan itu hanya di kasur, di sumur, di dapur dan lalu dikubur.
Padahal, dalam narasi pewayangan dan tentu saja filsafat) Jawa, terdapat perempuan yang disebut Srikandi (isteri Arjuna), Kunti (ibu Pandawa dan Kurawa), Drupadi (isteri Yudistira), Setyawati (isteri prabu Salya, paman Pandawa), Dewi Sitisundari dan Dewi Utari (keduanya isteri Abimanyu, yang pertama gugur bersama suami, yang kedua melahirkan Parikesit). Mpu Panuluh dan Mpu Sedah menulis Kakawin Baratayuda, satu karya sastra dab sekaligus filsafat dari zaman kejayaan Kediri yang dipimpin raja Jayabaya. Kakawin Baratayuda memaparkan bahwa perempuan tak hanya di rumah, mereka juga tampil di medan laga dan bertempur habis-habisan sebagai ksatria.
Salam Takzim.