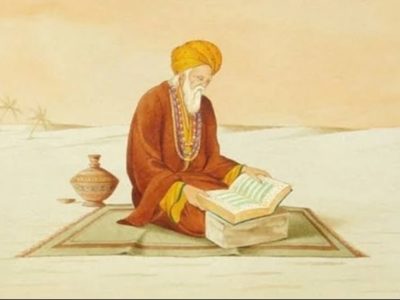Publik sangat mengenal Gus Dur, tapi sangat sedikit yang mengenal Gus Im. Padahal kakak-adik putra founding father dan tokoh NU KH Wahid Hasyim bin Hasyim Asy’ari tersebut ibarat satu keping mata uang di sisi yang berbeda. Dalam bahasa Gus Im sendiri, mereka adalah Ikarus kembar.
————–
Lahir di Jakarta 30 Oktober 1953, tiga bulan sebelum ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil yang ia yakini sebagai operasi intelijen, Gus Im yang bernama lengkap Hasyim Wahid adalah sosok yang misterius. Ia menyukai buku-buku tapi juga menggilai keris dan senjata. Ia jago aljabar dan matematika tapi juga menggeluti dunia klenik dan metafisika. Ia sangat rasional dalam sebuah kesempatan tapi bisa konspiratif dalam kesempatan yang berbeda. “Iim adalah adikku yang paling susah dimengerti,” kata Gus Dur suatu kali.
Meski besar sebagai anak Menteng dengan ayah mantan menteri dan kakek Rais Aam NU, Gus Im hobi keluyuran ke tempat-tempat kaum underdog. Sejak SMP ia sering bermain ke Pasar Jatinegara, sebuah kebiasaan yang ia lakukan hingga masa tuanya. Ia berteman dengan para penjual batu akik serta preman-preman yang ada di sana. Ia selalu berpikir dan bekerja agar dunia lebih terang tapi sangat menyukai–dan menertawakan–kisah-kisah kriminal yang gelap. Ia menyukai novel-novel John le Carre dan “Darkness is my ally” adalah salah satu kutipan yang sering ia tirukan, berasal dari film Zatoichi: The Blind Swordsman.
Ia akrab dengan buku tetapi juga hobi mengutak-utik sesuatu. Tak puas dengan karombol yang dibeli kakaknya, ia membuat karombol sendiri yang lebih baik kualitasnya. Craftsmanship adalah salah satu hobi dan keahliannya, yang masih terlihat hingga masa tuanya lewat aktivitas membuat keris atau merestorasi pistol tua.
Seperti Gus Dur, Gus Im dikenal cerdas oleh teman-teman atau saudaranya. “Ia bisa memecahkan soal aljabar dengan rumusnya sendiri,” kata Amanda Damayanti, teman SMA-nya. Saat teman-teman SMP-SMA-nya asyik dengan bacaan remaja ia sudah berkutat dengan memoar Gandhi dan puisi-puisi Pablo Neruda. Namun ia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Ia pernah masuk jurusan Teknik Kimia ITB serta jurusan Psikologi dan Ekonomi UI, tapi tiga-tiganya hanya dijalaninya sebentar saja. Tiap ditanya kenapa ia hanya menjawab pendek, “Enggak cocok aja.”
Sebagai orang yang dua puluh tahun lebih mengenalnya dan juga sebagai orang yang tidak berbakat kuliah, aku bisa memahaminya. Gus Im adalah seorang defian, outlier, ikonoklas, subversif. Ia pintar sekaligus punya mental pembangkang. Dalam sebuah puisinya ia menyebut diri sebagai “penganggur terselubung dan pembangkang terbuka.” Ia tak bisa dikungkung dan dibatasi oleh kotak-kotak sosial atau spesialisasi pengetahuan yang diciptakan oleh tradisi modern.
Seperti Gus Dur, ia juga penikmat musik yang di atas rata-rata. Jika Gus Dur lebih menyukai genre klasik—baru kemudian blues, Gus Im lebih menyukai rock & blues—baru kemudian klasik. Ia menggilai Jimi Hendrix setinggi langit dan tergila-gila dengan lirik “Permisi, biarkan aku mencium langit” dalam Purple Haze. Di rumahnya terpampang foto besar Jimi Hendrix dengan gitarnya.
Gus Im mengagumi para musisi generasi flower generation seperti Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan dan Led Zeppelin karena mewakili semangat perlawanan zaman–selain lirik-liriknya, tetapi juga penikmat sejati musik metal yang belakangan seperti Guns n Roses dan Metallica. Dalam sebuah kesempatan bersama Saleh Isre kami diajak menonton Metallica Night di sebuah klub dan ia asyik bernyanyi sambil berdiri dan menyalakan korek api. Sebelum Youtube–apalagi Spotify–mengemuka dan covering musik bisa dinikmati sedemikian mudahnya, ia sudah mengoleksi seratus lebih versi Knockin on Heaven’s Door yang dinyanyikan secara berbeda. Tentu saja ilegal, dari dunia darkweb yang sering ia telusuri.
Aku beruntung termasuk orang yang sering dibagi kopian koleksinya. Aku menonton DVD konser No Quarter Jimmy Page dan Robert Plant darinya. Aku mengenal gitaris jazz fusion John McLaughlin juga dari Gus Im. Belum lagi lagu-lagu Metallica yang aku juga menyukainya. Ia memang royal dalam soal berbagi musik, film atau buku kepada teman-temannya. Ia pernah membeli buku—terutama Bahasa Inggris—hingga ratusan juta dan sebagian dibagikan ke teman-temannya. Aku masih ingat terakhir kali diberi buku Oligarki karya Jeffrey Winters.
Sudah sejak muda Gus Im menaruh perhatian besar terhadap negara-bangsa Indonesia yang kemerdekaannya ikut diperjuangkan oleh ayah dan kakeknya. Tak satu kesempatan pun pertemuan kami yang luput membicarakan Indonesia. Ia akrab dengan anak-anak muda angkatan 80-an dan 90-an yang aktif dalam gerakan pro-demokrasi di era Orde Baru. Banyak kawan yang pernah terlibat diskusi dengannya. Ia banyak hadir di forum-forum dan komunitas aktivis mahasiswa. Ia sering muncul di YLBHI atau PIPHAM, dua markas yang sering dijadikan tempat berkumpul aktivis-aktivis penentang Orba, selain nongkrong di LKKNU, tempat nongkrongnya aktivitis muda NU. Namun tidak seperti Gus Dur yang kehadirannya selalu mengundang tatapan mata, kehadiran Gus Im sering tak menarik perhatian.
Ia tidak suka tampil dan memilih “berdiri di belakang” serta fokus dengan orang-orang yang ia anggap bisa diajak bergerak bersama. Seperti talent scout sepakbola ia mendekati aktivis-aktivis yang ia anggap satu frekuensi dan bisa memainkan peran dalam gerakan yang ia bayangkan. Tidak seperti leader yang tampil dan memimpin di depan, ia lebih seperti guru yang tut wuri handayani dan kawan yang ing madya mbangun karso. Ia adalah kawan, kakak dan guru bagi banyak aktivis pergerakan angkatan 80-an dan 90-an. Ia akrab dengan aktivis-aktivis Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) yang ditangkap dan dipenjarakan Orba karena menuntut Presiden Soeharto mundur 1993, dan ia ada di tengah-tengah massa saat terjadi demo menentang penyerangan kantor PDIP 27 Juli 1996.
Pengetahuannya tentang geopolitik yang luas menjadi sumbangan penting bagi perspektif internasional kami semua. Dan semua disampaikan tidak dalam cara yang menggurui dan superior, melainkan dalam mode brainstorming dan diskusi dialektik yang sangat egaliter. Dalam soal metode, Gus Im bisa dibilang seorang sokratik, yang alih-alih menyampaikan gagasan lewat presentasi panjang ia memilih pendekatan brainstorming dan dialog mendalam lewat beragam pertanyaan.
Karena lebih banyak menyampaikan gagasan lewat dialog langsung yang tidak direkam, maka pengetahuan dan pandangan-pandangannya hanya dinikmati oleh mereka yang mengenalnya secara langsung. Satu-satunya buku yang boleh dibilang mencerminkan pandangannya terkait geopolitik adalah buku kecil berjudul Telikungan Kapitalisme Global yang ditebitkan oleh LKiS tahun 1999, yang menurutnya perlu diupdate sesuai perkembangan terkini. Saat muda ia—bersama Gus Dur—juga menerjemahkan karya Sayd Hussein Nasr, Islam: Dalam Cita dan Fakta.
Kecuali keterlibatan dalam penerjemahan karya Hussein Nasr, Gus Im memang tidak banyak berbicara tentang keislaman seperti Gus Dur, dan hidupnya tidak bisa dibilang islami dalam arti konvensional. Namun seperti Gus Dur, pandangan hidupnya banyak dipengaruhi tradisi Qur’ani. Ia banyak memaknai dunia lewat insight-insight yang dikemukakan ayat-ayat Qur’an. Ia mencintai para sufi, dan sempat menuliskan puisi untuk Al-Hallaj, sufi yang dihukum mati karena keyakinannya dianggap sesat.
Ia menyukai dan mengagumi orang-orang yang berani melawan dan mengambil jalan berbeda. Hidup yang ia pilih–dan juga Gus Dur tempuh–pada dasarnya mewakili semangat itu: perlawanan terhadap rezim yang dominan, baik rezim politik, ekonomi, sosial maupun pemikiran. Meski harus ia akui ia sering kalah dalam pertarungan itu. Dalam puisinya Interogasi 1982 ia bercerita bagaimana ia ditangkap dan diinterogasi tentara Orba. Ia juga sering bercerita bagaimana bisnisnya selalu dibunuh oleh kroni Cendana saat belum berbunga. Dan yang paling tragis saat ia menyaksikan kakak yang dikasihinya meski sering bikin ia jengkel, Abdurrahman Wahid, dijatuhkan dari kursi kepresiden dengan tuduhan yang menyakitkan: terlibat korupsi.
Dari semua perjalanan hidupnya, juga tafsir atas perjalanan ayahnya (meninggal kecelakaan) dan ibundanya (sakit panjang juga akibat kecelakaan), ia sering memaknai dirinya sebagai representasi kekuatan yang berusaha melawan tapi harus diakui berakhir dengan kekalahan. Meski tidak pernah mengutip kalimat “Kita sudah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” yang diucapkan Nyai Ontosoroh dalam novel Pramoedya Bumi Manusia, tetapi aku sangat merasakan nada itu dalam banyak ceritanya. Puisi Tentang Sisyphus dan Ikarus Kembar adalah gambaran Gus Im terkait dirinya dan Gus Dur, yang selalu berusaha berjuang tapi harus dengan pahit menyaksikan apa yang diperjuangkannya selalu menggelinding lagi ke bawah dan menyadari kenyataan yang harus dihadapi bahwa jika mereka terbang terlalu tinggi maka lilin yang mengikat sayap-sayap mereka akan meleleh dan mereka pun jatuh ke bumi.
Ada terlalu banyak hal yang bisa diceritakan–dan juga tak bisa diceritakan, tapi Gus Im sosok eksentrik yang sulit dicari padanannya di kalangan nahdliyin. Ia seorang Gus tapi dengan lantang menyebut dirinya korak (preman). Tapi di luar penampilannya yang urakan dan gaya komunikasinya yang tak jarang memang seperti preman, Gus Im menyimpan kelembutan dan hatinya selalu untuk mereka yang disingkirkan dan dikorbankan. Buku kumpulan puisinya, Bunglon, sarat kritik sosial dan solidaritas atas orang-orang tertindas serta orang-orang yang bangkit melawan. Ia tidak suka tirani dan hegemoni. Hidupnya praktis dihabiskan untuk menentang tirani (Orde Baru) dan hegemoni (Amerika), bahkan olah spiritual dan kegiatan metafisiknya diarahkan ke sana. Melebihi Gus Dur, ia bisa berminggu-minggu menjelajahi makam-makam atau tempat keramat di Jawa, untuk berdzikir atau menebar rajah, demi keruntuhan Orde Baru atau keselamatan Indonesia. Kamarnya dipenuhi beragam keris dan serakan kertas bertuliskan doa-doa dan rajah dalam bahasa Arab. Tidak masuk akal sepertinya, tapi di situlah keunikan Gus Im. Ia tak ubahnya manusia multi-dimensional, yang tak mudah diidentifikasi dalam ragam identitas yang kita kenal.
Sabtu, 1 Agustus 2020, Gus Im telah pergi meninggalkan kita. Ia menyusul kakak yang sekaligus ia anggap sebagai ayahnya, Abdurrahman Wahid. Bukan hanya kaum nahdliyin yang kehilangan, tetapi juga komunitas pergerakan. Hari ini adalah haul pertama atas kematiannya, mari sejenak mendoakan arwahnya. Alfatihah! []