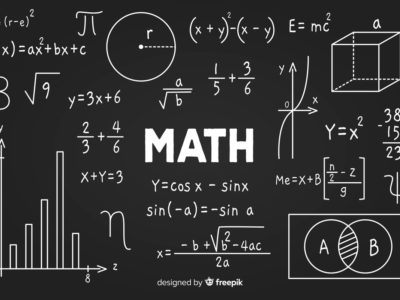Era keterlimpahan informasi -yang biasa dikenal sebagai disrupsi, melahirkan banyak sekali kemajuan-kemajuan peradaban manusia yang tidak pernah terjadi selama 5000 tahun terakhir semenjak peradaban Sumeria lahir. Manusia di era disrupsi dengan mudahnya menemukan solusi dari setiap permasalahan-pemasalahan yang mereka temui. Dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang mengancam nyawanya dapat diatasi dengan mudah.
Disrupsi memang menjadi anugerah tersendiri bagi manusia modern, akan tetapi ia memiliki “sisi gelap” tersendiri bagi keberlangsungan hidupnya. Ternyata tidak selamanya “informasi” yang didapatkan manusia digunakan sebagai alat untuk melindungi dan menciptakan “keadaban” manusia yang lain. Tak jarang “informasi” yang mereka dapatkan justru digunakan untuk “menghancurkan” manusia yang lainnya, dan berakibat “kehancuran” dirinya sendiri. Dengan kata lain semua bisa dan boleh mengakses “informasi”, tetapi ternyata tidak semua “pantas”mengaksesnya, karena justru informasi tersebut ia gunakan untuk hal-hal yang distruktif. Salah satu contoh anomali dalam mengakses informasi yaitu “peradaban Pendidikan“di Indonesia.
Di Indonesia, banyak sekali Lembaga-lembaga pendidikan yang lahir untuk mengakses informasi (baca:pengetahuan) dengan tujuan utamanya mencetak intelektual tradisional sebagaimana yang dimaksud oleh Antonio Gramsci dalam bukunya “the prison book”. Intelektual-intelektual ini banyak menghamba dan rela menjadi budak “hegemoni” penguasa dengan mengatasanamakan kebenaran dan demi kesejahteraan bersama.
Benarkah demikian? Nyatanya intelektual-intelektual tersebut dilahirkan hanya demi memenuhi hasrat “kapitalis” baru di era modern, Yaitu kapitalisme Pendidikan. Apa itu kapitalisme Pendidikan? Yaitu sebuah “mesin” penghasil kapital yang diciptakan dengan mengatasnamakan, “untuk mencerdaskan manusia” tetapi sejatinya hanya untuk melindungi kalangan “borjuis” dan”pemilik modal”dari terancamnya status quo mereka.
Berbeda dengan kaum ”kapitalisme” ekonomi yang dengan terang-terangan mempraktikan dan mengakui kepentingan mereka untuk melanggengkan kekuasaan “kapitalnya”, kapitalisme Pendidikan, dengan malu-malu mengakui hal tersebut, dengancara menutupi wajah “kapitalisme”nya menggunakan topeng “berjuang demi kehidupan manusia” yang lebih baik.
Dalam system “kapitalisme Pendidikan” ini, yang benar-benar hidup adalah mereka yang memiliki “kapital” lebih besar dibandingkan yang lain. Selain itu mereka yang memiliki “previllage” menempatkan diri mereka lebih tinggi lagi, dan bahkan tidak tersentuh. Dari sinilah muncul kesenjangan “intelegensia” dan rekognisi yang didapatkan, meskipun para “intelektual” tersebut menempuh “jenjang Pendidikan” yang sama, dan mungkin mendapatkan materi pembelajaran yang sama pula, tetapi ternyata hasil yang diadapatkan sangat jauh berbeda.
Oleh karena para intelektual tradisional rela “membayar berapa pun” untuk mendapatkan pengakuan “intelektual” mereka dari status quo, maka tak heran yang kita dapatkan adalah GBHN (Guru Besar Hanya Nama). Rekognisi “semu” inilah yang menjadikan masyarakat awam justru mencari “intelektual organik” yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pencerahan dari hiruk pikuk “banjirnya” informasi yang beredar. Mereka lahir dari “rahim” sistem pendidikan yang “cair” dan tidak terikat oleh “hegemoni” penguasa. Bahkan terkesan melawan sistem baku dari pemerintah, sistem itu dikenal sebagai pondok pesantren.
Contoh riil hasil dari “sistem pondok pesantren” akan kita dapati Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Gus Baha’ (Ahmad Baha’udin Nursalim), Kyai Sahal Mahfudz, Kyai Musthofa Bisri (Gus Mus) dan masih banyak lagi yang mana selama ini menunjukan kecerdasan sebagai intelektual organic, memberikan pencerahan dan Pelepas dahaga di tengah keringnya perdebatan ilmiah di zamannya.
Akan tetapi sangat disayangkan, akhir-akhir ini system pondok pesantren berangsur-angsur “terseret” arus perubahan zaman, tak mampu membendung “keterlimpahan informasi” yang beredar di masyarakat. Mereka berlomba-lomba membangun institusi yang menyerupai “institusi” penguasa. Rela dan tunduk terhadap “standar” yang ditetapkan penguasa, pada akhirnya “banyak pondok pesantren” justru mesra dengan melanggengkan “hegemoni” penguasa, dan tergulung arus “pasar” Pendidikan, demi mempertahankan eksistensinya. Memang di satu sisi mereka masih mampu mempertahankan “ciri khas” Pendidikan pondok pesantrennya, tetapi semakin sedikit melahirkan “intelektual organik” sebagaimana pada era-era tahun 90-an.
Intelektual-intelektual lulusan pesantren kini pun tak luput ikut terseret “gemerlapnya” menjadi intelektual tradisional. Mereka tak segan-segan lagi “menghambakan” diri dan memperjual belikan identitas “intelektual” pesantrennya demi melayani “hegemoni” penguasa. Mereka sulit sekali meraih “metakognisi” yang dahulu sangat khas sekali dimiliki oleh seorang santri. Akhirnya kini yang tampil dipublik “santri intelektual” yang kehilangan indentitas intelegensianya. Entah, apakah kita akan menemukan lagi “intelektual organik” seperti Gus Baha’, Gus Mus, Gus Dur, Cak Nun dalam 20, 30 bahkan 50 tahun mendatang, apabila “system pondok pesantren” ini tidak menyadari kehilangan besar tersebut. Semoga saja kekhawatiran saya ini tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Semoga!. []