Tingginya kasus kekerasan seksual yang menimpa negara kita, juga mengindikasikan masih banyak pikiran masyarakat yang terpatri pada budaya jahiliyyah. Bagaimana tidak, seseorang yang sepatutnya dijaga kehormatanya dirusak begitu saja oleh tindakan yang abnormal. Setiap hari tidak bosanya kita memperolah kabar di berbagai media mengenai kasus pencabulan terhadap anak, pemerkosaan, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual terhadap anak, pemaksaan perkawinan, dan masih banyak lagi. Hal ini diperparah dengan sikap apatis sebagian masyarakat kita terhadap peristiwa itu dan bahkan cenderung menyalahkan korban dan menjauhinya.
Sikap apatis terhadap korban dan menormalisasi peristiwa kekerasan seksual menjadi PR kita sebagai masyarakat yang dikenal dengan “masyarakat agamis”. Hal demikian mengakibatkan krisis identitas dalam jati diri bangsa yang besar ini. Sesuatu yang basisnya kekerasan seksual perlu dikutuk keras dan dijadikan pokok bahasan yang sentral dalam lingkup masyarakat Indonesia. Sehingga tidak ada dalih menormalisasikan kekerasan seksual sebab kelumrahan pada relasi kuasa.
Merujuk pada aturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual didefinisakan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik. Sedangkan variasi jenis kekerasan seksual pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 meliputi; a. Pekosaan; b. Perbuatan cabul; c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. Pemaksaan pelacuran; g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
Sejatinya banyak sekali cara dan upaya untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual ini, salah satunya adalah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan dipositifkan peraturan tersebut diharapkan terdapat ketakutan pada masyakarat jika melakukan perbuatan kekerasan yang berbasis seksual. Atau juga merefleksikan unsur antropologis, sosiologis, atau agama mengenai hakikat kekerasan seksual. Keduanya upaya ini nampaknya dapat dicermati mempunyai signifikansi sosiologis yang sama yaitu supaya membangun habitus anti kekerasan seksual.
Habitus akan lahir sebab adanya harmonisasi antara nilai keagaman, moral, pola perilaku, pengalaman, serta pengamalan masyarakat. Oleh karena itu hemat penulis, upaya nomor dua lebih tepat sebagai langkah awal untuk menguatkan nalar anti kekerasan seksual. Pertama yang perlu kita cerna betul adalah apakah tindakan kekerasan seksual merupakan budaya masyakat Indonesia? Apakah kekerasan seksual merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan kita? Dan apakah agama menormalisasi tindakan kekerasan berbasis seksual?. Ketiga pertanyaan tersebut akan menghantarkan kita untuk berpikir jernih dan menginventarisir nalar anti kekerasan seksual. Barulah ketika sudah memahami betul dan mencerna dengan baik makna dari suatu tindakan anti kekerasan seksual.
Pertama, dalam perspektif kajian sosiologi dan antopologi. Kekerasan seksual terjadi tidak secara spontanitas, melainkan terdapat akar terserabut yang mendorong seseorang berbuat itu. Satu hal yang bisa diidentifikasi dalam perspektif ini adalah adanya budaya ketimpangan relasi kuasa pada masyarakat Indonesia. Mereka yang lemah akan selalu tertindas sebab ketidakberdayaanya, dan produk dari perbuatan ini adalah kolonialisme dan imperealisme. Sebab negara Indonesia pernah dijajah ratusan tahun oleh bangsa barat, tidak heran jika variabel ini turut andil untuk menciptakan budaya diskriminatif “mereka yang tidak kuasa, mereka yang akan dijajah”.
Budaya miring bangsa barat yang suka mengkontrol seksualitas dan peran reproduksi perempuan akhirnya diturunkan kepada wilayah jajahanya. (Maggi Humm, The Dictionary of Feminist Theory, h. 23) Hasilnya secara eufimistis masyarakat menerima penindasan tersebut dan mengesagkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol sosial. Kondisi semacam ini yang dinamakan crime imination model yang mana masyarakat akan merekam segala bentuk diskriminalitas dan secara tidak sadar melakukan perilaku tersebut. Seperti halnya dalam tulisanya Brenner yang berjudul “Why Women Rule the Roost”, bahwa kekuasaan dan prestise mengakar pada mereka yang dianggap tidak berdaya tumbuh subur di zaman kolonialisme, terutama korbanya adalah perempuan yang tidak punya digdaya untuk mengontrol dirinya.
Budaya semacam ini tentu saja berkontradiksi dengan apa yang telah menjadi nilai, identitas, dan ruh masyarakat Indonesia. Nilai antropologi dan sosiologi ini dapat dicermati dalam nomenklatur kemanusiaan yang adil dan beradab yang terejawentahkan dalam sila pancasila. Secara etika masyarakat Indonesia dibangun dengan jalan harmonisasi relasi yang adil. Tidak ada tumpang tindih ketimpangan relasi yang menyebabkan diskriminasi. Tentunya diskriminasi yang berbasis kekerasan seksual bukanlah ciri khas masyarakat Indonesia, melainkan produk kolonialisme yang tidak relevan dengan ruh dan pemahaman masyarakat Indonesia.
Bersampingan dengan itu, identitas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang humanisme, dalam artian saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, tidak memandang suatu yang otonomis. Identitas ini sudah disepakati dari zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan lingkungan yang memang selalu mengedepankan etika dan etiket. Tentunya dengan adanya identitas bangsa yang humanis bisa menjadi bentuk refleksi dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam menyikapi kasus-kasus kekeresan seskual yang terjadi pada dewasa ini.
Kedua, berkaitan dengan adanya etika sosial dalam masyarakat Indonesia tindakan kekerasan seksual pastinya bukan suatu yang dapat dinormalisasikan, tetapi tindakan kriminalisasi yang harus mendapatkan perhatian lebih yang berujung eksekusi dan sanksi sosial. Masalahnya adalah adanya anggapan yang terpatri dalam masyarakat kita mengenai rape culture, yaitu adanya pihak yang menganggap kekerasan seksual sebagai kasus yang “biasa/normal”.
Terdapat salah satu penelitian mikro mengenai kultur normalisasi pelecehan, uniknya penelitian tersebut mengemukakan bahwa dari 57 responden, 47 orang merasa pernah mengalami pelecehan seksual baik fisik ataupun verbal dengan alasan “hanya bercanda” ataupun unsur kekhilafan. Artinya dalam ranah yang mikro, kasus seperti ini dibuat bahan bercanda dan tidak anggapan yang serius. Sehingga ketika terjadi counter dari pihak korban, maka korbanlah yang akan disalahkan yang akhirnya berujung pada victim blamming.
Bukti terbaru adanya aparatur penegak hukum yang seakan-akan menormalisasi kekerasan seksual pada kasus yang ada di Jawa Timur dengan dalih “bukan suatu pelecehan karena bajunya tidak terbuka” dan juga dalih “wajar mencium anak kecil karena gemas saja”. Pikiran seperti ini mengidentifikasikan adanya rape culture. Adanya normalisasi dan penyepelean kasus, banyak korban pelecehan seksual yang akhirnya enggan melaporkan tindakan kekerasan seksual yang mereka alami dan memilih untuk diam. Implikasi adalah masyarakat akan terjaring budaya normalisasi kekerasan seksual, padahal kasus kekerasan seperti ini menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan bangsa kedepanya. Bagaimana tidak, kekerasan seksual adalah candu sosial yang jika tidak segera ditanggulangi akan merusak culture sosial masyarakat.
Ketiga, perspektif kegamaman bahwa doktrin utama setiap agama adalah kebaikan yang berasaskan penghormatan kepada manusia. Tidak ada agama yang mendoktrin setiap pemeluknya untuk melakukan tindakan kekerasan, khsusunya kekerasan yang mengandung seksualitas. Misalnya saja dalam agama kristen terdapat ajaran kasih sayang yang mendoktrin ahar menjalin persaudaraan sesama manusia. Kemudian agama Hindu dengan ajaran karma yang memberikan pengaruh bagi manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan kerusakan.
Begitu juga dengan Islam dengan konsep karamah insaniyyah yang mengajarkan pemeluknya agar mengormati hak asasi sesama manusia.Singkatnya, dapat ditarik benang merah ketiga ajaran agama tersebut bahwa wacana konsep yang dibangun dalam ranah keagamaan adalah mengharuskan manusia berbuat baik kepada manusia lain. Artinya tidak ada satupun ajaran agama yang menormalisasi tindakan kekerasan.
Dalam agama Islam sendiri, visi dan misi utama adalah membebaskan manusia dari sistem yang berbau despotik dan totaliter yang identik dengan kekerasan dan penyelewengan. Artinya Islam hadir untuk membangun struktur masyarakat yang berkeadaban, yang mengamalkan nilai-nilai kemaslahatan seperti nilai keadilan, kesetaraan, dan kebenaran. Implikasinya, Islam tidak menormalisasi sistem kekerasan yang terjadi di masyarakat, khsusunya kekerasan seksual. Secara normatif Islam mengutuk tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan kaidah universalitas, bisa dilihat dalam Q.S. An-Nur: 22 yang melarang tindakan pelacuran. Dengan demikian nampak secara teks Islam mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan yang berbasis seksual.
Relevansi dan Internalisasi
Pemahaman mengenai kekerasan seksual bukan produk khas masyarakat Indonesia dan kriminalisasi dalam konteks keagamaan menandakan bahwa rape culture tidak relevan dengan corak khas perilaku masyarakat Indonesia. Hal ini harus disadari betul dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Meluaskan edukasi akan pemahaman terkait irelevansi rape culture pada masyarakat, setidaknya membantu kedepanya bahwa tindakan kekerasan seksual tidak lagi dinormalisasikan, melainkan suatu kriminalisasi dalam kehidupan. Sedangkan Internalisiasi disini untuk membantu dan menguatkan habitus anti kekerasan seksual yang berlandaskan nilai sosiologis, antropologis, dan nilai doktrin keagamaan yaitu kemaslahatan. [RZ]









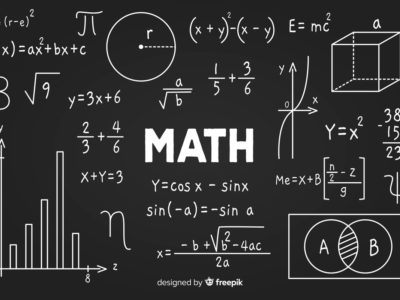














[…] Baca juga: Mencerna Habitus Anti Kekerasan Seksual […]