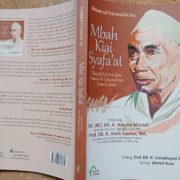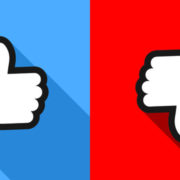Guru-guruku di Pesantren selalu mengajarkan, bahwa nanti saat pulang ke kampung halaman, kami para santri harus mau berjuang, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Harus mau Mulang! Selain itu, kami juga dititipi pesan, agar tetap berusaha dan bekerja, supaya tidak thamak mengharap pemberian manusia. Santri harus mampu menjadi Dalang di tengah-tengah masyarakat. Dalang yang mampu menggerakkan “wayang-wayang” masyarakat menuju kebaikan. Dalang yang, juga bisa menjadi singkatan dari: Dagang dan Mulang. Tidak malu untuk berusaha dan bekerja, salah satunya dengan berdagang. Sekaligus juga, senantiasa mau untuk berjuang dengan mulang.
Beberapa tahun setelah menikah, aku mengalami kegelisahan yang cukup dahsyat. Sebagai seorang suami, aku punya kewajiban bekerja untuk menafkahi istri. Dan sebagai seorang santri, aku mengemban amanat dari Mbah Kiai, harus meluangkan waktu untuk mengabdi. Sebenarnya, aku sudah membagi waktu untuk kedua hal itu. Prinsip “Dalang: Dagang dan Mulang” yang pernah diajarkan oleh Mbak Kiai, selalu aku pegangi.
Biasanya, pagi hingga siang aku bekerja. Sore hingga malam kugunakan untuk mengajar ngaji. Tentu harapan dan cita-citaku, dan semua santri di dunia ini, adalah berhasil di kedua-duanya. Berhasil menjadi pengusaha yang kaya raya, sekaligus juga bisa menjadi santri yang mampu mengamalkan ilmunya. Tetapi, kenyataan berkata lain.
Kukayuh pedal sepeda onta bututku sekencang mungkin. Berharap beban-beban kehidupan juga sirna bersama rodanya yang berputar. Melayarkembang kenangan-kenangan pahit yang pernah menyapa. Tak terasa bulir-bulir air mata deras mengalir di pipi. Hikssss….
Setelah menikah, aku telah mencoba segala macam usaha. Akan tetapi, hasilnya selalu gagal. Pernah kucoba menjadi Petani, sebuah profesi yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Setiap hari kurawat padiku. Tetapi, menjelang panen, sawahku terkena banjir. Banyak padi yang busuk. Panen di depan mata, lenyap begitu saja. Rasanya seperti hendak makan, sendok berisi makanan sudah di depan mulut, tetapi tersenggol dan akhirnya semua makanan terjatuh di tanah.
Aku juga pernah mencoba untuk beternak kambing. Menjelang musim Idul Adha, saat dimana para peternak kambing di seluruh dunia panen, kambing-kambingku malah terkena virus, sehingga harus kujual dengan harga yang sangat murah. Aku pun rugi banyak sekali.
Pernah pula, aku mencoba ikut menanam saham pada usaha teman. Tetapi, beberapa waktu kemudian, temanku menghilang tiada rimbanya. Saat ramai-ramainya trading, aku pun mencoba-coba ikut membeli bitcoin. Tetapi, hasilnya ambyar. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Semua uangku ludes habis. Hutangku menggunung.
Berulang kali gagal tak membuatku putus asa untuk berusaha. Otakku berpikir, usaha apa yang minim modal tapi bisa dijalankan dengan mudah? Akhirnya ketemu. Ojek Online! Aku pun mencoba usaha ojek online dengan motor istriku. Pagi hingga siang orderan yang menghampiri tidak begitu banyak. Orderan banyak dan sangat ramai, justru disaat waktu mengajar ngaji tiba.
“Pak Topa, ngaji tidak Pak?” Isma’il, bocah polos yang sangat aktif itu bertanya kepadaku, mewakili teman-temannya.
Aku bingung menjawabnya. Saatnya ngaji, malah datang orderan Go-Food bertubi-tubi. Aku tidak mau menolak rezeki. Akhirnya, terpaksa kujawab dengan getir pertanyaan bocah lugu itu.
“Ngajinya libur dulu ya, Mail. Bilangkan ke teman-teman, Pak Topa ngajinya libur dulu.”
“Horeeee…… Libur!” Pengumuman libur disambut gegap gempita seluruh anak yang mengaji kepadaku. Tetapi, tidak dengan orang tuanya.
Hatiku masih berkecamuk. Apakah yang kulakukan ini salah dan keliru? Akhirnya kuyakinkan bahwa apa yang kulakukan ini benar adanya. Aku berpikir bahwa mendatangi pesanan Go-Food ini lebih penting, sebab mencari nafkah adalah Fardhu ‘Ain, sedangkan mengajar ngaji hukumnya adalah Fardhu Kifayah.
Aku pun mendatangi beberapa warung tempat pesanan Go-Food. Butuh mengantri berjam-jam lamanya. Karena biasanya, warung-warung yang enak masakannya tentu banyak peminatnya. Saat semua pesanan siap untuk dikirim, tiba-tiba muncul notifikasi di aplikasi bahwa pesanan dibatalkan.
Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Sungguh teganya. Pemesan gak ada akhlak! Tubuhku langsung lemas. Mulutku komat kamit antara istighfar dan mengucapkan sumpah serapah. Semua pesanan itu pun akhirnya kubawa pulang. Aku berikan kepada istriku. Selebihnya kubagi-bagikan kepada tetangga.
Kegagalan demi kegagalan dalam berbisnis dan berusaha berulang kali menimpaku. Tidak pernah sekali pun aku mendapatkan untung. Bukannya untung, malah buntung. Yang ada adalah rugi, rugi dan rugi. Hutangku semakin menumpuk dimana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, saat menyadari bahwa anak-anak yang dulu mengaji kepadaku, sekarang sudah tidak ada satu pun yang mau ngaji lagi. Karena, aku mengajar ngaji seperti Puasa Dawud. Sehari mengajar, sehari tidak. Lebih banyak liburnya daripada ngajinya. Aku merasa menjadi manusia gagal. Hidupku betul-betul berantakan. Aku sungguh malu menjadi lulusan pesantren, yang diharapkan oleh Mbah Kiai-ku mampu menjadi Dalang di masyarakat. Bagaimana diriku mampu menjadi dalang, menjadi wayang saja pun ku tak mampu?
Kukayuh lagi pedal sepedaku, sambil menyaksikan spion-spion yang menampakkan kepedihanku di masa lalu. Tiba-tiba, hapeku berdering. Ternyata, istriku menelpon. Aku ragu, antara mengangkat teleponnya atau tidak. Lalu kuputuskan untuk tidak mengangkat teleponnya saat ini. Kutaruh hapeku di saku dan kuseka air mataku. Hape masih saja berdering beberapa kali. Namun tak kubris lagi. Kulanjutkan untuk mengayuh sepeda. Sudah 4 jam lamanya, aku menaiki sepeda onta tuaku ini tanpa henti. Akhirnya, sampailah aku pada tempat yang kutuju.
Hatiku berdesir oleh rindu. Mataku sembab oleh sendu. Aku baru saja sampai di tempat yang kutuju dan kurindu. Di pusara Mbah Kiai-ku. Banjir air mata pun membasahi pipi. Tak bisa kubendung lagi. Rasa rindu, sedih, cemas dan khawatir bercampur menjadi satu. Tiba-tiba terngiang-ngiang ucapannya dulu, suatu ketika menasehatiku.
“Mulanga, Nang! Nek sampek gak kuat mangan, patokku okak-okak!”
Kubersimpuh di pusara beliau, bukan untuk meng-okak-okak batu nisannya. Bukan untuk menagih janji-janjinya. Sekali lagi, bukan karena itu. Aku hanya mau mengadu kepada Mbah Kiai, bahwa aku ini adalah seorang santri durhaka. Hidupnya terombang-ambing oleh dunia. Seorang santri yang tak mampu menunaikan tugas dengan baik, tak mampu membahagiakan orang-orang tercintanya. Sambil terisak, aku lantunkan Surat Yasin, Tahlil dan doa-doa untuk Mbah Kiai. Salah satu doa yang terselip di bibir dan hatiku:
Mbah Kiai, meskipun dalem ini santri nakal, santri dugal, dalem memohon semoga Mbah Kiai masih berkenan mengakui saya sebagai santri Mbah Kiai dunia akhirat.
Selepas berziarah di makam Mbah Kiai, aku mencoba menenangkan diri. Rasanya, kepalaku sudah tidak begitu berat. Hatiku sudah cukup tenang. Memang ada benarnya, suatu perkataan yang terpahat di makam Kanjeng Sunan Kalijaga Demak: إذا تحيّرتم بالأمور فزوروا أصحاب القبور, ketika engkau kebingungan menghadapi suatu persoalan, maka berziarahlah kepada para penghuni kubur. Bukan untuk meminta-minta, menyekutukan Allah. Tetapi untuk berkunjung kepada orang-orang shalih kekasih Allah, yang di alam barzakh mereka masih hidup sebagaimana ketika di dunia.
Beberapa saat kemudian, aku membuka handphone. Ada 20 panggilan tak terjawab dari istriku. Aku pun meneleponnya. Baru dua detik, langsung diangkat.
“Halo, Mas? Mas wonten pundi? Maafkan Kula nggih, Mas. Hiksssss.” Pinta istriku sambil terdengar tangisannya.
“Mboten napa-napa, Dik. Mas yang minta maaf. Karena Mas yang salah. Tidak bisa jadi suami yang baik. Tidak bisa memberimu nafkah. Malah setiap hari selalu saja menumpuk hutang. Mas juga mohon maaf, Dik. Kemarin tidak bilang-bilang, bahwa sepeda motormu yang tak pakai untuk ngojek online tak jual Dik, untuk menutup hutang Mas. Nyuwun pangapunten estu, Mas gak bilang-bilang sampean.”
“Mboten menapa Mas. Kula ikhlas kok. Sing penting sakniki Mas kondur, monggo. Nyuwun pangapunten, jika tadi kula marahnya meledak-ledak dan di luar kendali. Mas sakniki wonten pundi?”
“Mas sowan makam Mbah Kiai, Dik. Ngadhem. Mboten usah sampean cari.”
“Ya Allah, la naik apa Mas?”
“Naik sepeda ontel, Dik.”
“MasyaAllah, sepeda ontel tua yang rantainya mudah lepas niku? Jepara-Pati, njenengan tempuh dengan naik sepeda ontel?”
“Nggih, Dik. Biar Mas merasakan susahnya hidup dan susahnya mencari pekerjaan. Sebab, Mas pernah mendengar, ada dosa-dosa yang tak mampu terhapus oleh shalat, puasa, zakat, pun tidak bisa terhapus oleh haji, tetapi bisa terhapus dengan susah payahnya mencari rizki. Hiksss… Maafkan Mas yang belum mampu jadi suami yang baik, Dik.”
“Sampun, Mas. Sampun, Hikssss. Jangan begitu, Mas! Tidak usah bicara hal-hal yang tidak penting. Yang terpenting, nanti kalau sudah selesai, Mas segera pulang nggih. Karena sudah malam.”
“Nggih, Dik. Maturnuwun. Aku cinta kamu. Terima kasih, sayang.”
Setelah menelepon istriku, kurebahkan tubuhku di dekat pusara Mbah Kiai. Baru terasa capeknya, mengayuh sepeda selama 4 jam. Kakiku terasa pegal-pegal. Aku pun tertidur. Kemudian, aku melihat Mbah Kiai hadir dalam mimpiku. Hatiku sangat bahagia bisa bertemu dengan Mbah Kiai. Seketika, aku pun sungkem, bersalaman dan mengecup asta mulianya begitu lama. Kemudian beliau mengusap ubun-ubunku, sambil berpesan.
“Madhep Dampar, ya Nang! Kowe Tajrid, Bojomu Kasab!”
Setelah mendengar kata-kata Mbah Kiai, aku tiba-tiba terbangun. Kuciumi telapak tanganku, yang baru saja bersalaman dengan tangan mulia Mbah Kiai di dalam mimpi. Meskipun di dalam mimpi, aroma parfum misik putih beliau rasa-rasanya masih tersisa di hidungku. Ketika benar-benar tersadarkan diri, aku pulang dari makam Mbah Kiai dengan membawa pertanyaan demi pertanyaan. Apa sebenarnya maksud perkataan Mbah Kiai: Madhep Dampar, ya Nang! Kowe Tajrid, Bojomu Kasab!
Kurenungi perkataan Mbah Kiai sambil mengayuh pedal sepeda, dari Kajen Pati menuju Jepara. Madhep Dampar? Apa artinya aku harus mau mengamalkan ilmuku? Aku harus mengajar ngaji masyarakatku? Memang setelah kuangan-angan, di desaku belum ada majlis-majlis pengajian, khususnya pengajian al Qur’an untuk anak-anak. Belum ada. Maka wajib hukumnya bagiku untuk madhep dampar, bersila menghadap bangku-bangku, untuk mengajar ngaji masyarakatku. Supaya hukum Fardhu Kifayah bisa gugur dari masyarakatku. Aku jadi teringat, bahwa dulu Mbah Kiai pernah ngendika, mengajar ngaji bagi seorang Guru ngaji itu Fardhu ‘Ain, bukan Fardhu Kifayah lagi. Ini merupakan salah satu prinsip beliau. Jika mengacu pada ngendikan Mbah Kiai yang ini, maka aku harus menunaikan tugas mengajar ngaji ini, dan tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk menunaikan perkara wajib yang lain, La Yutraku al-Wajibu illa li Waajib.
Lalu, bagaimana maksud perkataan Mbah Kiai “Kowe Tajrid, Bojomu Kasab!”? apa sebenarnya maksud Mbah Kiai ngendika ini? Apakah Tajrid dan Kasab ini maksudnya adalah Maqamat atau tingkatan manusia dalam perspektif Tasawuf? Tajrid, bermakna mligi ngibadah hanya beribadah kepada Gusti Allah, sedangkan Kasab maknanya adalah maqam bekerja? “Kowe Tajrid, Bojomu Kasab!” Apakah Mbah Kiai menghendaki aku hanya mengabdi kepada Gusti Allah dengan mengajar ngaji saja, tidak usah bekerja, atau bagaimana? Pertanyaan demi pertanyaan datang silih berganti menjejali pikiranku.
Setelah mengayuh sepeda beberapa jam, aku sampai rumah dan disambut dengan hangat oleh istriku. Kedua matanya tembam karena terlalu banyak mengeluarkan air mata. Ia lalu membuatkanku teh hangat, kemudian memijit kaki, lengan dan pundakku, sambil berulang kali meminta maaf, karena ia telah marah kepadaku.
“Nyuwun pangapunten, saestu nggih Mas? Mas mau memaafkanku, kan?”
“Nggih, Dik. Sudahlah, Mas yang minta maaf.” Kupeluk tubuhnya sambil kukecup keningnya.
“Mas ingin menyampaikan sesuatu, Dik.”
“Apa itu Mas?”
“Mas sudah menemukan jawaban atas segala kegelisahan yang selama ini mengganggu kehidupan kita. Sebuah jawaban atas persoalan hidup rumah tangga kita yang seakan-akan tidaka ada habisnya, Dik.”
“Apa itu Mas?”
“Saat berziarah ke makam Mbah Kiai tadi, mas tertidur dan mimpi bertemu Mbah Kiai, Dik. Baru bertemu di alam mimpi saja, rasanya beban hidup yang Mas rasakan semuanya luruh seperti debu-debu.”
“Alhamdulillah, MasyaAllah, Mas. Terus Mbah Kiai ngendikan punapa Mas?”
“Terus Mas sungkem, ngecup asta Mbah Kiai lama sekali, kemudian beliau ngendika: Madhep Dampar. Kowe Tajrid, Bojomu Kasab!”
“Apa itu maksudnya Mas?”
“Mungkin, maksudnya adalah Mbah Kiai ngersakke Mas istiqamah ngajar ngaji saja. Madhep Dampar. Menghadap bangku-bangku. Tetapi, bukan berarti tangan hanya berpangku, Dik, alias tidak mau usaha.”
“Lalu, Kowe Tajrid dan Bojomu Kasab?”
“Kalau menurut Mas, maksudnya begini. Kalau keliru, mohon dikoreksi. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini memang harus pintar dan paham dalam memosisikan diri, Dik. Ada manusia yang tingkatannya bekerja, Maqam Kasab. Maka, bekerja baginya lebih utama daripada hanya pasrah saja, hanya beribadah saja tanpa bekerja. Tetapi juga ada manusia yang tingkatannya Maqam Tajrid, yang hanya beribadah saja, atau mengaji saja, atau mengajar saja. Dan bagi mereka, mligi ngibadah atau focus beribadah itu lebih baik daripada bekerja secara langsung. Dan setelah merenungi pesan Mbah Kiai ini, Mas baru sadar, bahwa selama ini Mas keliru.
Kata orang Jawa, mburu uceng kelangan dheleg, mencari sesuatu yang sejatinya kecil bagi Mas, tetapi malah meninggalkan perkara yang hakikatnya jauh lebih besar. Lebih memilih jatuh bangun untuk bekerja meskipun tidak ada untungnya, tetapi justru meninggalkan kewajiban untuk mengajar ngaji. Mas memaknai dhawuh Mbah Kiai tadi, bahwa Mas harus istiqamah mengajar ngaji, Dik. Dengan tetap bekerja sekedarnya. Sedangkan sampean yang menjalankan tugas Kasab, Dik. Bukan berarti ini Mas lepas tanggung jawab menafkahi sampean. Karena kondisi tiap orang, kondisi tiap keluarga, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya.”
“Oh begitu Mas. Nggih, menawi Mas ngersakke kados ngoten, Kula insya Allah ndereaken lahir batin, Mas.”
MasyaAllah, mendengarkan jawaban istriku, aku merasa seolah-olah memiliki surga yang keindahan dan luasnya tanpa batas. Air mataku pun meleleh. Kukecupi lagi keningnya dan kupeluk penuh cinta. Sepasang suami-istri yang mampu mengerti dan saling memahami satu sama lain, seakan-akan memiliki surga sebelum surga di akhirat, meskipun mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa di dunia.
Pada akhirnya, kami mencoba mentaati nasehat Mbah Kiai. Aku berlatih untuk istiqamah mengajar. Istriku mulai mengurusi usaha yang pernah kulakukan. Ia tidak pernah terjun secara langsung. Mengurusi usahanya pun ala kadarnya. Tidak jatuh bangun, kepala di kaki kaki di kepala, seperti yang pernah kulakukan. Tetapi, hasilnya benar-benar berbeda. Sungguh istimewa. Sawah yang dulu ketika kuurus selalu rugi, semenjak dipegang istriku, selalu berhasil panen raya. Panen dua kali dalam setahun, hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kegiatan sehari-hari selama satu tahun. Bahkan masih ada lebihan untung banyak. Keuntungan panen padi ia pergunakan untuk membeli dua ekor kambing. Dari dua ekor kambing, beranak pinak menjadi enam, hingga berkembang menjadi ratusan. Setiap Idul Adha, selalu ramai pesanan kambing kurban. Ia lalu mengembangkan bisnis online, memproduksi jilbab, gamis dan busana muslim dengan brand sendiri. Dagangannya laris manis di pasaran. Resellernya ada di berbagai kota di Pulau Jawa. Apa yang ia lakukan tidak ngayawara, serius tapi santai. Sangat jauh berbeda dengan apa yang pernah kulakukan dulu: ngaya tetapi tidak ada hasilnya. Sungguh benar perkataan Imam Syafi’i dalam Diwannya:
ورزقك ليس ينقصه التأنّي :: وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور :: ولا بؤس عليك ورلا رخاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع :: فأنت ومالك الدنيا سواء
Rizki tak berkurang karena ketenangan :: Dan tak bertambah karena kepayahan
Takkan kekal sedih dan kebahagiaan :: Tak kekal pula susah dan kemudahan
Jika kau punya hati yang menerima :: Engkau dan pemilik dunia itu sama
Sesuai nasehat Mbah Kiai, aku pun akhirnya istiqamah mengajar ngaji. Tidak meninggalkan mengajar ngaji kecuali untuk urusan yang betul-betul penting dan wajib. Walaupun secara dhahir aku tidak bekerja, namun anehnya rizki yang diberikan Gusti Allah tidak ada habisnya. Aku semakin yakin bahwa rizki itu tidak ditentukan oleh pekerjaan, apalagi ditentukan oleh tempat dimana kita bekerja. Jika kita hanya memahami rizki hanya berasal dari tempat kerja, maka betapa sempit rizki Allah yang amat luas itu. Hutangku yang hampir mencapai satu Miliar, sedikit demi sedikit dapat kulunasi. Perlahan-lahan aku mampu membangun gedung Taman Pendidikan Al Qur’an dan Madrasah Diniyyah di desaku. Bukan hanya itu. Atas izin Allah, aku mampu menggaji Guru-guru ngaji yang mengajar di TPQ dan Madin dengan gaji yang layak, setara UMR di daerahku. Kebetulan ada beberapa orang kaya yang pernah berkunjung ke rumah, meminta doa dan biidznillah terkabul hajatnya. Mereka ini kemudian menjadi para donator tetap yang membiayai seluruh operasional TPQ dan Madin kami. Aku bahagia, sebagai pengelola, bisa menggaji guru-guru ngaji yang mulia dengan gaji yang layak. Tidak Moloekatan. Sehingga mereka pun bisa ikhlas dan disiplin dalam mengajar. Sama sekali tidak pernah terbesit pikiran untuk menjadi pelatih anjing milik para Crazy Rich, apalagi menjadi admin judi slot yang konon katanya gajinya berlipat-lipat dibanding bisyarah Guru Ngaji di desa-desa. [hw]
Siman, 17 Ramadhan 1445 H/28 Maret 2024