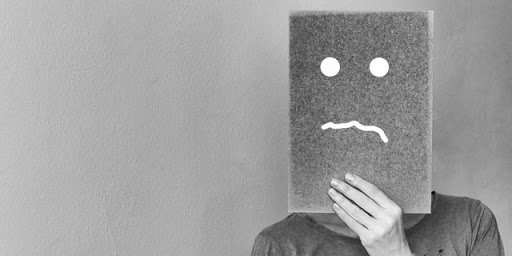Menyimak sesi pengajian online dari para Kiai di bulan Ramadan yang bertepatan dengan momentum rebahan massal adalah nikmat yang patut disyukuri, walaupun banyak hal yang harus kita relakan karena dampak dari pandemi saat ini. Alhamdulillah.
Salah satu nikmat itu adalah bisa tabarrukan online bersama Kiai Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) yang membacakan dua kitab karya Abah Beliau, Mbah Maimoen Zubair, yaitu al-Ulama al-Mujaddidun dan Nushush al-Akhyar.
Dalam sebuah kesempatan ngaji kitab itu, beliau mengangkat sebuah kisah yang sebetulnya pernah saya dengar sebelumnya tapi entah kenapa penuturan kisah dari beliau membuat saya terguncang ‘mbrebes mili‘.
Memang betul kalau gestur orang-orang alim selalu bikin betah walaupun sudah pernah saya dengar berulang kali. Mbetahi senajan bolan-baleni.
Kisah itu tentang Imam Fakhruddin ar-Razi, beliau adalah ulama ahli tafsir dan filsuf yang karya-karyanya abadi sampai hari ini.
Imam ar-Razi memiliki ribuan santri yang setiap hari sowan untuk istifadah (meminta faidah) dan mencatat dawuh-dawuh beliau. Beliau terkenal memiliki banyak hujah tentang ketuhanan dan mampu ‘membukakan’ nalar orang-orang yang masih ragu dengan wujud Tuhan.
Sampai suatu hari, beliau bersama para santri bertemu dengan seorang nenek dari desa yang menurut cerita sangat polos dan apa adanya. Saking polosnya Nenek itu tidak tahu siapa Imam Fakhruddin ar-Razi.
Banyak orang yang terkejut dengan kepolosan nenek, “Masak nenek gak tahu siapa Imam ar-Razi?”
“Iya, memangnya dia siapa?”
“Imam ar-Razi adalah tokoh agung di negeri ini, panutan kami semua, Nek.”
“Memangnya dia ngapain?”
“Imam ar-Razi sudah berjasa menjelaskan tentang wujud Tuhan kepada kami dengan ribuan hujah sehingga kami menjadi orang beriman.”
“Kalau percaya Tuhan butuh hujah, apa hebatnya? Kalau dia butuh seribu hujah tentang Tuhan itu artinya dia juga seribu kali meragukan Tuhan.”
Imam ar-Razi terkejut dengan jawaban nenek dan menangis sambil berdoa
اللهم اجعل ايماننا كايمان العجوز
Kisah itu mengingatkan saya tentang sosok-sosok sunyi di kampung yang melakukan aktivitas apapun, seperti beribadah dan bekerja murni untuk ‘melaksanakan kepatuhan’, walaupun pengetahuan mereka terbatas soal hiruk-pikuk perdebatan hukum halal-haram.
Mereka pergi ke pasar, ke sawah murni untuk ‘nglakoni sregep‘, tidak peduli tentang berapa besar keuntungan rupiah hari ini.
Mereka meliwet nasi, menumis terong murni untuk ‘mengganjal perut’, tidak terpikirkan apakah makan terong bagus untuk melembabkan kulit wajah atau melentikkan jari tangan.
Kepolosan dan kesunyian mereka lebih mahal nilainya dari setumpuk kajian ilmiah para pakar yang ‘seakan-akan’ mampu menjawab perkembangan zaman.
Saya ingat tentang cerita seorang santri yang pulang kampung dan kaget ketika menghadapi jamaah di majelis pengajiannya, banyak dari mereka yang tidak membawa alat tulis, bahkan lebih sering mengantuk daripada mendengarkan.
Santri itu merasa ‘tidak dihargai’ dan mengeluh kepada seorang Kiai, “Saya sudah menyiapkan materi semaksimal mungkin, tapi tampaknya jamaah tidak serius menyimak materi saya, Kiai.”
Kiai itu hanya tersenyum
“Ilmumu memang sudah matang, tapi sayang hatimu masih mentah. Mereka tidak salah, karena memang mereka berangkat ngaji semata-mata menjalankan kepatuhan atau mengistirahatkan tubuh setelah seharian berdagang dan bertani.”
Satu lagi, “Kepolosan mereka dari mengejar target fadilah ibadah bisa jadi justru lebih unggul dari kekayaan ilmumu tentang segala sesuatu.”
Santri itu diam dan menahan tangisnya dalam-dalam. [HW]