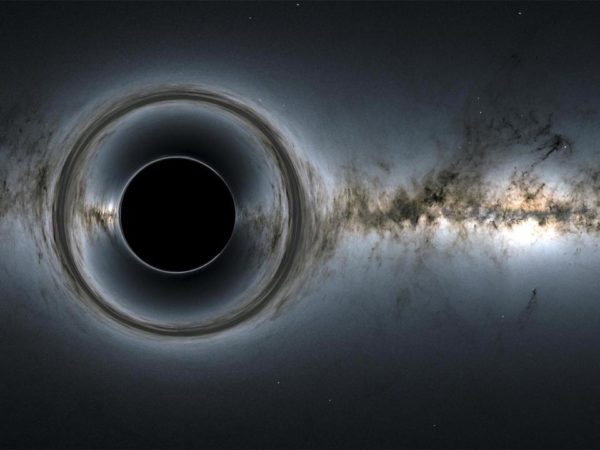Di Pulau Solomon, manakala sekelompok suku ingin membersihkan hutan untuk membuat ladang, mereka tidak menebang pohon. Mereka hanya berkumpul, mengelilingi pohon itu dan berteriak, memaki, menyumpahi dan mengutuk pohon itu. Perlahan tapi pasti, setelah beberapa hari, pohon-pohon mulai layu. Mati sendiri.
Pak Guru bernama Ram Shankar Nikumbh menceritakan kisah di atas kepada orangtua Ishaan, bocah berbakat yang sering mendapatkan teror kata-kata dari ayahnya. Ishaan, penderita disleksia, memang tidak secerdas kakaknya. Dia dianggap gagal secara akademik dan telat mengeja aksara. Selebihnya, oleh ayahnya, “kenakalan” dan “kebodohan”-nya selalu dibanding-bandingkan dengan prestasi kakaknya.
Nikumbh, yang diperankan dengan baik oleh Aamir Khan, adalah tipikal guru yang baik. Dia berkreasi dengan metodologi pembelajarannya dan mengapresiasi apapun yang dilakukan anak didiknya.
Nikumbh tidak pernah mencaci maki anak didiknya. Dia tidak pernah menteror murid-muridnya dengan kalimat sadis, kata-kata yang brutal, maupun cercaan yang bisa meruntuhkan mental dan kepercayaan para siswanya.
Apa yang dia gunakan? Pendekatan kasih sayang, apresiasi, dan penggunaan kalimat-kalimat positif. Dia sadar, sebagaimana makhluk bernama pohon yang akan mati jika dicaci maki secara terus menerus, kondisi batin dan psikis manusia akan remuk jika diteror dengan kalimat-kalimat negatif.
Taare Zameen Par (2007) yang memuat cerita di atas, adalah salah satu film favorit dan mengubah pandangan saya mengenai pendidik, siswa didik, dan pendidikan. Inspiratif.
Bahwa, jika mendidik dengan cinta (dalam istilah Ning Evi Ghozaly) bisa dilakukan dengan ceria dan bahagia, lantas mengapa masih ada cacimaki, umpatan “bodoh”, “nakal”, “tidak berguna”, “tidak punya masa depan”, “madesu”, “goblok”, dan kalimat brutal lain. Bukankah bisa diganti dengan diksi yang lebih motivatif?
Ada beberapa orangtua maupun guru yang menganggap apabila bentakan dan umpatan bisa menyelesaikan masalah dan bakal membuat anak (didik) berubah. Bagi saya, tidak! Masalahnya kompleks, dan tidak semua bisa diatasi dengan tudingan, bentakan, dan kalimat teror.
Dalam teori pendidikan, cara muhawarah/hiwari/dialogis bisa dipilih. Anak (didik) diajak ngobrol sebagai “sesama manusia….”, diberi motivasi, dan diarahkan dengan baik. Biasanya sifatnya evolutif, tapi dampaknya bisa jangka panjang. Dalam metodologi dakwah, cara ini seringkali berhasil karena pendekatan yang lebih manusiawi.
Pola semacam ini dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Asshiddiq manakala melihat bocah pengembala kambing yang punya potensi kecerdasan. Namanya Abdullah bin Mas’ud. Beliau mengajak ngobrol Ibnu Mas’ud dengan sesuatu yang dia sukai, yaitu soal “pengembalaan kambing”, soal teknik memerah susu dan seterusnya, lantas mempersilahkan Ibnu Mas’ud menemuinya di kemudian hari.
“Setelah itu, aku (Ibnu Mas’ud) pun datang menghadap beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, “Ajarkanlah kepadaku perkataan yang Engkau bawa (Al Qur’an -pen).”
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Sesungguhnya Engkau adalah anak yang terpelajar.”
Maka aku (Ibnu Mas’ud) pun mempelajari 70 surat langsung dari beliau dan tidak seorang pun yang mengalahkanku.”
Lihatlah, bagaimana Rasulullah mendekati Ibnu Mas’ud dengan bahasan yang ringan diiringi memberikan simpati, dan diakhiri dengan kalimat motivasi yang membuat Ibnu Mas’ud bersemangat.
Dalam kisah lain, remaja bernama Abdullah bin Umar bin Khattab sering tidur di masjid. Suatu malam dia bermimpi ada dua malaikat yang menyeretnya ke neraka. Esok paginya di bercerita kepada Ummul Mukminin Hafshah binti Umar yang tiada lain kakaknya. Sayidatuna Hafshah kemudian menyampaikan cerita ini kepada suami tercintanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.
“Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah Umar, andaikata dia mau melaksanakan shalat malam.”
Pujian dan motivasi ini adalah pendorong Ibnu Umar sehingga dia senantiasa qiyamul lail, dan kelak dia dikenal sebagai epigon Rasulullah, baik dalam perilaku dan amaliah maupun hal-hal kecil yang pernah dilakukan oleh beliau shallallahu alaihi wasallam.
Saya percaya, pada dasarnya manusia punya stok kalimat pujian dan motivasi yang melimpah. Namun, karena kita diam-diam dibesarkan di kawasan dimana bentakan dan cacian dianggap biasa dan serta pujian bagi orang lain dianggap tabu, apa daya, kalimat negatif untuk anak (didik) pun “dimaklumi”.
Padahal, kalimat negatif tetaplah membawa dampak negatif. Dalam Ihya Ulumiddin, Imam al-Ghazali memberi pesan: jangan banyak mencela dan memaki anak setiap saat. Karena sikap semacam ini akan membuat anak tersebut gampang mencela dan memaki karena terbiasa mendengarnya, mudah melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan berkata-kata kotor dalam hatinya.
Kalaupun anak (didik) bersalah, kritik anak apa adanya, tunjukkan letak kesalahan dan cara memperbaikinya, tapi jangan pernah memakinya. Ajak dialog, bukan monolog. Apresiasilah atas proses yang mereka lalui. Perhatikan mereka sebagaimana manusia seutuhnya yang punya hati dan pikiran. Sebab, merekalah yang kita harapkan doa-doanya setelah kita berkalang tanah. Baik dari anak kandung, maupun anak didik.
Kalaupun belum tampak perubahan drastis atas upaya yang dilakukan karena butuh waktu lama, Rasulullah memberikan tips: hendaklah bersabar atas mereka, atau hendaklah kalian menemani mereka dengan baik.
Wallahu A’lam Bisshawab