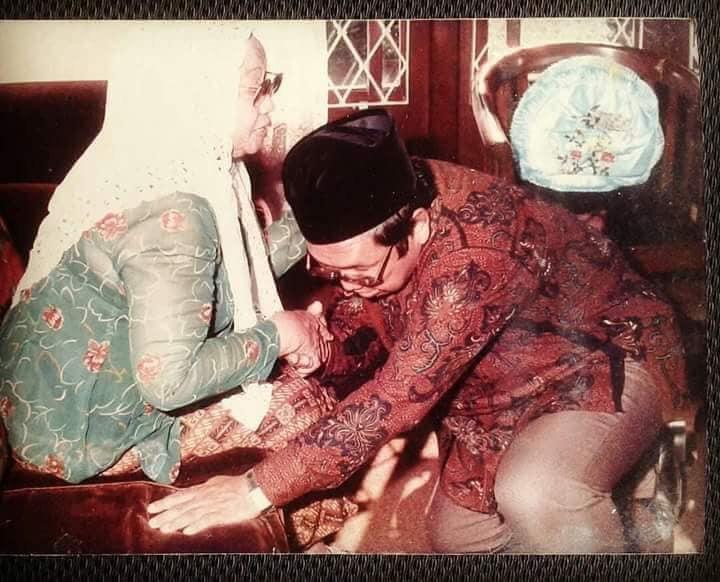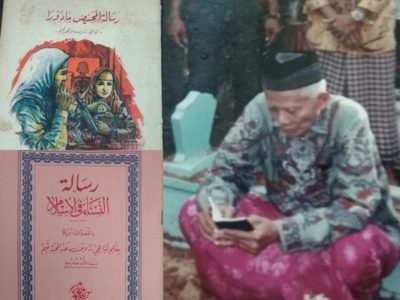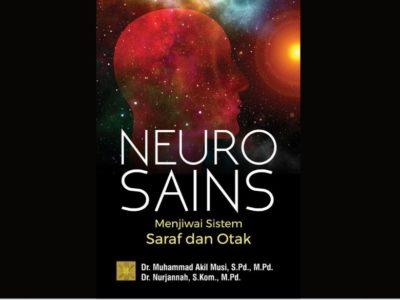Kartini sebagai potret perjuangan perempuan untuk ikut serta membangun peradaban sangat cocok jika disandingkan dengan spirit islam. Sebagaimana kita pahami, islam datang ke dunia juga dalam rangka merevolusi kebudayaan. Maka, akan menjadi aneh jika islam hanya dimonopoli oleh sebagian manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Ini bukan dalam rangka kebencian terhadap laki-laki, justru upaya ini adalah bagian dari mewujudkan kehendak Tuhan di bumi.
Kebanyakan perempuan, selain nama-nama besar dalam islam seperti Aisyah, tak mampu berperan lebih. Bukan saja karena watak tafsir yang cenderung patriarkhi, tetapi karena perempuan sendiri yang memilih untuk tak ikut andil dalam dinamika yang ada. Alhasil, bukan mencapai bentuk peradaban egaliter, yang ada ‘ogah-ogahan’ bergerak.
Jalan ruwet yang dipilih perempuan sudah berjibun menjadi ingatan kolektif yang sangat kuat mencengkram memori. Jelas pekerjaan yang tidak mudah untuk mengembalikan posisi kepada cara berpikir yang seimbang dan egalitarian. Namun, usaha harus terus dilakukan. Kita tak boleh begitu saja berhenti dan berkata “perempuan sulit untuk bangkit, wong dirinya saja tak mau bangkit.”
Eksistensi Perempuan: Mewujudkan Perlawanan Perempuan
Mansur Faqih memberikan sebuah gagasan segar untuk mengatasi problematika yang hadir membarengi eksistensi perempuan ini. Terdapat dua jalan yang harus dilalui untuk mewujudkan eksistensi perempuan menjadi kembali pada posisinya: 1) melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dengan dekonstruksi terhadap tafsir agama. Bisa dimulai dengan mempertanyakan peran perempuan dalam posisi sentral sampai kepada posisi yang paling partikular seperti pembagian kerja dalam rumah tangga. 2) Perlu kajian-kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam tafsir agama. Usaha ini sampai pada batas terakhir yaitu mewujudkan perempuan yang bisa mengontrol pengetahuannya sendiri. Artinya ia bisa menafsirkan sendiri tema-tema tentang dirinya, sehingga tak muncul ketidakadilan.
Mansur Faqih melihat bahwa perempuan bisa menemukan eksistensinya jika ia berperan. Dalam usahanya untuk mendekonstruksi dan mengambil alih jalan tafsir yang selama ini menindas mereka, harus dipahami juga di satu sisi, yang justru menjadikan blunder bagi usaha perempuan untuk melakukan perlawanan ini; yaitu penolakannya atas usaha dekonstruksi dan pengambil alihan itu oleh sebagian kelompok perempuan.
Seperti misalnya gerakan #IndonesiaTanpaFeminsi, yang sangat kontraproduktif di satu sisi dengan gerakan dekonstruksi. Gerakan yang menantang habis-habisan perlawanan atas dekonstruksi dan pengambil alihan itu diinisiasi oleh orang yang beragama ‘secara taat’. Alih-alih mereka mendukung, justru yang ada mengaburkan pemahaman. Mereka tak sampai pada pemahaman yang diharapkan Tuhan, mereka terjebak dalam tafsir yang selama ini berkembang. Sehingga, secara implisit, mereka percaya bahwa tafsir itu beku dan tak bisa untuk didekonstruksi.
Gerakan yang banyak menggunakan media sosial itu berhasil membius sebagian muslimah lain untuk sama-sama menentang dekonstruksi dan pengambil alihan tafsir. Walhasil, perempuan harus berhadapan pendukung dekonstruksi dengan perempuan yang lain (non dekonstruksi) dalam upayanya untuk mewujudkan eksistensi diri. Ini mirip seperti chaos-nya suatu negara. Jika kita membayangkan negara chaos, maka dapat dipastikan akan mudah dikolonialisasi oleh negara-negara lainnya. Apalagi oleh negara yang selama ini dianggap adidaya.
Perlawanan perempuan di satu sisi adalah upaya perwujudan “makna hamba Tuhan” dalam dunia, berhadapan dengan perwujudan “tafsir agama” buatan manusia yang ternyata diinisiasi oleh manusia berjenis kelamin laki-laki. Ambivalensi menggerogoti dunia perlawanan perempuan. sehingga, sampailah kita pada kata “perempuan karepe opo jane” (red. Jawa) yang mengundang berbagai tanda tanya. Bahkan, jika kita mau merefleksikan fenomena ini, maka akan bisa diketemukan bahwa selama ini perempuan benar-benar dipaksa menundukkan diri pada zaman. Tunduk pada zaman yang mana? Ialah modernisme tadi. Di mana modern sesungguhnya tak pernah bertuhan secara sungguh-sungguh. Mereka hanya bertuhan matrealisme. Sebuah pandangan yang menganggap bahwa Tuhan tak bisa ikut andil dalam selungsum kehidupan manusia. Ini sama dengan perempuan yang menentang dekonstruksi dan pengambil alihan tadi, yang sejatinya menentang Tuhan dan eksistensi perempuan di satu sisi. Ia terjebak pada pemahaman orang modern yang matrealistik.
Seperti apa yang diharapkan di awal: bahwa eksistensi perempuan sebenarnya didukung sepenuhnya oleh Tuhan telah gamblang. Dan, ternyata, kegamblangan dan kesadaran ini dikagetkan dengan kondisi eksistensi perempuan hari ini yang telah lunglai tak berdaya. Ini menjadi tamparan keras. Bahwa semangat berkobar untuk melakukan perjuangan terhadap segala bentuk penindasan terhadap perempuan (yang sebenarnya telah menciderai Tuhan itu). Menjadi wajib fardhu ‘ain. Dan bahwa siapa pun yang menciderai Tuhan, perempuan berkewajiban membela. Sebab di sanalah jiwa perempuan bersemayam.
Referensi:
Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)