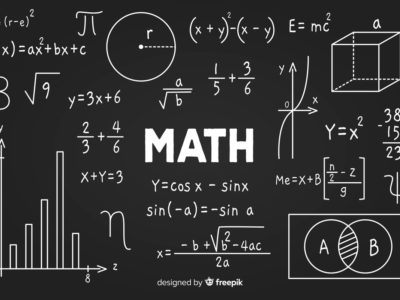Mas Edi, pemilik penerbit buku IRCiSoD dan Diva Press Yogyakarta, meminta saya untuk membedah buku saya yang terbit di sana di salah satu “warung kopi” yang dia kelola, Basabasi. Tepatnya pada tanggal 8 Juni 2024. Kali ini, pengusaha-intelektual atau Intelektual-pengusaha muda yang produktif melahirkan cuan dan menulis buku-buku pemikiran Islam asal Madura ini meminta saya untuk membedah buku yang berjudul “Menusantarakan Islam”, buku lama yang diterbitkan ulang di sana, atas permintaan beberapa orang yang peduli terhadap pemikiran Islam di Indonesia.
@@@
Saya ingin memulai ringkasan buku ini dari sebuah statemen bahwa “suasana kehidupan beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat kompleks, dan diramaikan oleh pelbagai kejadian mengenaskan, yakni muncul kekerasan atas nama agama, baik kekerasan wacana seperti semaraknya “fatwa sesat” atas pelbagai paham keberagamaaan, disusul tindakan “kekerasan fisik” terhadap pelbagai kelompok, baik terhadap individu, maupun organisasi yang dinilai berada di luar aliran mainstream. Anehnya lagi, mereka tidak hanya menjadikan “Islam transnasional-Arab” sebagai rujukan utamanya dalam memahami Islam, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai perwakilannya di Nusantara (Indonesia).
Kenyataan ini menandakan, Islam berada di bawah bayang-bayang budaya Arab, yang bersembunyi di balik aliran, organisasi, dan lembaga keagamaan maenstream di Nusantara. Akibatnya, pertama, Islam menjadi “sempit”, sebatas kreasi Islam Arab yang kini menjelma menjadi transnasional, aliran, organisasi dan lembaga keagamaan maenstream; kedua, individu dan budaya Nusantara yang tidak berafiliasi dan tidak sejalan dengan Islam Arab, aliran, organisasi dan lembaga keagamaan maenstream dinilai “tidak mempunyai otoritas” dalam memahami agama. Mereka akan difatwa sesat jika terpaksa melibatkan diri dalam memahami agama. Kekerasan pun bisa terjadi pada mereka.
Kondisi ini tidak memberikan ruang kondusif bagi masyarakat beragama untuk mengekspresikan paham dan keyakinan keagamaannya. Karena itu, secara epistemologis diperlukan suatu upaya melepaskan (otonomisasi) agama dari bayang-bayang budaya Arab berikut perangkat-perangkatnya di Indonesia. Tindakan ini menjadi langkah pendahuluan sebelum menggagas paradigma baru dalam menalar Islam di Nusantara dengan tujuan menusanatarakan Islam karena tanpa upaya ini, setiap gagasan baru apapun yang berada di luar maesntream akan dinilai sesat dan menyesatkan.
@@@
Islam lahir di Arab, dan pertama-tama Islam bergumul dengan budaya Arab. Terkadang Islam membiarkan bahkan mengambil sesuatu yang sudah menjadi tradisi di Arab pra Islam; Islam bersikap kritis, seperti terhadap konsep ketuhanan yang dilencengkan oleh penganut Yahudi dan Kristen; Islam juga mengisi bahkan mengganti budaya Arab dengan ajaran Islam, seperti mengenai perlakuan terhadap manusia. Di awal kelahirannya, Islam berdialog kritis dengan budaya Arab pra Islam.
Pada tataran pemahaman, para pemikir atau mujtahid Arab abad pertengahan juga acapkali mendialogkan Islam dengan budaya setempat. Ada banyak indikasi ke arah itu, sebagian di antaranya adalah lahirnya kaidah fiqhiyah al-‘Adah al-Muhakkamah, serta lahirnya dua rumusan berbeda di dua tempat berbeda dari pemikiran Imam syafi’i, yang kemudian dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Model pemahaman dialogis seperti ini memperkaya Islam. Di tempat yang berbeda akan lahir Islam yang berbeda.
Hanya saja, kondisi ini berubah akibat salah paham generasi belakangan terhadap penempatan kreasi Islam awal dan para Mujtahid abad pertengahan. Mereka bukannya meniru cara berfikir para pemikir dan mujtahid Arab itu. Mereka malah mengambil secara “kaku” kreasi para pemikir dan mujtahid Arab, dan secara “kaku” pula diberlakukan ke seluruh ruang dan waktu, termasuk ke Nusantara. Islam Arab dipaksakan berlaku di Nusantara kekinian. Maka terjadilah kolonialisasi budaya Arab yang bersembunyi di balik Islam.
Kolonialisasi budaya terjadi, karena terjadi pembalikan cara berfikir di kalangan mereka, antara Islam ideal dengan Islam historis. Islam ideal merupakan Islam yang abstrak dan universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan oleh karenanya ia diberlakukan kepada seluruh manusia di setiap ruang dan waktu, sedang Islam historis adalah Islam pada level ruang dan waktu. Pada level kedua ini, Islam telah mengalami dialektika dengan realitas, yang kemudian melahirkan berbagai kreasi intelektual, seperti teologi, fiqh, tasawuf dan tafsir. Kreasi intelekual ini, lahir di tanah Arab abad pertengahan.
Akan tetapi, kategori itu mengalami pergeseran fungsional. Kategori pertama yang mestinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, berbalik menjadi terikat oleh ruang dan waktu, sebaliknya kategori kedua, menjadi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Teologi, fiqh, tasawuf dan tafsir kreasi pemikir atau mujtahid abad pertengahan justru diberlakukan ke dalam seluruh level ruang dan waktu. Akhirnya Islam historis mengalami independensi, ia terlepas dari konteks historisnya dan mengubah diri menjadi Islam ideal yang berlaku di setiap ruang dan waktu. Sejak peristiwa ini, yang universal adalah Islam yang semula bergerak pada level historis, sebaliknya yang partikular adalah Islam yang semula bergerak di level ideal-universal. Hal ini mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap Islam ideal dan pada saat Islam historis diberlakukan pada setiap level ruang dan waktu, pada hakikatnya adalah sebuah pemaksaan epistemologis. Dikatakan pemaksaan karena ia bukan sesuatu yang bernilai universal tetapi dipaksa diberlakukan secara universal. Ia dipaksa diberlakukan di seluruh ruang dan waktu, termasuk di Nusantara.
Pola relasi seperti ini mengakibatkan Islam Arab mengabaikan sama sekali peran realitas di luar dirinya. Islam Arab diyakini seratus persen sebagai wacana yang benar dan layak diterapkan di seluruh ruang dan waktu, karena ia digali dari sumber yang murni dari Tuhan yang transendental. Pemikiran Islam terlepas sama sekali dengan realitas kekinian, karena ia dibuat dalam realitas masa lalu dan realitas masa lalu itu masih dipahami sebagai realitas yang direstui Tuhan. Pemikiran Islam yang dikembangkan di Indonesia justru mencerminkan realitas masyarakat Arab abad pertengahan, karena buku-buku referensi wacana yang hadir dan diadopsi oleh para pemikir Islam di Indonesia adalah wacana yang dikembangkan oleh para pemikir Arab klasik. Secara tidak langsung, bisa dikatakan, kita menempatkan diri kita sendiri sebagai “jajahan pemikiran dan budaya Arab, khususnya abad pertengahan.”
Kolonialisasi budaya Arab kian parah namun tidak disadari, ketika muncul aliran keagamaan, seperti Sunni, Syi’ah, dan Muktazilah, tiga aliran Islam yang mewarnai perdebatan bahkan konflik dalam sejarah Islam. Masing-masing aliran membentuk wadah transformasinya sendiri-sendiri berupa organisasi dan lembaga keagamaan. Masing-masing organisasi dan lembaga keagamaan itu juga mendirikan lembaga pendidikan, baik modern seperti sekolah maupun tradisional seperti pesantren. Organisasi dan lembaga pendidikan itu dimaksudkan untuk mentransformasikan ide-ide alirannya masing-masing.
Paparan di atas memperlihatkan betapa budaya Arab menyingkirkan budaya Nusantara dan umat Islam secara individual dengan menunggangi aliran, organisasi dan lembaga keagamaan. Akibatnya, pemikiran Islam menjadi kerdil, eksklusif, dan ideologis, sehingga tidak akan mampu mengatasi pelbagai persoalan yang ada di Nusantara, dan yang dihadapi manusia secara individual. Untuk itu, agama perlu dilepaskan dari bayang-bayang budaya Arab, aliran, organisasi dan lembagaan keagamaan yang menjadi wadah persemayam budaya Arab. Jika Islam dilepaskan dari bayang-bayang budaya Arab, maka budaya Nusantara dinilai absah merumuskan Islam yang khas Nusantara. Jika Islam dilepaskan dari aliran, organisasi dan lembaga keagamaan, maka setiap individu menjadi absah memahami Islam, tanpa terikat sedikitpun dengan aliran, organisasi dan lembaga keagamaan maenstream. Maka akan lahir Islam Nusantara, dan Islam Nusantara akan bervariasi sesuai sudut pandang yang digunakan setiap individu. Islam model ini akan mampu menjawab pelbagai persoalan individual yang mereka hadapi dalam arus modernitas yang kian tak terkendali ini, juga dapat menghindari kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik yang mengatasnamakan agama.
@@@
Bagaimana sejatinya berislam di Nusantara?
Jika menengok sejarah perkembangan pemikiran Islam, paham keislaman umat Islam bergantung pada “paradigma” dan “persoalan” kehidupan yang mereka hadapi. Karena persoalan yang mereka hadapi berbeda-beda, dan berkembang terus, maka cara orang berfikir dari waktu ke waktu juga berbeda-beda dan berubah. Di sinilah diperlukan paradigma baru dalam menalar Islam dan berislam di Nusantara.
Paradigma baru itu bisa dimulai dari nada pertanyaan, “apakah beragama itu sebagai sebuah “taklif” ataukah sebuah “hak”? Pertanyaan ini menarik, karena cara berfikir orang sekarang berbeda dengan cara berfikir orang dulu. Orang dulu berfikir dalam perspektif “taklif”, kini orang berfikir dalam perspektif “hak”. Orang dulu berfikir mengenai apa yang diperintahkan agama pada kita, dan apa pula tanggung jawab kita. Sedang orang sekarang berfikir mengenai apa hak kita dari agama, dan apa yang diberikan agama pada kita. Dengan pola pikir seperti ini bisa dipahami, bagi orang dulu, beragama dipahami sebagai “taklif”, sebaliknya bagi orang sekarang, beragama dipahami sebagai “hak”.
Beragama masuk ke dalam kategori “al-haq al-lazim”. Karena dirinya sendiri, seseorang mempunyai hak beragama, juga berhak memilih menggunakan haknya untuk beragama ataukah tidak. Ketika sudah menentukan pilihannya, orang lain tidak boleh ikut campur, selain menghormatinya. Tidak lebih dari itu. Sebab, dalam konteks ini, orang lain diberi “taklif al-lazim”. Andaikata seseorang tidak menghormati hak orang lain dalam menentukan pilihannya dalam beragama, dia tidak hanya melanggar hak orang lain dalam beragama, tetapi juga melanggar “taklif al-lazim” sendiri dalam posisinya sebagai manusia. Dengan kerangka seperti ini bisa dipahami bahwa manusia secara individual bebas beragama.
Kebebasan beragama tidak hanya dalam kerangka hak asasi manusia, tetapi juga dalam kerangka al-Qur’an. Dengan sangat jelas, al-Qur’an melarang adanya paksaan dalam beragama (al-Baqarah:256). Di sisi lain, al-Qur’an memberikan pilihan pada seseorang, apakah dia akan beragama ataukah tidak, beriman ataukah kafir (al-Kahfi:29). Tidak adanya paksaan serta diberikannya pilihan itulah yang membebani tanggung jawab pada manusia atas pilihannya. Tidak ada tanggung jawab bagi seseorang yang dipaksa beriman, begitu juga jika dipaksa kafir (al-Nahl:106).
Karena seringkali ekspresi kebebasan beragama menyinggung perasaan orang lain, kebebasannya dibatasi oleh kesadaran orang beragama itu sendiri. Dia harus menyadari bahwa ada orang lain yang juga mempunyai hak yang sama dengan dirinya dalam beragama dan mengekspresikan keyakinan agamanya. Dengan kesadarannya itu, dia sejatinya membatasi kebebasannya dalam beragama. Dengan kerangka ini, sejatinya hak seseorang dalam beragama tidak boleh dibatasi oleh sesuatu yang bersifat eksternal. Orang beragama harus bebas “dari” kekangan yang bersifat eksternal. Sebagai “al-haq al-lazim” dalam beragama, sejatinya seseorang juga bebas dari kekangan internal. Orang beragama harus bebas “untuk” mengekspresikan kebebasannya, tetapi juga harus memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan keyakinan keagamaannya.
Untuk siapa agama itu? Orang dulu selalu bericara tentang Tuhan dan kehidupan sesudah mati. Mereka gigih membela Tuhan dan itu diharapkan memberi mereka sesuatu setelah di akherat kelak, karena akhiratlah kehidupan yang hakiki. Pola pikir seperti ini disebut nalar Islam teosentris-eskatologis. Dengan nalar Islam ini, umat Islam berlomba-lomba membela Tuhan untuk mengejar kebahagiaan akhirat, tetapi mereka bersikap tidak manusiawi kepada manausia. Demi membela Tuhan, mereka rela menghancurkan ciptaan Tuhan.
Untuk menjaga eksistensi manusia dan kemanusiaan manusia, pradigma seperti ini harus dirubah kepada pandangan yang memusat pada manusia, tanpa melupakan Tuhan. Paradigma ini yang saya sebut nalar Islam antropsentris-transformatif.
Model nalar Islam antroposentris-transformatif ini melibatkan tiga unsur terkait: Tuhan, alam, dan manusia. Tuhan diletakkan pada posisi puncak eksistensi, alam sebagai kreasi Tuhan, dan manusia sebagai pelaksana pesan moral dan legislasi Tuhan. Berbeda dengan nalar Islam teosentris-eskatologis, nalar Islam antroposentris-transformatif meletakkan Tuhan sebagai penggerak bagi manusia untuk menjalankan pesan moral dan legislasi Tuhan di kerajaan manusia ini, bukan sebagai eksekutor Tuhan sebagaimana acapkali dijadikan jargon kalangan penganut nalar Islam teosentris-eskatologis, yang kini menjelma dalam Islam transnasional. Nalar Islam antroposentris-transformatif menyerahkan peran eksekusi pada Tuhan di akhirat kelak sebagai hari pembalasan. Yang berhak dijalankan manusia selama di dunia ini hanyalah pesan moril dan legislasi demi menjaga keseimbangan alam sebagai kreasi-Nya dan agar keharmonisan dan kesejahteraan hidup masyarakat tetap terjamin.
Rumusan nalar Islam antropsentris-transformatif ini cukup relevan dengan realitas kekinian. Bukan hanya karena manusia sekarang berfikir dalam kerangka hak, tetapi juga karena orang sekarang berfikir praksis, dan menjadikan agama sebagai sarana meningkatkan taraf kehidupan di dunia. Manusia sekarang lebih dekat pada beragama secara mashlahi (tadayyun mashlahi) atau beragama untuk meningkatkan taraf hidupnya (Tadayyun masyi’ati) daripada beragama secara epistemologi (tadayyun ma’rafi) dan beragama secara eksperimensial (tadayyun tajribati). Orang sekarang bertanya, apa yang diberikan agama pada kita, agar hidup kita meningkat, daripada bertanya, apa beban yang diberikan agama pada kita. Tentu saja, pola pikir seperti itu tidak berarti menegasikan peran Tuhan dalam beragama.







![KH. Mahsun Masyhudi: Kebijaksanaan dan Jalan Hidupnya [1]](https://pesantren.id/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-05-at-15.13.43-400x300.jpeg)