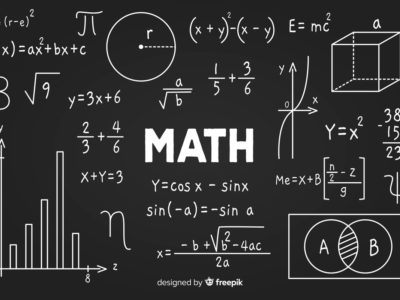Terhadap rencana perpindahan ibu kota Negara, saya adalah orang yang paling resah belakangan ini. Bukan semata urgensinya demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat, bukan! Yang paling saya risaukan adalah bagaimana jika Monumen Nasional atau Monas ikut-ikutan pindah ke ibu kota baru kelak, masih adakah gerakan politik monaslimin-monaslimat di sana? Nah, biarlah Jakarta saja yang identik dengan gerakan populisme 212 yang legendaris itu, sementara di ibu kota baru silahkan Pemerintah giat bekerja.
Sementara mesin-mesin dan alat berat Negara terus menderu, rakyat yang lelah dengan keseharian bisa mendapat hiburan di televisi dan medsos, saya rasa acara talkshow sampah, sinetron azab, pemburu tuyul, ceramah acakadut, dan kontes-kontes bau kentut lainnya sangat bagus untuk kita tertawakan oleh karena mereka mamang sulit menertawakan diri sendiri. Anda tahu, semua teori kesehatan dari berbagai peradaban menyarankan manusia tertawa.
Sembari menertawakan lelucon para pelawak gaek macam Tengku Zul dan Ridwan Saidi, serta akademisi-akademisi geblek, mari kita iseng-iseng bertanya: bagaimanakah nalar yang jernih seharusnya diuji di tengah gelegak zaman serba amatir ini? Silahkan nonton televisi dan kanal Youtube! Bagaimana pula akal sehat bisa mengalami turbulensi, terjun bebas dan bahkan membusuk? Monggo nonton acara-acara jualan bau mulut, air liur, lendir dan air mata di televisi! Di manakah kepakaran sungguh-sungguh mati? Di layar layar 14 inci dan gawai yang kita bawa sehari-hari.
Baik, siapkan kopi dan akal sehat Anda di awal tahun baru Hijriyah ini. Mengapa? Karena hijrah telah mengalami peyorasi dan pendangkalan nilai dengan hanya (maaf) sibuk memoles sisi lahir dan atribut saja, tak jarang, mereka yang baru belajar agama malah arogan dan memonopoli kebenaran. Apapun itu, saudara kita yang sedang belajar dan berhijrah harus kita support.
Di Eropa abad pertengahan yang lazim disebut zaman skolastik teologi selalu tampil sebagai “sang domina”, pengangkang filsafat sekaligus pendera sains. Praktis, para filsuf dianggap anti agama, anti doa, musuh agama, dan memang filsafat itu bukan mantra sekaligus doa. Inilah ujian penting akal sehat dan ilmu pengetahuan secara sistematis-struktural di era kejayaan lembaga agama (dalam hal ini gereja).
Sebagaimana tidak semua orang butuh filsafat, tidak setiap orang pula butuh agama. Mengapa? Hidup tak selalu berkorelasi dengan keduanya. Apa sebab? Tiap manusia tidak sama, tiap tempurung pasti berbeda. Sains tidak butuh agama, dan agama tidak memerlukan sains untuk diimani serta dijalani pemeluknya, meskipun faktanya kaum bumi datar sangat gandrung dengan cocokologi agama. Namun demikian, manusia membutuhkan sains dan agama. Fritjof Capra menambahkan dalam The Tao of Physic, bahkan manusia membutuhkan mistik untuk menjalani hidupnya. Ini bisa kita saksikan dalam keseharian. Dan, para predator bisnis serta oligark politik tahu betul mana yang layak jual demi rekening mereka.
Meski tak semua butuh agama, agama tak pernah mati. Memang, modernisasi membonceng sekularisasi, tapi sekularisme setelah pada dekade 70-80an merajalela menjadi dagangan basi: nasi sudah menjadi bubur dan bubur telah basi. Itu artinya sekularisasi dalam sains dan dunia politik, tidak otomatis berimbas pada agama dan penyangga-penyangganya berupa kebudayaan, tradisi, kearifan lokal dan suprastruktur lainnya, dan terutama lembaga agama, majlis tokoh agama dan ormas agama.
Alih-alih mengalami kematian, agama justru kian banyak diminati. Kini, tak hanya orang modern terpelajar, bahkan kaum cuti nalar sekalipun merasa perlu “kembali” ke agama, kembali ke Qur’an-Hadits, tentu saja karena mereka merasa telah meninggalkan agama dan baru tahu bahwa di depan hidung mereka selama ini ada Kitab Suci-Sabda Nabi. Di sinilah hijrah bermula, dengan cadar dan jenggot bikinan China. Apa yang salah? Ah, tulisan ini tidak untuk membincang hal ini.
Kisanak, Revolusi Eropa tak hanya merobohkan tembok Berlin, tapi juga sistem komunis Soviet. Persis, telah terjadi gerakan Balkan atau balkanisasi, yakni bangkitnya sentimen-sentimen suku dan agama bersamaan dengan runtuhnya gigantisme Uni Soviet. Lagi-lagi, akal sehat dan nalar kritis harus terperangkap oleh dogma untuk kedua kalinya.
Sentimen kesukuan yang sebelumnya ditindas melahirkan gerakan etnosentrisme, sementara keagamaan yang sekian lama dikekang melahirkan fundamentalisme. Keduanya praktis menjadikan “hantu” baru pasca komunisme. Tapi anehnya, isu komunisme masih laku dijual di kalangan kaum defisit otak dan sobat gurun. Di mana? Ya di Negeri kita, terutama menjelang dan sepanjang Pemilu.
Nah, tumbangnya Orde Baru di Indonesia lebih-kurang membawa konsekuensi logis seperti yang terjadi di Eropa. Maka, menjamur ormas-ormas yang kalau tidak etnosentris ya fundamentalis setelah bergulir reformasi, bak cendawan di musim hujan. Cepat dan pasti, menyeruak teror-teror yang menganggap denganmeminjam istilah Wolfgang Huber “kekerasan sebagai ibadah” (gewalt als gottesdienst).
Kekerasan atas nama agama merentang sejak 9/11, rangkaian bom Bali, Jakarta, Solo, Surabaya, Ambon, teror ISIS di berbagai kota dan negara, hingga pembakaran gereja dan persekusi terhadap minoritas. Tindak brutal jenis ini jelas-jelas mencoreng-moreng agama hingga koyak-moyak dan boyak. Memang, kekuasaan, kekuatan, dan wewenang bagi terjadinya kekerasan ini sangat berjalin-jemalin dengan politik global, akan tetapi (pseudo) “kebangkitan” agama pasca Balkan sangat menghambat proses penyembuhan luka setelah penjajahan Orde Baru selama 32 tahun. Apa sebab? The guruns ada yang bisa jawab nggak?
Kebangkitan agama bukan lagi kebangkitan sebagaimana ia diwahyukan pertama kali dan diajarkan para Nabi. Inilah ujian berikutnya bagi akal sehat dan pada saat yang sama merebak pembusukan nalar di ruang publik melalui televisi dan medsos. Para sister fillah dan sobat hijrahis pada tahu nggak, kenapa?
Memang, nilai-nilai sekuler khas Eropa, seperti HAM, ideologi pasar alias kapitalisme, ideologi sains alias naturalisme, ideologi politik alias liberalisme, dan yang tak kalah penting ideologi kelamin, yakni LGBTIQ kian populer dan berdaya jual di Indonesia dewasa ini. Anda juga sudah tahu siapa yang membiayai itu semua, kan? The jidatis, the jenggotis dan the cingkrangis pasti sangat gatal-gatal mendengar istilah LGBTIQ, sebagian kebakaran jenggot, meski tak berjenggot.
Kebangkitan pseudo agama, merebaknya uspal alias ustadz palsu, maraknya orang tersinggung atas nama agama, banalitas cara beragama, ramai dan gaduhnya orang menyembah bendera tauhid, kesurupan dan alergi terhadap simbol agama lain sembari minggat ke luar negeri, sejalan dengan terjun bebasnya nalar. Bukankah Nabi Muhammad Saw pernah mengingatkan bahwa agama itu akal? Bukankah orang yang tidak mendayagunakan akalnya alias cuti nalar disebut tidak beragama dalam hadits Nabi? Well, sudahkah Anda nonton TV hari ini? Kalau sudah, jangan lupa tertawa, karena tertawa itu pangkal bahagia.