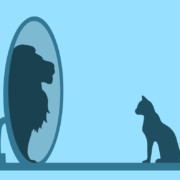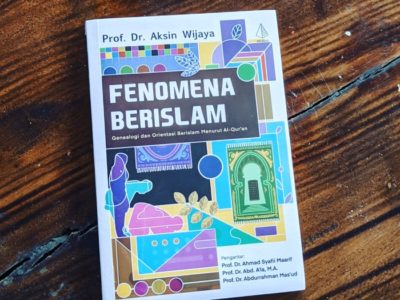Patut dimafhum bahwa prioritas agama adalah mewujudkan kehidupan yang benar-benar tenteram. Ia hadir sebagai wacana dan konsep atas kehidupan yang dinilai kurang tertata pada masa itu. Hingga kemudian, Islam sendiri diyakini sebagai konsep yang adiluhung dan terus mengiringi perjalanan hingga detik ini. Dalam perjalannya lintas musim dan waktu, sudah banyak dinamika dan fenomena-fenomena yang lahir atas nama agama.
Hal itu menunjukkan bahwa tata cara dan ekspresi dalam beragama selalu berubah. Tidak ada postulat ekpresi, dalam arti yang lebih sempit, untuk menampilkan rias Islam. Maka, interpretasi terhadap Islam tidak akan pernah sejalan tetapi diharap selalu beriringan.
Hari ini, sudah terlalu jauh pada dasawarsa pertama dalam masa Islam. Abad yang paling dan dianggap sebagai corak berislam yang kafah. Mayoritas, memang berpandangan demikian, bahwa tahun-tahun sekitaran zaman nabi adalah konsep dan ekspresi Islam yang terbaik. Dalam bagian ini, masa lalu seakan-akan terlah menghegemoni cara beragama hari ini.
Sehingga ihwal kaku, fundamentalis, rigiduitas, mencengkeram begitu kuat. Padahal, diakui atau tidak, konteks masa itu tidak sama atau bahkan jauh berbeda dengan konteks hari ini. Realitas hari ini, tidaklah bisa kemudian dicocokkan atau bahkan diserasikan dengan realitas saat itu. Nantinya, realitas ini yang turut andil dalam mengkonstruksi interpretasi dan ekspresi keagamaan.
Corak berislam masa itu terkultuskan dan kemudian menjadi akar. Muslim belakangan dengan gerakan yang serba ekstremis berusaha kembali kepada akar. Fenomena-fenomena yang muncul belakangan justru direspon dengan acuan utama zaman dahulu. Hegemoni masa lalu semakin menjadi-jadi, tatkala kebenaran hanya dipandang satu.
Tertutupnya kebenaran interpretasi dan ekspresi bagi kelompok lain, menegaskan ketertutupan dan kemunduran. Sehingga truth claim terhadap kelompok sendiri seolah menjadi yang satu-satunya dan cenderung apologetis. Itulah tetek-bengek awal dalam radikalisme beragama.
Secara sosiologi terdapat beberapa hal pokok dalam mngulik kembali akar dari radikalisme. Mula-mula ekstremisme cum radikalisme hadir sebagai respon pada hal yang berbeda, itu pasti. Ia berusaha mengkonfrontasi golongan dan interpretasi yang berbeda dengannya.
Dalam perspektif mereka sendiri, golongan yang berbeda ini telah melenceng. Sehingga ia kemudian berusaha untuk menarik kembali pada akar; berislam ala orang awal, sebagaimana saya sebut di atas.
Kedua, mereka kemudian memalak dan memaksakan kehendak dan ekspresi keberagamaannya. Dalam pemaksaan kehendak ini, apapun dilakukan sebagai sebuah jalan dalam hasutan persuasife atau bahkan non-persuasif. Mereka akan merubah dengan sangat fundamental golongan orang yang ekspresi dalam Islamnya berbeda.
Terakhir, klaim paling unggul telah meracuni pola fikir mereka. Sebagaimana sudah saya kutip di awal, bahwa salah satu hal yang ikut andil dalam membangun paradigma ekstremis ini justru wajah kebenaran tunggal. Di sini, saya atau mungkin Anda, tidak akan menjadi kaum Sofis yang skeptis terhadap kebenaran.
Tetapi, kebenaran dalam ekspresi keberagamaan tidaklah tunggal dan tidak ada pula mengenal klasifikasi. Dalam wacana ekspresi, sesuatu memang akan berubah sesuai konteks. Sebab, yang kekal dan patut dipertahankan adalah nilai—yang universal.
Sementara dalam tesmak Charles Kimball, penulis buku When Relogions Become Evil, ekstremisme hanya timbul dari klaim kebenaran. Di mana, klaim kebenaran tersebut lahir dari dan atas nama kesetiaan pada agama(Islam).
Klaim itu juga nantinya akan menghendaki keseragaman tafsiran dan ekspresi di tengah pemeluk agama yang majemuk. Lalu, diperparah dengan etos dan milintansi misionarisme yang tinggi. Girah atas nama agama dan formalitas agama memang sudah kuat mencekam paham ini.
Menggunakan pendekatan aksioma logis, bahwa perbedaan adalah hal yang memang pasti dan tidak bisa dirubah. Hal itu juga terus dirawat sambil lalu memelihara keharmonisan dalam perbedaan. Islam dalam hal ini tidaklah harus menjadi besar secara kuantitatif tetapi mengabaikan sisi kualitatif. Artinya, dalam perjalanan dan ekspresi penyebarannya pun harusnya memang ideal. Hendaknya, cara-cara yang ada harus melewati ruang selektif dan eklektik.
Dimana cara-cara tersebut tidak mencederai nilai Islam yang ramah pada kemanusia. Tidak menjadikan nyawa orang lain sebagai pembenaran dan pembelaan atas kesucian Tuhan. Misionaris dengan mengebiri hak-hak orang lain justru memuat Tuhan sendiri jijik. Saya juga skeptis bahwa Tuhan—yang konon Maha Pengasih dan Penyayang—suka pada kekerasan. Menurut kalian?. []