Kalau orang bule punya umpatan kasar, Mother F*cker, arek Surabaya punya umpatan tak kalah lucu sangar, “Makmu Kiper” yang kalau diterjemahkan oleh Pein Akatsuki (eh!), berarti Your Mother is Keeper. Embuh, ini jenis pisuhan atau apa, saya nggak tahu, hanya geli saya di telinga, lha sejak kapan si mbok jadi penjaga gawang.
Hanya saja, jenis pisuhan di atas malah kalah sedap dan kalah populer di banding dengan pisuhan yang paling oke oce: jancuk! Ini adalah umpatan paling merakyat se-antero Surabaya dan sekitarnya. Ada yang memaknainya sebagai sialan atau brengsek. Orang luar Surabaya mungkin memaknai Jancuk sebagai simbol umpatan paling kasar, sembrono, dan ngawur. Apalagi dengan pelafalan yang mantab diiringi dengan sepasang mata yang melotot. Pas sudah, makharijul huruf yang dipadupadankan sikap jengkel maupun marah.
Bagaimanakah kronologi munculnya istilah jancuk ini? Embuh. Saya nggak tahu sejarahnya. Sebab, di dalam serat, babad, legenda dan dongeng, nggak akan pernah kita jumpai para ksatria misuh-misuh begitu. Bahkan, pahlawan klasik Surabaya, Sawunggaling, dalam pementasan ketoprak pun nggak pernah bilang cuk, jancuk, maupun dancuk! (astaghfirullah, semoga malaikat Atid tidak mencatatnya sebagai dosa. Ampuni hamba-Mu, wahai Gusti!).
Yang pasti, dalam buku “Pertempuran Surabaya” (Yogyakarta: Penerbit Abhiseka Nusantara, 2012) karya Hario Kecik, kita menjumpai cuk, jancuk, dancuk, dan varian anak turunnya, yaitu jiamput, bertebaran dalam dialog para pelaku pertempuran akbar tersebut. Sekadar catatan Buku “Pertempuran Surabaya”, diambil dari 3 Bab pertama buku “Memoar Hario Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).
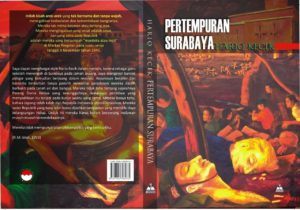
Di awal Oktober 1945, Hario Kecik alias Jenderal Suhario Padmodiwirjo, adalah arek Surabaya asli yang menjadi wakil panglima Polisi Tentara Keamanan rakyat (PTKR) Jawa Timur. Dalam kesatuan tempur ini, dia menjadi wakil Hasanuddin Pasopati, panglima PTKR Jawa Timur yang egaliter, dengan dialeg Madura yang kuat, berani dan sering misuh menggunakan dua pelafalan: jancuk dan jiamput!
Jancuk, kata Sujiwo Tejo yang mendaulat diri sebagai Sang Persiden Jancukers, merupakan simbol keakraban. Simbol kehangatan. Simbol kesantaian. Lebih-lebih di tengah khalayak ramai yang kian munafik, keakraban dan kehangatan serta santainya “jancuk” kian diperlukan untuk menggeledah sekaligus membongkar kemunafikan itu. (Sujiwo Tejo, Republik Jancukers [Jakarta: Kompas, 2012], hal. 397).
Berdasarkan ungkapan Sujiwo Tejo di atas, maka bisa dimaklumi apabila rakyat Surabaya dalam suasana mencekam karena kedatangan Sekutu menggunakan Jancuk sebagai simbol kehangatan. Dan, saya kira ini memang benar, sejak setengah abad silam jancuk memang multimakna. Tapi sebagai orang Jember yang lebih dasawarsa tinggal di Surabaya, saya melihat karakter Jancuk yang khas dan unik menjelang maupun pada saat pecahnya pertempuran akbar tersebut.
Hal ini misalnya tampak saat Usmanaji dan Sabaruddin, dua jagoan dalam revolusi Surabaya, yang ingin menjemput Suryo, salah seorang eks PETA, yang disembunyikan Hario Kecik di Markas PTKR. Nama terakhir menyelamatkan Suryo dengan adu pisuhan melawan Sabaruddin, yang terlibat persoalan pribadi dengan Suryo.
“Jancuk! Hario, endi Suryo? Tokno. Katene tak gowo. (Sialan, Hario. Mana Suryo? Keluarkan. Mau kubawa dia.)” kata Sabaruddin dengan kasar.
“Jancuk! Suryo wis minggat, gak onok kene. (Sialan. Suryo sudah minggat, nggak ada di sini.)” Jawab Hario Kecik.
“Hahahaha….jancuuuuuk!” jawab Sabaruddin. Nama terakhir ini di kemudian hari dieksekusi Polisi Istimewa pimpinan Muhammad Jasin, karena dia dan pasukannya terkenal brutal, sering memperkosa tawanan dan membunuh sebagian besar di antaranya. Demikianlah kronik revolusi.
Namun tak ada panglima yang sering misuh, selain Hasanuddin Pasopati, panglima Polisi tentara Keamanan Rakyat (PTKR) Jawa Timur, atasan Hario Kecik. Hal ini misalnya, tampak saat Hasanuddin dan pasukannya mengintai markas Kempeitai pada pertengahan Oktober 1945 dan berniat merebut gudang senjata di dalamnya. Dia dengan nada kocak dan logat Suroboyoan, bilang,
”Prasamu aku yo gak dek-dekan terus? Jancuk, sopo sing gak kuatir. Sing nok kono iku dudu prajurit biasa, Kempeitai (polisi rahasia) rek. Iyo nek telungatus Geisha ngono karuane. Jancuk! Kon ngerti, uwong-uwong gendheng iku meneng-meneng iso masang bom nek gelem.”
(Kamu sangka aku tidak berdebar-debar terus? Sialan, siapa yang tidak khawatir. Yang ada di situ bukan prajurit biasa, tapi Kempeitai. Lain jika tigaratus geisha, boleh juga. Brengsek! Kamu tahu, kalau mau, orang-orang gila itu diam-diam bisa memasang bom). (Hario Kecik, Pertempuran Surabaya [Yogyakarta: Penerbit Abhiseka Nusantara, 2012], hal. 62.)
Kalau membaca dialog Hasanuddin Pasopati, panglima kocak nan pemberani itu dengan anak buahnya, pasti anda ngakak. Sebab, ini panglima perang yang suka misuh. Tak hanya jancuk dan jiamput, kadang dia menggojlok anak buahnya dengan istilah dobol (yang berarti barang rusak), serta mengumpat pakai istilah kelamin laki-laki dalam Bahasa Londho. Ya maklum, meski suka misuh, dia ini pernah bersekolah guru di zaman Belanda. Jadi selain fasih cas-cis-cus ngomong Londho, dia juga pakar misuh dalam istilah Belanda.
Hasanuddin, yang nekat dan eksentrik ini, kemudian gugur sebagai syuhada di Yogyakarta dalam Agresi Militer II. Ayo rek, sejenak kita bacakan al-Fatihah dan mendoakan seorang martir kita ini yang walaupun suka misuh tapi baik hati. Lahul fatihah.
**
Bagi saya, dalam revolusi November 1945, selain pekik takbirnya Bung Tomo, teriakan Merdeka, dan slogan Merdeka Atau Mati, jancuk juga mendapat prioritas utama. Sebab, kata ini menjadi salah satu perekat egalitarian di antara rakyat maupun pejuang Surabaya. Berbeda dengan Palagan Ambarawa, Puputan Margarana, dan Serangan Umum 1 Maret 1949, yang ketiganya memiliki hierarki yang jelas dengan taktik militer modern, revolusi November di Surabaya terjadi secara sporadis tapi bergelombang. Hierarki militer kacau, karena TKR saat itu baru berusia selapan (35 hari), dan medan Surabaya lebih cocok menjadi sarana Perang Kota yang digerakkan para laskar dibantu arek-arek kampung. Teori “Massa Aksi” ala Tan Malaka mendapatkan pembuktian di ajang yang disebut serdadu Inggris sebagai “Neraka Surabaya” itu.
Di antara tumpukan buku dengan tema Pertempuran Surabaya (Oktober-November 1945), karya Hario Kecik saya anggap yang paling oke oce dan natural. Sebab, di buku ini Hario bisa mengontrol egonya sebagai seorang pelaku pertempuran akbar dengan tidak (terlampau) menonjolkan peranannya.
Alih-alih fokus menuliskan peranan tokoh-tokoh populer dalam 10 November 1945 seperti Gubernur Soerjo, drg. Moestopo, Bung Tomo, Soemarsono, Doel Arnowo, Roeslan Abdulgani, Muhammad Jasin, dan sebagainya, Hario Kecik malah menampilkan cerita arek-arek kampung: Mooeljono yang sepatunya bolong; Oerip yang diselamatkan arwah leluhurnya; Sudjak yang berani; Satrio “Keriting” yang agak nekat; Suwondo “Botak” serta Doel Wahab “Deglok” yang blak-blakan dan banyak akal; Bakri si ajudan Hasanuddin yang lugu; Sumarman sopir yang polos, dan Pak Darum, guru mengaji dari Nahdlatul Ulama, yang menjadi martir di awal serbuan Inggris, akhir Oktober 1945.
Hal ini berbeda dengan buku-buku lain tentang Pertempuran Surabaya lainnya yang lebih elite sentris: Nugroho Notosusanto dengan “Pertempuran Surabaya” (1982) lebih menonjolkan penceritaan dan pencitraan perwira bekas KNIL, Mayor Jenderal Suwardi, yang dianggap lebih tahu pertempuran dibanding arek-arek Suroboyo, apalagi buku Soemarsono yang berjudul “Revolusi Agustus” (2008) yang secara telanjang mendudukkan dirinya sebagai pencerita sebagai tokoh yang secara hierarkis lebih tinggi di atas ribuan arek-arek Suroboyo.
Hal ini sebenarnya selaras juga dengan tulisan William H. Frederick dalam “Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)” yang secara diametral menempatkan sosok Bung Tomo sebagai sentral, dan sedikit banyak meminggirkan tokoh lain, apalagi para arek kampung Surabaya.
Namun, Bung Tomo sendiri dalam “Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian dan Pengalaman Seorang Aktor Sejarah”, dengan rendah hati menyebut, “Jika ada yang dianggap pahlawan pada hari itu, segenap rakyat itulah yang harus dinamakan pahlawan.” (Sutomo (Bung Tomo), Pertempuran 10 November 1945: Kesaksian dan Perjalanan Seorang Aktor Sejarah [Jakarta: Visi Media, 2008], hal. 147)
Sayang, karena buku-buku di atas terlampau serius, akhirnya malah melewatkan kosakata jancuk dan peranannya sebagai lem perekat egalitarian di dalam Revolusi November 1945 itu sendiri. Wallahu A’lam Bisshawab. []
Catatan:
1. Tulisan di atas sudah saya muat dalam buku karya saya yang berjudul “Surabaya: Kota Pahlawan Santri” (Surabaya: LTN NU, 2017).
2. Hario Kecik, alias Mayjen TNI Soehario Padmodiwirio, foto tahun 1946.
3. Buku karya Hario Kecik berisi kronik Pertempuran Surabaya, 1945.























