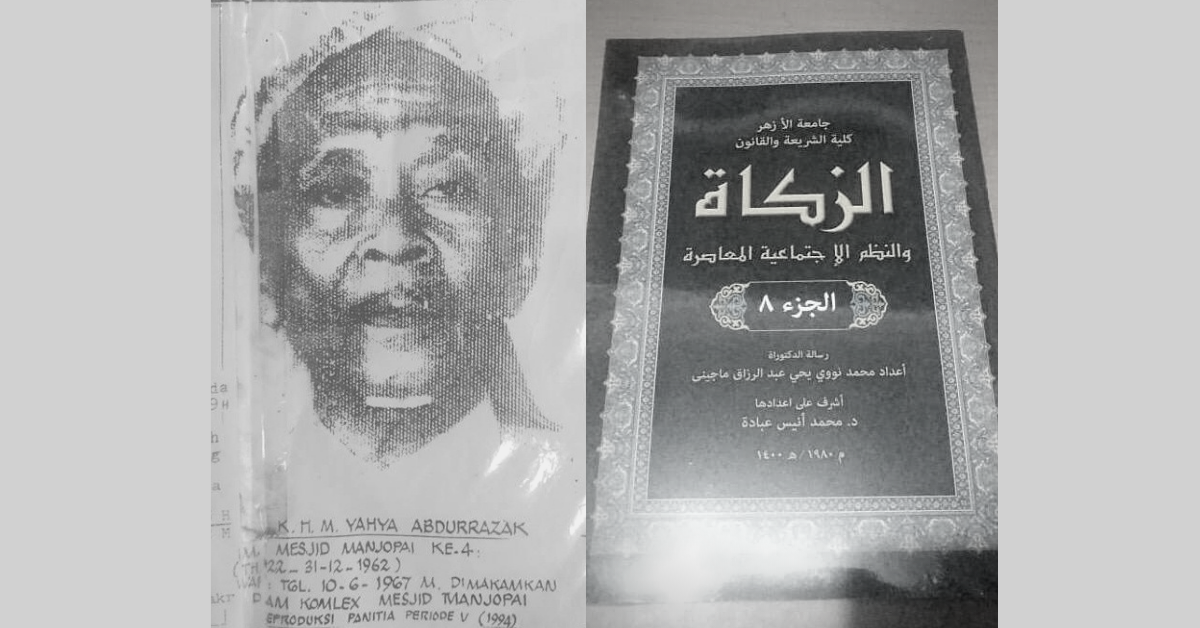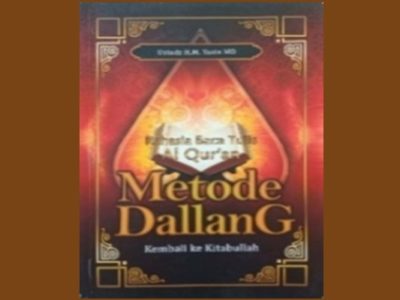Al-Anbiya: 44
بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَاۤءِ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُۗ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَاۗ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ
Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi negeri (yang berada di bawah kekuasaan orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?
Beberapa hal penting sebagai catatan dari para mufasir:
Pertama: Penggalan kalimat bal matta’nā hā`ulā`i wa ābā`ahum ḥattā ṭāla ‘alaihimul-‘umur (Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan [hidup di dunia] hingga panjang usia mereka) merupakan sindiran terhadap pemikiran orang-orang kafir yang keliru, manakala diberi kenikmatan dan umur yang panjang dimaknai bahwa mereka dijaga oleh tuhan-tuhan sesembahan mereka. Padahal apa yang mereka peroleh itu adalah sebentuk penangguhan dan perpanjangan waktu yang semakin membuat pengingkaran dan sifat keras hati yang menjadi-jadi. Mereka mengira akan tetap seperti itu selamanya, sampai tak mengerti bahwa hal tersebut hanyalah khayalan palsu belaka.
Tentang pemberian umur yang panjang tetapi tidak pasti baik bagi mereka juga disinggung dalam ayat lain, semisal,
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang Kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah; dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. (QS. Ali ‘Imran: 178)
Bahkan apa yang mereka nikmati hanyalah istidraj belaka,
فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِۗ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَۙ. وَاُمْلِيْ لَهُمْۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ
Maka serahkanlah kepada-Ku (urusannya) dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur’an). Kelak akan Kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencana-Ku sangat teguh. (QS. Al-Qalam: 44-45)
Mereka pun tetap dalam keadaan bodoh, lalai dan tertipu dengan semua itu.
Kedua: Pada bagian ayat a fa lā yarauna annā na`til-arḍa nanquṣuhā min aṭrāfihā (Maka apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi negeri [yang berada di bawah kekuasaan orang kafir] Kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri), lalu Kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri) jumhur ahli tafsir memaknainya sebagai kemenangan orang-orang beriman, menaklukkan satu-persatu negeri yang dihuni oleh kaum kafir, mulai dari sekitar Makkah dan terus ke berbagai penjuru. Sehingga semakin berkuranglah kekufuran dan kemusyrikan sejalan dengan kehancuran orang-orangnya.
Tentang kalimat nanquṣuhā min aṭrāfihā (Kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri), terdapat beberapa pendapat, sebagaimana termaktub dalam Mafātih al-Ghaib, antara lain: (a) Sy. Ibn Abbas, Imam Maqatil dan Imam al-Kalabi memaknainya sebagai penaklukkan suatu negeri (fath al-buldān); (b) Sy. Ibn Abbas dalam riwayat yang berbeda memaknainya sebagai kurangnya penduduk dan keberkahan pada negeri tersebut; (c) Imam Ikrimah menafsirkannya sebagai kehancuran suatu negeri ketika penduduknya meninggal; dan (d) Sebagian memaknai sebagai kematian para ulama. Untuk pendapat yang terakhir ini, andaikata riwayatnya memang sahih, tampaknya tidak begitu tepat untuk ayat ini. Karena, menurut Imam ar-Razi, yang lebih tepat adalah pendapat-pendapat yang berhubungan dengan ghalabah (kemenangan). Dengan alasan tersebut ayat ini lalu ditutup menggunakan frasa a fa humul-gālibụn (Apakah mereka yang menang?). Jadi yang dikurangi adalah bagian dari negeri orang-orang kafir dan memberi tambahan kaum beriman, lantas bagaimana bisa ia dimaknai sebagai “kematian para ulama”? Bahkan Imam al-Qaffal juga memberi komentar bahwa ayat ini diturunkan bagi kaum kafir Makkah, lantas bagaimana mungkin para ulama dan fuqaha termasuk di antara mereka?
Dalam tafsir Ta`wīlāt Ahl as-Sunnah, Imam al-Maturidi memang mengutip tafsir Sy. Ibn Abbas yang memaknai nanquṣuhā min aṭrāfihā sebagai kematian ahli ilmu (fuqaha`) dan orang-orang baik (khiyār) di negeri tersebut, penjelasan itu (pada poin [d] di atas) masih bisa diterima bila diartikan bahwa orang-orang hebat yang menjadi andalan orang-orang kafir itu mati, sehingga tidak ada yang memiliki otoritas keilmuan untuk membentengi ideologi, sehingga dakwah yang disebarkan ke masyarakat mereka sulit dibendung, apalagi ditolak.
Ketiga: Imam asy-Sya’rawi bercerita, manakala para ahli ilmu alam menemukan bahwa bumi tidak bulat sempurna, melainkan berbentuk oval, ada sebagian orang yang begitu bersemangat dalam masalah keagamaan mengemukakan bahwa Allah sudah mengatakannya di dalam al-Quran dengan kalimat a fa lā yarauna annā na`til-arḍa nanquṣuhā min aṭrāfihā (Maka apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi bumi, Kami kurangi luasnya dari berbagai sisi), karena ayat ini memungkinkan dimaknai bahwa bentuk bumi tak sama, diukur dari panjang garis khatulistiwa dengan garis yang ditarik dari dua kutub bumi. Dengan demikian, manakala para ilmuan menemukan bentuk oval, tentu al-Quran sudah mengatakannya sejak 14 abad silam.
Sayangnya, semangat mereka tidak disertai sikap kritis yang seimbang. Mereka lupa terhadap redaksi nanquṣuhā min aṭrāfihā (Kami kurangi luasnya dari berbagai sisi), bahwa bukan berkurang dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai penjuru. Hal ini membuka satu pintu bagi para orientalis untuk mengkritik al-Quran. Alih-alih membuktikan kebenaran dalam agama, mereka justru membuat titik buta sebagai sasaran empuk bagi kesalahan yang mereka ciptakan dari semangat berlebihan itu.
Maka adalah hak kita untuk mempertanyakan, apakah makna a fa lā yarauna (apakah mereka tidak melihat?) adalah penglihatan inderawi atau ilmiah? Jika memang ia merupakan penglihatan inderawi, kenapa ia baru diketahui pada abad ke 20 dan tidak ada seorang pun yang sebelumnya menyatakan demikian? Dari sini dapat disimpulkan bahwa kata “melihat” yang dimaksud pasti bukan inderawi. Jika dijawab dengan opsi kedua, bahwa ini merupakan temuan ilmiah, pertanyaannya adalah bagaimana ayat ini dapat diterima oleh orang-orang Arab 14 abad silam, yang notabene bukan masyarakat ilmiah dan belum memiliki peradaban teknologi yang memadai seperti saat ini? Dengan demikian, kata ini bukan juga bermakna temuan ilmiah.
Karenanya, Imam asy-Sya’rawi menyimpulkan bahwa tafsir ayat ini sejalan dengan tafsir jumhur para ulama sebagaimana telah diulas pada poin pertama dan kedua. Beliau kurang menyetujui bilamana penjelasan tentang ayat ini dibawa ke ranah ilmu alam—sebagaimana telah dilakukan sebagian orang yang hanya bermodalkan semangat tanpa sikap kritis terhadap teks al-Quran secara utuh.
Keempat: Pembacaan khas tafsir Isyāri yang dilakukan oleh Syaikh Najmuddin al-Kubra juga tak kalah menarik, bal matta’nā hā`ulā`i (Sebenarnya Kami telah memberi kenikmatan mereka) yaitu orang-orang yang terhijab oleh nafsu basyariyah, yang menikmati kesenangan duniawi dan memperhatikan syahwat mereka semata; ābā`ahum (nenek moyang mereka), yang dimaksud adalah akal para ahli hijab ruhaniah, untuk menikmati hal-hal rasional (al-ma’qulat) dan mengambil manfaat darinya; ḥattā ṭāla ‘alaihimul-‘umur (hingga panjang usia mereka) dan mendapati hati mereka mencintai hal-hal rasional itu sejurus dengan usia mereka yang kian lama; a fa lā yarauna (Maka apakah mereka tidak melihat) yaitu dua golongan yang dihijab dengan nafsu manusiawi dan hijab ruhaniah itu; annā na`til-arḍa (bahwa Kami mendatangi bumi) bumi kemanusiaan dalam diri mereka, nanquṣuhā min aṭrāfihā (lalu Kami kurangi luasnya dari berbagai sisi), sisi manusiawi dikurangi fungsi fisiknya, sisi ruhani dikurangi pula keistimewaan ruhaniahnya; jika kedua golongan ahli hijab itu memperoleh inayah (pertolongan), tentu mereka tidak sibuk menuntut bagian nafsu manusiawi dan ruhaniah belaka, melainkan lebih mementingkan al-wāridāt ar-Rabbāniyyah (anugerah Ilahi); a fa humul-gālibụn (Apakah mereka yang menang?) ataukah Kami? Dan tentu Allah lah yang menang dan menguasai segala sesuatu.
Kelima: Petuah manthīq al-hayah (logika kehidupan)[1] ialah bahwa “kebahagiaan” bisa mengantarkan kita pada usia yang lebih lama—tanpa menolak hukum takdir. Karena dalam ayat di atas disebutkan “panjangnya usia” (ḥattā ṭāla ‘alaihimul-‘umur) diawali dengan “kebahagiaan atau kenikmatan hidup” (matta’nā hā`ulā`i).
Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk menimam-nimang dalam renungan tentang makna ghalabah (kemenangan), jika hanya mendapat kesenangan dan umur yang panjang, namun digerus dari berbagai sisi, terkurangi akan apa-apa yang seharusnya dipertahankan, layakkah hal tersebut di anggap sebagai kemenangan?
Al-Anbiya: 45
قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۤءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu.” Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.
Tentang ayat ini, ada beberapa penjelasan dari para mufasir:
Pertama: Imam ar-Razi menjelaskan qul innamā unżirukum bil-waḥyi (Katakanlah [Muhammad], “Sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu”) yaitu al-Quran, firman Tuhan kalian. Karena itu janganlah kalian (orang-orang kafir) berasumsi bahwa ia berasal dari diriku (nabi Muhammad Saw), melainkan Allah yang mendatangkannya dan memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada kalian semua. Ketika aku telah melaksanakan tugas yang diwajibkan kepadaku, sementara kalian tetap tidak menerima dan tak mau menggubrisnya sama sekali, maka celaka dan bahaya itu akan kembali pada kalian.
Saat orang-orang kafir itu tidak menerima apa yang telah diperingatkan atas mereka, maka mereka seperti orang yang tuli. Karena tujuan dari suatu peringatan bukanlah sekedar agar mereka mendengarnya, melaikan kepercayaan terhadap hal itu, menjalankan apa-apa yang diwajibkan, menghindari sebisa mungkin dari sesuatu yang dilarang dan mengenal (mengakui) Allah sebagai Tuhan mereka. Jika tujuan ini tak didapati dalam diri mereka, maka wajarlah bila mereka dianggap tidak mendengar atau tuli (aṣ–ṣumm).
Kedua: Imam ar-Razi mengajukan sebuah tanya yang cukup menarik, yaitu “Bila Allah menyifati mereka sebagai orang-orang tuli, lalu bagaimana mereka dianggap mendapatkan peringatan? Bukankah peringatan hanya berlaku bagi mereka yang mendengar tentang apa-apa yang disampaikan kepada mereka?”
Lalu beliau menyampaikan jawabannya sebagai berikut: huruf alif-lam yang terdapat pada kata aṣ–ṣumm ialah untuk mereka yang jelas-jelas diberi peringatan (li al-‘ahd [untuk yang telah diketahui]), bukan secara keseluruhan (li al-jins [berdasarkan jenis manusia secara umum—entah yang telah diberi peringatan atau pun belum]). Jadi maknanya adalah “mereka tidak mendengar ketika diberi peringatan”, makna zahir berada pada posisi kata gantinya (wadh’ adz-dzāhir maudhi’ al-mudhmar) untuk menunjukkan kondisi mereka yang pura-pura tuli dan mencegah pendengaran mereka ketika diberi peringatan. Dengan demikian, ini merupakan bentuk sikap menentang dan kelancangan mereka tentang ayat-ayat peringatan yang diperuntukkan bagi mereka pada waktu itu.
Ketiga: Ketulian yang mereka alami ini tak lain karena pada dasarnya mereka tidak memiliki niat baik sama sekali, mereka pun selalu berpaling dari pengetahuan yang sangat jelas, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang berbeda,
وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْۗ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ
Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. (QS. Al-Anfal: 23)
Keempat: Syaikh Ibn ‘Ajibah menulis dalam tafsirnya perihal qul innamā unżirukum bil-waḥyi (Katakanlah [Muhammad], “Sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu”) untuk menunjukkan bahwa kondisi peringatan (al-indzār) hanyalah pemberian kabar, bukan bentuk nyata dan terjadi saat itu juga. Karena perihal keimanan, dalam konteks al-hikmah al-Ilahiyah, adalah sesuatu yang benar dan diyakini (al-burhānī), bukan hal yang terjadi secara langsung (al-‘iyānī). Orang-orang yang mengingkari dan (apalagi) meminta disegerakan azab bagi mereka berarti benar-benar tidak mau beriman sama sekali.
Di sisi lain, penggunaan kata ad-du’ā` (seruan atau panggilan), bukan dengan kata kalam (perkataan) atau kata lainnya, untuk memberi peringatan terhadap mereka, menunjukkan keingkaran mereka yang luar biasa. Sebab kata ad-du’ā` adalah isyarat tentang panggilan dengan suara tinggi (pasti didengar), yang diulang-ulang dan disertai kondisi yang paling memungkinkan untuk dijawab. Jika dengan hal ini mereka tidak mau menerimanya, berarti mereka berada dipuncak ketulian yang paling tinggi. Demikianlah keterangan Syaikh Ibn ‘Ajibah.
Kelima: Imam al-Maturidi menjelaskan konteks ayat ini adalah untuk merespon penolakan kaum kafir yang didasari pada diri para rasul sebagai manusia biasa, sebagaimana tersebut di awal surat,
…هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۚ…
(Orang) ini (Muhammad) tidak lain hanyalah seorang manusia (juga) seperti kamu. (Al-Anbiya: 3)
Karena itu dijawab qul innamā unżirukum bil-waḥyi (Katakanlah [Muhammad], “Sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu”), agar sisi manusiawi para rasul tidak dijadikan alasan untuk menolak dakwah pada ajaran tauhid dan apa-apa yang dibawa oleh rasul.
Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa ancaman yang dibawa oleh para rasul bukan berasal dari diri mereka, melaikan dari Allah. Sehingga jika seorang utusan tidak mengetahui datangnya Hari Kiamat, misalnya, hal itu tak bisa dibuat pendasaran bagi penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebaliknya, ketidaktahuan itu justru mempertegas posisi para rasul sebagai penyampai risalah semata, dan mereka tidak mengetahui sesuatu yang memang tak dikabarkan kepada mereka.
Pada penggalan akhir ayat ini lā yasma’uṣ–ṣummud-du’ā`a iżā mā yunżarụn (Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan) bisa dimaknai untuk menempuh cara lain selain da’wah (ajakan) semata, dengan tangan, peperangan yang diperbolehkan—atau menampakkan akhlak yang baik, misalnya. Sebagaimana mengajak orang tuli yang tak bisa dengan berbicara dengan mereka, melainkan dengan tindakan fisik yang memungkinkan bisa dipahami. [HW]
Referensi:
[1] Istilah ini memiliki pengertian yang sinonim dengan “al-Hikmah al-Quraniyyah” atau “Fiqh al-Hayah”.