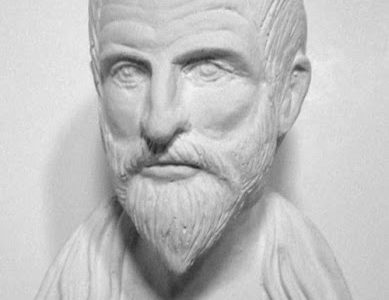Aku benar-benar menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa Tuhan menghisab (menghitung) amal hambanya sendiri. Ia tak didampingi satu malaikat pun di hari itu. Karena malaikat saat itu juga ikut mengantri untuk dihitung amalnya, meski sudah jelas semua perbuatannya baik. Tapi itulah aturan Tuhan. Konon masa perhitungan amal ini hanya memakan waktu satu hari dengan sekian banyaknya kontestan yang ikut ditimbang amalnya.
Dengan adil dan teliti Tuhan menimbang satu persatu amal semua makhluk. Manusia, jin, malaikat, bebatuan, pohon, bahkan setan yang jelas akan dimasukkan ke neraka oleh Tuhan pun tetap ditimbang perbuatannya. Jika satu dari makhluknya berat timbangan kebaikannya maka dengan segenap rahmat dan kasih sayangnya Tuhan tunjukkan ia jalan ke surga. Tetapi jika hambanya memiliki timbangan buruk lebih berat maka dengan seluruh pertimbangannya yang maha adil ia akan menuntunnya ke neraka.
Kalian ingin tahu bagaimana wujud Tuhan? Entahlah dengan posisi antrianku yang masih jauh sulit untuk menggambarkannya. Yang jelas ia tak sama dengan makhluknya. Juga ia terlalu indah untuk digambarkan dengan kata-kata. Mungkin aku akan mengilustrasikan seperti apa Tuhan kepada kalian saat aku sudah berada di antrian depan.
Entah karena amal baikku yang lebih berat atau karena hal lain antrian terasa begitu cepat bagiku. Sekitar sepuluh orang lagi sudah hampir tiba giliranku. Kini mungkin aku sudah bisa memberikan kalian gambaran realistis soal Tuhan. Ia tak punya tangan, kaki, dan kepala seperti yang digambarkan kaum mujassimah (sekelompok orang-orang yang mengklaim bahwa Tuhan memilki anggota tubuh). Ia sangat indah dan maha segala-galanya.
Kulihat ekspresi Tuhan begitu cepat berubah-ubah. Tergantung situasi yang didapati. Saat orang yang Ia timbang kebaikannya lebih berat maka Ia terlihat seperti tersenyum ramah. Mungkin itu bentuk ekspresi dari sifat ghafur rahim -pengampun dan penyayang- yang selalu kita dengar semasa di dunia.
“wah, beruntung sekali orang itu! Semoga saja aku bisa seperti dia” -ujar seseorang yang mengantri di depanku saat melihat satu manusia dipersilahkan Tuhan menuju surga.
Ekspresi Tuhan lalu berubah lagi saat giliran menimbang orang berwajah mirip keledai. Wajah Tuhan seolah-seolah berkata “kenapa kau sia-siakan banyak nikmat hidup yang kuanugerahkan padamu? Kenapa engkau tak pernah sekalipun mengingatku semasa di dunia?”. Batinku “inikah ekspresi kemarahan Tuhan?”. Di dunia ekspresi ini biasa kita dengar dengan syadidul adzab (maha kejam siksanya).
Kuberanikan diri mencolek orang yang berada di depanku. Namanya Jumaidi. Aku mengetahuinya dari tulisan di baju yang ia pakai.
“Heh, pak Jumaidi” -ujarku
“Iya, ada apa?” -jawab Jumaidi sambil menoleh ke belakang
“kira-kira dosa apa yang ia lakukan semasa hidupnya hingga Tuhan sedemikian marahnya?”
“Entahlah, mungkin ia berzina, mencopet, dan menculik anak kecil. Ehh… ia mungkin juga pernah mencekik anjing hingga mati”
Wajah Jumaidi sungguh terlihat yakin saat menjawab pertanyaanku. Oleh karenanya aku hanya manggut-manggut saja, tanda setuju. Melihat gelagatku yang tak butuh jawab lagi Jumaidi pun kembali membalikkan badan. Ia balik mengantri.
Sejurus kemudian kini giliran Jumaidi yang akan dihitung dan ditimbang perbuatannya di hadapan Tuhan. Dengan sigap dan rasa penuh percaya diri ia berjalan menuju ke hadapan Tuhan. Tuhan pun menyambutnya dengan senyum lebar. “akankah Jumaidi lulus dengan mudah?” -aku kembali membatin, Tuhan pasti tahu itu. Kan ia maha segalanya.
Sambil menghitung Tuhan menanyai Jumaidi.
“wahai hambaku, Jumaidi! Apa gerangan arti dari nama yang orang tuamu berikan padamu?”
“kata ayahku, artinya penyesuaian yang baik. Itu berasal dari bahasa Jawa gusti”
“Bagus!”
Ternyata Tuhan juga bertanya soal nama. Oh, iya. Namaku Hikam, artinya beberapa hikmah/kebijaksanaan atau menurut pengkaji filsafat artinya ya filsafat itu sendiri. Ayahku yang menyematkan nama itu padaku. Kata ayah pada ibu “agar kelak anak kita bisa menentukan perbuatannya sendiri. Mana yang baik baginya dan mana yang buruk”. Syukurlah aku ingat semua itu.
Lanjut soal interogasi Tuhan dengan Jumaidi.
“Lalu apa saja yang kamu lakukan di dunia semasa hidupmu?”
“Aku mengingatmu setiap saat dan menjalankan seluruh perintahmu, termasuk haji. Oh, iya Tuhan! Aku juga rajin melaksanakan salat. Bukankah engkau sendiri yang bilang bahwa amal yang pertama kali dihisab adalah salat?”
Tiba-tiba aku menganggukkan kepalaku. Ada sesuatu yang terlintas di kepalaku. Oh, ya aku ingat, kata pak ustadku dulu di pesantren salat memang dihisab paling awal. Dan itu benar. Insya Allah salat-salatku benar-benar lengkap. Jadi amanlah! Untuk masalah haji, aku kan saat ini masih berstatus pelajar dan berumur sekitar dua puluhan. Sedangkan Jumaidi sudah kepala lima dan mobilnya juga banyak, tentu ia wajib haji. Jadi Tuhan tak mungkin akan mengungkit soal haji kepadaku.
“Bagus!” -ujar Tuhan dengan lantang. Aku agak tersontak kaget.
Tuhan memberikan Jumaidi jalan yang baik. Ia dengan rahmatnya membukakan pintu surga untuk Jumaidi. Wah, beruntung sekali ia. Pantas saja ia terlihat sangat gagah saat mengantri tadi.
Aku termenung agak lama memandangi Jumaidi. Hingga tak sadar aku dicolek oleh seseorang di belakangku. “hei, majulah! Sekarang giliranmu!” -ujarnya.
Dengan agak ragu-ragu aku maju ke hadapan Tuhan yang akan menghisab amalku. Ekspresi Tuhan kepadaku bagaimana, menurut kalian? Malah tidak terlihat jelas ternyata. Ambigu, antara ia marah atau tersenyum. Yang bisa melihat realitas ekspresi itu ternyata malah bukan orang yang sedang diadili. Bagi mereka yang sedang diadili ekspresinya justru sangat abstrak.
Kini aku sudah benar-benar siap diadili. Tak peduli soal timbangan amalku. Aku benar-benar pasrah pada Tuhan.
“wahai hambaku, Hikam! Apa arti nama yang ayahmu berikan padamu?”
“kata abahku, artinya kebijaksanaan. Itu berasal dari bahasa Arab, Tuanku. Bahasa yang engkau pakemkan untuk ahli surga”
“sangat indah!” -puji Tuhan kepadaku.
Syukurlah aku lolos soal pertama. Lanjut pertanyaan kedua.
“Lantas apa saja yang engkau perbuat di dunia selama ini?”
Aku dengan perasaan yakin dan mantap menjawab pertanyaan ini.
“aku sama seperti Jumaidi. Melaksanakan perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu. Tapi aku belum melaksanakan haji, Gusti! Sebab aku masih mahasiswa dan tak mampu secara finansial. Bukankah Tuan hanya mewajibkan haji bagi yang mampu saja?”
“iya! Yang kamu katakan soal haji benar. Namun yang kusoal sekarang bukan itu. Tapi salatmu…”
Dengan berani aku menyela pembicaraan Tuhan. Aku yakin ia akan memaklumiku sebagai hambanya yang ceroboh.
“Bukankah salatku lengkap, gusti?”
“Iya, benar! Tapi engkau seringkali mengabaikan panggilanku di saat fajar menyingsing. Kamu tidur sangat nyenyak seolah panggilanku lewat speaker mushala tidak berarti bagimu”
Tuhan agaknya marah. Aku bisa merasakannya. Namun aku tetap akan mengajukan banding kepadanya.
“Hah” -wajahku penuh dengan ekspresi heran- “bukankah engkau sendiri yang bilang bahwa kewajiban orang yang tidur akan ditangguhkan sampai ia bangun”
“Benar sekali! Tapi bukankah satu hambaku yang tidur di sebelah ruanganmu telah membangunkanmu agar kau bisa salat menghadapku?”
“Benar, gusti! Temanku yang bernama Fatah itu membangunkanku tapi tidak sampai membuatku terbangun. Bahkan aku juga sudah memasang alarm agar bisa memenuhi panggilanmu. Tapi tetap saja itu tidak membuatku bangun. Bukankah itu berarti engkau membiarkanku salat di waktu qadha?”
“Apa yang kamu ajukan itu benar. Tapi bisakah kamu mengingkari ini? Bukankah kamu bangun saat teman sebelah ruanganmu sedang menelpon dengan pacarnya. Saat itulah aku merasa kecewa, karena kamu kembali menarik selimutmu agar bisa kembali tidur dengan lelap dan mengabaikan panggilanku”
“Tunggu!” -aku kembali menyela Tuhan untuk mengajukan banding- “bukankah telpon yang menghubungkan temanku dan pacarnya itu termasuk laranganmu. Jadi aku boleh saja merasa terganggu dan membiarkan badanku kembali terkujur di atas kasur. Karena aku merasa telpon itu bukan panggilan untuk aku melakukan salat”
“hah! Kamu benar-benar tidak sadar? Bukankah aku tidak akan menciptakan sebuah keburukan kecuali di belakangnya ada kebaikan. Pun saat aku sedang membiarkan hambaku menelpon pacarnya dan mengalihkan cinta yang seharusnya untukku kepada pacarnya sebenarnya aku sedang membangunkanmu supaya melakukan salat subuh. Namun apa yang kudapati? Kamu malah mengabaikanku dan lebih memilih asyik masyuk dengan tidurmu”
Kini aku sudah tak bisa mengelak lagi. Aku pasrah terhadap apa yang akan Tuhan lakukan kepadaku. Dan sepertinya ia akan melemparkanku ke neraka.
**
Aku tunggu-tunggu keputusan Tuhan.
“sayang, kamu mau makan apa hari ini?”
Suara itu terdengar seperti suara perempuan. Akankah Tuhan itu perempuan? Tidak mungkin, Tuhan kan tak punya gender. Lalu suara apakah itu? Aku mencoba membelalakkan mataku yang tadi sempat terpejam di hadapan Tuhan karena rasa takut. Aku dengarkan dengan seksama sumber suara itu. Dan betul, ternyata itu suara Tuhan. Tapi dalam bentuk lain. Ia yang maha kuasa sedang berusaha membangunkanku lewat suara telepon sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Tuhan sedang mencoba menarik selimutku agar bisa memenuhi panggilannya di waktu fajar. Syukurlah ternyata kemarahan Tuhan yang tadi hanya mimpi.
Akankah aku akan memenuhi panggilannya? Atau justru tidur lagi? Itu urusan pribadiku. Pembaca cerita ini tak perlu tahu.