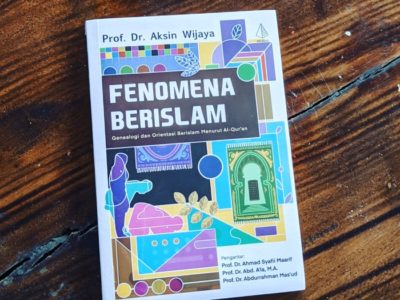Dentuman dahsyat berupa informasi terus membanjir-sesaki kesadaran kita bak layanan tanpa turun dengan bertera-tera bit sampah dan pembodohan. Miris, dengan telepon pintar, justru kedunguan menjalar. Tak ayal, kepribadian dan pekerti adalah urusan gawai, sementara belajar menjadi manusia, cukup kita serahkan ke SD-SMP-SMA Online.
Lupakan dulu gerombolan mualaf pandir pseudo ustaz pengasong intoleransi yang skill-nya hanya menista agama lama mereka, abaikan juga rencana perpindahan ibukota tanpa membawa serta tugu Monas karena demo berjilid-jilid kawanan monaslimin masih akan menjadi jualan para oligark dan demagog untuk kaum cuti nalar dan defisit akal sehat, terutama demi kepentingan politik eletronik, eh elektoral.
Dengan terus membubungkan doa ke angkasa dan membantu sebisanya untuk krisis kemanusiaan terburuk di Yaman sepanjang 100 tahun terakhir akibat kebiadaban rezim despotik Arab Saudi, juga kesenjangan Palestina-Israel yang terus digoreng di Negeri kita sendiri, terutama oleh para makelar investasi bodong ala 212 Mart, donasi kapal selam, donasi-donasian Palestina, donasi ISIS, donasi toko waralaba, tipu-tipu perumahan syariah, investasi kampung kurma, travel umroh, dll.
Kali ini kita ngopi ke Benua Biru, menepi di tengah kesibukan yang nyaris hilang arti. Abad pertengahan di Eropa, yang lazim disebut zaman kegelapan, agama selalu ditampilkan sebagai “sang domina”, pengangkang filsafat sekaligus pendera sains. Tentu Anda masih ingat bagaimana Galileo sebagai simbol pengetahuan dihukum mati lantaran pandangannya bertentangan dengan fatwa gereja? Praktis, para filsuf dianggap anti agama, anti doa, musuh agama dan memang filsafat itu bukan mantra sekaligus doa. Filsafat adalah Ibunda Agung segala ilmu, meski kehadirannya kerap dianggap sebagai pengganggu untuk hampir setiap matra dan dimensi waktu.
Sebagaimana tidak semua orang perlu filsafat, tidak setiap orang pula butuh agama. Mengapa? Hidup tak selalu berjalin-jemalin dengan keduanya. Apa sebab? Tiap manusia tidak sama, tiap tempurung pasti berbeda. Sains tidak butuh agama, dan agama tidak memerlukan sains untuk diimani serta dijalani pemeluknya. Tak ayal, cocokologi kerap menjadi upacara bunuh diri bagi keagungan agama. Sementara itu, filsafat (sebagaimana agama) ada kalanya malfungsi, tidak bekerja, ada kalanya sangat berguna. Kadang, filsafat malah sibuk onani dengan egonya yang jumawa. Namanya juga onani menara gading, enaknya sendirian, paralel dengan ilmuwan yang hanya mengabdi pada kekuasaan demi sekian digit rekening, sementara rakyat dibiarkan bodoh agar tidak ada perlawanan.
Tentu ada bisa menduga keras bahwa yang anti filsafat dan malah masturbasi agama tak jauh-jauh dari gerombolan Neo-khawarij Wahabi Takfiri serta kawanan fundamentalis radikal sejenis, Ikhwanul Muslimin Indonesia, DII/TII reborn, Masyumi reborn, PKS, HTI-FPI reborn, yang lebih sibuk dengan aksesoris berupa jenggot impor, jidat biru, jubah ala Dimas Kanjeng serta celana dan otak cingkrang dengan jargon “poligami untuk membangun negeri” yang lebih memahami agama dari perspektif hormonal-selangkangan. Jika tidak meneror, membunuh sebagaimana para milenial pelaku bom bunuh diri, ya merusak fasilitas umum, melakukan persekusi pada minoritas sembari pekik takbir seolah Indonesia adalah Suriah. Tetapi, mereka hanya kawanan kambing-kambing transnasional yang gembalanya masih digembalakan lagi oleh gembala yang lebih tinggi. Kantornya bisa di London, Paris dan Washington. Anda tahu bagaimana Trump bertakhta dengan menggoreng isu SARA, juga Jail Bolsonaro di Brazil, Le Pen di Prancis, Lutzbachman di Jerman, Great Wilders di Belanda? Di Indonesia? Gerombolan 212.
Namun demikian, manusia membutuhkan filsafat dan sekaligus agama. Fritjof Capra menambahkan dalam magnum opusnya, The Tao of Physic, bahkan manusia membutuhkan mistik untuk menjalani hidupnya. Terbukti, mitos cukup berperan membentuk peradaban manusia, terutama mitos kecantikan, mitos 212, Sunda Empire, mitos emansipasi, mitos HAM, mitos pemberantasan korupsi, mitos Senayan, mitos YouTubers receh, dan mitos-mitos bikinan korporasi dan keterlanjuran sistem yang bercorak kapitalistik. Sehingga, tak hanya sains, agama dan kelaminpun diperjualbelikan sedemikian rupa demi pangsa pasar yang entah sedemikian gila. Dan, kabar buruknya, justru pandemi covid-19 semakin menghampakan karpet merah untuk segala bentuk jualan berbasis internet of thing. Anda tahu, era 4.0 adalah surga para tengkulak dan makelar yang bisa menggunakan big data.
Benarkah filsafat musuh agama? Bukankah telah banyak tuduhan murahan dan sinisme kampungan bahwa filsafat merusak seluruh korpus agama, salah satunya yang digaungkan oleh kiblat kaum puritan alias para skriptualis, Ibnu Taimiyah misalnya? Bagaimana meluruskan pandangan ini?
Telah sejak lama Immanuel Kant, dengan agnostismenya, menjaga batas-batas nalar dan agama justru secara rasional demi membangun era baru bertajuk zaman pencerahan dari perspektif nalar murni. Pada gilirannya, GWF Hegel malah menghancurkan dan menghapus demarkasi itu agar kelak sejarah hidup umat manusia menjadi ideal, dan tak lama kemudian, Soren Kierkegaard tetap mempertahankan batas-batas iman dan rasio itu justru dari sisi iman Kristiani. Ada apa gerangan atau gerangan yang mengada-ada?
Memang, hubungan filsafat dengan teologi, atau setidaknya rasio dengan wahyu, tak lain adalah topik klasik tentang kawin-cerai di satu sisi dan perselingkuhan di sisi lain. Peran filsafat sebagai ancilla theologiae bagi gereja abad pertengahan adalah catatan hitam sejarah bagi filsafat, jika bukan lubang hitam bagi agama, sampai kelak zaman pencerahan datang dengan pongahnya sains dan jumawanya teknologi yang menjadikan kebanyakan manusia sedemikian dehumanistik. Memang, teknologi tak jarang membuat manusia kian rapuh dan keropos, tak ada jarak geografis, sementara jarak antropologis kian menganga-merentang.
Sekarang? Inilah dentuman mahadahsyat bernama ledakan informasi digital, yang merubah cara kita hidup tapi tidak cara beragama dan pandangan sebagian besar kita terhadap agama yang kontra produktif. Alih-alih memancar-tularkan nilai kasih, malah agama dijadikan pembenar untuk syahwat rendah bernama penindasan dan perbudakan jenis baru. Walhasil, gerombolan defisit ilmu dan cuti nalar itu menganggap agama atau bahkan mazhab sebagai tujuan, bukan jalan, serta menilai NKRI tidak penting, kecuali untuk hajatan lima bernama Pemilu.
Pandemi? Ya, agama memang seolah tunduk pada sains, tapi begitu politik elektoral berupa Pilkada dan momen mudik datang, mitos-mitos agama menenggelamkan sains. Inilah “kawin-cerai” yang saya maksud. Belum lagi mitos Euro, Liga Champions, liga Zimbabwe dan liga-liga favorit kita lainnya. Oh ya, karena PBB dan Liga Arab nampaknya sudah tidak mampu menangani krisis kemanusiaan di Yaman, Palestina, Suriah dan Irak, tidak ada salahnya Liga Indonesia mengambil alih, tapi, ya daftar ulang dulu ke Sunda Empire berikut paket demo berjilid-jilid melalui agen 212 dan eks HTI-FPI yang syahwat demonya adalah api tak kunjung padam.
Acapkali, filsafat dituduh sebagai sumber ketidakpercayaan terhadap apapun selain dirinya, biang keladi relativisme nilai-nilai dan bahkan nihilisme akut terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Relatif karena kebenaran memiliki lanskapnya sendiri dalam filsafat, nihil karena agama tak cukup menjadi solusi dalam hidup yang kompleks oleh dentuman informasi dan tsunami disinformasi. Meskipun tentu saja tuduhan gerombolan Wahabi dan kaum puritan tidak secerdas itu. Yang paling penting bagi para Wahaboy, ormas pentungan, parpol penjual agama, kaum monaslimin dan sebangsanya, tudingan haram dan kafir dulu, bid’ah dan syirik dilayangkan dulu, urusan lain belakangan. Toh nanti ada juragan-juragan yang mau kasih nasi bungkus.
Sementara gereja abad skolastik terus mewaspadai krisis iman akibat filsafat, mazhab-mazhab utama dalam filsafat Barat malah mencurigai penyusupan teologi ke dalam argumentasi-argumentasinya.
Meski tak terlalu lantang, aliran-aliran filsafat itu ingin meninggalkan metafisika dan pada gilirannya teologi juga, namun demikian kepentingan politik tak buntung akal, situasi boleh berubah, libido kekuasaan harus terus bertakhta, dan “obat kuatnya” adalah isu agama. Ini semacam dendam sejarah dari rasio selama kekang abad pertengahan membelenggu di bawah kendali oknum otoritas gereja. Adakah sekuel ini sedang de javu di Indonesia pasca formalisme agama merebak di setiap denyut kehidupan? Tidakkah situasinya justru lebih runyam setelah HTI-FPI dibubarkan, hanya dengan merobohkan papan namanya saja, sementara ideologinya tetap berkeliaran di dunia maya dan nyata?
Di sisi lain, karena para oknum pemangku agama semakin antipati filsafat, agama kian mengalami radikalisasi, kian luntur keluas-muliaannya, semakin banal cinta-kasihnya. Walhasil, krisis rasionalitas kaum beragama di abad pertengahan itu menyebabkan puritanisasi dan kekerasan atas nama agama hingga era revolusi industri 4.0 ini. Tidak percaya?
Tengok saja menjamurnya uspal (ustaz palsu), ulama karbitan dan mualaf-mualaf pseudo da’i satu-dua dekade terakhir: mencaci-maki agama lama, cari makan di agama yang baru, begitu ceramah teriak-teriak layaknya makelar terminal zaman Orde Baru. Kualitas mereka, karena memang karbitan, lahir dari kontes dai televisi dan ajang-ajang pencarian bakat bau kentut lainnya, maka para usdak (ustaz dadakan) itu harus jual agama, jualan kafir-syirik-bid’ah-takhayul-khurafat, jualan isu komunis dan yahudi, dagangan NKRI bersyariah, membenturkan agama vs Pancasila di tengah palagan politik, karena memang ilmu tidak mereka punya, apalagi sains. Padahal, tak kurang dari 824 ayat dalam Al-Qur’an membawa pesan sains. Lazim, para oknum penceramah musiman yang tak paham Kitab Suci, filsafat, saintek, psikologi, sejarah, antropologi dan apalagi geopolitik, mutu ceramahnya pasti tidak jauh-jauh dari ancaman neraka, ketiak bidadari, halal-haram dan kampanye poligami untuk menghindari zina. Padahal, solusi untuk tidak berzina ya jangan berzina, solusi untuk tidak mencuri ya jangan mencuri. Banyak jalan hidup yang jauh lebih mulia dan bermartabat daripada sekadar mengumbar libido atas nama agama.
Ini pula yang menjadi salah satu penyebab utama yang membumihanguskan sebagian negara Timur Tengah dan belakangan menyeruak mengemuka di Negeri kita. Semua berasal dari krisis akal sehat. Dampaknya, beragama tanpa akal ala ormas radikal dan paguyuban nasi bungkus alumni Monas. Jakarta telah manuai hasil dari jualan isu SARA dengan memilki gubernur maniak ngeles, ahli tata kata, bukan tata kota! Itu pun masih dibela mati-matian oleh pendukungnya meski tak becus kerja. Anda bisa sebutkan nama-nama kepala daerah lainnya yang satu spesies. Ah, politik memang hanya anies di bibir.
Bahkan, gerombolan cuti nalar permanen yang istikamah dengan kebebalan dan bangga dengan defisit otaknya serta-merta secara serampangan menawarkan konsep negara khilafah sebagai solusi bagi segala persoalan hidup. Bukankah sebaiknya cacat logika dan krisis akal sehat stadium 4 itu diobati terlebih dahulu sebelum berbicara tentang negara? Miskin solusinya kerja, bebal solusinya belajar, jomblo solusinya menikah, bukan khilafah!
Tak bisa dibantah bahwa agama dan rasio, wahyu dan filsafat, kini sama-sama berada dan bernaung dalam negara, berlindung di bawah konstitusi dan undang-undang negara. Kita tahu, negara dan konstitusi lahir dari filsafat. Hubungan filsafat dan wahyu bisa saling jalin-jemalin membantu negara, boleh jadi saling mencabik dan menikam demi menguasai negara, bisa pula mendominasi ala Antonio Gramsci atau setidaknya mereifikasi ala Gyorgy Lukacs berdasarkan maunya negara dan demi kepentingan (oknum penguasa) negara. Jangan lupa, manusia berada dalam ketiganya, bermain-main di dalamnya, atau malah memasang sebelah kaki di agama dan sebelah kaki di negara, lantas bisa kapanpun berselingkuh ria dengan negara, demi kelamin dan syahwat berkuasa. [HW]
bersambung…