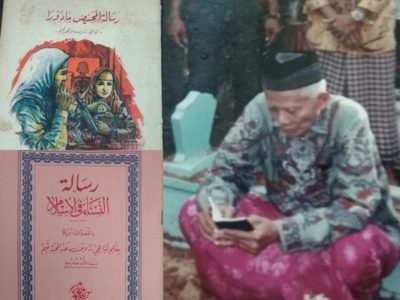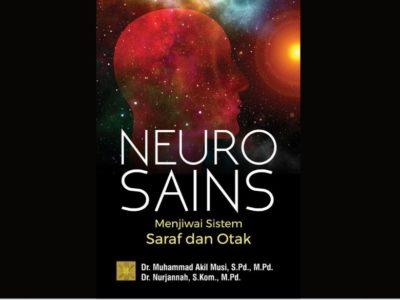Peran perempuan di ranah publik menjadi isu krusial dan sensitif yang hampir selalu memicu penolakan yang luar biasa, khususnya di Indonesia. Lebih menyedihkannya lagi ketika penolakan yang muncul disertai dengan semboyan atas nama agama. Berlindung dalam jubah agama seperti itu seakan mengabsahkan bahwa sejarah dan pengalaman hidup perempuan yang riil dalam tatanan masyarakat harus dipadamkan.
Kesempatan perempuan untuk memasuki dan berkiprah ke dunia publik khususnya politik sebenarnya sudah terbuka lebar. Pemerintah telah berupaya secara optimal dan berhasil me-publish kebijakan, salah satunya berupa UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik mendapat porsi sebanyak 30% mendapat legitimasi Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008.
Namun fakta lapangan berbicara berbeda, adanya pemenuhan porsi dalam partai politik hanyalah sebatas formalitas belaka, sehingga porsi 30% yang tertulis tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Sebagaimana yang dilansir www.kemenkopmk.go.id (14/04/2021) partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Cukup miris hasil pendataan World Bank (2019), disebutkan Indonesia menempati peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
Padahal Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan keterwakilan perempuan minimal 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Meskipun banyak perangkat hukum yang telah lahir untuk melegitimasi partisipasi politik perempuan, namun tetap saja sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan suatu hal yang sukar untuk dipertemukan.
Hal itu membuktikan adanya ketidaksesuaian antara das sollen (peraturan hukum) dan das sein (fakta lapangan), di satu sisi yang lain perempuan Indonesia dituntut untuk berkontribusi dalam semua sektor. Tidak cukup itu, di sisi lain juga muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodratnya sebagai second person. Situasi dilematis semacam ini yang sedang dihadapi perempuan Indonesia saat ini, sehingga menyebabkan partisipasi politiknya berjalan tidak maksimal.
Keterlibatan perempuan dalam catur perpolitikan sebenarnya bukan untuk mengambil lahan kekuasaan laki-laki, melainkan diharapkan agar perempuan benar-benar mampu berkolaborasi sebagai mitra politik laki-laki secara bersama-sama. Namun selama ini karena adanya steriotype negatif kepada perempuan, hak-hak politik perempuan menjadi terpasung dan memicu munculnya pandangan sex difference leaders (pemilihan pemimpin berdasar jenis kelamin).
Isu partisipasi perempuan dalam dunia politik dari awal sudah disorot tajam oleh fiqh politik klasik. Al-Mawardi ketika menguaraikan konsep kepemimpinan dalam al-Ahkam al-Sulthaniyahnya meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan persyaratan menjadi pemimpin dilihat dari jenis kelamin (laki-laki/perempuan), tetapi secara eksplisit dia mengutip hadits: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).
Tidak berhenti di situ, fiqh politik kontemporer juga turut menyuburkan pemahaman tersebut. Wahbah al-Zuhaili dalam Nidham al-Islamnya menyebutkan adanya syarat laki-laki dalam mengangkat kepala pemerintahan. Rupanya al-Zuhaili menggunakan parameter fisik dalam memaparkan ketidakbolehan perempuan menjadi kepala pemerintahan. Secara kodrat perempuan dinilai tidak mampu memikul tugas-tugas berat dan beresiko tinggi.
Untuk menguatkan argumennya, al-Zuhaili juga mencari sandaran legitimasi dari hadits yang sama: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Meskipun didukung oleh hadits tersebut, hal ini justru mempertontonkan wajah fiqh yang bias gender dan tidak ramah perempuan.
Setidaknya al-Kahlani telah menunjukkan informasi penting dalam kitab Subul al-Salam penjelasan dari kitab Bulugh al-Maram, bahwa cendikiawan fiqh klasik berselisih pendapat dalam memahami hadits tersebut. Misalnya, Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi pemimpin kecuali dalam masalah hukum hudud, sedangkan Ibn Jarir membolehkan kepemimpinan perempuan secara mutlak.
Dalam hal ini juga terkait partisipasi perempuan dalam ranah pemilu, pandangan al-Siba’i seorang mantan dekan Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan menunjuk perempuan lainnya untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai anggota masyarakat. (Al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun, 155)
Jika perempuan telah dianggap boleh berpartisipasi dalam pemilu, maka terlebih lagi partisipasinya dalam ranah parlemen sudah bisa dipastikan kebolehannya. Bukankah keanggotaan di parlemen pada dasarnya adalah wujud nyata dari partisipasi kaum perempuan dalam ranah pemilu? Oleh karena tidak ada indikasi larangan langsung baik dalam al-Qur’an maupun hadits, maka Abu Syuqqah dalam Tahrir al-Mar’ahnya juga tidak mempermasalahkannya.
Pendapat Abu Syuqqah tersebut mengacu kepada kaidah al-fiqhiyyah al-asasiyah: الأَصْلُ فِيْ الْأَشَيَاءِ اْلِإبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْل عَلَى التَّحْرِيْمِ (segala sesuatu itu pada asalnya dibolehkan, sejauh tidak ada ketentuan yang melarang). Alasan kebolehan ini, juga mendapat dukungan kembali oleh al-Siba’i.
Menurut al-Siba’i Islam tidak pernah melarang perempuan terlibat dalam penyusunan perundang-undangan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan kerangka amar ma’ruf nahu munkar. Dalam kerangka itulah al-Siba’i menilai perempuan boleh saja menjadi anggota parlemen.
Senada dengan pendapat di atas, Abu Syuqqah menukil pandangan Yusuf al-Qardhawi, yang memandang tidak adanya larangan atas partisipasi perempuan dalam parlemen, sebab hal itu dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan sosial-bersama. Justru kepentingan sosial sangat membutuhkan partisipasi perempuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan yang berkeadilan. (Tahrir al-Mar’ah, 542).
Berdasarkan penjelasan di atas, nampaknya tawaran al-Siba’i, Abu Syuqqah, dan al-Qardhawi dinilai lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Maka sudah saatnya kaum perempuan tidak dipandang lagi sebagai mahluk domestik, tapi sebagai agen yang turut aktif berpartisipasi dalam dunia politik, terlebih untuk mempercepat terwujudnya arah dan keputusan politik Indonesia yang lebih substansial dan akomodatif. Waallahu a’lam. []