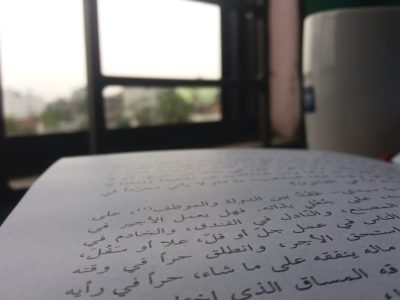Sudah maklum bagi sekalian umat muslim seputar empat kewajiban bagi yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Yaitu memandikan, mengkafani, mensalati dan menguburkannya. Dalil-dalil kewajibannya pun sudah jelas dan tak dapat terbantahkan lagi.
Namun, yang menjadi soal dan ajang silang pendapat di kalangan ulama, yaitu menyangkut teknis dan tata cara merawat jenazah itu sendiri. Sebut saja dalam urusan memandikan mayat. Seperti perbedaan pendapat ulama tentang jenazah perempuan yang hanya sempat diurusi oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya, lantaran tiada satu pun perempuan di sana. Dalam hal ini, menurut segolongan ulama, jenazahnya tak usah dimandikan, melainkan cukup dengan mentayamuminya. Itu pun harus melapisi tangan, agar tidak menyentuh kulit jenazah tersebut. Mengingat adanya keharaman melihat aurat si mayat, lebih lagi menyentuhnya.
Namun, satu golongan lain berpandangan berbeda. Yaitu harus dengan memandikannya. Dengan alasan, bahwa tayamum hanya bisa dilakukan setelah menghilangkan najis mayat tersebut. Sehingga solusinya harus dimandikan, walaupun dengan cara diceburkan ke air, semisal sungai atau yang lain. Dan ini adalah pendapat yang lebih rasional, karena memandikan tak harus melihat dan menyentuh aurat. Begitulah gambaran silang pendapat ulama dalam hal teknis memandikan jenazah.
Kemudian dalam urusan mengkafani mayat, ulama berbeda pendapat dalam banyak hal. Diantaranya menyangkut hukum mengkafani mayat perempuan dengan sutra. Menurut imam Ibnu Shalah, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Dengan mengiaskannya kepada keharaman menghiasi rumah dengan kain sutra. Jadi, beliau mengharamkan mengkafani mayat dengan sutra, berdasarkan dalil kias (analogi). Dengan titik temu (illat) tadlyi’ul mal atau tabdzir al-mal (menyia-nyiakan harta). Karena menghiasi rumah dengan sutra termasuk laku yang sia-sia, alias tidak memanfaatkan harta dengan semestinya, maka jelas mengkafani jenazah dengan sutra, juga sia-sia, bahkan bisa lebih. Kira-kira demikian argumentasi Ibnu Shalah, sebagaimana dalam Fath al-Mu’in bi Syarhi Qurratil ‘Ain.
Sementara imam Jalaluddin al-Bulqiniy, malah memandangnya sebagai hal yang boleh saja. Karena illat-nya bukan tadlyi’ul mal sebagaimana di atas, melainkan illat-nya adalah tadlyi’ul mal atau tabdzir al-mal li gharadlin (menyia-nyiakan harta untuk tujuan yang baik). Sehingga hukum mengkafani mayat dengan sutra tidak bisa dianalogikan dengan keharaman menghiasi rumah dengan sutra. Sebab illat-nya berbeda.
Imam Jalaluddin al-Bulqiniy dalam membolehkan hal itu, menggunakan hadis Rasulullah SAW berikut:
أحسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم
Artinya: “Perindahlah kain kafan orang-orang mati di antara kalian, karena mereka saling berbangga-bangga dengan kafan-kafan mereka.”
Melalui hadis ini, dapat dipahami bahwa tak jadi masalah bila jenazah berkafankan sutra. Sebab, di sana terdapat pemuliaan besar kepada si mayat. Dan itu jelas tidak sia-sia. Memang menurut imam an-Nawawi, idla’tul mal adalah mengalokasikan harta tidak pada tempat semestinya berdasarkan pandangan syariat, dengan kata lain, merusak manfaatnya secara sia-sia. Namun, berdasarkan keterangan dari imam asy-Syafi’i yang dinukil oleh al-Qurthubiy, bahwa tidak ada istilah tabdzir al-mal dalam semua perbuatan baik. Berikut redaksinya;
التبذير هو إنفاقُ المال في غير حقِّه، ولا تبذيرَ في عمل الخير
Artinya: “At-Tabdzir adalah menggunakan harta tidak pada semestinya, dan tidak akan ada yang sia-sia kala digunakan untuk kebaikan.”
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk keharaman mengkafani jenazah perempuan dengan kain sutra. Mengingat bahwa itu termasuk perbuatan baik, yaitu memuliakan mayat (ikram al-mayyit wa ta’dhimuhu). Dalam hal ini, syekh Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi dalam Hasyiah I’anah at-Thalibin, menyuguhkan sebuah kaidah fikih yang berbunyi,
فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها
Artinya: “Setiap yang boleh dikenakan seorang perempuan di masa hidupnya, maka boleh juga ia kenakan setelah matinya.”
Berdasarkan kaidah ini, memakaikan perhiasan emas kepada mayat perempuan pun tak jadi masalah, yang penting masih dalam kadar kebolehan pemakaiannya di dunia.
Menurut imam Ibnu Qasim, bahwa pendapat yang diutarakan oleh Jalaluddin al-Bulqiniy dalam masalah ini adalah pendapat yang dijadikan pegangan oleh imam Muhammad ar-Ramli. Wallahu a’lam. [HW]