Salah satu tokoh idola almarhum Gus Dur adalah teolog-sufi, Al-Hujwiri (w. 1073 M/465 H di Lahore). Nama lengkapnya, Abil Hasan Ali bin Utsman bin Al-Ghaznawi Al-Jullabi Al-Hujwiri. Dalam bukunya, Kasyf al-Mahjub (The Revelation of Mystery), yang berisi kupas-tuntas 12 aliran tasawuf mayor yang berkembang di zamannya, serta penjelasan bernas tentang ‘irfan, Al-Hujwiri menceritakan bahwa kanjeng Nabi Saw melepas dan lantas menghamparkan jubah kesayangan beliau untuk tempat duduk seorang kepala suku non Muslim yang datang bertamu. Pada kesempatan lain, kanjeng Nabi berdiri menghormati jenazah orang Yahudi yang hendak dikebumikan. Sederhana, siapapun, beragama atau tidak, tetap akan mati menghadap sang Khaliq.
Cara Al-Hujwiri mereportase kepribadian dan sosok Muhammad Saw sebagai Nabiyyur Rahmah (Nabi yang penuh cinta-kasih), bukan Nabi yang pendera, pemarah, pendendam, bengis dan otoriter, rupa-rupanya telah memukau Gus Dur untuk menduplikasi metode ini dalam kehidupan beragama di Indonesia yang sangat heterogen. Kelak, pada aspek inilah sepak terjang seorang Abdurrahman ad-Dakhil ini kian cerlang memancar.
Gus Dur, tentu saja, sedang mengajak kita untuk melek sejarah, melek literasi, agar tidak gemampang dan gegabah menghakimi siapapun yang berbeda, terutama dengan legitimasi agama. Bukankah mertua baginda Nabi yang bernama Huyay bin Akhthab seorang Yahudi? Bukankah dulu nubuwat kanjeng Nabi justru dijelaskan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal kepada sayyidah Khadijah al-Kubro? Bukankah membangun interaksi dan hidup membaur dengan mereka yang liyan justru dianjurkan oleh Kitab Suci (QS. Al-Mumtahanah: 8-9), bukankah Al-Qur’an menyebut non muslim dengan sebutan Ahli Kitab?
Nah, mengapa masih ada sebagian bani micin, kaum otak cingkrang, gerombolan cuti nalar dan jamaah monaslimin yang belum melek sejarah, sehingga ketika rekan-rekan Banser menjaga gereja di Hari Natal, misalnya, malah dituduh murtad dan syirik? Lantas, mereka bangun narasi serampangan bahwa Islam Nusantara melindungi kafir dan memusuhi sesama muslim. Saya kira para ulama kita, dan khususnya rekan-rekan Banser sudah biasa menghadapi perundungan, fitnah, ujaran kebencian dan segala propaganda nirmakna murahan lainnya
Dalam salah satu mangun opusnya, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Gus Dur mengutip pandangan Al-Hujwiri (h. 67),
Bila engkau menganggap Allah itu ada hanya karena engkau merumuskannya, hakikatnya engkau telah menjadi kafir. Allah tak perlu disesali kalau Dia menyulitkan kita, juga tak perlu dibela jika orang-orang menyerang hakikatNya.”
Gus Dur dan para Kiai NU pada umumnya sadar betul bahwa teks Al-Qur’an tidak bisa dimaknai secara tunggal. Satu kata dan terma dalam Kitab Suci memiliki sejumlah kemungkinan makna dan kontekstualisasi nilai. Teranglah kini bahwa memahami Islam secara tekstual dengan memonopoli kebenaran dan bahkan menyamakan Arab dengan Islam dan menjadi Islam harus menjadi Arab adalah kebodohan yang nyata, kesesatan terstruktur dan masif (fi dhalalin mubin).
Dalam banyak kesempatan, Gus Dur juga kerap mengutip para pemikir klasik lintas disiplin, salah satunya sang bijak bestari, Maulana Jalaluddin Rumi, satu nama besar yang otoritas kesufiannya tetap benderang hingga kini. Rumi memiliki banyak santri, cantrik dan atau mahasiswa dari berbagai agama dan latar belakang etnis. Juga bagaimana seorang Jarjiyus Bakhtisyu II, direktur Rumah Sakit Jundisapur, seorang Majusi yang dipercaya menjadi dokter pribadi Harun ar-Rasyid. Bahkan, ketika Jarjiyus/George wafat, sang Khalifah sendiri yang mengantar jenazahnya bersama ribuan pelayat dari berbagai agama dan menanggung biaya pemakaman. Kabar baiknya, Gus Dur adalah Rumi-nya Indonesia.
Memang, penting bagi generasi muda untuk membuka khazanah intelektual klasik yang sarat dengan pertentangan ilmiah dan adu argumentasi rasional, di mana otoritas ulama sangat meniscayakan kualifikasi dan prasyarat yang sungguh-sungguh ketat, tidak asal pakai sorban dan daster lalu teriak takbir di jalanan. Ulama adalah mereka yang memiliki spiritualitas tinggi, kadang tidak populer di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Ulama adalah para pembaca, pengajar dan pengamal nilai-nilai Kitab Suci (rabbaniyyun, ribbiyyun), serta ulama juga seorang konsultan (ahl adz-dzikr). Semua itu ada pada sosok Kiai Pesantren, kaum sarungan!
Kira-kira tiga tahun silam, saya membaca dan mengkhatamkan Al-Munqidz minadh-Dhalal selama Ramadhan bersama para luhurian (sebutan untuk santri Pesantren Luhur Baitul Hikmah), salah satu yang menarik adalah ketika Imam Al-Ghazali dikritik kaum fundamentalis (zaman sekarang para ulama Monaslimin) bahwa pemikiran beliau terpengaruh para pemikir Yunani (falasifah al-qudama’). Al-Ghazali menjawab dengan sangat mengejutkan: “Apabila ucapan itu benar dan dibangun berdasarkan argumentasi rasional, serta tidak menyalahi Al-Qur’an dan Al-Hadits, mengapa harus dibuang dan diingkari?”
Juga pandangan Ibnu Rusyd dalam Fashlul Maqal fi ma Baynas Syari’ah wal Hikmah minal Ittishal bahwa: “Jika kita mendapati kebenaran dari mereka yang beda agama, seharusnya kita terima dengan gembira dan sikap menghargai. Tapi, jika salah, patutlah kita peringatkan dan kita terima (permintaan) maafnya.”
Itulah mengapa membela dan mempertahankan Nusantara (dulu namanya Hindia Belanda) berikut semua kekayaan dan khazanah keislaman di dalamnya wajib. Hal ini semakin dipertegas dalam Muktamar NU 1935 di Banjarmasin. Pendek kata, para Ulama waktu itu lebih berpikir substantif daripada formalistik mengenai agama.
Khazanah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah yang bercirikan moderasi pemikiran dan prilaku dengan menjunjung tinggi sikap moderat (tawassuth), berimbang (tawazun) dan toleran (tasamuh), tidak gampang menghakimi dan mengedepankan aspek tabayun (bertanya dan konfirmasi langsung) inilah yang terus dirawat dan terus dikampanyekan oleh Gus Dur, Kiai Sahal Mahfudh, Kiai Maimoen Zubair dan belakangan Gus Mus, Prof Quraish Shihab, Habib Luthfi, Kiai Said, dan Kiai-kiai muda lainnya juga beberapa tokoh Islam moderat yang datang kemudian.
Lucunya, bagi sobat gurun yang kerap mabuk Arab, nama-nama tersebut kerap dicap liberal, antek Yahudi, syiah dan komunis, karena seringkali Gus Dur membela penganut Syiah, sekte Ahmadiyah dan bahkan Inul Daratista, padahal, sudah jamak diketahui bahwa yang dibela adalah kemanusiaannya, hak hukumnya, bukan membenarkan mazhab dan kesalahannya. Tak pelak, nama-nama di atas kerap menjadi obyek sinisme dan sasaran perundungan dari kaum sumbu pendek defisit ilmu dan pekerti.
Sementara itu, Islam, dalam pandangan Gus Dur seperti benih atau bibit padi, ia jika ditanam di Eropa akan menjadi padi Eropa, apabila ditanam di Indonesia menjadi padi Indonesia. Inilah gagasan orisinal dari sang Super Gus, yakni Pribumisasi Islam yang telah ia canangkan sejak 1984. Jadi, Islam Nusantara hanya nomenklatur dari Islam yang menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal sejak zaman para Wali dan penganjur kesalehan yang datang kemudian, hingga kini dan selamanya.
Universalisme Islam mengharuskan para pengikutnya untuk berkerja sama dengan semua komponen bangsa, sebab Islam agama dialog, agama cinta dan agama yang memanusiakan manusia. Sementara itu, tradisi dan kearifan lokal diislamisasi dengan sangat elegan dan santun dengan tidak menghilangkannya dan membabat habis sama sekali. Oleh karena itu, pluralisme Gus Dur tidak hanya berlaku terhadap non muslim (pluralisme eksternal), tetapi juga kepada sesama penganut Islam sendiri (pluralisme internal) dengan tidak memonopoli kebenaran. Kabar baiknya, pesantren sudah ratusan tahun menjadi basis pembelajaran pluralisme dan multikulturalisme. Demikan dijabarkan dalam buku Peradaban Sarung: Veni, Vidi, Santri
Oleh karena itu, masa depan negara bangsa berikut empat pilarnya (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sangat bergantung kepada kiprah pesantren dan kaum sarungan. Alangkah istimewanya jika sebelum kita mempelajari Tuhan dan agama, terlebih dahulu menghayati manusia dan kemanusiaan. Sehingga, apabila suatu saat nanti kita membela agama, kita tidak lupa diri bahwa kita manusia. Kita bukan Tuhan yang punya otoritas benar-salah dan kafir-mukmin.
Islam Nusantara tak lain adalah Islam “di” Nusantara, yakni Islam yang dikembangkan di Tanah Air kita ini setidaknya sejak era Walisongo, sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang agung, yang sesuai dengan kekayaan dan kearifan bangsa Indonesia. Pendek kata, pribumisasi Islam ala Gus Dur sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat-istiadat lokal di Indonesia kian mendapati bentuknya dalam konsep Islam Nusantara yang dicanangkan oleh NU sejak 2015 lalu.
Islam Nusantara adalah Islam yang menyelaraskan Agama dengan budaya, Islam yang sinergi dengan semangat kebangsaan. Penggagas utama Islam Nusantara adalah Walisongo, sehingga melahirkan semangat Islam yang ramah dan santun. Karena Islam datang ke Nusantara bukan dengan perang dan kekerasan.
Puncak konsep Islam Nusantara, dalam pandangan Kiai Said, adalah saat hadratusysyaikh KH. Hasyim Asy’ari berhasil menggabungan Islam dan kebangsaan. Simpulannya, “Islam Nusantara bukan mazhab, bukan aliran, tapi tipologi, mumayyizaat, khashais,” terang Kiai Said.
Habib Luthfi juga menegaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah Islam yang anti dan benci Arab. Alih-alih benci, Islam Nusantara adalah Islam yang penuh cinta-kasih, santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, menjadi mercusuar ilmu dan peradaban. Kini, Islam Nusantara kian berkibar dan mendunia dibawah komando Kiai Said Agil Siroj.
Gus Dur sebagai Ayatullah Demokrasi dan Doktor Humoris Causa, mengajarkan bagaimana berpikir visioner dan mengedepankan kemanusiaan-keindonesiaan. Gus Dur adalah seorang stoic, filsuf Stoa dan mistikus abad ini yang mendedahkan sebuah nilai dengan sebilah tanya yang menikam ke jantung kesadaran kita, khususnya milenial: Bisakah kita meludahi langit? Mungkinkah kita mengotori samudera dengan setetes air kencing? Jika seseorang memberi kita sesuatu dan kemudian kita dengan ramah menolaknya, menjadi milik siapakah pemberian itu?
Jika seseorang mencaci, mencemooh dengan cercaan kebun binatang, kemudian kita balas dengan menggonggong dan menyalak-nyalak melebihi serigala kelaparan, apa bedanya dengan mereka?
Memaafkan tak lain adalah yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Menyalahkan dan mencari wedus ireng bukan solusi. Ada hal-hal yang tak butuh pahlawan kesorean, biar waktu yang menalannya menjadi masa lalu dan lalu hadir sebagai serbuk-serbuk kenangan dan pembelajaran. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. (QS. Al-Hijr: 85)
Jika kita sadari bahwa mereka yang berusaha meludahi langit itu adalah manusia sia-sia, akan segera kita renung-insyafi bahwa pelajaran yang bisa kita petik darinya tak pernah sia-sia. Tahukah Anda bahwa dari sekian banyak kesalahan yang pernah manusia lakukan terdapat kesalahan yang sempurna? Apa itu, Kianak? Ya, satu-satunya kesalahan yang sempurna adalah kesalahan yang kita tidak memetik pelajaran darinya, terutama dari para pembenci. Ajaran mendiang Gus Dur yang terus hidup dan menyala ini, saya menyebutnya: Filsafat Gitu Aja Kok Repot! Alfatehah untuk beliau dan semua ulama NUsantara. [RZ]




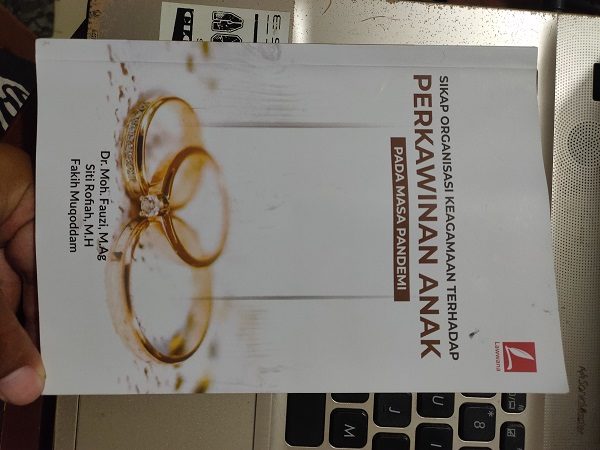




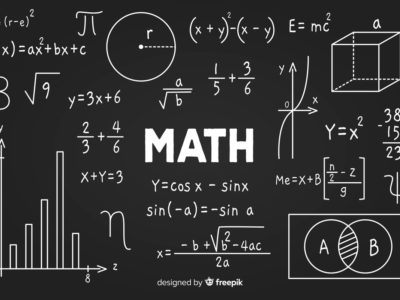














[…] ! Ternyata kalimat “GITU SAJA KOK REPOT” masih terlalu repot untuk kita pahami bersama, Gus… […]