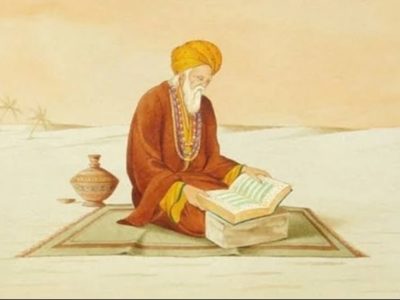Kalau engkau lahir dan tumbuh besar dalam kultur Nahdlatul Ulama, maka engkau pasti tahu kalau salah satu ciri ruang tamu di rumah orang NU, selain kaligrafi atau gambar kota Mekah, pasti adalah pajangan gambar atau foto para tokoh. Tokoh tersebut biasanya adalah guru ngaji atau sesepuh yang menjadi guru dari guru ngajimu, atau mata air pengetahuan dari guru-gurumu. Di rumah saya, foto tokoh itu adalah Simbah KH Maimoen Zubair.
Usia saya belasan. Setiap hari bakda maghrib, saya selalu mengamat-amati lampu ruang tamu kami yang sempit, tempat Bapak mengajar mengaji sebelum akhirnya mendirikan musala kecil di samping rumah.
Kata Bapak, kalau kita mengajar Al Quran, rumah kita akan jadi terang. Rumahku kecil dan jelek. Berdinding kayu kas rapuh dan belum beralas lantai saat itu. Naluri lugu saya sebagai kanak-kanak berpikir, bagaimana pula rumah akan terang sedangkan kami ini miskin? Satu lampu yg sedikit terang hanya di ruang tamu sempit itu, bilik kamar kecil dan pawon kami cuma diterangi lampu dop kuning kecil.
Belakangan saya tahu, kepercayaan itu adalah wasiat Romo KH Maimoen Zubair. Maksudnya tentu saja bukan lampu rumah kami yang akan jadi lebih terang, tapi jiwa kami yang akan luas dan tidak gentar kepada dunia jika kami mencintai Al Quran. Itu juga sebabnya, pesan Bapak ketika saya tinggal di mana pun adalah cari masjid yang dekat, cari guru, dan tetap mengajar.
Sejak kanak, telinga saya akrab mendengar nama Mbah Moen. Mungkin kami hanya sedikit beruntung sebab rumah kami ada di Blora, sedangkan Romo Kiai Maimoen adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang. Satu jam saja dari rumah. Cerita bahwa Mbah Moen amat alim, Mbah Moen jadi anggota dewan tapi tidak pernah ambil gaji, menjadikan kami potret keluarga biasa yang masih percaya pada partai bernama PPP karena ketokohan Mbah Moen.
Bapak mengaji di sebuah komunitas kecil, bernama majelis ta’lim Nurussalam di Kota Blora. Pengasuh majelis ta’lim itu adalah Romo KH Muhtadi Noor, santri KH Maimoen.
Setiap tahun saat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di majelis, Mbah Moen hadir sebagai penyampai mauizah utama. Momen pengajian maulid Nurussalam selalu jadi favorit karena penabuh hadrah terbaik dari pesantren Khozinatul Ulum akan tampil, akan ada pembaca tilawatil Quran dengan suara terbaik dan haflah akhirussanah “santri kalong” yang membacakan surat-surat di juz 30 diakhiri doa khatam Al Quran oleh KH Muharror Ali, dan juga banyak sekali pedagang jajanan dan mainan anak-anak di sekitar lokasi acara.
Santri kalong di majelis Nurussalam adalah orang-orang kecil yang berprofesi pedagang pentol gerobak, pedagang sayur keliling, buruh tani, hingga kuli bangunan. Romo KH Muhtadi mengajar kitab kepada mereka setiap hari setiap malam, tentu saja tanpa biaya.
Di peringatan maulid Nabi, Mbah Moen selalu menyampaikan hal yang sama dari tahun ke tahun, sejak saya SD hingga remaja, yakni tentang Nur Muhammad. Mbah Moen biasanya baru naik panggung selepas pukul sepuluh malam dan mengakhiri ceramah lewat pukul satu malam. Beliau mengisahkan tarikh Nabi. Ceramah itu, meskipun tak saya pahami, senantiasa saya simpan dalam ingatan.
Setelah sedikit sekali membaca literatur tasawuf dan sudah dapat mengkoneksikan satu bidang pengetahuan dengan bidang pengetahuan lainnya, saya baru memahami jika nur Muhammad adalah spirit kebaikan Rasulullah Muhammad yang terbit sejak sebelum dunia ini ada dan akan senantiasa abadi hingga akhir zaman. Rasulullah bukan sekadar persona fisik, ia adalah tajalli Allah, al awwalu wal akhiru, alasan mengapa bumi dan seisinya ini diciptakan. Ia adalah kabar gembira untuk kedukaan umat manusia. Kita semua manusia biasa ini hidup untuk mengilhami nur Muhammad itu, kita mengejar cahaya itu.
Sepuluh tahun terakhir, Mbah Moen sudah jarang hadir ke Nurussalam. Lebih sering dibadali oleh Gus Ghofur. Gus Ghofur pun halus retorikanya seperti Romo Kiai.
Momen membahagiakan adalah ketika menyimak Mbah Moen berceramah di syukuran pernikahan Kak Ova bin Abah Kiai Gus Mus di Leteh. Lalu, Maret 2017, barangkali adalah momen saya menyimak pidato Mbah Moen terakhir kali. Indonesia sedang ribut sekali yang asalnya adalah keributan tarik menarik kekuasaan dari Jakarta. Secara cukup mendadak, terselenggara Silaturahim Nasional Alim Ulama Nusantara. Mbah Moen mengundang Kiai-Kiai khos untuk bermusyawarah di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang. Mbah Moen berpidato dua jam yang lalu dirumuskan dalam poin-poin Risalah Sarang, wasiat penting untuk menjaga kedamaian NKRI dan merespons tantangan teknologi yang membuat umat terpecah belah.
Kalau hari ini saya sedih, sesungguhnya saya khawatir karena mautul alim mautul alam adalah nyata. Mbah Moen, adalah Kiai yang sangat ilmiah. Beliau bisa menjelaskan mengapa kita tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari dengan argumen-argumen yang ilmiah. Beliau bisa menerangkan kebudayaan Islam Nusantara yang dekat dengan kultur agraris untuk memberi penghormatan para petani yang pandai membaca alam dengan amat mengagumkan. Mbah Moen bisa bercerita risalah Islam dunia dan nusantara.
Pagi tadi saya menelpon Bapak sambil menangis gemetar di Bandara Gorontalo. Bapak sudah dengar kabar Mbah Moen kapundhut, mungkin dari grup pengajian. Bapak bilang, kita harus ikhlas, toh “tinggalan” Mbah Moen sudah banyak. Tinggalan artinya legacy, warisan kepada generasi berikutnya.
Ya, termasuk sebuah petuah kecil untuk selalu mengajarkan Al Quran di mana saja, yang diilhami oleh seseorang biasa saja yang bukan keturunan orang alim sekali pun seperti Bapak di rumah.
Ini tulisan dari saya, bukan sesiapa, orang biasa, seorang pengagum yang memperhatikan Mbah Moen dari jauh sekali. Seperti masa kanak-kanak dulu, Mbah Moen ada di panggung, dan saya menyimaknya sambil bermain-main lalu perlahan mengantuk di baris belakang para santri.